“Ada karyawan pergi ke orang pintar. Dia jampi-jampi kamu supaya gampang dikasih pinjam uang.” Ucapan itu keluar begitu saja dari mulut kakak Sony, yang tiba-tiba muncul di kantornya.
Sony tertegun. Benar. Baru saja Sugiono, messenger-nya, dengan wajah memelas, pakai menitikkan air mata pula, mengajukan kasbon. Ada masalah keluarga, katanya. Anak lelakinya masuk sel karena mbacok orang. Untung tidak sampai mati. Harus ditebus dan mengganti biaya rumah sakit.
Sony jadi keheranan. Dari mana kakaknya tahu? Padahal, pembicaraan tadi terjadi di ruang kerjanya yang tertutup. Lagian, tidak mungkin dia membiarkan karyawan lain melihat Sugiono, bapak empat anak yang asli Balaraja, Tangerang itu, menangis tersedu-sedu. Tentu tak etis membiarkan hal seperti itu menjadi tontotan orang. Sekalipun itu kakaknya sendiri.
Sony memang gampang jatuh iba bila berhadapan dengan orang yang menangis. Kalau dibilang cengeng, sebenarnya tidak juga. Hanya saja, dia suka tak tahan bila melihat orang menitikkan air mata. Nonton sinetron juga begitu, tiba-tiba saja matanya sembab ketika terbawa oleh adegan yang mengharukan. Sehingga harus ngumpet-ngumpet mengelap air mata dengan lengan bajunya, agar tak ketahuan istri dan anak-anaknya.
Pernah sekali dia akan memecat seorang karyawan karena melakukan kesalahan fatal. Tapi karena Sandy, si Belanda Depok, sekretarisnya itu, terus menangis dan berjanji tak akan mengulangi kesalahannya, akhirnya tidak jadi dia keluarkan. Tak tega rasanya. Begitu pula, ketika Sugiono menangis kebingungan karena tak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalah anaknya, kena lagi dia.
“Berapa?”
“Lima juta, Pak.”
Wah, bagaimana ini. Minggu kemarin Sugiono baru saja kasbon lima juta, anak perempuannya mau masuk sekolah perawat, katanya. Sony meluluskan permintaan itu, karena demi pendidikan anak. Sisa hutang dari kasbon lama langsung dipotong dari kasbon baru. Tapi, sekarang lain lagi soalnya. Aturannya, dia tidak boleh kasbon sebelum kasbon pertama lunas. Peraturan is peraturan. Tidak boleh dilanggar. Tapi ini soal kayaknya sangat gawat. Akhirnya, karena tak tahan dan kasihan, Sony mengambil duit di laci yang sedianya akan dipakai untuk bayar tagihan kartu kredit.
“Ini, saya cuma punya empat juta. Selesaikan baik-baik itu masalah. Dan kalau sampai di rumah, anakmu dicambukin saja sampai ampun-ampun. Biar nggak sembarangan bacok orang,” kata Sony sambil memberikan amplop coklat berisi uang.
“Jangan ngomong sembarangan. Dari mana kamu tahu ada orang jampi-jampi saya?” tanya Sony kepada kakaknya yang sedang asyik bermain-main dengan asap rokoknya.
“Saya tahu,” jawabnya singkat, sambil mencetak empat lingkaran asap yang berbaris lurus. Dia tidak sedikitpun memperhatikan Sony yang tampak jengkel. Malahan, dia kembali asyik membuat lingkaran-lingkaran asap gandeng yang menyerupai logo Audi.
Tapi Sony tak mau kalah. Dia merasa sangat tidak nyaman ditembak seperti itu. Mangkel, seolah dianggap sebagai orang yang lemah. Karena itu, Sony terus membantah omongan kakaknya. Bahkan dengan sesumbar, “Saya tak mempan dijampi-jampi. Dan karyawan saya tidak ada yang suka pergi ke dukun.”
“Sekarang begini saja, Son. Kamu mau enggak saya beri pegangan? Untuk pagar diri, biar tak mempan dijampi-jampi,” katanya sambil mengulurkan sebuah lipatan kecil kertas putih.
Sony diam saja. Masih kesal dia, karena kakaknya tidak menjawab pertanyaannya. Eh, sekarang, kakaknya itu, malah menawarkan ajimat lagi. Lagian, Sony sama sekali tidak percaya dengan yang begituan. Hanya saja, dia selalu mempunyai kertarikan yang kadang agak berlebihan terhadap hal-hal gaib. Diam-diam dia lirik lipatan kertas itu. Dia penasaran sekali mengenai apa yang ada di dalam bungkusan tersebut.
“Apa ini?” tanyanya sambil tak sabar membuka lipatan kertas tersebut. Tapi Sony agak kecewa, karena hanya mendapati dua helai rambut keriting seukuran tusuk gigi. Warnanya cokelat kehitaman dan besar-besar. Seperti kumis kerbau. Kasar. Kayaknya tidak pernah kenal shampoo.
“Ini bulu gendoruwoh,” sahut kakaknya dengan suara agak pelan. “Ada penunggunya, Bejo dan Beji,” tambahnya lagi sambil menjumput kedua helai rambut gedoruwoh itu. “Mau bukti, kamu?” katanya, seolah menantang Sony.
Ditantang seperti itu, Sony langsung bereaksi. “Ayo. Siapa takut?” jawabnya dengan nada menantang balik.
Kakaknya segera mengangkat cangkir kopi dari cawan yang mengalasinya. Kemudian dia tuangkan air putih dari gelas minum Sony ke dalam cawan hijau itu. Setelah air mulai tenang, dia masukkan kedua helai bulu gendoruwoh tersebut ke dalamnya. Ajaib. Bulu-bulu kasar itu langsung berjoget seperti cacing kepanasan. Ngulet. Meluruskan diri, seolah sedang meregangkan punggungnya yang pegal. Begerak kesana-kemari seperti perenang profesional.
“Hebat. Dapat dari mana kamu?” tanya Sony.
Kemudian dia bercerita. Bulu gendoruwoh itu dia dapatkan tanpa sengaja. Ketika sedang sholat malam di Masjid Jami’ di kampung halaman sana, dia merasa seperti ada tangan-tangan yang sangat besar mengganggu konsentrasinya. Tangan-tangan raksasa itu bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan secara tak beraturan dan berusaha menyentuhnya. Karena merasa sangat terganggu, maka dikibaskanlah tangan kanannya untuk mengusir tangan-tangan jail tersebut. Gangguan itu langsung hilang. Dia melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat barulah dia sadar kalau di telapak tangan kanannya telah menempel dua helai bulu yang besar-besar itu. Rupanya, kibasan tangannya tadi telah merontokkan bulu tangan gendoruwoh yang mengganggunya.
Kakak Sony yang satu ini memang seorang dukun. Namun demikian, sholatnya tekun. Tak pernah telat, malah suka lebih. Ke mana-mana bawa tasbih. Baju koko jadi kostum harian. Dengan kopyah putih yang agak kebesaran. Tak sedikit pun terkesan bahwa dia seorang dukun. Dan lagi, pada dasarnya dia juga tak suka disebut dukun. “Hanya mengamalkan ilmu,” katanya.
Sony sendiri tak tahu sejak kapan kakaknya punya ilmu. Setahu dia, tak seorang pun kerabatnya yang menjadi dukun. Jadi, dari mana dia mendapatkan ilmu? Sony sering menanyakan hal itu. Tapi tak pernah dijawab. Setelah dia desak terus, empat tahun lalu, akhirnya kakaknya buka kartu.
“Itu piaraan Mbah Jiran yang ngintil terus dan kemudian saya rawat,” katanya dengan setengah terpaksa. “Sebelumnya, macan putih itu sempat menunggu mushola di samping kanan rumah selama hampir tiga puluh tahun,” tambahnya lagi.
Mbah Jiran, kakek Sony, memang orang hebat. Seorang haji yang sholatnya tak pernah telat. Suka menolong orang yang lagi kesrakat. Seorang petinggi yang dicintai masyarakat. Makanya, ketika meninggal banyak sekali yang melayat. Tetangga dan kenalan beramai-ramai mengantarnya ke tempat beristirahat.
Sony sendiri tidak terlalu paham dengan semua keramaian itu. Karena masih SD kelas satu. Terselip di antara para pelayat ada sejumlah ibu-ibu. Dan orang-orang yang tak dikenalnya berwajah biru. Tatapan mata mereka beku. Mereka menangis tersedu-sedu. Belakangan, setelah sepuluh tahun berlalu, barulah Sony tahu. Mereka ternyata istri-istri dan anak-anak kakeknya yang datang dari segala penjuru.
Jadi, begini ceritanya. Mbah Jiran semasa mudanya berprofesi sebagai saudagar tembakau yang sukses. Setiap saat bepergian ke daerah-daerah di mana petani menanam daun beraroma harum itu. Lembaran-lembaran daun tembakau yang lebar-lebar diborong dan disimpan di dalam keranjang-keranjang berbungkus tikar di rumahnya yang sangat besar.
Sebuah rumah bergaya kolonial dengan langit-langit tinggi dan penuh selasar. Ubinnya menghampar indah dengan tegel-tegel bergambar. Dengan tiang-tiang yang begitu kokoh dan kekar. Dengan banyak daun pintu dan jendela dua lapis yang lebar-lebar. Terasnya beratap seng gelombang tebal berlembar-lembar. Di rumah itulah tembakau dikumpulkan. Di sebuah gudang persis di sebelah kamar mandi. Setelah jumlahnya mencukupi, tembakau kemudian dijual ke pabrik rokok di Kudus, Jawa Tengah.
Rupanya kakek Sony yang keturunan Madura itu termasuk penganut filosofi bekerja sambil berkarya. “Business is pleasure,” mungkin nasehat seperti itu yang akan diberikannya kepada Sony seandainya sekarang masih hidup. Karena Mbah Jiran sangat dekat dengan Sony, dan cenderung memanjakannya, seperti bapaknya.
Di tempat-tempat yang biasa didatanginya, Mbah Jiran selalu menyempatkan diri menyunting dara. Duit banyak. Semangat meledak-ledak. Badan perkasa. Malam-malam sendirian di desa. Daripada susah tidur, lebih baik mengasah sangkur. Pulangnya diulur-ulur.
“Ada apa ini?” Padahal, di rumah, nenek Sony ayu benar. Kulitnya bersih bersinar. Hidungnya mancung dan tipis. Senyumnya manis. Kurang opo to, Mbah? Sudah jauh-jauh diboyong dari Kudus, Mbah Murni tetap saja tak pernah menjadi ratu tunggal bagi Mbah Jiran.
Lebih dari itu, nenek Sony juga pebisnis yang tangguh. Pedagang serba bisa. Sama seperti kesebelas anak-anaknya, yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Tanpa harus merengek-rengek minta THR, nenek Sony yang jago masak dan bikin kue itu berjualan aneka penganan selama bulan puasa. Digelar di depan rumah. Laris sekali. Pesanan datang dari mana-mana.
Mbah Murni adalah salah satu penopang utama ekonomi keluarga besar tempat mereka semua berteduh. Bersama adik perempuannya sebagai ujung tombak, nenek Sony membuka warung nasi rawon yang enak. Sampai sekarang warung itu masih ada dan tak pernah beranak. Tetap sohor dan pelanggannya banyak. Diteruskan oleh salah seorang bibinya. Bila ada acara-acara besar di kabupaten, Pak Bupati selalu menyajikan nasi rawon bikinan bibinya itu untuk menjamu para tamu kehormatannya.
Ini rawon sungguh istimewa. Sekali makan pasti tak akan pernah lupa. Boleh dicoba. Tes rasa. Memanjakan selera. Sambil cuci mata. Biarkan lidah bergoyang lenso. Menikmati rawon yang rasanya macho. Ramuan bumbunya berbeda dari rawon biasa. Tak perlu kluweg sebagai penambah rasa. Atau pemberi warna hitam pada kuahnya. Bawang goreng juga bukan jodohnya. Tidak pula potongan-potongan kecil daging bergajih. Kuahnya yang encer berwarna kecokelatan selalu mendidih. Dengan potongan-potongan kasar daun bawang yang menyebar. Rahasianya, kuah rawon dibuat dari kaldu rebusan daging dan jeroan yang digodok semalaman di atas tungku kayu bakar. Dengan kuali besar yang terbuat dari tembikar.
Lauknya disajikan terpisah di nampan-nampan beling. Empal, paru, babat, ati, otak dan tempe digoreng setengah garing. Terkadang ada juga dendeng bikinan sendiri dan telor asin Tjap Suling. Tak lupa ditaburkan kecambah cebol di bibir piring. Tinggal pilih lauk apa yang disuka. Boleh ambil dua atau tiga. Suka-suka, silahkan saja. Tak perlu takut soal harga. Karena terhitung murah. Dijamin, dompet tak akan merekah. Seperti nasi panas yang banjir disiram kuah. Rasanya yang istimewa memijit-mijit lidah. Habis sepiring pasti ingin nambah. Apalagi ditemani krupuk udang yang renyah. Mata melek-merem mulut menganga. Merasakan keunikan sambelnya yang berwana coklat muda. Berupa kotokan tahu diiris-iris ukuran dadu unyil dan jerohan yang dirajang halus. Rasanya …, mak nyuuuus.
Tak bisa sembarang waktu menikmati nasi rawon ini. Selama bulan puasa jualan berhenti. Baru setelah beberapa hari lewat riyoyo kupatan warung dibuka kembali. Buka jam enam tutup jam sembilan pagi. Paling telat pukul sepuluh pagi. Sekalipun pembeli masih ngantri. Mereka tak bisa dilayani. Karena sudah kehabisan nasi. Jualan selama tiga jam saja. Khusus melayani orang-orang yang mau sarapan sebelum berangkat bekerja.
Ini rawon memiliki khasiat luar biasa. Bisa mengubah kebiasaan manusia. Dijamin, apabila si penikmat seorang karyawan, maka setelah sarapan nasi rawon ini akan menjadi pekerja yang kreatif dan cekatan. Dan otomatis disayang atasan. Apabila si penyantap seorang pelajar yang agak pemalas, maka setelah sarapan nasi rawon ini akan menjadi siswa yang pintar dan cerdas. Dan otomatis disayang walikelas. Sony sudah membuktikannya sendiri. Ini janji bergaransi. Kalau tak percaya, silahkan ngomel sendiri.
Aroma sedap yang berkibar-kibar dari dua piring nasi rawon yang dibawakan Usep membuyarkan lamunan Sony. “Ayo makan. Keburu dingin. Ngendal nanti.”
Seusai makan, Sony dan kakaknya berdua bermain perang-perangan dengan asap rokok, sambil mengobrol mengenai kampung halaman. Tiba-tiba saja kakaknya bercerita mengenai peliharaan barunya. Aneh, kalau soal seperti itu biasanya dia pelit bicara. Tumben-tumben, pikir Sony.
Jadi, begini ceritanya. Dia mendapatkan satu lagi piaraan dari mertuanya yang sudah pikun. Sebelum meninggal, mertua lelakinya itu berpesan agar perewangan-nya dipelihara dengan tekun. Kayak cerita sinetron di TV saja.
Tapi itulah hidup. Bahkan, kadang-kadang Sony juga berpikir bahwa hidup tak ubahnya seperti lintasan-lintasan cerita dalam sinetron. Toh, pada dasarnya sinetron mengangkat kisah dari babak-babak kehidupan manusia, meski sering kali logika berceritanya berputar-putar agar bisa dipanjang-panjangkan, semua masalah dapat terselesaikan dengan solusi yang serba kebetulan, dan tak masuk akal.
Namun, meski terkesan merendahkan kecerdasan manusia, tetap saja penontonnya tak pernah protes. Mereka hanya jengkel dan bosan bila sebuah serial terlalu memberikan ruang yang berlebihan kepada karakter antagonis. Begitu tokoh yang menyebalkan muncul dengan mimiknya yang menjijikkan, para pemirsa biasanya langsung pergi ke dapur untuk mengambil minuman atau pindah saluran. Maunya menjaring banyak iklan, eh, nggak tahunya malah panen makian. Jadinya, konyol.
Konyol? Benar. Kakak Sony yang satu ini, Slamet namanya, orangnya jujur, polos, tulus, kocak, berhati mulia, namun terkadang suka konyol. Dibandingkan dengan kakak-kakak dan adik-adiknya, dia termasuk kurang beruntung kalau dilihat dari sisi kehidupan dunia. Namun ini hanya pendapat mereka. Bisa jadi dia berpandangan sebaliknya.
Wah! Jangan-jangan ada kacamata tripleks lima mili yang selama ini memburamkan mata mereka tentang apa sebenarnya makna hidup dan kebahagiaan. Buktinya, meskipun keluarganya hidup pas-pasan, Slamet tak pernah minta-minta kepada saudara-saudaranya yang mampu. Kalaupun diberi, dia lebih sering menolak. Setelah dipaksa-paksa, baru dia tak bisa mengelak. Sony kadang jadi terharu.
Slamet. Sebenarnya nama aslinya bagus sekali. Malah jauh lebih bagus dari nama saudara-saudaranya yang lain. Apalagi Tukul. Ndak level. Jauh ke mana-mana. Hanya seujung kuku. Namun, karena semasa masih bayi sering sakit panas dan dua kali kejang-kejang alias step, dan syukurlah akhirnya sembuh jua, nenek Sony memanggilnya Slamet, yang artinya “selamat”. Karena dia selamat dan berhasil melewati masa kritisnya.
“Nama aslinya terlalu berat untuk disandang,” kata neneknya, yang sangat menyayangi Slamet itu. “Kita ganti saja namanya menjadi Slamet, agar dia selamat. Biar tidak sakit-sakit lagi,” tambahnya.
Benar. Setelah namanya diganti, dia tak pernah sakit panas lagi. Slamet. Ya, Slamet.
Slamet tumbuh menjadi anak yang kurang pintar di kelas. Berbeda sekali dengan saudara-saudaranya. Pernah sekali dia tinggal kelas ketika SD. Dia paling benci pelajaran berhitung, matematika. Matek-matekan, katanya, karena harus belajar mati-matian. “Ndak nyucuk utekku,” keluhnya. Kalaupun akhirnya naik kelas, nilainya harus dikatrol dulu.
Namun, kalau di rumah, jangan tanya. Slamet adalah anak yang luar biasa. Bersih-bersih rumah dan nyapu-nyapu paling rajin. Cuci baju dan menyetrika. Bahkan memasak. Sepertinya dia selalu bergerak lebih cepat agar tidak didahului oleh saudara-saudaranya yang lain, yang malas-malas itu. Yang, kalau disuruh, harus diteriaki berkali-kali dulu baru mau jalan.
Dengan semua keterbatasan kemampuan kognitifnya, Slamet akhirnya berhasil juga lulus STM. Dia sempat bekerja di beberapa tempat. Namun tak pernah lama. Kalau merasa benar, atasan pun akan dihardiknya. Dipecat? Tidak takut. “Allah yang kasih makan keluarga saya,” katanya suatu kali kepada Sony. Selalu begitu. Bekerja. Nganggur lagi. Bekerja. Nganggur lagi.
Pernah dia ikut kakak Sony yang pemborong bangunan. Itu pun tak lama. Bentrok melulu. “Sampeyan harus jujur. Jangan main harga,” katanya dengan suara ketus dan mata melotot.
Dengan muka masam Mas Yusa menggerutu, “Bagaimana mau untung kalau caranya begini?”
We lha, sing rukun to Mas ….
Sony pun turun tangan. Maka dia tarik kakaknya yang unik itu untuk bekerja di kantornya. Pada mulanya biasa-biasa saja. Namun, lama-kelamaan mulai beredar bisik-bisik di kalangan karyawan karena mereka sering melihat Slamet makan kemenyan. Untunglah, setelah hampir dua bulan kerja di kantor Sony di Jakarta, Slamet mengundurkan diri. Kangen sama anaknya, katanya.
Life begins at fourty. Begitulah. Slamet mulai menjadi dukun setelah mencapai umur empat puluh tahun. Beberapa tetangga menyebutnya dukun tiban. Artinya, tiba-tiba saja jadi dukun. Namun tidak demikian bagi keluarga Sony. Sebelumnya tanda-tanda itu memang sudah kelihatan. Tapi, apakah dia benar-benar dukun sakti? Sony tak begitu tahu.
Dalam kenyataannya, ada saja orang yang belum juga sembuh penyakitnya setelah berkali-kali berobat ke dokter datang menemui dia. Mulai dari penderita kencing manis, stroke, liver, kanker prostat dan lain sebagainya. Anehnya, mereka sembuh total. Dari mana mereka tahu Slamet dapat mengobati. Padahal, itu anak tidak pernah woro-woro maupun gembar-gembor seperti yang dilakukan banyak paranormal yang setiap hari beriklan di koran-koran kuning.
Saking berterima kasihnya, pasien-pasien yang merasa berhutang nyawa itu rela memberikan apa saja. Uang, barang, sembako dan lain-lain. Aneh bin ajaib, Slamet selalu marah bila diberi imbalan atas jasanya. Dia tak mau menerima pemberian apapun. Kalau si pasien ngotot mau memberikan sesuatu, bisa-bisa dia tambah sewot dan mengusirnya dengan kasar. Hanya mengamalkan ilmu. Itu saja alasannya.
Tapi pasien tak kalah pintar. Secara sembunyi-sembunyi, dan diam-diam, tentu saja tanpa harus mengendap-endap seperti maling ayam, mereka berikan imbalan itu kepada anak atau istrinya. “Tapi ini rahasia, jangan sampai ketahuan Bapak,” si pasien menyerahkan pemberiannya sambil mewanti-wanti.
“Ya, Oom. Saya ndak akan bilang sama Bapak.”
Beres sudah. Tahu-tahu gentong di dapur sudah terisi penuh dengan beras.
Kali lain datang seorang penjaja cinta yang biasa mangkal di komplek pelesiran birahi tak jauh dari rumah mertuanya di Surabaya. Perempuan kenes itu minta dijampi-jampi agar laris. Gawat. Dijampi-jampi betulan. Dan laris pula. Selang beberapa minggu kemudian datanglah rombongan teman-temannya minta dijampi-jampi juga. Maka, ramailah rumah kecil itu dengan perempuan-perempuan berbusana seronok. Duduk seenaknya sambil mengepulkan asap rokok. Sampai-sampai istri Slamet minggat dua hari karena cemburu, dan malu sama tetangga.
Tapi Slamet jalan terus, sambil tak lupa berpesan, “Kalau sudah dapat uang banyak, kamu berhenti ya. Harus tobat.”
We lha, Met … Met …. Ini kan sama saja kamu mendorong orang jadi maling asalkan kalau sudah kaya dari hasil malingnya harus berhenti, tidak jadi maling lagi. Kacau dunia.
Pada kali yang lain, Slamet dimintai tolong oleh beberapa orang rahib dari sebuah kelenteng untuk mengambil sebuah batu aneh dari di dalam mangkuk yang dipegang oleh sesosok arca. Mereka sedang membersihkan kelenteng saat itu, dan ketika akan mengelap mangkuk tersebut, mereka mendapati sebutir batu berwarna putih tua nongkrong di dalamnya.
Ini batu benar-benar bandel, tidak mau dipindahkan. Disentuh sedikit saja langsung berulah. Setiap kali seorang rahib hendak meraih batu itu, tentu saja didahului dengan bermacam-macam jurus seperti dalam filem Kung Fu, langsung terjengkang dan terlempar. Dari mulutnya keluar darah segar. Beberapa orang sudah jadi korban. Mereka kehabisan akal, dan akhirnya nyerah.
“Kalian ini apa? Ini kan hanya batu. Masa, kalah sama batu.” Ketakaburan itu mulai menampakkan wujudnya secara nyata.
Mereka diam saja disemprot seperti itu. Setelah menunjukkan tempat batu nakal tersebut bersemayam, mereka mundur mengambil jarak. Menonton dari tempat yang aman. Slamet langsung beraksi. Mulutnya komat-kamit sebentar. Kemudian batu tersebut dia ambil, dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Tidak terjadi apa-apa. Pun, ketika batu itu diminta oleh Mas Yusa. Dia berikan begitu saja.
“Mudah-mudahan cocok,” pesannya.
Ketika Sony menanyakan kepada kakak sulungnya tersebut di mana batu itu sekarang, dia malah kebingungan, tak tahu di mana. Katanya, batu mokong tersebut ditaruh di lemari dan tahu-tahu hilang begitu saja.
Saudara-saudaranya, terutama Sony, sebagai adik yang urutan kelahirannya tepat di bawah Slamet, sering menasehati agar itu ilmu dibuang saja. Tidak ada manfaatnya.
“Met, itu tipu daya jin agar kamu takabur. Supaya kamu membantu orang untuk berbuat tidak baik,” kata Mbak Rahma, kakak perempuan Sony.
Tapi, seperti biasanya, Slamet selalu ngotot, dengan mata mendelik. “Ilmu saya bersumber dari Asmaul Husna.”
Sudah capek saudara-saudaranya menasehati. Sehingga akhirnya dijadikan guyonan saja. Pernah suatu kali Sony menantangnya, “Met, kalau kamu benar-benar sakti, coba suruh jin piaraanmu menambahkan tiga angka nol pada tabungan saya di bank.” Dinasehati tidak mau, ya sudah, ditantang saja sekalian. Lumayan kan, dengan tambahan tiga angka nol, juta bisa jadi milyar. Curang bener.
Slamet menanggapi tantangan itu secara sambil lalu. “Ndak bisa kalau yang begitu. Bank juga piara jin penunggu,” kilahnya.
“Yo wis, kalau gitu,” jawab Sony.
Fadli, adik Sony, cemberut mendengar percakapan tersebut. Meski tak terucap, Sony merasa adiknya ngomong begini, “Sudahlah, nggak usah ngomongin macam-macam. Bagaimanapun, dia kakakmu. Ojo diguyu. Harus kita hormati. Sabar. Mudah-mudahan dia segera mendapatkan hidayah.” Sony jadi malu sendiri.
Tapi kadang-kadang dia tak bisa menahan diri. Keingintahuannya yang begitu besar terhadap hal-hal gaib – sama seperti curiousity banyak orang yang dicoba dipuaskan oleh stasiun-stasiun TV melalui tayangan misteri – sering kali menggelitik urat jailnya untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan penuh jebakan. Karena dijawab terus, ya dia tanya terus. Jarang-jarang kesempatan seperti ini. Hanya ada selagi pulang kampung.
Jedueeeer! Wah. Sony kuwalat. Jendela kamar depan rontok. Untung temboknya retak belaka. Tapi kaca depan mobil Sony hancur berantakan, seperti kerikil kaca. Moncongnya ringsek. Slamet keluar dari dalam mobil dan kemudian terduduk lunglai di undakan teras. Pucat pasi mukanya. Napasnya tak beraturan. Tersengal-sengal. Badannya gemetaran.
Sony merasa kasihan melihatnya. Tapi ini bukan salahnya. Ini pasti salah Fadli, adiknya itu. Malam sebelumnya, Slamet digojlok habis-habisan. “Punya SIM kok ndak berani nyetir. Apa sih susahnya nyetir. Itu ada mobil. Tinggal pilih, mau pakai yang mana.”
Seperti biasa, Sony kebagian menabur bumbu. “Gampang. SIM kamu tempel di stir pakai selotip. Langsung putar kunci starter. Ngeeeeng. Kamu diam saja. Nggak usah ngapa-ngapain. Biarkan SIM itu yang nyetir.”
Semua jadi tergelak. Sebaliknya, Slamet tersenyum kecut. Matanya melerok.
Siapa nyana, pagi itu ternyata Slamet sudah merasa siap menerima tantangan. “Endi kontake?”
Sony langsung memberikan kunci mobilnya. Mereka semua berkumpul memberikan semangat.
“Larang-larang mbayar kursus nyetir, kok tidak ada manfaatnya. Sudah. Genjot saja.”
Sreeng …. Mesin mobil langsung hidup. Slamet berkonsentrasi. Tapi, seperti biasanya, dia tak pernah fokus pada apa yang dikerjakannya. Malah asyik memperhatikan orang-orang yang sedang menontonnya. Pasang aksi.
Sony jadi ingat zaman dulu, pada waktu kecil, ketika Slamet baru bisa naik sepeda roda dua. Sambil melaju, dia melepaskan kedua tangannya dari stang sambil berteriak lantang, “Gayaee booooo …!” Perhatiannya pun teralih. Tak lagi konsen menjaga keseimbangan sepeda yang sedang dikendarai. Sebaliknya, dia malah tingak-tinguk melihat orang-orang yang sedang menyoraki. Byuuuur! Kecebur got. We lha, kojur kowe.
Kejadian lebih dari tiga puluh tahun lalu itu terulang kembali. Dengan raut muka serius dia mulai mengoper gigi. Kopling lepas, gas langsung tekan. Jedueeerr. Jendela jadi korban. Rupanya bukan gigi mundur yang dia pakai, tapi gigi maju.
“Untung jalannya ke depan, jadi nabrak jendela. Kalau atret, pasti rontok tuh pagar besi,” sempat-sempatnya dia membela diri. Namun tetap tergurat ketakutan di wajahnya.
Saudara-saudaranya cekakaan semua. Sony ketawa paling keras. Padahal mobilnya bonyok. Ya sudah. Blahi slamet. Kecelakaan, tapi tidak ada yang celaka. Orangnya aman-aman saja. Tak kurang satu apa pun. Selamat. Tumben dia bisa nyantai begini. Padahal, kalau di Jakarta, mobil baret sedikit saja bawaannya uring-uringan melulu.
Tapi, cara Slamet membela diri mengigatkannya pada cerita mengenai orang Madura yang menabrak pohon ketika belajar naik motor. Persis sama. Setelah beberapa kali masuk selokan dan membabat habis semak-semak di pinggir jalan, akhirnya dia harus berhenti karena menyeruduk pohon besar di ujung gang. Motornya hancur, tapi orangnya selamat dan masih bisa berkelakar, “Puas aku. Sudah lama aku incar ini pohon.”
Peristiwa seperti ini memberikan pencerahan luar biasa bagi Sony. Kalaupun harta benda yang paling disukai hancur atau hilang, tak masalah. Asal manusianya selamat. Barang-barang duniawi dapat dicari lagi. Bisa dibeli lagi kalau sudah kumpul duit. Tapi, kalau orang-orang tercinta celaka, bisa sedih. Makanya, sayangi badan, bukan harta.
Sungguh berbeda dengan perilaku para penghuni rumah kos putri di gang sebelah kantor Sony. Lorong sempit yang selalu tergenang air setinggi tumit setiap musim hujan itu menjadi kendala ketika gadis-gadis penghuni rumah kos itu berangkat kerja di pagi hari maupun sepulang kerja di sore hari. Tapi mereka punya cara jitu mengatasinya. Cukup lepas sepatu dan kemudian ditenteng. Kaki-kaki mulus itu pun berjalan nyeker menyaruk-nyaruk genangan air yang tak begitu dalam.
Perhitungannya pasti begini. Kalau sepatu tetap dipakai, pasti langsung hancur. Bisa mlenyok, kisut, njeber, mangap dan rontok. Juga bau. Sekalipun bikinan Prada. Tentu biaya reparasinya mahal. Terlebih kalau harus beli lagi. Tapi, kalau hanya ibujari kaki sedikit berdarah karena tergores kerikil tajam, cukup diolesi Betadine. Besok-besok pasti juga sembuh. Berapa sih, harga Betadine? Mereka belum mendapatkan pencerahan.
Pengalaman serupa pernah dialami Fadli ketika rumahnya disatroni perampok pada malam hari. Dua mobil dan satu motor dibawa lari. Anehnya, tak satupun penghuni rumah yang terjaga. Padahal salah seorang perampok sempat kentut di dalam rumah. Buktinya, si Herman, kucing peliharaan mereka, tak ada di sekitar situ. Kucing berwarna oranye itu selalu lari ketakutan kalau ada orang yang kentut dengan suara menggelegar.
Tetangga bilang perampoknya pakai aji sirep. Bisa jadi jampi-jampi itu didapat dari dukun yang amat sakti sehingga tetangga sekitar ikut terkena pengaruhnya. Dengan deretan rumah yang begitu rapat, masa tidak ada seorang pun yang nglilir mendengar suara hiruk-pikuk para pencoleng yang sedang mencongkel jendela sambil guyon dengan saling melempar pantun berbalas, membongkar pintu garasi dan pagar, dan kemudian membawa lari hasil jarahannya.
Tentu sedih sekali kalau harus kehilangan sesuatu yang berharga. Sony tak tega melihat adiknya segundah itu. Fadli hanya terduduk pasrah. Matanya berkaca-kaca. Apalagi, di bagasi mobil ada seperangkat peralatan golf kesayangannya, yang belum sempat diturunkan oleh supirnya.
Tapi seorang polisi kerempeng dengan bijak membesarkan hatinya. “Sudahlah, Pak. Ini musibah. Kita akan bantu cari. Yang penting semua selamat,” hibur Pak Rohan yang asli Cimahi itu dengan suaranya yang lembut.
Benar. Untung tidak ada yang bangun. Polisi menduga jumlah mereka lebih dari empat orang. Minimal bawa sepucuk senjata api. Belum lagi golok dan belati. Kalau sampai ada yang bangun, pasti langsung di-dor. Bisa cilaka. Sudahlah. Toh, semuanya sudah di-cover asuransi. Tak perlu terlalu bersedih. Ini blahi slamet. Malahan, harusnya bersyukur. Kalau perlu bikin selamatan.
Jadi, meskipun mobilnya bonyok, Sony tetap merasa bersyukur karena kakak kesayangannya itu tidak apa-apa. Tidak celaka. Namun adegan French kiss yang mesra lagi bergelora antara mobil dan jendela tersebut rupanya menimbulkan penyesalan yang amat dalam pada diri Slamet. Dia merasa sangat bersalah. Dan amat gundah. Merasa telah merepotkan adiknya. Berkali-kali Sony harus meyakinkan kakaknya bahwa itu bukan masalah besar.
“Berapa sih, mbetulin mobil? Paling cuma segitu. Kalau uang segitu, sekali kedip langsung dapat.” Kadang-kadang Sony dihinggapi penyakit sombong seperti ini.
Slamet jadi agak pendiam. Malam hari dia hanya duduk sendirian di sudut teras sambli lengar-lenger. Bersila. Kepalanya menunduk. Kedua genggaman tangannya menyatu menahan dahinya yang tidak terlalu lebar. Matanya menerawang. Wah, gawat ini. Segera saja saudara-saudaranya beramai-ramai menghampirinya.
“Met, nggak usah dipikirin terus. Mobil kan sudah dibetulin. Sudahlah.” Mereka mencoba menghiburnya.
“Tapi aku sudah merugikan kamu, Son. Rugi! Rugi! Rugi!”
Semua jadi terdiam.
“Sekarang begini saja ….”
Dia pun mulai memaparkan rencananya. Singkatnya begini. Supaya pakpok alias impas, Slamet bersedia memenuhi permintaan Sony yang kemarin. Dia akan suruh Salim dan Rejeb, dua jin peliharaannya itu, minta tolong kepada teman-temannya sesama jin yang ngerti soal bank supaya bisa menambahkan tiga angka nol pada tabungan Sony di bank. Gila. Dimakan juga itu umpan.
“Mana nomer bank?”
Dengan cekatan Sony segera menuliskan nomor rekening di atas secarik kertas. ATM juga ikut berpindah tangan. “Nih. Jangan sampai keliru. Meleset satu angka bisa masuk ke rekening orang lain itu duit,” Sony mencoba mewanti-wanti.
“Beres. Tengah malam nanti saya olah. Kamu tunggu tiga hari. Besok kan kamu balik ke Jakarta, sesampainya di sana bisa langsung dicek,” jawabnya dengan penuh percaya diri.
Sony mengiyakan dengan anggukan serius. Tapi Mbak Rahma malah senyam-senyum. Dengan setengah berbisik dia meledek Sony, “Kalau benar ketambahan tiga angka nol, kamu nyamleng. Bagaimana bila Salim dan Rejeb bingung, sehingga bukannya menambahkan tapi malah mengurangi tiga angka nol? Bisa nangis kamu.”
Sony jadi gamang. Mbuh wis. Ndak usah dipikir. Ini semua kan cuma guyon. Lupakan.
Tapi, anehnya, setiap kali pergi ke ATM, jantung Sony selalu berdebar-debar kencang. Tangannya suka gemetaran. Berharap-harap kalau-kalau sudah ada tambahan tiga angka nol di tabungannya. Setiap kali selalu begitu. Tapi, tak pernah sekalipun ada tambahan tiga angka nol yang mau mampir.
Be’e, wis gendeng … aku iki, pikirnya. Sony benar-benar merasa tersika dipermainkan oleh harapan-harapan yang melambung tapi tidak pernah kesampaian tersebut. Lama-lama dia tak tahan juga menanggung beban yang sangat berat itu, sehingga akhirnya bercerita kepada beberapa orang kawannya. Bukannya menghibur, mereka malah pada ketawa ngakak. Sialan. Sony pun jadi ikutan ngekek. Wis …, gendeng kabeh. Nasib. Nasib.
Akhirnya, dengan sedikit ragu, Sony memberanikan diri menelepon kakaknya untuk menanyakan soal itu.
Jawabannya enteng saja. “Ndak berhasil, Son. Sudah saya coba. Kata Salim dan Rejeb, permintaan seperti itu dapat mengganggu perjanjian antara raja jin dengan manusia.”
Sony agak kecewa.
Tapi buru-buru Slamet menyambung omongannya, “Son, saya jadi ndak enak sama kamu. Kalau kamu pulang nanti saya akan kasih sesuatu sebagai gantinya. Atau saya saja yang pergi ke Jakarta, Son?”
Pada mulanya Sony tidak terlalu berminat menanggapi omongan kakaknya. Tiba-tiba saja, tak ada angin tak ada hujan, Sony begitu antusias menanyakan apa gerangan hadiah yang akan diberikan kepadanya. “Apaan, Met? Jum’at besok saya ada acara ke Surabaya. Sekalian saja, saya mampir ke sana. Sampeyan tidak ke mana-mana, kan?”
Sabtu pagi. Di samping rumah Sony, di kampung halaman. Slamet memasukkan dua butir kemenyan, kira-kira seukuran jagung, ke dalam mulutnya. Dia kunyah-kunyah. Setelah komat-kamit sebentar, tiba-tiba dia merentangkan kedua tangannya sambil menggerang. Persis seperti auman seekor macan. Dia berjalan menuju tembok pagar. Pless. Slamet menembus tembok itu. Dan lenyap begitu saja.
Sony ketakutan. Dia merasa bergidik. Ini sama sekali bukan tipuan. Bukan pula trick kamera. Sony langsung melangkahkan kakinya menuju tembok tersebut. Dia raba-raba tembok itu. Keras. Tidak ada pintunya. Dia mencoba memasukkan tangannya ke dalam tembok. Tidak berhasil. Malah tangannya terasa sakit. Karena tembok itu agak kasar.
Heran dia. Bagaimana mungkin Slamet masuk ke dalam tembok. Kali ini Sony mencoba dengan cara lain. Mencontoh cara yang dilakukan kakaknya tadi. Diambilnya sebutir kemenyan dan kemudian dia kunyah. Rasanya aneh. Pahit. Sambil mengaum, direntangkannya kedua tangannya. Dia berjalan menuju tembok itu. Bukannya tembus. Jidatnya malah kebentur tembok. Sakit sekali.
“Ngapain kamu, Son?”
Semakin kaget saja dia. Slamet ternyata sudah berdiri di belakangnya. “Dari mana kamu?” tanyanya dengan terbata-bata. Belum hilang rasa takutnya.
“Lha, tadi saya keluar dari sebelah kiri kamu. Masa tidak lihat?” jawabnya.
Kemudian Slamet bercerita kepada Sony. Tembok itu adalah pintu gerbang kerajaan jin. Di balik tembok tersebut, terhampar dunia lain. Bukan dunia manusia. Tapi dunia jin, dengan semua aktivitasnya. Mundari, penunggu pintu gerbang tersebut, mengizinkan Slamet masuk.
“Ini, saya bawakan oleh-oleh dari sana.” Slamet memberikan dua butir batu kepada Sony.
Tak terlalu istimewa batu itu. Masing-masing sebesar kelereng, lebih kecil sedikit. Warnanya hitam mengkilat. Tapi terasa agak berat bila dibandingkan dengan ukurannya. Lebih aneh lagi, kedua batu tersebut selalu menempel satu sama lain. Seperti ada magnetnya.
“Met, bisa nggak saya ikut kamu masuk ke sana. Saya ingin tahu kayak apa di sana,” Sony mulai merengek-rengek. Sudah lama dia ingin melihat jin. Apalagi, ini kerajaan. Pasti seru.
Slamet diam saja. Tapi kemudian dia menyanggupi. Mungkin tak tahan melihat adiknya mengiba-iba seperti itu. “Begini saja. Besok, saya akan coba bawa kamu masuk ke sana. Tapi saya tidak janji. Bisa berhasil. Bisa juga tidak. Semuanya tergantung kamu sendiri. Kalau kamu bisa membuang semua pikiranmu hingga otakmu benar-benar kosong, kamu pasti bisa melewati tembok itu.”
Girang sekali Sony mendapatkan jawaban seperti itu. Siang harinya dia langsung belanja peralatan. Dibelinya segulung tambang ukuran satu inci yang panjangnya sekitar lima puluh meter. Juga sebuah troli dorong.
Pagi itu semuanya sudah siap. Sony berdiri di depan tembok. Mengamat-ngamati pagar setinggi dua setengah meter tersebut. Keras, dan bisu. Sementara Slamet masih sarapan. Sony menunggunya, sambil sesekali berteriak memanggilnya. Sudah tak sabar lagi dia. Akhirnya Slamet muncul juga.
“Son, ngapain kamu bawa beginian. Kapan belinya? Memangnya mau bikin apa?” tanya Slamet.
Sony tidak menjawab. Malu rasanya. Tapi akhirnya dia berterus-terang kepada kakaknya. Sony membeberkan rencananya. Tambang itu akan dia ikatkan ke badannya, sedangkan ujung yang satunya lagi akan ditambatkan pada pohon melinjo tak jauh dari tempat itu. Hanya jaga-jaga, kalau-kalau dia tersesat di dunia jin. Dengan bantuan tambang tersebut, dia akan lebih mudah mencari jalan keluar. Sedangkan troli, sengaja disiapkan kalau-kalau di sana nanti dia menemukan emas. Bisa mengambil sebanyak-banyaknya. Jadi tak perlu repot-repot menentengnya.
Slamet akhirnya mengalah. “Ya sudah. Kalau maunya begitu. Silahkan,” katanya.
Mereka pun melakukan persiapan.
“Son, kamu ikuti semua yang saya lakukan. Ingat, buang semua isi pikiranmu. Harus kosong melompong,” pesannya.
Slamet mulai mengunyah kemenyan. Sony segera mengambil remahan-remahan berwarna kecoklatan itu dan kemudian memasukkan ke dalam mulutnya. Dia kunyah. Ketika Slamet mengaum, Sony pun ikut mengaum. Slamet langsung merentangkan kedua tangannya dan berjalan menuju tembok. Sony mengekor di belakangnya sambil mendorong troli, sementara badannya terikat pada seutas tambang.
Slamet hilang ditelan tembok. Sony langsung mengikutinya. Tapi langkahnya tertahan oleh kereta dorong yang menabrak tembok keras. Dia dorong dengan sekuat tenaga troli beroda satu itu. Tapi tak juga mampu menembus tembok. Dirabanya tembok itu. Kasar, seperti biasanya. Sialan. Gagal, pikirnya. Kecewa sekali dia. Sony mencampakkan kereta dorong baru itu dan melepaskan ikatan tambang di badannya. Duduk di tanah.
Setelah sekitar lima menit, Slamet muncul dari balik tembok. Dia tersenyum kecil melihat Sony duduk lesu di tanah, tanpa alas. “Son, kamu belum bisa. Pikiranmu terlalu banyak isinya,” katanya, dengan badan sedikit dibungkukkan. “Sudahlah. Yang penting, kamu sudah saya bawakan oleh-oleh dari sana kemarin. Masih ada, kan?” tambahnya, seolah hendak menghibur Sony.
Dalam hati, Sony membenarkan ucapan kakaknya. Dia memang tidak mampu mengosongkan pikirannya. Terlalu banyak rencana yang berkecamuk di dalam benaknya. Termasuk angan-angannya untuk membawa emas hingga setroli penuh. Dia juga meludahkan kemenyan yang dikunyahnya, karena pahit. Pada waktu mengaum, dia juga tidak sungguh-sungguh. Hanya menirukan apa yang dilakukan kakaknya.
“Met, memangnya ini batu apaan?” tanya Sony sambil menimang-nimang kedua butir batu hitam itu di telapak tangannya.
Slamet diam saja. Dia malah mengambil kedua batu itu dari telapak tangan Sony. Kemudian dia lemparkan salah satu batu tersebut ke kiri dan satunya lagi ke kanan. Ajaib, kedua batu itu berjalan menggelinding menuju telapak tangan Slamet di tanah dan kemudian saling menempel lagi. “Ini batu pengasihan. Pelet,” katanya singkat.
Sony jadi bingung. Tak paham. Untuk apa kakaknya itu memberinya aji pelet. Supaya nyeleweng, kali. Berselingkuh. Wah, itu bukan tabiatnya. Kecuali, kalau terpaksa. “Met, kok sampeyan kasih aku barang beginian?” Sony bertanya dengan setengah ketawa.
“Dapatnya itu, Son. Ya, itu yang saya kasih ke kamu. Kalau tak mau tidak apa-apa. Saya kembalikan saja.”
Akal Sony langsung berputar. Dia ambil kedua batu itu dari tangan kakaknya dan kemudian dimasukkannya ke dalam saku celana. Suatu saat nanti, kedua batu itu pasti ada gunanya.
Eureka. Jum’at kemarin, di Surabaya, dia bertemu dengan seorang klien wanita yang sangat ketus dan cenderung melecehkannya. Semua omongan Sony selalu dimentahkannya. Pendeknya, tidak ada yang beres di mata wanita beraroma wangi itu. Sebelumnya, dia memang sudah diberi tahu akan bertemu dengan Bu Narti, seorang perawan tua, tapi posisinya sangat menentukan di dalam perusahaan.
Sekarang Sony sudah bisa tersenyum. Ancang-ancang langsung disusun. Besok Senin, sebelum balik ke Jakarta, akan dia temui sekali lagi ratu cerewet itu. Akan dia pelet. Akan dia pacari. Biar dikasih banyak proyek besar. Toh, Bu Narti, sebenarnya, lumayan menarik. Kulitnya putih bersih. Hidungnya mancung. Perawakannya juga mbodi. Lumayan tinggi untuk ukuran wanita Indonesia. Hanya saja, mulutnya suka tidak terkontrol kalau sedang berbicara. Judes.
“Son, kamu kan pemasar. Ngapain main dukun?”
Suara dari alam bawah sadar itu mengingatkan Sony. Awalnya terdengar sayup-sayup. Tapi kemudian semakin keras. Berulang-ulang. Benar. Gengsi rasanya kalau seorang pemasar harus menghancurkan sebongkah cadas dengan bantuan dukun.
“Met, kamu berikan saja batu pelet ini sama orang yang belum laku. Biar dia cepat kawin. Ada teman saya di Surabaya, perawan tua. Tolong bantu dia. Supaya cepat dapat jodoh,” kata Sony, sambil menuliskan nomor HP Bu Narti.
Sony tertegun. Benar. Baru saja Sugiono, messenger-nya, dengan wajah memelas, pakai menitikkan air mata pula, mengajukan kasbon. Ada masalah keluarga, katanya. Anak lelakinya masuk sel karena mbacok orang. Untung tidak sampai mati. Harus ditebus dan mengganti biaya rumah sakit.
Sony jadi keheranan. Dari mana kakaknya tahu? Padahal, pembicaraan tadi terjadi di ruang kerjanya yang tertutup. Lagian, tidak mungkin dia membiarkan karyawan lain melihat Sugiono, bapak empat anak yang asli Balaraja, Tangerang itu, menangis tersedu-sedu. Tentu tak etis membiarkan hal seperti itu menjadi tontotan orang. Sekalipun itu kakaknya sendiri.
Sony memang gampang jatuh iba bila berhadapan dengan orang yang menangis. Kalau dibilang cengeng, sebenarnya tidak juga. Hanya saja, dia suka tak tahan bila melihat orang menitikkan air mata. Nonton sinetron juga begitu, tiba-tiba saja matanya sembab ketika terbawa oleh adegan yang mengharukan. Sehingga harus ngumpet-ngumpet mengelap air mata dengan lengan bajunya, agar tak ketahuan istri dan anak-anaknya.
Pernah sekali dia akan memecat seorang karyawan karena melakukan kesalahan fatal. Tapi karena Sandy, si Belanda Depok, sekretarisnya itu, terus menangis dan berjanji tak akan mengulangi kesalahannya, akhirnya tidak jadi dia keluarkan. Tak tega rasanya. Begitu pula, ketika Sugiono menangis kebingungan karena tak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalah anaknya, kena lagi dia.
“Berapa?”
“Lima juta, Pak.”
Wah, bagaimana ini. Minggu kemarin Sugiono baru saja kasbon lima juta, anak perempuannya mau masuk sekolah perawat, katanya. Sony meluluskan permintaan itu, karena demi pendidikan anak. Sisa hutang dari kasbon lama langsung dipotong dari kasbon baru. Tapi, sekarang lain lagi soalnya. Aturannya, dia tidak boleh kasbon sebelum kasbon pertama lunas. Peraturan is peraturan. Tidak boleh dilanggar. Tapi ini soal kayaknya sangat gawat. Akhirnya, karena tak tahan dan kasihan, Sony mengambil duit di laci yang sedianya akan dipakai untuk bayar tagihan kartu kredit.
“Ini, saya cuma punya empat juta. Selesaikan baik-baik itu masalah. Dan kalau sampai di rumah, anakmu dicambukin saja sampai ampun-ampun. Biar nggak sembarangan bacok orang,” kata Sony sambil memberikan amplop coklat berisi uang.
“Jangan ngomong sembarangan. Dari mana kamu tahu ada orang jampi-jampi saya?” tanya Sony kepada kakaknya yang sedang asyik bermain-main dengan asap rokoknya.
“Saya tahu,” jawabnya singkat, sambil mencetak empat lingkaran asap yang berbaris lurus. Dia tidak sedikitpun memperhatikan Sony yang tampak jengkel. Malahan, dia kembali asyik membuat lingkaran-lingkaran asap gandeng yang menyerupai logo Audi.
Tapi Sony tak mau kalah. Dia merasa sangat tidak nyaman ditembak seperti itu. Mangkel, seolah dianggap sebagai orang yang lemah. Karena itu, Sony terus membantah omongan kakaknya. Bahkan dengan sesumbar, “Saya tak mempan dijampi-jampi. Dan karyawan saya tidak ada yang suka pergi ke dukun.”
“Sekarang begini saja, Son. Kamu mau enggak saya beri pegangan? Untuk pagar diri, biar tak mempan dijampi-jampi,” katanya sambil mengulurkan sebuah lipatan kecil kertas putih.
Sony diam saja. Masih kesal dia, karena kakaknya tidak menjawab pertanyaannya. Eh, sekarang, kakaknya itu, malah menawarkan ajimat lagi. Lagian, Sony sama sekali tidak percaya dengan yang begituan. Hanya saja, dia selalu mempunyai kertarikan yang kadang agak berlebihan terhadap hal-hal gaib. Diam-diam dia lirik lipatan kertas itu. Dia penasaran sekali mengenai apa yang ada di dalam bungkusan tersebut.
“Apa ini?” tanyanya sambil tak sabar membuka lipatan kertas tersebut. Tapi Sony agak kecewa, karena hanya mendapati dua helai rambut keriting seukuran tusuk gigi. Warnanya cokelat kehitaman dan besar-besar. Seperti kumis kerbau. Kasar. Kayaknya tidak pernah kenal shampoo.
“Ini bulu gendoruwoh,” sahut kakaknya dengan suara agak pelan. “Ada penunggunya, Bejo dan Beji,” tambahnya lagi sambil menjumput kedua helai rambut gedoruwoh itu. “Mau bukti, kamu?” katanya, seolah menantang Sony.
Ditantang seperti itu, Sony langsung bereaksi. “Ayo. Siapa takut?” jawabnya dengan nada menantang balik.
Kakaknya segera mengangkat cangkir kopi dari cawan yang mengalasinya. Kemudian dia tuangkan air putih dari gelas minum Sony ke dalam cawan hijau itu. Setelah air mulai tenang, dia masukkan kedua helai bulu gendoruwoh tersebut ke dalamnya. Ajaib. Bulu-bulu kasar itu langsung berjoget seperti cacing kepanasan. Ngulet. Meluruskan diri, seolah sedang meregangkan punggungnya yang pegal. Begerak kesana-kemari seperti perenang profesional.
“Hebat. Dapat dari mana kamu?” tanya Sony.
Kemudian dia bercerita. Bulu gendoruwoh itu dia dapatkan tanpa sengaja. Ketika sedang sholat malam di Masjid Jami’ di kampung halaman sana, dia merasa seperti ada tangan-tangan yang sangat besar mengganggu konsentrasinya. Tangan-tangan raksasa itu bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan secara tak beraturan dan berusaha menyentuhnya. Karena merasa sangat terganggu, maka dikibaskanlah tangan kanannya untuk mengusir tangan-tangan jail tersebut. Gangguan itu langsung hilang. Dia melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat barulah dia sadar kalau di telapak tangan kanannya telah menempel dua helai bulu yang besar-besar itu. Rupanya, kibasan tangannya tadi telah merontokkan bulu tangan gendoruwoh yang mengganggunya.
Kakak Sony yang satu ini memang seorang dukun. Namun demikian, sholatnya tekun. Tak pernah telat, malah suka lebih. Ke mana-mana bawa tasbih. Baju koko jadi kostum harian. Dengan kopyah putih yang agak kebesaran. Tak sedikit pun terkesan bahwa dia seorang dukun. Dan lagi, pada dasarnya dia juga tak suka disebut dukun. “Hanya mengamalkan ilmu,” katanya.
Sony sendiri tak tahu sejak kapan kakaknya punya ilmu. Setahu dia, tak seorang pun kerabatnya yang menjadi dukun. Jadi, dari mana dia mendapatkan ilmu? Sony sering menanyakan hal itu. Tapi tak pernah dijawab. Setelah dia desak terus, empat tahun lalu, akhirnya kakaknya buka kartu.
“Itu piaraan Mbah Jiran yang ngintil terus dan kemudian saya rawat,” katanya dengan setengah terpaksa. “Sebelumnya, macan putih itu sempat menunggu mushola di samping kanan rumah selama hampir tiga puluh tahun,” tambahnya lagi.
Mbah Jiran, kakek Sony, memang orang hebat. Seorang haji yang sholatnya tak pernah telat. Suka menolong orang yang lagi kesrakat. Seorang petinggi yang dicintai masyarakat. Makanya, ketika meninggal banyak sekali yang melayat. Tetangga dan kenalan beramai-ramai mengantarnya ke tempat beristirahat.
Sony sendiri tidak terlalu paham dengan semua keramaian itu. Karena masih SD kelas satu. Terselip di antara para pelayat ada sejumlah ibu-ibu. Dan orang-orang yang tak dikenalnya berwajah biru. Tatapan mata mereka beku. Mereka menangis tersedu-sedu. Belakangan, setelah sepuluh tahun berlalu, barulah Sony tahu. Mereka ternyata istri-istri dan anak-anak kakeknya yang datang dari segala penjuru.
Jadi, begini ceritanya. Mbah Jiran semasa mudanya berprofesi sebagai saudagar tembakau yang sukses. Setiap saat bepergian ke daerah-daerah di mana petani menanam daun beraroma harum itu. Lembaran-lembaran daun tembakau yang lebar-lebar diborong dan disimpan di dalam keranjang-keranjang berbungkus tikar di rumahnya yang sangat besar.
Sebuah rumah bergaya kolonial dengan langit-langit tinggi dan penuh selasar. Ubinnya menghampar indah dengan tegel-tegel bergambar. Dengan tiang-tiang yang begitu kokoh dan kekar. Dengan banyak daun pintu dan jendela dua lapis yang lebar-lebar. Terasnya beratap seng gelombang tebal berlembar-lembar. Di rumah itulah tembakau dikumpulkan. Di sebuah gudang persis di sebelah kamar mandi. Setelah jumlahnya mencukupi, tembakau kemudian dijual ke pabrik rokok di Kudus, Jawa Tengah.
Rupanya kakek Sony yang keturunan Madura itu termasuk penganut filosofi bekerja sambil berkarya. “Business is pleasure,” mungkin nasehat seperti itu yang akan diberikannya kepada Sony seandainya sekarang masih hidup. Karena Mbah Jiran sangat dekat dengan Sony, dan cenderung memanjakannya, seperti bapaknya.
Di tempat-tempat yang biasa didatanginya, Mbah Jiran selalu menyempatkan diri menyunting dara. Duit banyak. Semangat meledak-ledak. Badan perkasa. Malam-malam sendirian di desa. Daripada susah tidur, lebih baik mengasah sangkur. Pulangnya diulur-ulur.
“Ada apa ini?” Padahal, di rumah, nenek Sony ayu benar. Kulitnya bersih bersinar. Hidungnya mancung dan tipis. Senyumnya manis. Kurang opo to, Mbah? Sudah jauh-jauh diboyong dari Kudus, Mbah Murni tetap saja tak pernah menjadi ratu tunggal bagi Mbah Jiran.
Lebih dari itu, nenek Sony juga pebisnis yang tangguh. Pedagang serba bisa. Sama seperti kesebelas anak-anaknya, yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Tanpa harus merengek-rengek minta THR, nenek Sony yang jago masak dan bikin kue itu berjualan aneka penganan selama bulan puasa. Digelar di depan rumah. Laris sekali. Pesanan datang dari mana-mana.
Mbah Murni adalah salah satu penopang utama ekonomi keluarga besar tempat mereka semua berteduh. Bersama adik perempuannya sebagai ujung tombak, nenek Sony membuka warung nasi rawon yang enak. Sampai sekarang warung itu masih ada dan tak pernah beranak. Tetap sohor dan pelanggannya banyak. Diteruskan oleh salah seorang bibinya. Bila ada acara-acara besar di kabupaten, Pak Bupati selalu menyajikan nasi rawon bikinan bibinya itu untuk menjamu para tamu kehormatannya.
Ini rawon sungguh istimewa. Sekali makan pasti tak akan pernah lupa. Boleh dicoba. Tes rasa. Memanjakan selera. Sambil cuci mata. Biarkan lidah bergoyang lenso. Menikmati rawon yang rasanya macho. Ramuan bumbunya berbeda dari rawon biasa. Tak perlu kluweg sebagai penambah rasa. Atau pemberi warna hitam pada kuahnya. Bawang goreng juga bukan jodohnya. Tidak pula potongan-potongan kecil daging bergajih. Kuahnya yang encer berwarna kecokelatan selalu mendidih. Dengan potongan-potongan kasar daun bawang yang menyebar. Rahasianya, kuah rawon dibuat dari kaldu rebusan daging dan jeroan yang digodok semalaman di atas tungku kayu bakar. Dengan kuali besar yang terbuat dari tembikar.
Lauknya disajikan terpisah di nampan-nampan beling. Empal, paru, babat, ati, otak dan tempe digoreng setengah garing. Terkadang ada juga dendeng bikinan sendiri dan telor asin Tjap Suling. Tak lupa ditaburkan kecambah cebol di bibir piring. Tinggal pilih lauk apa yang disuka. Boleh ambil dua atau tiga. Suka-suka, silahkan saja. Tak perlu takut soal harga. Karena terhitung murah. Dijamin, dompet tak akan merekah. Seperti nasi panas yang banjir disiram kuah. Rasanya yang istimewa memijit-mijit lidah. Habis sepiring pasti ingin nambah. Apalagi ditemani krupuk udang yang renyah. Mata melek-merem mulut menganga. Merasakan keunikan sambelnya yang berwana coklat muda. Berupa kotokan tahu diiris-iris ukuran dadu unyil dan jerohan yang dirajang halus. Rasanya …, mak nyuuuus.
Tak bisa sembarang waktu menikmati nasi rawon ini. Selama bulan puasa jualan berhenti. Baru setelah beberapa hari lewat riyoyo kupatan warung dibuka kembali. Buka jam enam tutup jam sembilan pagi. Paling telat pukul sepuluh pagi. Sekalipun pembeli masih ngantri. Mereka tak bisa dilayani. Karena sudah kehabisan nasi. Jualan selama tiga jam saja. Khusus melayani orang-orang yang mau sarapan sebelum berangkat bekerja.
Ini rawon memiliki khasiat luar biasa. Bisa mengubah kebiasaan manusia. Dijamin, apabila si penikmat seorang karyawan, maka setelah sarapan nasi rawon ini akan menjadi pekerja yang kreatif dan cekatan. Dan otomatis disayang atasan. Apabila si penyantap seorang pelajar yang agak pemalas, maka setelah sarapan nasi rawon ini akan menjadi siswa yang pintar dan cerdas. Dan otomatis disayang walikelas. Sony sudah membuktikannya sendiri. Ini janji bergaransi. Kalau tak percaya, silahkan ngomel sendiri.
Aroma sedap yang berkibar-kibar dari dua piring nasi rawon yang dibawakan Usep membuyarkan lamunan Sony. “Ayo makan. Keburu dingin. Ngendal nanti.”
Seusai makan, Sony dan kakaknya berdua bermain perang-perangan dengan asap rokok, sambil mengobrol mengenai kampung halaman. Tiba-tiba saja kakaknya bercerita mengenai peliharaan barunya. Aneh, kalau soal seperti itu biasanya dia pelit bicara. Tumben-tumben, pikir Sony.
Jadi, begini ceritanya. Dia mendapatkan satu lagi piaraan dari mertuanya yang sudah pikun. Sebelum meninggal, mertua lelakinya itu berpesan agar perewangan-nya dipelihara dengan tekun. Kayak cerita sinetron di TV saja.
Tapi itulah hidup. Bahkan, kadang-kadang Sony juga berpikir bahwa hidup tak ubahnya seperti lintasan-lintasan cerita dalam sinetron. Toh, pada dasarnya sinetron mengangkat kisah dari babak-babak kehidupan manusia, meski sering kali logika berceritanya berputar-putar agar bisa dipanjang-panjangkan, semua masalah dapat terselesaikan dengan solusi yang serba kebetulan, dan tak masuk akal.
Namun, meski terkesan merendahkan kecerdasan manusia, tetap saja penontonnya tak pernah protes. Mereka hanya jengkel dan bosan bila sebuah serial terlalu memberikan ruang yang berlebihan kepada karakter antagonis. Begitu tokoh yang menyebalkan muncul dengan mimiknya yang menjijikkan, para pemirsa biasanya langsung pergi ke dapur untuk mengambil minuman atau pindah saluran. Maunya menjaring banyak iklan, eh, nggak tahunya malah panen makian. Jadinya, konyol.
Konyol? Benar. Kakak Sony yang satu ini, Slamet namanya, orangnya jujur, polos, tulus, kocak, berhati mulia, namun terkadang suka konyol. Dibandingkan dengan kakak-kakak dan adik-adiknya, dia termasuk kurang beruntung kalau dilihat dari sisi kehidupan dunia. Namun ini hanya pendapat mereka. Bisa jadi dia berpandangan sebaliknya.
Wah! Jangan-jangan ada kacamata tripleks lima mili yang selama ini memburamkan mata mereka tentang apa sebenarnya makna hidup dan kebahagiaan. Buktinya, meskipun keluarganya hidup pas-pasan, Slamet tak pernah minta-minta kepada saudara-saudaranya yang mampu. Kalaupun diberi, dia lebih sering menolak. Setelah dipaksa-paksa, baru dia tak bisa mengelak. Sony kadang jadi terharu.
Slamet. Sebenarnya nama aslinya bagus sekali. Malah jauh lebih bagus dari nama saudara-saudaranya yang lain. Apalagi Tukul. Ndak level. Jauh ke mana-mana. Hanya seujung kuku. Namun, karena semasa masih bayi sering sakit panas dan dua kali kejang-kejang alias step, dan syukurlah akhirnya sembuh jua, nenek Sony memanggilnya Slamet, yang artinya “selamat”. Karena dia selamat dan berhasil melewati masa kritisnya.
“Nama aslinya terlalu berat untuk disandang,” kata neneknya, yang sangat menyayangi Slamet itu. “Kita ganti saja namanya menjadi Slamet, agar dia selamat. Biar tidak sakit-sakit lagi,” tambahnya.
Benar. Setelah namanya diganti, dia tak pernah sakit panas lagi. Slamet. Ya, Slamet.
Slamet tumbuh menjadi anak yang kurang pintar di kelas. Berbeda sekali dengan saudara-saudaranya. Pernah sekali dia tinggal kelas ketika SD. Dia paling benci pelajaran berhitung, matematika. Matek-matekan, katanya, karena harus belajar mati-matian. “Ndak nyucuk utekku,” keluhnya. Kalaupun akhirnya naik kelas, nilainya harus dikatrol dulu.
Namun, kalau di rumah, jangan tanya. Slamet adalah anak yang luar biasa. Bersih-bersih rumah dan nyapu-nyapu paling rajin. Cuci baju dan menyetrika. Bahkan memasak. Sepertinya dia selalu bergerak lebih cepat agar tidak didahului oleh saudara-saudaranya yang lain, yang malas-malas itu. Yang, kalau disuruh, harus diteriaki berkali-kali dulu baru mau jalan.
Dengan semua keterbatasan kemampuan kognitifnya, Slamet akhirnya berhasil juga lulus STM. Dia sempat bekerja di beberapa tempat. Namun tak pernah lama. Kalau merasa benar, atasan pun akan dihardiknya. Dipecat? Tidak takut. “Allah yang kasih makan keluarga saya,” katanya suatu kali kepada Sony. Selalu begitu. Bekerja. Nganggur lagi. Bekerja. Nganggur lagi.
Pernah dia ikut kakak Sony yang pemborong bangunan. Itu pun tak lama. Bentrok melulu. “Sampeyan harus jujur. Jangan main harga,” katanya dengan suara ketus dan mata melotot.
Dengan muka masam Mas Yusa menggerutu, “Bagaimana mau untung kalau caranya begini?”
We lha, sing rukun to Mas ….
Sony pun turun tangan. Maka dia tarik kakaknya yang unik itu untuk bekerja di kantornya. Pada mulanya biasa-biasa saja. Namun, lama-kelamaan mulai beredar bisik-bisik di kalangan karyawan karena mereka sering melihat Slamet makan kemenyan. Untunglah, setelah hampir dua bulan kerja di kantor Sony di Jakarta, Slamet mengundurkan diri. Kangen sama anaknya, katanya.
Life begins at fourty. Begitulah. Slamet mulai menjadi dukun setelah mencapai umur empat puluh tahun. Beberapa tetangga menyebutnya dukun tiban. Artinya, tiba-tiba saja jadi dukun. Namun tidak demikian bagi keluarga Sony. Sebelumnya tanda-tanda itu memang sudah kelihatan. Tapi, apakah dia benar-benar dukun sakti? Sony tak begitu tahu.
Dalam kenyataannya, ada saja orang yang belum juga sembuh penyakitnya setelah berkali-kali berobat ke dokter datang menemui dia. Mulai dari penderita kencing manis, stroke, liver, kanker prostat dan lain sebagainya. Anehnya, mereka sembuh total. Dari mana mereka tahu Slamet dapat mengobati. Padahal, itu anak tidak pernah woro-woro maupun gembar-gembor seperti yang dilakukan banyak paranormal yang setiap hari beriklan di koran-koran kuning.
Saking berterima kasihnya, pasien-pasien yang merasa berhutang nyawa itu rela memberikan apa saja. Uang, barang, sembako dan lain-lain. Aneh bin ajaib, Slamet selalu marah bila diberi imbalan atas jasanya. Dia tak mau menerima pemberian apapun. Kalau si pasien ngotot mau memberikan sesuatu, bisa-bisa dia tambah sewot dan mengusirnya dengan kasar. Hanya mengamalkan ilmu. Itu saja alasannya.
Tapi pasien tak kalah pintar. Secara sembunyi-sembunyi, dan diam-diam, tentu saja tanpa harus mengendap-endap seperti maling ayam, mereka berikan imbalan itu kepada anak atau istrinya. “Tapi ini rahasia, jangan sampai ketahuan Bapak,” si pasien menyerahkan pemberiannya sambil mewanti-wanti.
“Ya, Oom. Saya ndak akan bilang sama Bapak.”
Beres sudah. Tahu-tahu gentong di dapur sudah terisi penuh dengan beras.
Kali lain datang seorang penjaja cinta yang biasa mangkal di komplek pelesiran birahi tak jauh dari rumah mertuanya di Surabaya. Perempuan kenes itu minta dijampi-jampi agar laris. Gawat. Dijampi-jampi betulan. Dan laris pula. Selang beberapa minggu kemudian datanglah rombongan teman-temannya minta dijampi-jampi juga. Maka, ramailah rumah kecil itu dengan perempuan-perempuan berbusana seronok. Duduk seenaknya sambil mengepulkan asap rokok. Sampai-sampai istri Slamet minggat dua hari karena cemburu, dan malu sama tetangga.
Tapi Slamet jalan terus, sambil tak lupa berpesan, “Kalau sudah dapat uang banyak, kamu berhenti ya. Harus tobat.”
We lha, Met … Met …. Ini kan sama saja kamu mendorong orang jadi maling asalkan kalau sudah kaya dari hasil malingnya harus berhenti, tidak jadi maling lagi. Kacau dunia.
Pada kali yang lain, Slamet dimintai tolong oleh beberapa orang rahib dari sebuah kelenteng untuk mengambil sebuah batu aneh dari di dalam mangkuk yang dipegang oleh sesosok arca. Mereka sedang membersihkan kelenteng saat itu, dan ketika akan mengelap mangkuk tersebut, mereka mendapati sebutir batu berwarna putih tua nongkrong di dalamnya.
Ini batu benar-benar bandel, tidak mau dipindahkan. Disentuh sedikit saja langsung berulah. Setiap kali seorang rahib hendak meraih batu itu, tentu saja didahului dengan bermacam-macam jurus seperti dalam filem Kung Fu, langsung terjengkang dan terlempar. Dari mulutnya keluar darah segar. Beberapa orang sudah jadi korban. Mereka kehabisan akal, dan akhirnya nyerah.
“Kalian ini apa? Ini kan hanya batu. Masa, kalah sama batu.” Ketakaburan itu mulai menampakkan wujudnya secara nyata.
Mereka diam saja disemprot seperti itu. Setelah menunjukkan tempat batu nakal tersebut bersemayam, mereka mundur mengambil jarak. Menonton dari tempat yang aman. Slamet langsung beraksi. Mulutnya komat-kamit sebentar. Kemudian batu tersebut dia ambil, dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Tidak terjadi apa-apa. Pun, ketika batu itu diminta oleh Mas Yusa. Dia berikan begitu saja.
“Mudah-mudahan cocok,” pesannya.
Ketika Sony menanyakan kepada kakak sulungnya tersebut di mana batu itu sekarang, dia malah kebingungan, tak tahu di mana. Katanya, batu mokong tersebut ditaruh di lemari dan tahu-tahu hilang begitu saja.
Saudara-saudaranya, terutama Sony, sebagai adik yang urutan kelahirannya tepat di bawah Slamet, sering menasehati agar itu ilmu dibuang saja. Tidak ada manfaatnya.
“Met, itu tipu daya jin agar kamu takabur. Supaya kamu membantu orang untuk berbuat tidak baik,” kata Mbak Rahma, kakak perempuan Sony.
Tapi, seperti biasanya, Slamet selalu ngotot, dengan mata mendelik. “Ilmu saya bersumber dari Asmaul Husna.”
Sudah capek saudara-saudaranya menasehati. Sehingga akhirnya dijadikan guyonan saja. Pernah suatu kali Sony menantangnya, “Met, kalau kamu benar-benar sakti, coba suruh jin piaraanmu menambahkan tiga angka nol pada tabungan saya di bank.” Dinasehati tidak mau, ya sudah, ditantang saja sekalian. Lumayan kan, dengan tambahan tiga angka nol, juta bisa jadi milyar. Curang bener.
Slamet menanggapi tantangan itu secara sambil lalu. “Ndak bisa kalau yang begitu. Bank juga piara jin penunggu,” kilahnya.
“Yo wis, kalau gitu,” jawab Sony.
Fadli, adik Sony, cemberut mendengar percakapan tersebut. Meski tak terucap, Sony merasa adiknya ngomong begini, “Sudahlah, nggak usah ngomongin macam-macam. Bagaimanapun, dia kakakmu. Ojo diguyu. Harus kita hormati. Sabar. Mudah-mudahan dia segera mendapatkan hidayah.” Sony jadi malu sendiri.
Tapi kadang-kadang dia tak bisa menahan diri. Keingintahuannya yang begitu besar terhadap hal-hal gaib – sama seperti curiousity banyak orang yang dicoba dipuaskan oleh stasiun-stasiun TV melalui tayangan misteri – sering kali menggelitik urat jailnya untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan penuh jebakan. Karena dijawab terus, ya dia tanya terus. Jarang-jarang kesempatan seperti ini. Hanya ada selagi pulang kampung.
Jedueeeer! Wah. Sony kuwalat. Jendela kamar depan rontok. Untung temboknya retak belaka. Tapi kaca depan mobil Sony hancur berantakan, seperti kerikil kaca. Moncongnya ringsek. Slamet keluar dari dalam mobil dan kemudian terduduk lunglai di undakan teras. Pucat pasi mukanya. Napasnya tak beraturan. Tersengal-sengal. Badannya gemetaran.
Sony merasa kasihan melihatnya. Tapi ini bukan salahnya. Ini pasti salah Fadli, adiknya itu. Malam sebelumnya, Slamet digojlok habis-habisan. “Punya SIM kok ndak berani nyetir. Apa sih susahnya nyetir. Itu ada mobil. Tinggal pilih, mau pakai yang mana.”
Seperti biasa, Sony kebagian menabur bumbu. “Gampang. SIM kamu tempel di stir pakai selotip. Langsung putar kunci starter. Ngeeeeng. Kamu diam saja. Nggak usah ngapa-ngapain. Biarkan SIM itu yang nyetir.”
Semua jadi tergelak. Sebaliknya, Slamet tersenyum kecut. Matanya melerok.
Siapa nyana, pagi itu ternyata Slamet sudah merasa siap menerima tantangan. “Endi kontake?”
Sony langsung memberikan kunci mobilnya. Mereka semua berkumpul memberikan semangat.
“Larang-larang mbayar kursus nyetir, kok tidak ada manfaatnya. Sudah. Genjot saja.”
Sreeng …. Mesin mobil langsung hidup. Slamet berkonsentrasi. Tapi, seperti biasanya, dia tak pernah fokus pada apa yang dikerjakannya. Malah asyik memperhatikan orang-orang yang sedang menontonnya. Pasang aksi.
Sony jadi ingat zaman dulu, pada waktu kecil, ketika Slamet baru bisa naik sepeda roda dua. Sambil melaju, dia melepaskan kedua tangannya dari stang sambil berteriak lantang, “Gayaee booooo …!” Perhatiannya pun teralih. Tak lagi konsen menjaga keseimbangan sepeda yang sedang dikendarai. Sebaliknya, dia malah tingak-tinguk melihat orang-orang yang sedang menyoraki. Byuuuur! Kecebur got. We lha, kojur kowe.
Kejadian lebih dari tiga puluh tahun lalu itu terulang kembali. Dengan raut muka serius dia mulai mengoper gigi. Kopling lepas, gas langsung tekan. Jedueeerr. Jendela jadi korban. Rupanya bukan gigi mundur yang dia pakai, tapi gigi maju.
“Untung jalannya ke depan, jadi nabrak jendela. Kalau atret, pasti rontok tuh pagar besi,” sempat-sempatnya dia membela diri. Namun tetap tergurat ketakutan di wajahnya.
Saudara-saudaranya cekakaan semua. Sony ketawa paling keras. Padahal mobilnya bonyok. Ya sudah. Blahi slamet. Kecelakaan, tapi tidak ada yang celaka. Orangnya aman-aman saja. Tak kurang satu apa pun. Selamat. Tumben dia bisa nyantai begini. Padahal, kalau di Jakarta, mobil baret sedikit saja bawaannya uring-uringan melulu.
Tapi, cara Slamet membela diri mengigatkannya pada cerita mengenai orang Madura yang menabrak pohon ketika belajar naik motor. Persis sama. Setelah beberapa kali masuk selokan dan membabat habis semak-semak di pinggir jalan, akhirnya dia harus berhenti karena menyeruduk pohon besar di ujung gang. Motornya hancur, tapi orangnya selamat dan masih bisa berkelakar, “Puas aku. Sudah lama aku incar ini pohon.”
Peristiwa seperti ini memberikan pencerahan luar biasa bagi Sony. Kalaupun harta benda yang paling disukai hancur atau hilang, tak masalah. Asal manusianya selamat. Barang-barang duniawi dapat dicari lagi. Bisa dibeli lagi kalau sudah kumpul duit. Tapi, kalau orang-orang tercinta celaka, bisa sedih. Makanya, sayangi badan, bukan harta.
Sungguh berbeda dengan perilaku para penghuni rumah kos putri di gang sebelah kantor Sony. Lorong sempit yang selalu tergenang air setinggi tumit setiap musim hujan itu menjadi kendala ketika gadis-gadis penghuni rumah kos itu berangkat kerja di pagi hari maupun sepulang kerja di sore hari. Tapi mereka punya cara jitu mengatasinya. Cukup lepas sepatu dan kemudian ditenteng. Kaki-kaki mulus itu pun berjalan nyeker menyaruk-nyaruk genangan air yang tak begitu dalam.
Perhitungannya pasti begini. Kalau sepatu tetap dipakai, pasti langsung hancur. Bisa mlenyok, kisut, njeber, mangap dan rontok. Juga bau. Sekalipun bikinan Prada. Tentu biaya reparasinya mahal. Terlebih kalau harus beli lagi. Tapi, kalau hanya ibujari kaki sedikit berdarah karena tergores kerikil tajam, cukup diolesi Betadine. Besok-besok pasti juga sembuh. Berapa sih, harga Betadine? Mereka belum mendapatkan pencerahan.
Pengalaman serupa pernah dialami Fadli ketika rumahnya disatroni perampok pada malam hari. Dua mobil dan satu motor dibawa lari. Anehnya, tak satupun penghuni rumah yang terjaga. Padahal salah seorang perampok sempat kentut di dalam rumah. Buktinya, si Herman, kucing peliharaan mereka, tak ada di sekitar situ. Kucing berwarna oranye itu selalu lari ketakutan kalau ada orang yang kentut dengan suara menggelegar.
Tetangga bilang perampoknya pakai aji sirep. Bisa jadi jampi-jampi itu didapat dari dukun yang amat sakti sehingga tetangga sekitar ikut terkena pengaruhnya. Dengan deretan rumah yang begitu rapat, masa tidak ada seorang pun yang nglilir mendengar suara hiruk-pikuk para pencoleng yang sedang mencongkel jendela sambil guyon dengan saling melempar pantun berbalas, membongkar pintu garasi dan pagar, dan kemudian membawa lari hasil jarahannya.
Tentu sedih sekali kalau harus kehilangan sesuatu yang berharga. Sony tak tega melihat adiknya segundah itu. Fadli hanya terduduk pasrah. Matanya berkaca-kaca. Apalagi, di bagasi mobil ada seperangkat peralatan golf kesayangannya, yang belum sempat diturunkan oleh supirnya.
Tapi seorang polisi kerempeng dengan bijak membesarkan hatinya. “Sudahlah, Pak. Ini musibah. Kita akan bantu cari. Yang penting semua selamat,” hibur Pak Rohan yang asli Cimahi itu dengan suaranya yang lembut.
Benar. Untung tidak ada yang bangun. Polisi menduga jumlah mereka lebih dari empat orang. Minimal bawa sepucuk senjata api. Belum lagi golok dan belati. Kalau sampai ada yang bangun, pasti langsung di-dor. Bisa cilaka. Sudahlah. Toh, semuanya sudah di-cover asuransi. Tak perlu terlalu bersedih. Ini blahi slamet. Malahan, harusnya bersyukur. Kalau perlu bikin selamatan.
Jadi, meskipun mobilnya bonyok, Sony tetap merasa bersyukur karena kakak kesayangannya itu tidak apa-apa. Tidak celaka. Namun adegan French kiss yang mesra lagi bergelora antara mobil dan jendela tersebut rupanya menimbulkan penyesalan yang amat dalam pada diri Slamet. Dia merasa sangat bersalah. Dan amat gundah. Merasa telah merepotkan adiknya. Berkali-kali Sony harus meyakinkan kakaknya bahwa itu bukan masalah besar.
“Berapa sih, mbetulin mobil? Paling cuma segitu. Kalau uang segitu, sekali kedip langsung dapat.” Kadang-kadang Sony dihinggapi penyakit sombong seperti ini.
Slamet jadi agak pendiam. Malam hari dia hanya duduk sendirian di sudut teras sambli lengar-lenger. Bersila. Kepalanya menunduk. Kedua genggaman tangannya menyatu menahan dahinya yang tidak terlalu lebar. Matanya menerawang. Wah, gawat ini. Segera saja saudara-saudaranya beramai-ramai menghampirinya.
“Met, nggak usah dipikirin terus. Mobil kan sudah dibetulin. Sudahlah.” Mereka mencoba menghiburnya.
“Tapi aku sudah merugikan kamu, Son. Rugi! Rugi! Rugi!”
Semua jadi terdiam.
“Sekarang begini saja ….”
Dia pun mulai memaparkan rencananya. Singkatnya begini. Supaya pakpok alias impas, Slamet bersedia memenuhi permintaan Sony yang kemarin. Dia akan suruh Salim dan Rejeb, dua jin peliharaannya itu, minta tolong kepada teman-temannya sesama jin yang ngerti soal bank supaya bisa menambahkan tiga angka nol pada tabungan Sony di bank. Gila. Dimakan juga itu umpan.
“Mana nomer bank?”
Dengan cekatan Sony segera menuliskan nomor rekening di atas secarik kertas. ATM juga ikut berpindah tangan. “Nih. Jangan sampai keliru. Meleset satu angka bisa masuk ke rekening orang lain itu duit,” Sony mencoba mewanti-wanti.
“Beres. Tengah malam nanti saya olah. Kamu tunggu tiga hari. Besok kan kamu balik ke Jakarta, sesampainya di sana bisa langsung dicek,” jawabnya dengan penuh percaya diri.
Sony mengiyakan dengan anggukan serius. Tapi Mbak Rahma malah senyam-senyum. Dengan setengah berbisik dia meledek Sony, “Kalau benar ketambahan tiga angka nol, kamu nyamleng. Bagaimana bila Salim dan Rejeb bingung, sehingga bukannya menambahkan tapi malah mengurangi tiga angka nol? Bisa nangis kamu.”
Sony jadi gamang. Mbuh wis. Ndak usah dipikir. Ini semua kan cuma guyon. Lupakan.
Tapi, anehnya, setiap kali pergi ke ATM, jantung Sony selalu berdebar-debar kencang. Tangannya suka gemetaran. Berharap-harap kalau-kalau sudah ada tambahan tiga angka nol di tabungannya. Setiap kali selalu begitu. Tapi, tak pernah sekalipun ada tambahan tiga angka nol yang mau mampir.
Be’e, wis gendeng … aku iki, pikirnya. Sony benar-benar merasa tersika dipermainkan oleh harapan-harapan yang melambung tapi tidak pernah kesampaian tersebut. Lama-lama dia tak tahan juga menanggung beban yang sangat berat itu, sehingga akhirnya bercerita kepada beberapa orang kawannya. Bukannya menghibur, mereka malah pada ketawa ngakak. Sialan. Sony pun jadi ikutan ngekek. Wis …, gendeng kabeh. Nasib. Nasib.
Akhirnya, dengan sedikit ragu, Sony memberanikan diri menelepon kakaknya untuk menanyakan soal itu.
Jawabannya enteng saja. “Ndak berhasil, Son. Sudah saya coba. Kata Salim dan Rejeb, permintaan seperti itu dapat mengganggu perjanjian antara raja jin dengan manusia.”
Sony agak kecewa.
Tapi buru-buru Slamet menyambung omongannya, “Son, saya jadi ndak enak sama kamu. Kalau kamu pulang nanti saya akan kasih sesuatu sebagai gantinya. Atau saya saja yang pergi ke Jakarta, Son?”
Pada mulanya Sony tidak terlalu berminat menanggapi omongan kakaknya. Tiba-tiba saja, tak ada angin tak ada hujan, Sony begitu antusias menanyakan apa gerangan hadiah yang akan diberikan kepadanya. “Apaan, Met? Jum’at besok saya ada acara ke Surabaya. Sekalian saja, saya mampir ke sana. Sampeyan tidak ke mana-mana, kan?”
Sabtu pagi. Di samping rumah Sony, di kampung halaman. Slamet memasukkan dua butir kemenyan, kira-kira seukuran jagung, ke dalam mulutnya. Dia kunyah-kunyah. Setelah komat-kamit sebentar, tiba-tiba dia merentangkan kedua tangannya sambil menggerang. Persis seperti auman seekor macan. Dia berjalan menuju tembok pagar. Pless. Slamet menembus tembok itu. Dan lenyap begitu saja.
Sony ketakutan. Dia merasa bergidik. Ini sama sekali bukan tipuan. Bukan pula trick kamera. Sony langsung melangkahkan kakinya menuju tembok tersebut. Dia raba-raba tembok itu. Keras. Tidak ada pintunya. Dia mencoba memasukkan tangannya ke dalam tembok. Tidak berhasil. Malah tangannya terasa sakit. Karena tembok itu agak kasar.
Heran dia. Bagaimana mungkin Slamet masuk ke dalam tembok. Kali ini Sony mencoba dengan cara lain. Mencontoh cara yang dilakukan kakaknya tadi. Diambilnya sebutir kemenyan dan kemudian dia kunyah. Rasanya aneh. Pahit. Sambil mengaum, direntangkannya kedua tangannya. Dia berjalan menuju tembok itu. Bukannya tembus. Jidatnya malah kebentur tembok. Sakit sekali.
“Ngapain kamu, Son?”
Semakin kaget saja dia. Slamet ternyata sudah berdiri di belakangnya. “Dari mana kamu?” tanyanya dengan terbata-bata. Belum hilang rasa takutnya.
“Lha, tadi saya keluar dari sebelah kiri kamu. Masa tidak lihat?” jawabnya.
Kemudian Slamet bercerita kepada Sony. Tembok itu adalah pintu gerbang kerajaan jin. Di balik tembok tersebut, terhampar dunia lain. Bukan dunia manusia. Tapi dunia jin, dengan semua aktivitasnya. Mundari, penunggu pintu gerbang tersebut, mengizinkan Slamet masuk.
“Ini, saya bawakan oleh-oleh dari sana.” Slamet memberikan dua butir batu kepada Sony.
Tak terlalu istimewa batu itu. Masing-masing sebesar kelereng, lebih kecil sedikit. Warnanya hitam mengkilat. Tapi terasa agak berat bila dibandingkan dengan ukurannya. Lebih aneh lagi, kedua batu tersebut selalu menempel satu sama lain. Seperti ada magnetnya.
“Met, bisa nggak saya ikut kamu masuk ke sana. Saya ingin tahu kayak apa di sana,” Sony mulai merengek-rengek. Sudah lama dia ingin melihat jin. Apalagi, ini kerajaan. Pasti seru.
Slamet diam saja. Tapi kemudian dia menyanggupi. Mungkin tak tahan melihat adiknya mengiba-iba seperti itu. “Begini saja. Besok, saya akan coba bawa kamu masuk ke sana. Tapi saya tidak janji. Bisa berhasil. Bisa juga tidak. Semuanya tergantung kamu sendiri. Kalau kamu bisa membuang semua pikiranmu hingga otakmu benar-benar kosong, kamu pasti bisa melewati tembok itu.”
Girang sekali Sony mendapatkan jawaban seperti itu. Siang harinya dia langsung belanja peralatan. Dibelinya segulung tambang ukuran satu inci yang panjangnya sekitar lima puluh meter. Juga sebuah troli dorong.
Pagi itu semuanya sudah siap. Sony berdiri di depan tembok. Mengamat-ngamati pagar setinggi dua setengah meter tersebut. Keras, dan bisu. Sementara Slamet masih sarapan. Sony menunggunya, sambil sesekali berteriak memanggilnya. Sudah tak sabar lagi dia. Akhirnya Slamet muncul juga.
“Son, ngapain kamu bawa beginian. Kapan belinya? Memangnya mau bikin apa?” tanya Slamet.
Sony tidak menjawab. Malu rasanya. Tapi akhirnya dia berterus-terang kepada kakaknya. Sony membeberkan rencananya. Tambang itu akan dia ikatkan ke badannya, sedangkan ujung yang satunya lagi akan ditambatkan pada pohon melinjo tak jauh dari tempat itu. Hanya jaga-jaga, kalau-kalau dia tersesat di dunia jin. Dengan bantuan tambang tersebut, dia akan lebih mudah mencari jalan keluar. Sedangkan troli, sengaja disiapkan kalau-kalau di sana nanti dia menemukan emas. Bisa mengambil sebanyak-banyaknya. Jadi tak perlu repot-repot menentengnya.
Slamet akhirnya mengalah. “Ya sudah. Kalau maunya begitu. Silahkan,” katanya.
Mereka pun melakukan persiapan.
“Son, kamu ikuti semua yang saya lakukan. Ingat, buang semua isi pikiranmu. Harus kosong melompong,” pesannya.
Slamet mulai mengunyah kemenyan. Sony segera mengambil remahan-remahan berwarna kecoklatan itu dan kemudian memasukkan ke dalam mulutnya. Dia kunyah. Ketika Slamet mengaum, Sony pun ikut mengaum. Slamet langsung merentangkan kedua tangannya dan berjalan menuju tembok. Sony mengekor di belakangnya sambil mendorong troli, sementara badannya terikat pada seutas tambang.
Slamet hilang ditelan tembok. Sony langsung mengikutinya. Tapi langkahnya tertahan oleh kereta dorong yang menabrak tembok keras. Dia dorong dengan sekuat tenaga troli beroda satu itu. Tapi tak juga mampu menembus tembok. Dirabanya tembok itu. Kasar, seperti biasanya. Sialan. Gagal, pikirnya. Kecewa sekali dia. Sony mencampakkan kereta dorong baru itu dan melepaskan ikatan tambang di badannya. Duduk di tanah.
Setelah sekitar lima menit, Slamet muncul dari balik tembok. Dia tersenyum kecil melihat Sony duduk lesu di tanah, tanpa alas. “Son, kamu belum bisa. Pikiranmu terlalu banyak isinya,” katanya, dengan badan sedikit dibungkukkan. “Sudahlah. Yang penting, kamu sudah saya bawakan oleh-oleh dari sana kemarin. Masih ada, kan?” tambahnya, seolah hendak menghibur Sony.
Dalam hati, Sony membenarkan ucapan kakaknya. Dia memang tidak mampu mengosongkan pikirannya. Terlalu banyak rencana yang berkecamuk di dalam benaknya. Termasuk angan-angannya untuk membawa emas hingga setroli penuh. Dia juga meludahkan kemenyan yang dikunyahnya, karena pahit. Pada waktu mengaum, dia juga tidak sungguh-sungguh. Hanya menirukan apa yang dilakukan kakaknya.
“Met, memangnya ini batu apaan?” tanya Sony sambil menimang-nimang kedua butir batu hitam itu di telapak tangannya.
Slamet diam saja. Dia malah mengambil kedua batu itu dari telapak tangan Sony. Kemudian dia lemparkan salah satu batu tersebut ke kiri dan satunya lagi ke kanan. Ajaib, kedua batu itu berjalan menggelinding menuju telapak tangan Slamet di tanah dan kemudian saling menempel lagi. “Ini batu pengasihan. Pelet,” katanya singkat.
Sony jadi bingung. Tak paham. Untuk apa kakaknya itu memberinya aji pelet. Supaya nyeleweng, kali. Berselingkuh. Wah, itu bukan tabiatnya. Kecuali, kalau terpaksa. “Met, kok sampeyan kasih aku barang beginian?” Sony bertanya dengan setengah ketawa.
“Dapatnya itu, Son. Ya, itu yang saya kasih ke kamu. Kalau tak mau tidak apa-apa. Saya kembalikan saja.”
Akal Sony langsung berputar. Dia ambil kedua batu itu dari tangan kakaknya dan kemudian dimasukkannya ke dalam saku celana. Suatu saat nanti, kedua batu itu pasti ada gunanya.
Eureka. Jum’at kemarin, di Surabaya, dia bertemu dengan seorang klien wanita yang sangat ketus dan cenderung melecehkannya. Semua omongan Sony selalu dimentahkannya. Pendeknya, tidak ada yang beres di mata wanita beraroma wangi itu. Sebelumnya, dia memang sudah diberi tahu akan bertemu dengan Bu Narti, seorang perawan tua, tapi posisinya sangat menentukan di dalam perusahaan.
Sekarang Sony sudah bisa tersenyum. Ancang-ancang langsung disusun. Besok Senin, sebelum balik ke Jakarta, akan dia temui sekali lagi ratu cerewet itu. Akan dia pelet. Akan dia pacari. Biar dikasih banyak proyek besar. Toh, Bu Narti, sebenarnya, lumayan menarik. Kulitnya putih bersih. Hidungnya mancung. Perawakannya juga mbodi. Lumayan tinggi untuk ukuran wanita Indonesia. Hanya saja, mulutnya suka tidak terkontrol kalau sedang berbicara. Judes.
“Son, kamu kan pemasar. Ngapain main dukun?”
Suara dari alam bawah sadar itu mengingatkan Sony. Awalnya terdengar sayup-sayup. Tapi kemudian semakin keras. Berulang-ulang. Benar. Gengsi rasanya kalau seorang pemasar harus menghancurkan sebongkah cadas dengan bantuan dukun.
“Met, kamu berikan saja batu pelet ini sama orang yang belum laku. Biar dia cepat kawin. Ada teman saya di Surabaya, perawan tua. Tolong bantu dia. Supaya cepat dapat jodoh,” kata Sony, sambil menuliskan nomor HP Bu Narti.
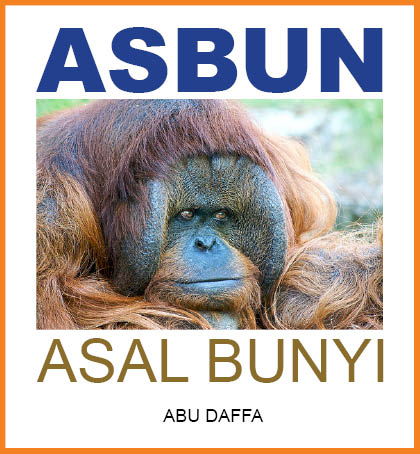
Tidak ada komentar:
Posting Komentar