“Orang mati kok ndak boleh dikubur,” keluh Christine Hakim dengan nada geram. Rambutnya agak awut-awutan. Tergurat kesedihan yang mendalam di wajahnya. Putus asa. Maka dia pun membiarkan mayit anaknya yang mati ditikam preman pasar itu teronggok begitu saja di halaman depan rumah, karena sudah tidak ada lagi uang untuk biaya pemakaman.
Sepotong dialog lugas dalam salah satu adegan filem Daun Di Atas Bantal garapan sutradara cemerlang Garin Nugroho itu membuat Sony terperangah. Bukan hanya orang yang masih hidup yang mengalami kesengsaraan karena biaya hidup yang mencekik leher. Orang yang sudah meninggal pun harus dibebani dengan biaya mati yang juga tak bisa ditawar. Hidup susah, mati pun susah.
Padahal, filem itu mengambil setting kehidupan masyarakat bawah di Kota Gudeg, Yogyakarta. Bagaimana di Jakarta? Jangan sampai meninggal dalam keadaan miskin. Biaya mati di sini tidaklah murah, bahkan lebih mahal daripada biaya hidup. Di lingkungan tempat tinggal Sony harga tanah masih berkisar pada angka delapan ratus ribu rupiah per meter persegi. Sementara di pemakaman yang menghampar tak jauh dari rumahnya biaya penguburan dipatok dua setengah juta per kepala. Artinya, per meter persegi harganya mencapai satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah. Apabila ingin full service, paket lengkap dengan segala tetek bengek perawatan jenazah sekalian, harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Tiga juta rupiah.
“Pak, ada warga kita meninggal tadi malam. Tapi pihak keluarga tak punya biaya,” kata Pak RT sambil mengulurkan formulir sumbangan yang dijepit rapi di dalam map hijau itu kepada Sony.
Tenggorokan Sony seperti tercekat. Baru saja dia menonton VCD yang membuatnya menitikkan air mata. Kini, tetangganya sendiri yang mengalami hal serupa. Dia langsung merogoh dompetnya. Diambilnya semua uang yang ada di dalam dompet itu tanpa menghitungnya lagi. Diberikannya kepada Pak RT. Tak tahu jumlahnya berapa. Karena dia menolak mengisi formulir sumbangan.
Ini urusan mendesak. Tak bisa ditunda. Syukurlah, warga perumahan yang hampir semuanya kaum pendatang mempunyai kepedulian sangat tinggi atas kesusahan yang menimpa tetangga. Jadilah almarhum, Pak Samad, yang semasa hidupnya tinggal hanya berdua dengan istrinya itu, dikuburkan dengan biaya yang ditanggung orang sekomplek. Ya, sebuah pemakaman yang layak, sebagai bentuk penghormatan kepada sahabat yang telah pergi mendahului.
Namun, pemakaman yang layak saja tidaklah cukup. Harus pula aman. Jangan sampai telat, apalagi lupa, membayar iuran tahunan jika tak ingin kuburan kerabat dianggap tak bertuan. Liang baru akan digali di atas kuburan yang tak terbayar untuk menampung penghuni lain. Sebagai antisipasi, Perda melarang peti mati dibuat dari bahan kayu jati atau kayu keras lainnya. Harus dari kayu lunak sehingga mudah lapuk dan hancur dalam hitungan dua atau tiga tahun.
Lantas, di manakah rasa hormat kita kepada orang yang sudah meninggal? Jangan-jangan hantu tanpa kepala di Pemakaman Jeruk Purut itu merupakan korban dari tukang gali kubur yang tanpa sengaja mencangkul tengkorak kepalanya hingga hancur ketika sedang menyiapkan liang lahat baru untuk tamu yang sudah membayar penuh masa sewa tiga puluh tahun.
Rest in peace. Bersemayam dalam damai. Beristirahat dengan tenang. Pesarean, demikian orang Jawa menyebut kuburan. Karena di situlah orang yang sudah meninggal dapat sare atau tidur dengan tenang untuk menunggu dibangkitkan di hari perhitungan. Jadi jangan diganggu. Apalagi digusur. Tapi, siapa peduli pada jeritan dari dalam kubur?
“Sudah mati. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita butuh tempat ini untuk orang yang masih hidup,” mereka beralasan begitu. Seolah tak punya kerabat yang sudah dikubur. Bagaimana bila di pemakaman itu ada salah satu anggota keluarganya yang sedang tidur. Masih tega juga? Bisa jadi, karena takut digusur di belakang hari, atau karena lokasinya yang semakin jauh, biayanya mahal dan harus rutin bayar iuran tahunan pula, sebagian warga asli Jakarta memilih menguburkan anggota keluarganya di halaman rumah.
Banyak areal pemakaman di Jakarta yang telah beralih fungsi menjadi apartemen, mall, perumahan, perkantoran dan restoran. Melenceng jauh dari rencana semula. Bongkaran kuburan batal menjadi jalan dan fasilitas umum. Begitu sudah bersih dari batu nisan, rencana awal dibelokkan. Tak terhitung pemakaman yang bernasib seperti itu.
Dalih bisa dicari. Itu tanah harus diincar. Kalau perlu dikasih panjar. Kemudian ditutup pagar. Satu per satu kuburan dibongkar. Meski seorang tukang gali jatuh terkapar. Ketika mencoba mengutak-atik sebuah kuburan sangar. Terletak tak jauh dari rimbun belukar. Sebagian daunnya sudah hangus dibakar. Itu makam Abu Bakar. Semasa hidupnya dulu seorang pendekar. Tapi anak keturunannya sudah tak mampu lagi bayar. Karena biayanya terus mekar. Salah seorang cucunya menatap nanar. Melihat kuburan moyangnya dibongkar. Bubar.
Suatu saat nanti tidak ada lagi kuburan di Jakarta. Hanya TMP Kalibata yang masih tersisa. Tapi arealnya semakin menyempit saja. Ribuan nisan tegak berdiri berdesak-desakan. Saling berhimpit-himpitan. Karena sudah penuh, hanya orang penting yang dikuburkan di sana. Tim seleksi akan menentukan siapa yang boleh tidur dengan tenang di pemakaman yang teduh itu. Untuk orang-orang yang tidak penting, bukan urusan mereka.
Jakarta harus bersih dari kuburan. Seperti halnya Jakarta harus bersih dari sampah. Kalau sampah masyarakat ibukota saja bisa dititipkan di luar wilayah DKI, kenapa kuburan tidak? Retribusinya kan masuk ke mereka. Bisa nambah-nambah kas Pemda. Sekalian, dapat dijadikan obyek wisata ziarah. Lagian, itu orang-orang kan sudah mati. Jadi jangan khawatir. Mereka tidak akan bikin keributan di sana. Cilaka.
Siapa suruh datang Jakarta? Tak seorang pun dapat melarang mereka datang ke Jakarta. Bahkan jumlah penduduk kota metropolitan itu selalu bertambah sehabis Lebaran. Banyak pemudik yang balik ke ibukota dengan membawa beberapa orang kerabat. Sebagian lagi datang sendiri naik kereta. Umpet-umpetan di Stasiun Senen dan di Terminal Pulo Gadung menghindari petugas razia.
Orang pergi ke Jakarta bukan cari mati. Mereka berbondong-bondong datang ke ibukota untuk meraih mimpi. Mengais rezeki. Mencoba mengadu nasib. Dengan selembar ijazah yang menyisip. Ada yang mujur. Ada yang tersungkur. Sebagian jadi masyhur. Banyak pula yang babak belur. Tapi mereka pantang mundur. Kalau perlu cari uang pakai sangkur. Nongkrongnya di daerah Galur. Sambil makan ketupat sayur. Minumnya bajigur. Diselingi permainan catur. Siang tidur. Malam ngeluyur. Paginya nyarap bubur. Daripada nganggur.
“Pak Gubernur …. Janganlah aku digusur. Ototku sudah kendur. Aku tak punya sedulur. Harta yang kupunya tinggal selembar kasur,” seorang nenek uzur menjerit histeris melihat rumah kardusnya hancur. Perempuan sebatang kara itu terlihat bingung sambil berjalan mundur. Akhirnya jatuh terduduk di bibir trotoar. Sementara suara buldozer menderu-deru main bongkar. Sehingga tangisnya yang menyayat terdengar samar.
Dengan lembut dan penuh empati seorang anggota Satpol PP mencoba menenangkannya. Dia teringat nenek di kampung halamannya. Hatinya trenyuh dibuatnya. Namun tak ada sesuatu pun yang bisa dilakukannya. Menitiklah air matanya. Kawan-kawannya hanya tertawa melihatnya.
“Sudahlah. Biarkan saja. Entar juga bikin gubuk lagi di tempat lain. Kita garuk lagi.”
Berjalan dengan langkah tegap pentungan digenggam. Berkumis sangar berkacamata hitam. Berkacak pinggang dengan kaki mengangkang. Menghardik siapa saja yang dianggap membangkang. Siapa bilang gerombolan Satpol PP yang beseragam biru gahar dengan kopel besar dan belati tajam di pinggang itu orang-orang yang tak punya hati? Mereka juga manusia, sama seperti rocker. Sebagian dari mereka juga berasal dari keluarga yang tergusur. Mereka bisa merasakan kesedihan itu. Keputusasaan. Kemarahan. Ketidakberdayaan. Hati mereka tersayat-sayat. Tapi harus tetap kuat. Karena sedang menjalankan tugas. Ini perintah dari atas. Mesti dilaksanakan secara tuntas. Meski dengan cara yang kurang pantas. Nurani untuk sementara ditinggalkan di rumah. Disimpan di lemari dimasukkan ke dalam toples kaca. Di raganya tinggal sekerat hati. Tanpa isi.
Satpol PP punya surat tugas. Pemukim liar punya berkas.
“Sudah lima belas tahun saya tinggal di sini. Setiap bulan bayar sewa. Sudah punya KTP DKI pula. Ini wilayah RT lima. Resmi tercatat di buku besar Pak Lurah. Saya Ketua RT-nya. Kok sampeyan bilang liar.”
Kalau sudah begini, repot jadinya. Ini pemukiman liar tapi resmi. Juga, resmi tapi liar. Mereka punya Kartu Keluarga. Bahkan ikut nyoblos dalam Pilkada. PLN dan Telkom juga tak keberatan mereka jadi pelanggannya. Demikian pula PAM Jaya yang kini sudah digunting menjadi dua. Mereka pun berang meneriakkan hak-haknya. Batu jadi senjata. Dahan pohon jadi gadah. Sejumlah anak muda membuat pagar betis dengan bertelanjang dada. Sebagian lagi menyiapkan anak panah. Satpol PP kalah jumlah. Akhirnya mengalah. Untuk sementara.
Sebagian pangkal masalah bersumber dari tingkah polah oknum yang nakal. Demi fulus KTP diobral. Syarat kurang lengkap bisa ditambal. Meski serba tertutup, itu tetap skandal. Dengan pelanggan kaum bersandal. Korban sekaligus tumbal. Dasar berandal. Seragamnya necis tapi perilakunya seperti begundal. Rajin mencari sabetan untuk memanjakan rudal. Di tepian rel kereta terkenal paling royal. Bangga dikelilingi perempuan-perempuan sundal.
Di kantor gayanya meyakinkan. Hebatnya lagi, berani memberikan jaminan. Mau bangun gubuk di mana saja silahkan. Asal bayar. Dan harus sabar. Karena setiap saat bisa dibongkar. Terkadang juga dibakar. Oleh orang-orang berbadan kekar. Berwajah sangar. Sehingga malam itu mereka tidur beralas tikar. Ditemani obat nyamuk bakar. Tak ada lagi lampu pijar. Apalagi roti bakar.
“Tuan, apakah kami tak boleh mencari nafkah dengan tenang? Tanpa harus dikejar-kejar. Sehingga terpaksa sembunyi di balik pagar. Menunggu aman hingga fajar. Sementara waktu terus melar. Perut terasa lapar.”
Para pekerja tak berkantor itu meratap pilu. Menggigit kuku. Sudah kepalang, tak mungkin berpaling. Tapi mereka tak mau jadi maling. Hanya menginginkan setetes rezeki yang halal. Menyambung hidup yang tak seempuk bantal.
Tapi aparat Tramtib punya alasan. “Kalian cuma bikin kotor kota ini. Jakarta metropolitan bukan kota gembel. Bukan kerajaan asongan. Tidak pula negeri kaki lima. Semua mesti tertib. Tak boleh kacau-balau. Harus berkilau. Supaya orang luar silau.”
Gundulmu.
Beberapa produsen rokok telah berkontribusi dengan menghibakan kios-kios cantik sebagai pengganti gerobak-gerobak kumal. Beriklan sambil beramal. Meski dimusuhi dengan Perda larangan merokok di tempat umum yang majal itu, mereka tak pernah dendam. Lagian, iklan rokok sudah diatur habis-habisan di media massa, mulai dari format hingga jam tayangnya. Tinggal media luar ruang yang bikin mereka agak leluasa.
Pemda DKI sebenarnya bisa memanfaatkan mereka. Dengan menawarkan kavling-kavling non-komersial. Agar ditempatkan kios-kios mungil yang genit itu di setiap sudut perempatan, dan di ujung-ujung gang. Untuk mengakomodasi pedagang asongan dan anak jalanan. Sementara kios knock-down yang lebih besar bisa dibagikan kepada pedagang kaki lima. Aparat Tramtib tenang. Produsen rokok gembira. Rakyat kecil bahagia. Semua orang happy. Karena Jakarta untuk semua, seperti yang dijanjikan Bang Kumis.
Kios-kios mungil dengan warna-warni mencorong itu juga dapat berfungsi sebagai bunga-bunga artifisial bagi taman kota dan hutan kota, dan tempat-tempat umum lainnya. Enak dipandang menyejukkan mata. Asal selalu dijaga kebersihannya.
Jumlah maling dan pencoleng, termasuk gerombolan Kapak Merah, akan berkurang bila semakin banyak anak jalanan yang mendapatkan kesempatan kerja. Di mana pun tak ada orang yang mau jadi maling atau rampok, karena jadi susah cari pacar.
Jakarta berbenah. Jakarta bersolek. Jakarta indah. Jakarta hijau. Jakarta berbunga. Jakarta manusiawi. Jakarta aman. Jakarta tenteram. Jakarta macet.
Siapa bilang Jakarta macet? Salah itu. Jakarta tidak macet. Tapi, muuuaaaceeet. Termasuk kemacetan temporer akibat galian kabel telepon, pipa air, kabel listrik, perbaikan jalan dan selokan, serta pembangunan jalur bus raja.
Kemacetan juga tak pernah berkurang meskipun banyak mobil lebih suka nongkrong di kandang. Dipanasi setiap pagi hanya untuk dipajang. Karena banyak orang beralih dari mobil ke motor yang biayanya lebih murah. Meski dalam balutan jaket badan terasa gerah. Di balik kaca helm mata memerah. Terpaksa, karena hidup makin susah.
Morat-marit ekonomi keluarga kelas menengah. Dan anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah. Sebab pendapatan orangtuanya habis dipakai untuk mengisi tabung gas cebol yang harganya suka memanjat setinggi galah. Agar anak-anaknya tidak menyantap makanan mentah. Bisa muntah. Kadang bercampur darah. Berwarna merah. Seperti bus Trans Jakarta.
Busway telah bermula. Masih terbatas armada maupun jalurnya. Penumpang berjubel di dalamnya. Kebanyakan mereka orang-orang yang terpelajar dan santun. Meski tak suka saling melempar pantun. Karena harus menjalani rutinitas kerja. Pergi dari rumah di pagi buta. Belum sempat sarapan hingga badan agak lemah. Pulang kerja pun dalam keadaan lelah. Bila harus berdiri, pandangan mata terhalang deretan kepala. Bila beruntung dapat tempat duduk, di depan mata berjajar pusar belaka.
Apanya yang nyaman? Kalau cepat memang iya. Tapi tetap harus menunggu lama. Di halte perak tak bernyawa.
“Tuan, apakah Tuan tidak tergerak untuk memberikan sedikit kenyaman kepada mereka? Yang telah mencoblos kumis Tuan.”
Pertumbuhan pesat jumlah motor juga jadi masalah. Setiap kali berhenti di lampu merah, pasukan tawon itu selalu melebihi marka. Sangat besar jumlahnya. Begitu lampu hijau menyala, mereka berdengung seperti lebah raksasa. Saling menyalip. Saling memotong. Berlomba menunjukkan siapa yang raja. Jalanan disulap menjadi istana. Sekaligus neraka. Mereka berjumpalitan semaunya. Meski nyawa jadi taruhannya.
Kasihan Pak Polisi. Karena harus tidur terlentang di tengah jalan tanpa pernah bisa pulang. Berselimut semen dan batu bata. Agar kendaraan melambat lajunya. Dulu Sony pernah mengira itu kuburan ular. Ternyata polisi yang sedang tidur. Mungkin lagi berantem sama istrinya.
Mobil juga sama saja. Jumlahnya terus membuncah. Sementara ruas jalan tak pernah bertambah. Sebagian malah dirampok oleh busway yang gagah. Berbeda dengan manusia, ada yang lahir ada yang mati. Pertumbuhannya agak terkendali. Mobil di Jakarta bertambah terus, tapi tak ada yang afkir. Jumlahnya kian membanjir. Sudah waktunya menerapkan pembatasan umur kendaraan. Dua puluh tahun – sebagaimana batasan umur pesawat terbang yang masih diijinkan beroperasi di Indoesia – ditetapkan sebagai usia paling tua.
Kepada mobil-mobil tua itu, diterapkan peraturan yang berbeda. Mereka hanya boleh melenggang di jalanan pada hari libur saja. Dengan demikian orang tak bisa lagi menunggang mobil gaek untuk berangkat bekerja. Lagian, mobil tua suka mencuri uang dari dalam dompet tuannya, karena gemar minum dan hobinya keluyuran di bengkel.
Tak peduli mobil mewah, supermewah, kendaraan umum, omprengan ataupun mobil keluarga, kalau umurnya sudah baya, harus tetap di kandang pada hari kerja. Bila perlu, dibawa keluar saja dari Jakarta. Taruh di rumah orangtua di daerah. Sehingga kalau pulang kampung cukup naik pesawat atau kereta. Karena di sana sudah tersedia mobil kesayangan yang siap mengantar ke mana saja.
Atau, jual murah kepada kerabat dan tetangga di kampung halaman, agar mereka bisa bergaya. Berkendara sambil sesekali buka kaca. Bisnis mobil bekas pasti akan ramai di sana. Bengkel-bengkel mobil semakin hidup dan bertambah jumlahnya. Penjualan suku cadang kendaraan tak lagi berpusat di Jakarta. Berkembang merata di daerah. Tak hanya di Jawa, tapi menjangkau seluruh Nusantara.
Dengan menerapkan aturan pembatasan usia kendaraan bermotor, jumlah mobil yang berlalu-lalang di jalanan ibukota pada hari kerja paling tidak akan menyusut secara alami. Sehingga kemacetan lebih mudah ditanggulangi. Namun Pemda DKI harus siap dengan sistem transportasi urban yang mumpuni. Armada dan jalur Busway diperluas lagi. Dengan angkutan pengumpan (feeder) yang ditata lebih rapi. Monorel harus sudah jadi. KRL diubah menjadi subway trilili. Sementara moda angkutan kota yang sudah ada biarkan saja tetap beroperasi. Mereka akan berbenah diri. Karena calon penumpang punya banyak pilihan mandiri. Apabila tidak bersaing, mereka akan mati sendiri.
Namun, ada mobil tua ada mobil kuno. Mobil tua sudah uzur dan peot. Asap hitam menyembur dari knalpot. Suara mesinnya kasar tak terawat. Mogok di perempatan, lalu-lintas langsung gawat. Sedangkan mobil kuno itu antik dan klasik. Sesekali dibawa jalan sambil memutar musik. Lagunya asyik-asyik. Tidak berisik.
Ditetapkan umur mobil antik di atas enam puluh tahun. Tidak digolongkan sebagai mobil pikun. Kepadanya diberikan STNK abadi tanpa perlu diperpanjang lagi. Seperti para orang tua mendapatkan KTP abadi, yang berlaku sampai mati. Mereka boleh melenggang di jalanan ibukota kapan saja setiap hari. Ini untuk mengakomodasi para pehobi. Toh, tak semua orang gemar mengoleksi. Karena biaya restorasi dan perawatan mobil antik sering kali melebihi harga mobil baru.
Bagaimana dengan mobil nenek-nenek dari kawasan penyangga ibukota dan dari luar kota yang ingin masuk ke Jakarta pada hari kerja? Bila warga sendiri saja tak boleh mengendarai mobil peot di Jakarta pada hari kerja, masa tetangga mau seenaknya. Boleh-boleh saja bawa mobil tua untuk berangkat kerja. Tapi tinggalkan di pingiran kota. Di tempat parkir terminal atau stasiun. Perjalanan bisa dilanjutkan dengan angkutan umum atau taksi. Juga kereta api.
Kalau mereka memaksa, bagaimana? Orang-orang DLLAJR dan Polantas pasti sudah punya jawabannya. Mereka sudah biasa. Mengutak-atik kesempatan yang ada. Namun harus tetap dijaga. Hanya mobil-mobil baru dan kinclong yang meramaikan Jakarta pada hari kerja. Dengan tingkat emisi yang sangat rendah. Sehingga bersahabat udara kita. Maka sehatlah jiwa dan raga.
“Emangnya kita orang miskin tak boleh piara mobil? Berangkat kerja naik mobik?” tanya Pak Cecep dengan sangat khawatir karena mobil Mitisubishi Galant kesayangannya itu akan merayakan ulang tahun ketujuh belas bulan depan.
Siapa bilang begitu? Siapa melarang orang punya mobil? Siapa saja boleh punya mobil, tak ada larangan, asalkan mengikuti ketentuan dan aturan yang ada. Seperti halnya tak ada larangan untuk tetap menggunakan kompor minyak tanah, bahkan setelah program konversi minyak tanah ke gas terlaksana secara merata. Tapi harus siap-siap. Minyak tanah akan menjadi barang langka, dan mahal harganya. Bahkan jauh lebih mahal jatuhnya dibandingkan dengan kalau menggunakan kompor dan tabung gas cebol yang sudah dibagikan secara cuma-cuma.
“Kamu datang modal dengkul sama kumis ….” Lirik lagu dangdut itu tentu tidak ditujukan kepada Bang Fauzi. Beliau orang kaya, berpendidikan tinggi dan berpengalaman mengelola ibukota. Tapi Jakarta adalah miniatur Indonesia. Dibutuhkan kemampuan dan kerja ekstra untuk mengaturnya. Soal tata ruang kota, misalnya, tak pernah terlaksana sesuai rencana. Persaingan peruntukan lahan untuk pemukiman, usaha, fasilitas umum dan jalur hijau selalu saja menyerah pada hukum pasar, di mana uang berkuasa. Belum lagi soal banjir. Setiap tahun selalu hadir. Hadiah dari hulu ke hilir. Tamu tak diundang itu selalu bikin orang nyengir.
Banjir memang tak selalu bisa dielakkan. Bahkan dengan pembangunan kanal raksasa yang sedang berjalan. Belum lagi banjir raya yang sering bertingkah ugal-ugalan. Karena hujan tak pernah bisa dijadwalkan. Dia datang suka-suka, dan pergi suka-suka pula. Kadang seharian menari-nari di atas langit Jakarta. Berhenti sebentar. Kemudian berjoget lagi selama tiga hari penuh dalam alunan irama petir yang menyambar-nyambar.
Sementara dari kawasan puncak dan Bogor, rombongan besar Hidrogen dan Oksigen sudah tak sabar lagi ingin berwisata ke ibukota. Mereka saling bergandengan tangan sambil tertawa-tawa. Setiap Oksigen satu digandeng oleh Hidrogen dua. Mereka berpacaran, tapi dalam jalinan cinta segitiga. Sehingga tak disukai oleh tanah Jakarta. Seraya membuang muka, dia berkata, “Ke laut saja.”
Laut pun tersinggung dibuatnya. Dia pasang badan, dengan mengundang sekawanan gelombang untuk berdansa, agar air menjadi pasang. Maka Jakarta tergenang. Penduduk berenang. Rumah berendam. Mobil tenggelam.
“Bang Fauzi, kenapa tidak kita sewa saja semua pawang hujan? Kalau perlu kita datangkan bala bantuan dari Kalimantan, juga dari Banten, tetangga kita itu. Kita gelar Festival Tolak Hujan di Pantai Carnaval. Biar mereka bikin atraksi dan berkolaborasi mengusir gumpalan-gumpalan awan. Agar gerombolan kabut susu itu pergi jauh dan mengungsi ke Gunung Kidul. Sehingga tanah di sana tak lagi gundul.”
Tapi rencana itu tak berjalan. Rumah pawang hujan juga kebanjiran. Dua bilah kerisnya hilang. Juga sekaleng kemenyan.
“Boro-boro tolak hujan, seharian perut belum kemasukan apa-apa. Hanya ada pisang raja. Tapi itu pantangan. Bisa luntur ilmu saya,” katanya sambil bersungut-sungut dan ngeloyor pergi begitu saja. Dia menghampiri istrinya yang sedang menangis sesenggukan. Tak kuat menghadapi kenyataan bahwa sandal kesayangannya hilang di tempat pengungsian.
Sony berkirim surat kepada Bang Fauzi. Kebetulan, mereka berdua masih terhitung saudara jauh. Juuuaaauuuh buuuaaangeeet.
“Bang, berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, sudah saatnya Pemda DKI memiliki Dinas Banjir dalam struktur pemerintahannya. Dan Suku Dinas Banjir dibentuk di lima Kantor Walikota sebagai ujung tombak operasionalnya, minus Kabupaten Kepulauan Seribu, yang tak mungkin kebanjiran, karena hanya bisa tenggelam ditelan lautan, maka dinamakan saja Suku Dinas Tenggelam.”
Ini bukanlah anjuran mengada-ada. Pula, sama sekali tak berlebihan. Apalagi cuma olok-olok. Ini penting sekali. Bahkan lebih penting dari yang kurang penting. Terlebih ketika Sony memperhatikan Sudin-Sudin yang sudah ada. Karena ada yang ada karena diada-adakan. Bingung, kagak?
Di setiap Kantor Walikota, Sony mendapati ada Sudin Pertanian dan Kehutanan, Sudin Kelautan dan Perikanan atau yang sejenisnya lah. Tapi tidak ada Sudin Silalahi di sana. Berdasarkan beban kerjanya dan agar tidak terkesan mengada-ada, Sudin-Sudin tersebut sebaiknya dipermak saja menjadi Sudin PERMAKAN, dengan skope kerja yang mencakup bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Di-merger, baik lingkup kerja maupun sumber dayanya. Sehingga tidak disepelekan lagi oleh Sudin-Sudin lain yang merasa lebih penting.
Kalau urusan pertamanan, Sony setuju belaka. Jakarta membutuhkan banyak taman kota yang harus terus ditambah jumlahnya dan dirawat dengan baik. Sedangkan urusan hutan kota, yang suka rancu dengan taman kota, serahkan saja kepada Sudin Pertamanan.
Pertanian di Jakarta? Ada. Dan sama sekali tidak mengada-ada. Sebagian orang menyebutnya pertanian kota, urban farming. Bagi Sony, yang mengada-ada hanyalah kenapa harus ada Sudin Pertanian dan Kehutanan, mengingat luasan kerjanya tak seberapa. Dengan harga tanah yang begitu tinggi, tentu tidak ekonomis untuk dijadikan lahan pertanian. Mending dibangun ruko, jelas return-nya.
Memang, ada aktivitas produksi yang menghilangkan faktor tanah sebagai modal, dengan menerapkan teknologi hidroponik atau aeroponik. Tapi skalanya tak besar. Biasanya sekedar hobi. Ada pula aktivitas pertanian yang memanfaatkan lahan tidur. Itu pun tak banyak. Sehingga, saking bingungnya harus ngapain, Sudin Pertanian dan Kehutanan getol membina industri rumahan yang mengolah produk-produk pertanian – yang didatangkan dari luar Jakarta – menjadi makanan olahan dalam kemasan.
Urusan beginian, serahkan saja kepada Sudin Perindustrian dan Perdagangan, Seksi Industri Kecil. Karena untuk produk-produk pertanian, jujur saja, Jakarta tak lebih dari sebuah pasar besar belaka. Beli saja. Ngapain tanam sendiri?
Demikian pula soal Suku Dinas Kelautan dan Perikanan. Setahu Sony, dari lima Kota dan satu Kabupaten yang ada di wilayah DKI Jakarta, hanya Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu yang memiliki garis pantai maupun kegiatan perikanan. Di sana ada aktivitas budidaya maupun penangkapan ikan di laut, dalam skala yang lumayan besar, termasuk juga pemasarannya. Sedangkan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, yang ada hanyalah budidaya ikan hias di dalam aquarium, yang tidak membutuhkan banyak lahan. Budidaya ikan air tawar untuk konsumsi? Jangan tanya lagi. Masyarakat Jakarta tak lebih dari sekedar konsumen. Beli saja. Ngapain piara sendiri?
Ditangkap langsung dari kolam. Dimasak dalam keadaan segar. Gurame goreng. Sambil menyantap ikan berdaging tebal itu di Restoran Sari Kuring, Sony mencoret-coret blocknote kecilnya. Dia hendak berkirim surat lagi kepada Bang Fauzi.
“Bang, kalau ente jadi membentuk Sudin Banjir, tolong dong, perhatikan benar lokasi kantornya. Tempatkan di kawasan bebas banjir. Jangan sampai hanya karena salah lokasi Sudin Banjir akhirnya berubah menjadi Sudin Kebanjiran. Di samping menggelikan, juga akan melumpuhkan aktivitasnya yang strategis pada saat-saat genting. Kantor Sudin Banjir juga mesti dilengkapi dengan gudang-gudang penyimpanan sarana penanggulangan banjir dan logistik bantuan. Dibangun pula perumahan bagi karyawan dan keluarganya. Tidak lucu bila pada saat banjir datang Sudin Banjir tidak berfungsi karena karyawannya pada mangkir. Dengan alasan rumahnya banjir. Atau, tak bisa menyeberangi genangan air.”
Gayung bersambut. Dalam perjalanan kembali ke kantor, Sony tertidur pulas di jok belakang mobilnya. Bang Fauzi menghampirinya di dalam mimpi.
“Mas Sony, saya sudah baca surat sampeyan. Pikiran kita sama. Sudah lama saya ingin membentuk Sudin Banjir.”
Sony kegirangan mendengar jawaban itu, dan langsung balik bertanya. “Apa tugas Sudin Banjir, Bang?”
Dengan sistematis Bang Fauzi membeberkan rencana besarnya. Tugas Sudin Banjir bukan mengundang banjir, karena yang begituan sudah mejadi keahlian umum manusia. Dan bukan pula meniadakan banjir. Karena tak seorang pun mampu menolak banjir. Tapi Jakarta bisa bersahabat dengan banjir, dan tak perlu membencinya. Hanya perlu penajaman manajemen penanganan banjir. Ada empat momen penting di mana Sudin Banjir akan memikul tugas besar. Pertama, menjelang banjir. Kedua, ketika banjir. Ketiga, pasca-banjir. Keempat, pada saat tidak banjir.
Pekerjaan terbesar harus dilakukan menjelang banjir, untuk mematangkan persiapan menyambut limpahan air. Buang kebiasaan buruk yang baru bergerak setelah banjir datang. Dan, satu hal yang sangat penting, paradima berpikir harus diubah. Jangan sekali-kali melihat banjir sebagai ancaman. Ia hanyalah tamu yang ingin berkunjung. Kadang menginap sebentar, kadang menginap agak lama. Harus dihormati, seperti mempelakukan kerabat dari kampung yang sedang berwisata ke Jakarta. Baik-baiklah bersikap kepadanya. Kalau tidak, dia akan marah. Kemudian mengontak gerombolan bonek untuk ramai-ramai menemaninya. Bisa berabe nantinya.
Pertama, menjelang banjir. Sudin Banjir mengambil alih tugas Sudin Pekerjaan Umum yang selama ini rajin membersihan aliran sungai dan selokan menjelang musim hujan. Selanjutnya, bekerja sama dengan BMG yang gemar mengintip awan yang sedang mandi dan menghitung berapa banyak hujan yang akan bertamu, dan juga berapa lama mereka akan berwisata di Jakarta, Sudin Banjir dapat mengantisipasi sampai sejauh mana sungai-sungai di ibukota mampu menyiapkan kamar bagi para wisatawan dari langit itu. Kalaupun akhirnya over-booked dan fully-occupied, dan kemudian meluber karena rombongan studi banding tersebut terlalu banyak jumlahnya, sementara laut tak mau diajak kerja sama, Sudin Banjir dapat membuat perkiraan kawasan mana saja yang akan menjadi homestay bagi mereka. Seberapa penuh, sampai berapa lama.
Barulah kemudian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan langganan banjir, diajak bersiap menyambut tamu yang akan bertandang. Siskamling banjir digalakkan. Dengan bantuan media massa, internet, kecamatan, kelurahan, RT/RW dan kumpulan-kumpulan arisan, Sudin Banjir mengajarkan kepada masyarakat cara-cara praktis menjamu tamu yang terkadang memang suka ugal-ugalan itu. Macan dayoh, kata nenek Sony. Tuan rumah harus berlapang dada dan sabar, juga sedikit mengalah.
Dengan memetakan secara detil kawasan langganan banjir di ibukota, Sudin Banjir dapat menentukan di mana akan disiapkan dan dibangun (atau dipinjam sementara) tempat pengungsian yang memiliki daya tampung dan fasilitas umum yang memadai, termasuk tempat parkir mobil dan motor. Kalau perlu dilakukan koordinasi dengan kawasan-kawasan bebas banjir agar mereka mau dititipi mobil dan motor yang suka berenang di air kotor itu. Penempatan lokasi pengungsian jangan terlalu terpencar-pencar, agar aksesnya mudah, sehingga bantuan lebih gampang disalurkan, termasuk untuk acara kunjungan artis dan pejabat.
Khusus untuk logistik bantuan, dibuat perencanaan yang lebih komprehensif. Jangan cuma berpikir soal mie instan dan biskuit, atau nasi bungkus dan air minum dalam kemasan. Dan bukan pula sekedar alas tidur dan selimut. Yang pertama dan utama adalah pemenuhan kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Karena itu, bantuan sembako perlu dilengkapi dengan peralatan memasak. Biar para pengungsi punya kegiatan dan tidak bengong. Jangan lupa pula perlengkapan, makanan dan susu untuk bayi. Juga obat-obatan serta kelengkapan mandi dan cuci. Termasuk sandal, handuk, sarung, pakaian dalam, pembalut wanita, dan tusuk gigi. Sebagian besar disiapkan oleh Sudin Banjir, dan sebagian lagi dihimpun dari donatur melalui sistem koordinasi. Untuk kosmetik, suruh mereka beli sendiri.
Dinas Banjir tingkat provinsi juga berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam penghimpunan donasi. Baik yang dilakukan oleh institusi maupun pribadi. Agar distribusinya lebih terkendali dan mudah diawasi. Terutama dalam soal pemerataan distribusi bantuan. Tak perlu lagi ada lokasi-lokasi pengungsian favorit yang setiap hari dikunjungi artis dan pejabat, dengan limpahan bantuan tanpa henti, sementara banyak lokasi pengungsian yang terpencar-pencar tak pernah ditengok sama sekali.
Karenanya, perlu dibentuk badan pengawas yang melibatkan unsur aparat dan masyarakat. Agar bantuan bisa disalurkan secara merata, tepat sasaran dan cepat. Secepat gerakan perahu karet yang harus segera melesat. Dan pompa-pompa hidran yang mampu menyedot air hingga tanah menjadi kesat. Juga genset cadangan agar malam tak bertambah pekat.
“Aduh … perutku mulas. Sudah dua hari buang-buang air tanpa dibilas. Hanya diusap pakai kertas. Tak bersih tuntas. Kalau begini terus, bisa jadi kadas.” Pemuda gedongan yang berkulit bersih itupun menyeringai dan sesekali meringis sambil memegangi perutnya yang buncit. Matanya yang sipit berkedip-kedip.
Dibutuhkan puluhan ribu, atau mungkin lebih banyak lagi, mobile MCK yang portable dan moveable dengan sistem knock-down untuk ditempatkan di barak-barak pengungsian. Dilengkapi dengan tandon-tandon air yang setiap hari diisi dengan air banjir yang sudah dimurnikan melalui mesin-mesin filter buatan anak negeri. Agar orang tidak buang hajat sembarangan. Sehingga Pos Kesehatan tidak melulu mengobati orang diare dan anak-anak yang terserang penyakit gatal.
Rencana koordinasi juga digelar secara rinci dengan pihak keamanan, baik polisi maupun tentara, agar warga dengan sukarela meninggalkan rumah mereka yang terendam. Tanpa khawatir hartanya digondol maling. Demikian pula koordinasi dengan PLN. Agar pabrik setrum itu segera mematikan aliran listrik di titik-titik rawan. Sehingga tidak perlu lagi ditemukan orang yang mati kesetrum seperti hewan. Dalam soal koordinasi inilah Sudin Banjir berperan sangat penting. Agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan yang hanya buang-buang energi. Jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan yang tak bertuan, dan tuan-tuan yang tidak bekerja.
Kedua, ketika banjir. Dengan persiapan yang matang dalam menyambut rombongan tamu yang akan datang, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan bila air mulai menjulang. Mereka juga sudah tahu apa saja yang perlu diamankan, apa yang harus dibawa, dan ke lokasi pengungsian mana mereka akan pergi.
Maka berbondong-bondonglah mereka mengungsi. Sebagian besar berjalan kaki. Mobil melaju di kanan, motor di sebelah kiri. Dalam barisan yang tertata rapi. Gadis-gadis saling bertukar pipi. Bapak-bapak memegang kunci. Ibu-ibu menabuh kuali. Sambil mendendangkan lagu jali-jali. Beberapa orang bahkan menari-nari. Anak-anak bermain lompat tali. Tak seorang pun kehilangan nyali. Seolah mereka hendak piknik ke Bali. Di sana telah menunggu tempat pengungsian yang asri. Cukup layak untuk ditinggali beberapa hari. Hingga air pergi.
Pasukan Dinas Banjir bergerak serentak. Dengan langkah tegap yang menghentak. Komandannya orang Batak. Garis wajahnya agak kotak. Rambutnya dipotong cepak. Senjatanya sebilah kampak. Tiupan peluit mengawali gerak yang serempak.
Para pahlawan itu menyebar bak pasukan rayap. Dengan mulut mangap. Gerakannya lincah seolah mereka bersayap. Di badan melingkar baju pelampung. Keluar masuk memeriksa setiap kampung. Meminggirkan kayu-kayu dan sampah yang mengapung. Agar penghalang laju air itu tak menggunung. Mereka terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan HT. “Kancil memanggil macan. Leher jerapah nyangkut di dahan.”
Berkelompok-kelompok tentara dan polisi. Berjaga sambil minum kopi. Sarapannya roti. Mereka sedang mengamankan harta dan materi. Agar terusir kegalauan hati. Penduduk yang sedang mengungsi. Regu Siskamling banjir ikut menemani. Sehingga orang luar mudah dikenali. Bersama-sama mereka berpatroli. Bergerak dengan penuh antisipasi. Berkeliling sehari tiga kali. Sore, malam dan pagi hari. Sementara dua perahu karet berseliweran kesana-kemari. Mereka sedang mencari-cari Pak Ali. Seorang kakek tua yang tinggal di pinggiran kali. Pintu rumahnya tertutup tanpa dikunci. Di meja plastik yang terapung hanya tertinggal sebuah peci. Akhirnya pria gaek itu ditemukan di plafon rumahnya sedang mendekap seekor kelinci.
“Saudara-saudaraku yang kucintai, Jakarta untuk semua. Baik yang kebanjiran maupun yang tidak kebanjiran.” Demikian kata penutup sambutan Pak Gubernur. Acara dilanjutkan dengan makan malam bersama di tempat pengungsian. Nasi uduk dihidangkan. Lauknya telor dan ikan. Di piring besar bertumpuk potongan buah-buahan. Tersedia pula beberapa jenis cemilan.
“Ayo kita beryanyi. Berdendang menghibur hati. Begadang sampai pagi.” Anisa Bahar menghangatkan suasana dengan goyangan patah-patah. Beberapa pemuda ikut berjoget sambil melepas baju. Pak Gubernur tersenyum haru. Melihat rakyatnya bergembira. Tetesan hangat menitik dari kedua sudut matanya. Menerobos garis pipi, kemudian menyelinap dan bersembunyi di balik kumisnya.
Hari-hari di tempat pengungsian diwarnai keceriaan. Sudin Banjir telah menyiapkan. Layar tancap dan bermacam-macam hiburan. Para remaja disibukkan dengan aneka permainan. Ibu-ibu menggoreng tempe. Bapak-bapak membakar sate. Anak-anak main prosotan. Sebagian lagi duduk-duduk di Pos Kesehatan.
Ketiga, pasca-banjir. Air mulai surut. Sebagian besar pergi ke laut. Sebagian diminum oleh mesin-mesin hidran yang mulutnya penuh baut. Dan sebagian lagi diserap tanah hingga menyusut. Tak ada lagi barang-barang yang hanyut. Sampah-sampah sudah mulai diangkut. Agar tidak menyebarkan bau kentut.
Jalanan dibersihkan. Lumpur dipinggirkan. Para pengungsi kembali ke rumah-rumah mereka. Berjalan bersama dalam canda tawa. Pekerjaan berat sudah menunggu di sana. Bersih-bersih rumah. Buang-buang sampah. Lantai dipel. Tembok dibersihkan dari kotoran yang menempel. Barang-barang mulai dicuci dan dijemur. Kiri kanan berendeng jemuran menjulur-julur. Kehidupan normal kembali diulur.
Sudin Banjir membentuk task-force pendampingan korban banjir bekerja sama dengan Sudin-Sudin terkait lainnya. Mereka membantu masyarakat untuk memperoleh kemudahan mengurus dokumen-dokumen yang hilang. Bekerja sama dengan sejumlah ATPM, Sudin Banjir juga memberikan diskon untuk perbaikan mobil dan motor yang terendam. Membersihkan jalan dan jembatan. Menyisir sungai dan selokan. Serta memulihkan sarana dan prasarana umum lainnya. Mereka keluar masuk kampung untuk mengidentifikasi dan memboyong para penderita penyakit pasca-banjir ke rumah-rumah sakit. Namun kali ini rumah sakit tidak lagi sesibuk tahun-tahun sebelumnya. Penyakit pasca-banjir sudah bisa ditekan dan dikendalikan. Karena sesungguhnya mereka hidup sangat normal selama berada di pengungsian.
Keempat, pada saat tidak banjir. Sudin Banjir tak akan bengong saja pada saat Jakarta tidak banjir. Justru ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya, memperbaiki dan merawat peralatan penanggulangan banjir dan perlengkapan pengungsian. Tampak remeh-temeh, tetapi sesungguhnya sangat penting. Setelah banjir pergi, Sony sering melihat perahu-perahu karet digeletakkan begitu saja hingga akhirnya rusak dan usang.
Di samping itu, Sudin Banjir secara rutin dan berkala merawat serta membersihkan sungai dan selokan agar aliran air tidak tersendat atau terjadi pendangkalan. Sehingga dampak banjir bisa diminimalisir. Namun pekerjaan ini membutuhkan koordinasi dan pengaturan bersama dengan kawasan penyangga ibukota. Karena air bah tak pernah mau tahu apakah lagi asyik bermain di wilayah DKI atau di halaman tetangga. Dan Sudin Banjir juga tak pernah bertanya apakah seseorang punya KTP DKI atau tidak pada waktu mereka menolong korban banjir.
Masalah koordinasi dan pengaturan bersama inilah – tentu saja tak hanya dalam soal penanggulangan banjir, tetapi juga berbagai aspek lain terkait dengan hubungan antara ibukota dan kawasan penyangganya – yang mengilhami Bang Yos untuk menggulirkan gagasan gemilang mengembangkan Jakarta metropolitan menjadi Jakarta megapolitan. Gagasan dasarnya adalah mengintegrasikan kawasan penyangga ibukota ke dalam wilayah DKI agar koordinasi dan pengaturannya lebih mudah. Menimbang besaran dan kompleksitas dari gabungan wilayah yang akan diurusi itu, maka diusulkan agar Jakarta megapolitan tidak lagi dipimpin oleh seorang gubernur, tapi pejabat setingkat menteri.
Di sini kelihatan sekali kalau Bang Yos ngebet betul untuk memimpin Jakarta megapolitan yang diidamkannya itu. Karena tak mungkin lagi menjadi gubernur, ya harus kepala daerah setingkat menteri. Seandainya saja gagasan besar itu terwujud, rasa-rasanya memang tidak ada orang lain yang pantas memimpin Jakarta megapolitan selain Bang Yos, mengingat prestasinya yang luar biasa ketika menjadi Gubernur DKI selama dua periode berturut-turut.
Namun, masih relevankah gagasan itu? Jakarta megapolitan? Sebagian orang mencibir sinis. Nggak usah macam-macamlah. Sebagai kota metropolitan saja, Jakarta tak punya bandara internasional. Selama ini numpang ke tetangga. Di kelokan belalai gajah tempampang gambar besar logo Pemprov Banten memelototi semua penumpang yang hendak masuk ke atau keluar dari pesawat. Seolah-olah sedang menyindir, “Ini wilayah gue, loe cuma nebeng.” Sementara di bagian selatan sana, Universitas Indonesia yang dibangga-banggakan masyarakat Jakarta harus kos di Depok.
Tapi jangan salah, banyak juga orang yang menginginkan Jakarta megapolitan terwujud. Lagian, kalau pemekaran daerah saja diizinkan oleh Undang-Undang, apakah penggabungan wilayah tidak dimungkinkan?
Pinggirkan dulu pandangan masyarakat Jakarta. Fokus saja kepada orang-orang yang tinggal di kawasan penyangga ibukota, karena sebenarnya merekalah yang menjadi target pengembangan Jakarta megapolitan. Dengan pola yang ada sekarang, kepentingan dan aspirasi politik penduduk siang yang jumlahnya mencapai lebih dari dua juta jiwa itu sama sekali tidak terakomodasi dalam Pilkada DKI 2007.
Mereka dianggap tak pernah ada. Padahal mereka berkontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi Jakarta, dan juga perekonomian nasional. Hanya kebetulan bila malam tiba mereka pulang dan tidur di luar wilayah DKI. Seandainya dibuat jajak pendapat, atau angket lewat media massa, misalnya, yang menawarkan kepada para penghuni kawasan penyangga ibukota untuk bergabung dengan wilayah DKI atau tetap bergabung dengan provinsi semula, Sony haqul yakin sebagian besar akan menjawab lebih suka bergabung dengan DKI. Tentu saja ada beberapa alasan yang melandasi jawaban mereka.
Pertama, percepatan pembangunan. Dengan bergabung ke dalam wilayah DKI, mereka akan menjadi bagian dari sebuah provinsi yang PAD maupun APBD-nya berukuran raksasa. Bahkan terbilang jumbo dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Sektor pendidikan akan mendapatkan manfaat luar biasa karena Pemprov DKI terkenal sangat royal kepada sektor ini. Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur akan berjalan lebih kencang karena pendanaan sudah tak lagi jadi kendala. Dan, secara psikologis, Pemprov DKI akan memanjakan wilayah-wilayah yang baru bergabung itu agar tidak terlintas sedikitpun dalam pikiran mereka keinginan untuk kembali ke pangkuan provinsi semula. Persis sama seperti pemerintah pusat memperlakukan Papua, Irian Jaya Barat dan Nanggroe Aceh Darrusalam.
Kedua, kepentingan ekonomi. Banyak penduduk yang tinggal di kawasan penyangga ibukota mencari nafkah di Jakarta. Atau, kalau dibalik cara berpikirnya, sesungguhnya mereka adalah warga Jakarta yang tinggal di luar wilayah DKI. Bagi mereka, ini hanya masalah domisili. Kenyataannya, kegiatan ekonomi di kawasan penyangga ibukota digerakkan oleh orang-orang yang bekerja di Jakarta dan sebagian besar ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat Jakarta. Dengan bergabung ke dalam wilayah DKI, secara otomatis mereka akan menjadi bagian dari jaringan pasar yang lebih besar. Sementara efek berganda dari pembangunan yang terus dipacu untuk mengejar kesetaraan dengan kakak-kakaknya akan memberikan darah segar bagi kegiatan ekonomi lokal. Demikian pula, harga tanah akan terkerek naik sehingga nilai ekonominya bertambah tinggi. Para pengembang akan berpesta pora.
Ketiga, identitas dan gengsi. Meski tidak mengantongi identitas formal KTP DKI, misalnya, sebagian besar masyarakat kawasan penyangga ibukota menyandang semua atribut yang dimiliki masyarakat Jakarta. Semua identitas kehidupan mereka berkiblat ke Jakarta, mulai dari gaya hidup, pergaulan, bacaan, kegemaran dan lain sebagainya. Mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat Jakarta.
Perhatikan iklan-iklan properti. Meski mengambil tempat di Depok, misalnya, mereka selalu mengatakan berlokasi di selatan Jakarta. Peta yang dimunculkan pun peta Jakarta, dengan Monas di tengahnya, kemudian ditambahkan anak panah yang menunjukkan di mana lokasi perumahan itu berada. Maka, ketika pulang kampung pada Hari Lebaran, orang-orang yang tinggal di kawasan penyangga ibukota disebut sebagai orang Jakarta oleh para kerabatnya. Mereka sama sekali tidak keberatan disebut begitu. Malahan, bangga. Gengsi mereka akan naik bila disebut sebagai orang Jakarta.
Jakarta metropolitan. Jakarta megapolitan.
Sepotong dialog lugas dalam salah satu adegan filem Daun Di Atas Bantal garapan sutradara cemerlang Garin Nugroho itu membuat Sony terperangah. Bukan hanya orang yang masih hidup yang mengalami kesengsaraan karena biaya hidup yang mencekik leher. Orang yang sudah meninggal pun harus dibebani dengan biaya mati yang juga tak bisa ditawar. Hidup susah, mati pun susah.
Padahal, filem itu mengambil setting kehidupan masyarakat bawah di Kota Gudeg, Yogyakarta. Bagaimana di Jakarta? Jangan sampai meninggal dalam keadaan miskin. Biaya mati di sini tidaklah murah, bahkan lebih mahal daripada biaya hidup. Di lingkungan tempat tinggal Sony harga tanah masih berkisar pada angka delapan ratus ribu rupiah per meter persegi. Sementara di pemakaman yang menghampar tak jauh dari rumahnya biaya penguburan dipatok dua setengah juta per kepala. Artinya, per meter persegi harganya mencapai satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah. Apabila ingin full service, paket lengkap dengan segala tetek bengek perawatan jenazah sekalian, harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Tiga juta rupiah.
“Pak, ada warga kita meninggal tadi malam. Tapi pihak keluarga tak punya biaya,” kata Pak RT sambil mengulurkan formulir sumbangan yang dijepit rapi di dalam map hijau itu kepada Sony.
Tenggorokan Sony seperti tercekat. Baru saja dia menonton VCD yang membuatnya menitikkan air mata. Kini, tetangganya sendiri yang mengalami hal serupa. Dia langsung merogoh dompetnya. Diambilnya semua uang yang ada di dalam dompet itu tanpa menghitungnya lagi. Diberikannya kepada Pak RT. Tak tahu jumlahnya berapa. Karena dia menolak mengisi formulir sumbangan.
Ini urusan mendesak. Tak bisa ditunda. Syukurlah, warga perumahan yang hampir semuanya kaum pendatang mempunyai kepedulian sangat tinggi atas kesusahan yang menimpa tetangga. Jadilah almarhum, Pak Samad, yang semasa hidupnya tinggal hanya berdua dengan istrinya itu, dikuburkan dengan biaya yang ditanggung orang sekomplek. Ya, sebuah pemakaman yang layak, sebagai bentuk penghormatan kepada sahabat yang telah pergi mendahului.
Namun, pemakaman yang layak saja tidaklah cukup. Harus pula aman. Jangan sampai telat, apalagi lupa, membayar iuran tahunan jika tak ingin kuburan kerabat dianggap tak bertuan. Liang baru akan digali di atas kuburan yang tak terbayar untuk menampung penghuni lain. Sebagai antisipasi, Perda melarang peti mati dibuat dari bahan kayu jati atau kayu keras lainnya. Harus dari kayu lunak sehingga mudah lapuk dan hancur dalam hitungan dua atau tiga tahun.
Lantas, di manakah rasa hormat kita kepada orang yang sudah meninggal? Jangan-jangan hantu tanpa kepala di Pemakaman Jeruk Purut itu merupakan korban dari tukang gali kubur yang tanpa sengaja mencangkul tengkorak kepalanya hingga hancur ketika sedang menyiapkan liang lahat baru untuk tamu yang sudah membayar penuh masa sewa tiga puluh tahun.
Rest in peace. Bersemayam dalam damai. Beristirahat dengan tenang. Pesarean, demikian orang Jawa menyebut kuburan. Karena di situlah orang yang sudah meninggal dapat sare atau tidur dengan tenang untuk menunggu dibangkitkan di hari perhitungan. Jadi jangan diganggu. Apalagi digusur. Tapi, siapa peduli pada jeritan dari dalam kubur?
“Sudah mati. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita butuh tempat ini untuk orang yang masih hidup,” mereka beralasan begitu. Seolah tak punya kerabat yang sudah dikubur. Bagaimana bila di pemakaman itu ada salah satu anggota keluarganya yang sedang tidur. Masih tega juga? Bisa jadi, karena takut digusur di belakang hari, atau karena lokasinya yang semakin jauh, biayanya mahal dan harus rutin bayar iuran tahunan pula, sebagian warga asli Jakarta memilih menguburkan anggota keluarganya di halaman rumah.
Banyak areal pemakaman di Jakarta yang telah beralih fungsi menjadi apartemen, mall, perumahan, perkantoran dan restoran. Melenceng jauh dari rencana semula. Bongkaran kuburan batal menjadi jalan dan fasilitas umum. Begitu sudah bersih dari batu nisan, rencana awal dibelokkan. Tak terhitung pemakaman yang bernasib seperti itu.
Dalih bisa dicari. Itu tanah harus diincar. Kalau perlu dikasih panjar. Kemudian ditutup pagar. Satu per satu kuburan dibongkar. Meski seorang tukang gali jatuh terkapar. Ketika mencoba mengutak-atik sebuah kuburan sangar. Terletak tak jauh dari rimbun belukar. Sebagian daunnya sudah hangus dibakar. Itu makam Abu Bakar. Semasa hidupnya dulu seorang pendekar. Tapi anak keturunannya sudah tak mampu lagi bayar. Karena biayanya terus mekar. Salah seorang cucunya menatap nanar. Melihat kuburan moyangnya dibongkar. Bubar.
Suatu saat nanti tidak ada lagi kuburan di Jakarta. Hanya TMP Kalibata yang masih tersisa. Tapi arealnya semakin menyempit saja. Ribuan nisan tegak berdiri berdesak-desakan. Saling berhimpit-himpitan. Karena sudah penuh, hanya orang penting yang dikuburkan di sana. Tim seleksi akan menentukan siapa yang boleh tidur dengan tenang di pemakaman yang teduh itu. Untuk orang-orang yang tidak penting, bukan urusan mereka.
Jakarta harus bersih dari kuburan. Seperti halnya Jakarta harus bersih dari sampah. Kalau sampah masyarakat ibukota saja bisa dititipkan di luar wilayah DKI, kenapa kuburan tidak? Retribusinya kan masuk ke mereka. Bisa nambah-nambah kas Pemda. Sekalian, dapat dijadikan obyek wisata ziarah. Lagian, itu orang-orang kan sudah mati. Jadi jangan khawatir. Mereka tidak akan bikin keributan di sana. Cilaka.
Siapa suruh datang Jakarta? Tak seorang pun dapat melarang mereka datang ke Jakarta. Bahkan jumlah penduduk kota metropolitan itu selalu bertambah sehabis Lebaran. Banyak pemudik yang balik ke ibukota dengan membawa beberapa orang kerabat. Sebagian lagi datang sendiri naik kereta. Umpet-umpetan di Stasiun Senen dan di Terminal Pulo Gadung menghindari petugas razia.
Orang pergi ke Jakarta bukan cari mati. Mereka berbondong-bondong datang ke ibukota untuk meraih mimpi. Mengais rezeki. Mencoba mengadu nasib. Dengan selembar ijazah yang menyisip. Ada yang mujur. Ada yang tersungkur. Sebagian jadi masyhur. Banyak pula yang babak belur. Tapi mereka pantang mundur. Kalau perlu cari uang pakai sangkur. Nongkrongnya di daerah Galur. Sambil makan ketupat sayur. Minumnya bajigur. Diselingi permainan catur. Siang tidur. Malam ngeluyur. Paginya nyarap bubur. Daripada nganggur.
“Pak Gubernur …. Janganlah aku digusur. Ototku sudah kendur. Aku tak punya sedulur. Harta yang kupunya tinggal selembar kasur,” seorang nenek uzur menjerit histeris melihat rumah kardusnya hancur. Perempuan sebatang kara itu terlihat bingung sambil berjalan mundur. Akhirnya jatuh terduduk di bibir trotoar. Sementara suara buldozer menderu-deru main bongkar. Sehingga tangisnya yang menyayat terdengar samar.
Dengan lembut dan penuh empati seorang anggota Satpol PP mencoba menenangkannya. Dia teringat nenek di kampung halamannya. Hatinya trenyuh dibuatnya. Namun tak ada sesuatu pun yang bisa dilakukannya. Menitiklah air matanya. Kawan-kawannya hanya tertawa melihatnya.
“Sudahlah. Biarkan saja. Entar juga bikin gubuk lagi di tempat lain. Kita garuk lagi.”
Berjalan dengan langkah tegap pentungan digenggam. Berkumis sangar berkacamata hitam. Berkacak pinggang dengan kaki mengangkang. Menghardik siapa saja yang dianggap membangkang. Siapa bilang gerombolan Satpol PP yang beseragam biru gahar dengan kopel besar dan belati tajam di pinggang itu orang-orang yang tak punya hati? Mereka juga manusia, sama seperti rocker. Sebagian dari mereka juga berasal dari keluarga yang tergusur. Mereka bisa merasakan kesedihan itu. Keputusasaan. Kemarahan. Ketidakberdayaan. Hati mereka tersayat-sayat. Tapi harus tetap kuat. Karena sedang menjalankan tugas. Ini perintah dari atas. Mesti dilaksanakan secara tuntas. Meski dengan cara yang kurang pantas. Nurani untuk sementara ditinggalkan di rumah. Disimpan di lemari dimasukkan ke dalam toples kaca. Di raganya tinggal sekerat hati. Tanpa isi.
Satpol PP punya surat tugas. Pemukim liar punya berkas.
“Sudah lima belas tahun saya tinggal di sini. Setiap bulan bayar sewa. Sudah punya KTP DKI pula. Ini wilayah RT lima. Resmi tercatat di buku besar Pak Lurah. Saya Ketua RT-nya. Kok sampeyan bilang liar.”
Kalau sudah begini, repot jadinya. Ini pemukiman liar tapi resmi. Juga, resmi tapi liar. Mereka punya Kartu Keluarga. Bahkan ikut nyoblos dalam Pilkada. PLN dan Telkom juga tak keberatan mereka jadi pelanggannya. Demikian pula PAM Jaya yang kini sudah digunting menjadi dua. Mereka pun berang meneriakkan hak-haknya. Batu jadi senjata. Dahan pohon jadi gadah. Sejumlah anak muda membuat pagar betis dengan bertelanjang dada. Sebagian lagi menyiapkan anak panah. Satpol PP kalah jumlah. Akhirnya mengalah. Untuk sementara.
Sebagian pangkal masalah bersumber dari tingkah polah oknum yang nakal. Demi fulus KTP diobral. Syarat kurang lengkap bisa ditambal. Meski serba tertutup, itu tetap skandal. Dengan pelanggan kaum bersandal. Korban sekaligus tumbal. Dasar berandal. Seragamnya necis tapi perilakunya seperti begundal. Rajin mencari sabetan untuk memanjakan rudal. Di tepian rel kereta terkenal paling royal. Bangga dikelilingi perempuan-perempuan sundal.
Di kantor gayanya meyakinkan. Hebatnya lagi, berani memberikan jaminan. Mau bangun gubuk di mana saja silahkan. Asal bayar. Dan harus sabar. Karena setiap saat bisa dibongkar. Terkadang juga dibakar. Oleh orang-orang berbadan kekar. Berwajah sangar. Sehingga malam itu mereka tidur beralas tikar. Ditemani obat nyamuk bakar. Tak ada lagi lampu pijar. Apalagi roti bakar.
“Tuan, apakah kami tak boleh mencari nafkah dengan tenang? Tanpa harus dikejar-kejar. Sehingga terpaksa sembunyi di balik pagar. Menunggu aman hingga fajar. Sementara waktu terus melar. Perut terasa lapar.”
Para pekerja tak berkantor itu meratap pilu. Menggigit kuku. Sudah kepalang, tak mungkin berpaling. Tapi mereka tak mau jadi maling. Hanya menginginkan setetes rezeki yang halal. Menyambung hidup yang tak seempuk bantal.
Tapi aparat Tramtib punya alasan. “Kalian cuma bikin kotor kota ini. Jakarta metropolitan bukan kota gembel. Bukan kerajaan asongan. Tidak pula negeri kaki lima. Semua mesti tertib. Tak boleh kacau-balau. Harus berkilau. Supaya orang luar silau.”
Gundulmu.
Beberapa produsen rokok telah berkontribusi dengan menghibakan kios-kios cantik sebagai pengganti gerobak-gerobak kumal. Beriklan sambil beramal. Meski dimusuhi dengan Perda larangan merokok di tempat umum yang majal itu, mereka tak pernah dendam. Lagian, iklan rokok sudah diatur habis-habisan di media massa, mulai dari format hingga jam tayangnya. Tinggal media luar ruang yang bikin mereka agak leluasa.
Pemda DKI sebenarnya bisa memanfaatkan mereka. Dengan menawarkan kavling-kavling non-komersial. Agar ditempatkan kios-kios mungil yang genit itu di setiap sudut perempatan, dan di ujung-ujung gang. Untuk mengakomodasi pedagang asongan dan anak jalanan. Sementara kios knock-down yang lebih besar bisa dibagikan kepada pedagang kaki lima. Aparat Tramtib tenang. Produsen rokok gembira. Rakyat kecil bahagia. Semua orang happy. Karena Jakarta untuk semua, seperti yang dijanjikan Bang Kumis.
Kios-kios mungil dengan warna-warni mencorong itu juga dapat berfungsi sebagai bunga-bunga artifisial bagi taman kota dan hutan kota, dan tempat-tempat umum lainnya. Enak dipandang menyejukkan mata. Asal selalu dijaga kebersihannya.
Jumlah maling dan pencoleng, termasuk gerombolan Kapak Merah, akan berkurang bila semakin banyak anak jalanan yang mendapatkan kesempatan kerja. Di mana pun tak ada orang yang mau jadi maling atau rampok, karena jadi susah cari pacar.
Jakarta berbenah. Jakarta bersolek. Jakarta indah. Jakarta hijau. Jakarta berbunga. Jakarta manusiawi. Jakarta aman. Jakarta tenteram. Jakarta macet.
Siapa bilang Jakarta macet? Salah itu. Jakarta tidak macet. Tapi, muuuaaaceeet. Termasuk kemacetan temporer akibat galian kabel telepon, pipa air, kabel listrik, perbaikan jalan dan selokan, serta pembangunan jalur bus raja.
Kemacetan juga tak pernah berkurang meskipun banyak mobil lebih suka nongkrong di kandang. Dipanasi setiap pagi hanya untuk dipajang. Karena banyak orang beralih dari mobil ke motor yang biayanya lebih murah. Meski dalam balutan jaket badan terasa gerah. Di balik kaca helm mata memerah. Terpaksa, karena hidup makin susah.
Morat-marit ekonomi keluarga kelas menengah. Dan anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah. Sebab pendapatan orangtuanya habis dipakai untuk mengisi tabung gas cebol yang harganya suka memanjat setinggi galah. Agar anak-anaknya tidak menyantap makanan mentah. Bisa muntah. Kadang bercampur darah. Berwarna merah. Seperti bus Trans Jakarta.
Busway telah bermula. Masih terbatas armada maupun jalurnya. Penumpang berjubel di dalamnya. Kebanyakan mereka orang-orang yang terpelajar dan santun. Meski tak suka saling melempar pantun. Karena harus menjalani rutinitas kerja. Pergi dari rumah di pagi buta. Belum sempat sarapan hingga badan agak lemah. Pulang kerja pun dalam keadaan lelah. Bila harus berdiri, pandangan mata terhalang deretan kepala. Bila beruntung dapat tempat duduk, di depan mata berjajar pusar belaka.
Apanya yang nyaman? Kalau cepat memang iya. Tapi tetap harus menunggu lama. Di halte perak tak bernyawa.
“Tuan, apakah Tuan tidak tergerak untuk memberikan sedikit kenyaman kepada mereka? Yang telah mencoblos kumis Tuan.”
Pertumbuhan pesat jumlah motor juga jadi masalah. Setiap kali berhenti di lampu merah, pasukan tawon itu selalu melebihi marka. Sangat besar jumlahnya. Begitu lampu hijau menyala, mereka berdengung seperti lebah raksasa. Saling menyalip. Saling memotong. Berlomba menunjukkan siapa yang raja. Jalanan disulap menjadi istana. Sekaligus neraka. Mereka berjumpalitan semaunya. Meski nyawa jadi taruhannya.
Kasihan Pak Polisi. Karena harus tidur terlentang di tengah jalan tanpa pernah bisa pulang. Berselimut semen dan batu bata. Agar kendaraan melambat lajunya. Dulu Sony pernah mengira itu kuburan ular. Ternyata polisi yang sedang tidur. Mungkin lagi berantem sama istrinya.
Mobil juga sama saja. Jumlahnya terus membuncah. Sementara ruas jalan tak pernah bertambah. Sebagian malah dirampok oleh busway yang gagah. Berbeda dengan manusia, ada yang lahir ada yang mati. Pertumbuhannya agak terkendali. Mobil di Jakarta bertambah terus, tapi tak ada yang afkir. Jumlahnya kian membanjir. Sudah waktunya menerapkan pembatasan umur kendaraan. Dua puluh tahun – sebagaimana batasan umur pesawat terbang yang masih diijinkan beroperasi di Indoesia – ditetapkan sebagai usia paling tua.
Kepada mobil-mobil tua itu, diterapkan peraturan yang berbeda. Mereka hanya boleh melenggang di jalanan pada hari libur saja. Dengan demikian orang tak bisa lagi menunggang mobil gaek untuk berangkat bekerja. Lagian, mobil tua suka mencuri uang dari dalam dompet tuannya, karena gemar minum dan hobinya keluyuran di bengkel.
Tak peduli mobil mewah, supermewah, kendaraan umum, omprengan ataupun mobil keluarga, kalau umurnya sudah baya, harus tetap di kandang pada hari kerja. Bila perlu, dibawa keluar saja dari Jakarta. Taruh di rumah orangtua di daerah. Sehingga kalau pulang kampung cukup naik pesawat atau kereta. Karena di sana sudah tersedia mobil kesayangan yang siap mengantar ke mana saja.
Atau, jual murah kepada kerabat dan tetangga di kampung halaman, agar mereka bisa bergaya. Berkendara sambil sesekali buka kaca. Bisnis mobil bekas pasti akan ramai di sana. Bengkel-bengkel mobil semakin hidup dan bertambah jumlahnya. Penjualan suku cadang kendaraan tak lagi berpusat di Jakarta. Berkembang merata di daerah. Tak hanya di Jawa, tapi menjangkau seluruh Nusantara.
Dengan menerapkan aturan pembatasan usia kendaraan bermotor, jumlah mobil yang berlalu-lalang di jalanan ibukota pada hari kerja paling tidak akan menyusut secara alami. Sehingga kemacetan lebih mudah ditanggulangi. Namun Pemda DKI harus siap dengan sistem transportasi urban yang mumpuni. Armada dan jalur Busway diperluas lagi. Dengan angkutan pengumpan (feeder) yang ditata lebih rapi. Monorel harus sudah jadi. KRL diubah menjadi subway trilili. Sementara moda angkutan kota yang sudah ada biarkan saja tetap beroperasi. Mereka akan berbenah diri. Karena calon penumpang punya banyak pilihan mandiri. Apabila tidak bersaing, mereka akan mati sendiri.
Namun, ada mobil tua ada mobil kuno. Mobil tua sudah uzur dan peot. Asap hitam menyembur dari knalpot. Suara mesinnya kasar tak terawat. Mogok di perempatan, lalu-lintas langsung gawat. Sedangkan mobil kuno itu antik dan klasik. Sesekali dibawa jalan sambil memutar musik. Lagunya asyik-asyik. Tidak berisik.
Ditetapkan umur mobil antik di atas enam puluh tahun. Tidak digolongkan sebagai mobil pikun. Kepadanya diberikan STNK abadi tanpa perlu diperpanjang lagi. Seperti para orang tua mendapatkan KTP abadi, yang berlaku sampai mati. Mereka boleh melenggang di jalanan ibukota kapan saja setiap hari. Ini untuk mengakomodasi para pehobi. Toh, tak semua orang gemar mengoleksi. Karena biaya restorasi dan perawatan mobil antik sering kali melebihi harga mobil baru.
Bagaimana dengan mobil nenek-nenek dari kawasan penyangga ibukota dan dari luar kota yang ingin masuk ke Jakarta pada hari kerja? Bila warga sendiri saja tak boleh mengendarai mobil peot di Jakarta pada hari kerja, masa tetangga mau seenaknya. Boleh-boleh saja bawa mobil tua untuk berangkat kerja. Tapi tinggalkan di pingiran kota. Di tempat parkir terminal atau stasiun. Perjalanan bisa dilanjutkan dengan angkutan umum atau taksi. Juga kereta api.
Kalau mereka memaksa, bagaimana? Orang-orang DLLAJR dan Polantas pasti sudah punya jawabannya. Mereka sudah biasa. Mengutak-atik kesempatan yang ada. Namun harus tetap dijaga. Hanya mobil-mobil baru dan kinclong yang meramaikan Jakarta pada hari kerja. Dengan tingkat emisi yang sangat rendah. Sehingga bersahabat udara kita. Maka sehatlah jiwa dan raga.
“Emangnya kita orang miskin tak boleh piara mobil? Berangkat kerja naik mobik?” tanya Pak Cecep dengan sangat khawatir karena mobil Mitisubishi Galant kesayangannya itu akan merayakan ulang tahun ketujuh belas bulan depan.
Siapa bilang begitu? Siapa melarang orang punya mobil? Siapa saja boleh punya mobil, tak ada larangan, asalkan mengikuti ketentuan dan aturan yang ada. Seperti halnya tak ada larangan untuk tetap menggunakan kompor minyak tanah, bahkan setelah program konversi minyak tanah ke gas terlaksana secara merata. Tapi harus siap-siap. Minyak tanah akan menjadi barang langka, dan mahal harganya. Bahkan jauh lebih mahal jatuhnya dibandingkan dengan kalau menggunakan kompor dan tabung gas cebol yang sudah dibagikan secara cuma-cuma.
“Kamu datang modal dengkul sama kumis ….” Lirik lagu dangdut itu tentu tidak ditujukan kepada Bang Fauzi. Beliau orang kaya, berpendidikan tinggi dan berpengalaman mengelola ibukota. Tapi Jakarta adalah miniatur Indonesia. Dibutuhkan kemampuan dan kerja ekstra untuk mengaturnya. Soal tata ruang kota, misalnya, tak pernah terlaksana sesuai rencana. Persaingan peruntukan lahan untuk pemukiman, usaha, fasilitas umum dan jalur hijau selalu saja menyerah pada hukum pasar, di mana uang berkuasa. Belum lagi soal banjir. Setiap tahun selalu hadir. Hadiah dari hulu ke hilir. Tamu tak diundang itu selalu bikin orang nyengir.
Banjir memang tak selalu bisa dielakkan. Bahkan dengan pembangunan kanal raksasa yang sedang berjalan. Belum lagi banjir raya yang sering bertingkah ugal-ugalan. Karena hujan tak pernah bisa dijadwalkan. Dia datang suka-suka, dan pergi suka-suka pula. Kadang seharian menari-nari di atas langit Jakarta. Berhenti sebentar. Kemudian berjoget lagi selama tiga hari penuh dalam alunan irama petir yang menyambar-nyambar.
Sementara dari kawasan puncak dan Bogor, rombongan besar Hidrogen dan Oksigen sudah tak sabar lagi ingin berwisata ke ibukota. Mereka saling bergandengan tangan sambil tertawa-tawa. Setiap Oksigen satu digandeng oleh Hidrogen dua. Mereka berpacaran, tapi dalam jalinan cinta segitiga. Sehingga tak disukai oleh tanah Jakarta. Seraya membuang muka, dia berkata, “Ke laut saja.”
Laut pun tersinggung dibuatnya. Dia pasang badan, dengan mengundang sekawanan gelombang untuk berdansa, agar air menjadi pasang. Maka Jakarta tergenang. Penduduk berenang. Rumah berendam. Mobil tenggelam.
“Bang Fauzi, kenapa tidak kita sewa saja semua pawang hujan? Kalau perlu kita datangkan bala bantuan dari Kalimantan, juga dari Banten, tetangga kita itu. Kita gelar Festival Tolak Hujan di Pantai Carnaval. Biar mereka bikin atraksi dan berkolaborasi mengusir gumpalan-gumpalan awan. Agar gerombolan kabut susu itu pergi jauh dan mengungsi ke Gunung Kidul. Sehingga tanah di sana tak lagi gundul.”
Tapi rencana itu tak berjalan. Rumah pawang hujan juga kebanjiran. Dua bilah kerisnya hilang. Juga sekaleng kemenyan.
“Boro-boro tolak hujan, seharian perut belum kemasukan apa-apa. Hanya ada pisang raja. Tapi itu pantangan. Bisa luntur ilmu saya,” katanya sambil bersungut-sungut dan ngeloyor pergi begitu saja. Dia menghampiri istrinya yang sedang menangis sesenggukan. Tak kuat menghadapi kenyataan bahwa sandal kesayangannya hilang di tempat pengungsian.
Sony berkirim surat kepada Bang Fauzi. Kebetulan, mereka berdua masih terhitung saudara jauh. Juuuaaauuuh buuuaaangeeet.
“Bang, berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, sudah saatnya Pemda DKI memiliki Dinas Banjir dalam struktur pemerintahannya. Dan Suku Dinas Banjir dibentuk di lima Kantor Walikota sebagai ujung tombak operasionalnya, minus Kabupaten Kepulauan Seribu, yang tak mungkin kebanjiran, karena hanya bisa tenggelam ditelan lautan, maka dinamakan saja Suku Dinas Tenggelam.”
Ini bukanlah anjuran mengada-ada. Pula, sama sekali tak berlebihan. Apalagi cuma olok-olok. Ini penting sekali. Bahkan lebih penting dari yang kurang penting. Terlebih ketika Sony memperhatikan Sudin-Sudin yang sudah ada. Karena ada yang ada karena diada-adakan. Bingung, kagak?
Di setiap Kantor Walikota, Sony mendapati ada Sudin Pertanian dan Kehutanan, Sudin Kelautan dan Perikanan atau yang sejenisnya lah. Tapi tidak ada Sudin Silalahi di sana. Berdasarkan beban kerjanya dan agar tidak terkesan mengada-ada, Sudin-Sudin tersebut sebaiknya dipermak saja menjadi Sudin PERMAKAN, dengan skope kerja yang mencakup bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Di-merger, baik lingkup kerja maupun sumber dayanya. Sehingga tidak disepelekan lagi oleh Sudin-Sudin lain yang merasa lebih penting.
Kalau urusan pertamanan, Sony setuju belaka. Jakarta membutuhkan banyak taman kota yang harus terus ditambah jumlahnya dan dirawat dengan baik. Sedangkan urusan hutan kota, yang suka rancu dengan taman kota, serahkan saja kepada Sudin Pertamanan.
Pertanian di Jakarta? Ada. Dan sama sekali tidak mengada-ada. Sebagian orang menyebutnya pertanian kota, urban farming. Bagi Sony, yang mengada-ada hanyalah kenapa harus ada Sudin Pertanian dan Kehutanan, mengingat luasan kerjanya tak seberapa. Dengan harga tanah yang begitu tinggi, tentu tidak ekonomis untuk dijadikan lahan pertanian. Mending dibangun ruko, jelas return-nya.
Memang, ada aktivitas produksi yang menghilangkan faktor tanah sebagai modal, dengan menerapkan teknologi hidroponik atau aeroponik. Tapi skalanya tak besar. Biasanya sekedar hobi. Ada pula aktivitas pertanian yang memanfaatkan lahan tidur. Itu pun tak banyak. Sehingga, saking bingungnya harus ngapain, Sudin Pertanian dan Kehutanan getol membina industri rumahan yang mengolah produk-produk pertanian – yang didatangkan dari luar Jakarta – menjadi makanan olahan dalam kemasan.
Urusan beginian, serahkan saja kepada Sudin Perindustrian dan Perdagangan, Seksi Industri Kecil. Karena untuk produk-produk pertanian, jujur saja, Jakarta tak lebih dari sebuah pasar besar belaka. Beli saja. Ngapain tanam sendiri?
Demikian pula soal Suku Dinas Kelautan dan Perikanan. Setahu Sony, dari lima Kota dan satu Kabupaten yang ada di wilayah DKI Jakarta, hanya Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu yang memiliki garis pantai maupun kegiatan perikanan. Di sana ada aktivitas budidaya maupun penangkapan ikan di laut, dalam skala yang lumayan besar, termasuk juga pemasarannya. Sedangkan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, yang ada hanyalah budidaya ikan hias di dalam aquarium, yang tidak membutuhkan banyak lahan. Budidaya ikan air tawar untuk konsumsi? Jangan tanya lagi. Masyarakat Jakarta tak lebih dari sekedar konsumen. Beli saja. Ngapain piara sendiri?
Ditangkap langsung dari kolam. Dimasak dalam keadaan segar. Gurame goreng. Sambil menyantap ikan berdaging tebal itu di Restoran Sari Kuring, Sony mencoret-coret blocknote kecilnya. Dia hendak berkirim surat lagi kepada Bang Fauzi.
“Bang, kalau ente jadi membentuk Sudin Banjir, tolong dong, perhatikan benar lokasi kantornya. Tempatkan di kawasan bebas banjir. Jangan sampai hanya karena salah lokasi Sudin Banjir akhirnya berubah menjadi Sudin Kebanjiran. Di samping menggelikan, juga akan melumpuhkan aktivitasnya yang strategis pada saat-saat genting. Kantor Sudin Banjir juga mesti dilengkapi dengan gudang-gudang penyimpanan sarana penanggulangan banjir dan logistik bantuan. Dibangun pula perumahan bagi karyawan dan keluarganya. Tidak lucu bila pada saat banjir datang Sudin Banjir tidak berfungsi karena karyawannya pada mangkir. Dengan alasan rumahnya banjir. Atau, tak bisa menyeberangi genangan air.”
Gayung bersambut. Dalam perjalanan kembali ke kantor, Sony tertidur pulas di jok belakang mobilnya. Bang Fauzi menghampirinya di dalam mimpi.
“Mas Sony, saya sudah baca surat sampeyan. Pikiran kita sama. Sudah lama saya ingin membentuk Sudin Banjir.”
Sony kegirangan mendengar jawaban itu, dan langsung balik bertanya. “Apa tugas Sudin Banjir, Bang?”
Dengan sistematis Bang Fauzi membeberkan rencana besarnya. Tugas Sudin Banjir bukan mengundang banjir, karena yang begituan sudah mejadi keahlian umum manusia. Dan bukan pula meniadakan banjir. Karena tak seorang pun mampu menolak banjir. Tapi Jakarta bisa bersahabat dengan banjir, dan tak perlu membencinya. Hanya perlu penajaman manajemen penanganan banjir. Ada empat momen penting di mana Sudin Banjir akan memikul tugas besar. Pertama, menjelang banjir. Kedua, ketika banjir. Ketiga, pasca-banjir. Keempat, pada saat tidak banjir.
Pekerjaan terbesar harus dilakukan menjelang banjir, untuk mematangkan persiapan menyambut limpahan air. Buang kebiasaan buruk yang baru bergerak setelah banjir datang. Dan, satu hal yang sangat penting, paradima berpikir harus diubah. Jangan sekali-kali melihat banjir sebagai ancaman. Ia hanyalah tamu yang ingin berkunjung. Kadang menginap sebentar, kadang menginap agak lama. Harus dihormati, seperti mempelakukan kerabat dari kampung yang sedang berwisata ke Jakarta. Baik-baiklah bersikap kepadanya. Kalau tidak, dia akan marah. Kemudian mengontak gerombolan bonek untuk ramai-ramai menemaninya. Bisa berabe nantinya.
Pertama, menjelang banjir. Sudin Banjir mengambil alih tugas Sudin Pekerjaan Umum yang selama ini rajin membersihan aliran sungai dan selokan menjelang musim hujan. Selanjutnya, bekerja sama dengan BMG yang gemar mengintip awan yang sedang mandi dan menghitung berapa banyak hujan yang akan bertamu, dan juga berapa lama mereka akan berwisata di Jakarta, Sudin Banjir dapat mengantisipasi sampai sejauh mana sungai-sungai di ibukota mampu menyiapkan kamar bagi para wisatawan dari langit itu. Kalaupun akhirnya over-booked dan fully-occupied, dan kemudian meluber karena rombongan studi banding tersebut terlalu banyak jumlahnya, sementara laut tak mau diajak kerja sama, Sudin Banjir dapat membuat perkiraan kawasan mana saja yang akan menjadi homestay bagi mereka. Seberapa penuh, sampai berapa lama.
Barulah kemudian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan langganan banjir, diajak bersiap menyambut tamu yang akan bertandang. Siskamling banjir digalakkan. Dengan bantuan media massa, internet, kecamatan, kelurahan, RT/RW dan kumpulan-kumpulan arisan, Sudin Banjir mengajarkan kepada masyarakat cara-cara praktis menjamu tamu yang terkadang memang suka ugal-ugalan itu. Macan dayoh, kata nenek Sony. Tuan rumah harus berlapang dada dan sabar, juga sedikit mengalah.
Dengan memetakan secara detil kawasan langganan banjir di ibukota, Sudin Banjir dapat menentukan di mana akan disiapkan dan dibangun (atau dipinjam sementara) tempat pengungsian yang memiliki daya tampung dan fasilitas umum yang memadai, termasuk tempat parkir mobil dan motor. Kalau perlu dilakukan koordinasi dengan kawasan-kawasan bebas banjir agar mereka mau dititipi mobil dan motor yang suka berenang di air kotor itu. Penempatan lokasi pengungsian jangan terlalu terpencar-pencar, agar aksesnya mudah, sehingga bantuan lebih gampang disalurkan, termasuk untuk acara kunjungan artis dan pejabat.
Khusus untuk logistik bantuan, dibuat perencanaan yang lebih komprehensif. Jangan cuma berpikir soal mie instan dan biskuit, atau nasi bungkus dan air minum dalam kemasan. Dan bukan pula sekedar alas tidur dan selimut. Yang pertama dan utama adalah pemenuhan kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Karena itu, bantuan sembako perlu dilengkapi dengan peralatan memasak. Biar para pengungsi punya kegiatan dan tidak bengong. Jangan lupa pula perlengkapan, makanan dan susu untuk bayi. Juga obat-obatan serta kelengkapan mandi dan cuci. Termasuk sandal, handuk, sarung, pakaian dalam, pembalut wanita, dan tusuk gigi. Sebagian besar disiapkan oleh Sudin Banjir, dan sebagian lagi dihimpun dari donatur melalui sistem koordinasi. Untuk kosmetik, suruh mereka beli sendiri.
Dinas Banjir tingkat provinsi juga berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam penghimpunan donasi. Baik yang dilakukan oleh institusi maupun pribadi. Agar distribusinya lebih terkendali dan mudah diawasi. Terutama dalam soal pemerataan distribusi bantuan. Tak perlu lagi ada lokasi-lokasi pengungsian favorit yang setiap hari dikunjungi artis dan pejabat, dengan limpahan bantuan tanpa henti, sementara banyak lokasi pengungsian yang terpencar-pencar tak pernah ditengok sama sekali.
Karenanya, perlu dibentuk badan pengawas yang melibatkan unsur aparat dan masyarakat. Agar bantuan bisa disalurkan secara merata, tepat sasaran dan cepat. Secepat gerakan perahu karet yang harus segera melesat. Dan pompa-pompa hidran yang mampu menyedot air hingga tanah menjadi kesat. Juga genset cadangan agar malam tak bertambah pekat.
“Aduh … perutku mulas. Sudah dua hari buang-buang air tanpa dibilas. Hanya diusap pakai kertas. Tak bersih tuntas. Kalau begini terus, bisa jadi kadas.” Pemuda gedongan yang berkulit bersih itupun menyeringai dan sesekali meringis sambil memegangi perutnya yang buncit. Matanya yang sipit berkedip-kedip.
Dibutuhkan puluhan ribu, atau mungkin lebih banyak lagi, mobile MCK yang portable dan moveable dengan sistem knock-down untuk ditempatkan di barak-barak pengungsian. Dilengkapi dengan tandon-tandon air yang setiap hari diisi dengan air banjir yang sudah dimurnikan melalui mesin-mesin filter buatan anak negeri. Agar orang tidak buang hajat sembarangan. Sehingga Pos Kesehatan tidak melulu mengobati orang diare dan anak-anak yang terserang penyakit gatal.
Rencana koordinasi juga digelar secara rinci dengan pihak keamanan, baik polisi maupun tentara, agar warga dengan sukarela meninggalkan rumah mereka yang terendam. Tanpa khawatir hartanya digondol maling. Demikian pula koordinasi dengan PLN. Agar pabrik setrum itu segera mematikan aliran listrik di titik-titik rawan. Sehingga tidak perlu lagi ditemukan orang yang mati kesetrum seperti hewan. Dalam soal koordinasi inilah Sudin Banjir berperan sangat penting. Agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan yang hanya buang-buang energi. Jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan yang tak bertuan, dan tuan-tuan yang tidak bekerja.
Kedua, ketika banjir. Dengan persiapan yang matang dalam menyambut rombongan tamu yang akan datang, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan bila air mulai menjulang. Mereka juga sudah tahu apa saja yang perlu diamankan, apa yang harus dibawa, dan ke lokasi pengungsian mana mereka akan pergi.
Maka berbondong-bondonglah mereka mengungsi. Sebagian besar berjalan kaki. Mobil melaju di kanan, motor di sebelah kiri. Dalam barisan yang tertata rapi. Gadis-gadis saling bertukar pipi. Bapak-bapak memegang kunci. Ibu-ibu menabuh kuali. Sambil mendendangkan lagu jali-jali. Beberapa orang bahkan menari-nari. Anak-anak bermain lompat tali. Tak seorang pun kehilangan nyali. Seolah mereka hendak piknik ke Bali. Di sana telah menunggu tempat pengungsian yang asri. Cukup layak untuk ditinggali beberapa hari. Hingga air pergi.
Pasukan Dinas Banjir bergerak serentak. Dengan langkah tegap yang menghentak. Komandannya orang Batak. Garis wajahnya agak kotak. Rambutnya dipotong cepak. Senjatanya sebilah kampak. Tiupan peluit mengawali gerak yang serempak.
Para pahlawan itu menyebar bak pasukan rayap. Dengan mulut mangap. Gerakannya lincah seolah mereka bersayap. Di badan melingkar baju pelampung. Keluar masuk memeriksa setiap kampung. Meminggirkan kayu-kayu dan sampah yang mengapung. Agar penghalang laju air itu tak menggunung. Mereka terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan HT. “Kancil memanggil macan. Leher jerapah nyangkut di dahan.”
Berkelompok-kelompok tentara dan polisi. Berjaga sambil minum kopi. Sarapannya roti. Mereka sedang mengamankan harta dan materi. Agar terusir kegalauan hati. Penduduk yang sedang mengungsi. Regu Siskamling banjir ikut menemani. Sehingga orang luar mudah dikenali. Bersama-sama mereka berpatroli. Bergerak dengan penuh antisipasi. Berkeliling sehari tiga kali. Sore, malam dan pagi hari. Sementara dua perahu karet berseliweran kesana-kemari. Mereka sedang mencari-cari Pak Ali. Seorang kakek tua yang tinggal di pinggiran kali. Pintu rumahnya tertutup tanpa dikunci. Di meja plastik yang terapung hanya tertinggal sebuah peci. Akhirnya pria gaek itu ditemukan di plafon rumahnya sedang mendekap seekor kelinci.
“Saudara-saudaraku yang kucintai, Jakarta untuk semua. Baik yang kebanjiran maupun yang tidak kebanjiran.” Demikian kata penutup sambutan Pak Gubernur. Acara dilanjutkan dengan makan malam bersama di tempat pengungsian. Nasi uduk dihidangkan. Lauknya telor dan ikan. Di piring besar bertumpuk potongan buah-buahan. Tersedia pula beberapa jenis cemilan.
“Ayo kita beryanyi. Berdendang menghibur hati. Begadang sampai pagi.” Anisa Bahar menghangatkan suasana dengan goyangan patah-patah. Beberapa pemuda ikut berjoget sambil melepas baju. Pak Gubernur tersenyum haru. Melihat rakyatnya bergembira. Tetesan hangat menitik dari kedua sudut matanya. Menerobos garis pipi, kemudian menyelinap dan bersembunyi di balik kumisnya.
Hari-hari di tempat pengungsian diwarnai keceriaan. Sudin Banjir telah menyiapkan. Layar tancap dan bermacam-macam hiburan. Para remaja disibukkan dengan aneka permainan. Ibu-ibu menggoreng tempe. Bapak-bapak membakar sate. Anak-anak main prosotan. Sebagian lagi duduk-duduk di Pos Kesehatan.
Ketiga, pasca-banjir. Air mulai surut. Sebagian besar pergi ke laut. Sebagian diminum oleh mesin-mesin hidran yang mulutnya penuh baut. Dan sebagian lagi diserap tanah hingga menyusut. Tak ada lagi barang-barang yang hanyut. Sampah-sampah sudah mulai diangkut. Agar tidak menyebarkan bau kentut.
Jalanan dibersihkan. Lumpur dipinggirkan. Para pengungsi kembali ke rumah-rumah mereka. Berjalan bersama dalam canda tawa. Pekerjaan berat sudah menunggu di sana. Bersih-bersih rumah. Buang-buang sampah. Lantai dipel. Tembok dibersihkan dari kotoran yang menempel. Barang-barang mulai dicuci dan dijemur. Kiri kanan berendeng jemuran menjulur-julur. Kehidupan normal kembali diulur.
Sudin Banjir membentuk task-force pendampingan korban banjir bekerja sama dengan Sudin-Sudin terkait lainnya. Mereka membantu masyarakat untuk memperoleh kemudahan mengurus dokumen-dokumen yang hilang. Bekerja sama dengan sejumlah ATPM, Sudin Banjir juga memberikan diskon untuk perbaikan mobil dan motor yang terendam. Membersihkan jalan dan jembatan. Menyisir sungai dan selokan. Serta memulihkan sarana dan prasarana umum lainnya. Mereka keluar masuk kampung untuk mengidentifikasi dan memboyong para penderita penyakit pasca-banjir ke rumah-rumah sakit. Namun kali ini rumah sakit tidak lagi sesibuk tahun-tahun sebelumnya. Penyakit pasca-banjir sudah bisa ditekan dan dikendalikan. Karena sesungguhnya mereka hidup sangat normal selama berada di pengungsian.
Keempat, pada saat tidak banjir. Sudin Banjir tak akan bengong saja pada saat Jakarta tidak banjir. Justru ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya, memperbaiki dan merawat peralatan penanggulangan banjir dan perlengkapan pengungsian. Tampak remeh-temeh, tetapi sesungguhnya sangat penting. Setelah banjir pergi, Sony sering melihat perahu-perahu karet digeletakkan begitu saja hingga akhirnya rusak dan usang.
Di samping itu, Sudin Banjir secara rutin dan berkala merawat serta membersihkan sungai dan selokan agar aliran air tidak tersendat atau terjadi pendangkalan. Sehingga dampak banjir bisa diminimalisir. Namun pekerjaan ini membutuhkan koordinasi dan pengaturan bersama dengan kawasan penyangga ibukota. Karena air bah tak pernah mau tahu apakah lagi asyik bermain di wilayah DKI atau di halaman tetangga. Dan Sudin Banjir juga tak pernah bertanya apakah seseorang punya KTP DKI atau tidak pada waktu mereka menolong korban banjir.
Masalah koordinasi dan pengaturan bersama inilah – tentu saja tak hanya dalam soal penanggulangan banjir, tetapi juga berbagai aspek lain terkait dengan hubungan antara ibukota dan kawasan penyangganya – yang mengilhami Bang Yos untuk menggulirkan gagasan gemilang mengembangkan Jakarta metropolitan menjadi Jakarta megapolitan. Gagasan dasarnya adalah mengintegrasikan kawasan penyangga ibukota ke dalam wilayah DKI agar koordinasi dan pengaturannya lebih mudah. Menimbang besaran dan kompleksitas dari gabungan wilayah yang akan diurusi itu, maka diusulkan agar Jakarta megapolitan tidak lagi dipimpin oleh seorang gubernur, tapi pejabat setingkat menteri.
Di sini kelihatan sekali kalau Bang Yos ngebet betul untuk memimpin Jakarta megapolitan yang diidamkannya itu. Karena tak mungkin lagi menjadi gubernur, ya harus kepala daerah setingkat menteri. Seandainya saja gagasan besar itu terwujud, rasa-rasanya memang tidak ada orang lain yang pantas memimpin Jakarta megapolitan selain Bang Yos, mengingat prestasinya yang luar biasa ketika menjadi Gubernur DKI selama dua periode berturut-turut.
Namun, masih relevankah gagasan itu? Jakarta megapolitan? Sebagian orang mencibir sinis. Nggak usah macam-macamlah. Sebagai kota metropolitan saja, Jakarta tak punya bandara internasional. Selama ini numpang ke tetangga. Di kelokan belalai gajah tempampang gambar besar logo Pemprov Banten memelototi semua penumpang yang hendak masuk ke atau keluar dari pesawat. Seolah-olah sedang menyindir, “Ini wilayah gue, loe cuma nebeng.” Sementara di bagian selatan sana, Universitas Indonesia yang dibangga-banggakan masyarakat Jakarta harus kos di Depok.
Tapi jangan salah, banyak juga orang yang menginginkan Jakarta megapolitan terwujud. Lagian, kalau pemekaran daerah saja diizinkan oleh Undang-Undang, apakah penggabungan wilayah tidak dimungkinkan?
Pinggirkan dulu pandangan masyarakat Jakarta. Fokus saja kepada orang-orang yang tinggal di kawasan penyangga ibukota, karena sebenarnya merekalah yang menjadi target pengembangan Jakarta megapolitan. Dengan pola yang ada sekarang, kepentingan dan aspirasi politik penduduk siang yang jumlahnya mencapai lebih dari dua juta jiwa itu sama sekali tidak terakomodasi dalam Pilkada DKI 2007.
Mereka dianggap tak pernah ada. Padahal mereka berkontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi Jakarta, dan juga perekonomian nasional. Hanya kebetulan bila malam tiba mereka pulang dan tidur di luar wilayah DKI. Seandainya dibuat jajak pendapat, atau angket lewat media massa, misalnya, yang menawarkan kepada para penghuni kawasan penyangga ibukota untuk bergabung dengan wilayah DKI atau tetap bergabung dengan provinsi semula, Sony haqul yakin sebagian besar akan menjawab lebih suka bergabung dengan DKI. Tentu saja ada beberapa alasan yang melandasi jawaban mereka.
Pertama, percepatan pembangunan. Dengan bergabung ke dalam wilayah DKI, mereka akan menjadi bagian dari sebuah provinsi yang PAD maupun APBD-nya berukuran raksasa. Bahkan terbilang jumbo dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Sektor pendidikan akan mendapatkan manfaat luar biasa karena Pemprov DKI terkenal sangat royal kepada sektor ini. Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur akan berjalan lebih kencang karena pendanaan sudah tak lagi jadi kendala. Dan, secara psikologis, Pemprov DKI akan memanjakan wilayah-wilayah yang baru bergabung itu agar tidak terlintas sedikitpun dalam pikiran mereka keinginan untuk kembali ke pangkuan provinsi semula. Persis sama seperti pemerintah pusat memperlakukan Papua, Irian Jaya Barat dan Nanggroe Aceh Darrusalam.
Kedua, kepentingan ekonomi. Banyak penduduk yang tinggal di kawasan penyangga ibukota mencari nafkah di Jakarta. Atau, kalau dibalik cara berpikirnya, sesungguhnya mereka adalah warga Jakarta yang tinggal di luar wilayah DKI. Bagi mereka, ini hanya masalah domisili. Kenyataannya, kegiatan ekonomi di kawasan penyangga ibukota digerakkan oleh orang-orang yang bekerja di Jakarta dan sebagian besar ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat Jakarta. Dengan bergabung ke dalam wilayah DKI, secara otomatis mereka akan menjadi bagian dari jaringan pasar yang lebih besar. Sementara efek berganda dari pembangunan yang terus dipacu untuk mengejar kesetaraan dengan kakak-kakaknya akan memberikan darah segar bagi kegiatan ekonomi lokal. Demikian pula, harga tanah akan terkerek naik sehingga nilai ekonominya bertambah tinggi. Para pengembang akan berpesta pora.
Ketiga, identitas dan gengsi. Meski tidak mengantongi identitas formal KTP DKI, misalnya, sebagian besar masyarakat kawasan penyangga ibukota menyandang semua atribut yang dimiliki masyarakat Jakarta. Semua identitas kehidupan mereka berkiblat ke Jakarta, mulai dari gaya hidup, pergaulan, bacaan, kegemaran dan lain sebagainya. Mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat Jakarta.
Perhatikan iklan-iklan properti. Meski mengambil tempat di Depok, misalnya, mereka selalu mengatakan berlokasi di selatan Jakarta. Peta yang dimunculkan pun peta Jakarta, dengan Monas di tengahnya, kemudian ditambahkan anak panah yang menunjukkan di mana lokasi perumahan itu berada. Maka, ketika pulang kampung pada Hari Lebaran, orang-orang yang tinggal di kawasan penyangga ibukota disebut sebagai orang Jakarta oleh para kerabatnya. Mereka sama sekali tidak keberatan disebut begitu. Malahan, bangga. Gengsi mereka akan naik bila disebut sebagai orang Jakarta.
Jakarta metropolitan. Jakarta megapolitan.
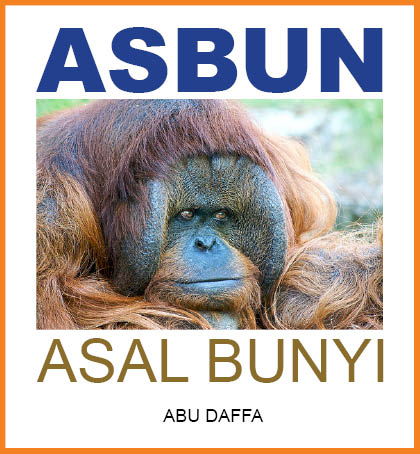
Tidak ada komentar:
Posting Komentar