Pahlawan devisa. Sebutan bagi pekerja yang mengantongi visa. Karena di kampung halaman sudah tak ada lagi pekerjaan tersisa. Berangkat di hari Selasa. Mengarungi samudera membelah angkasa. Menyeberangi laut berbusa. Demi mengejar sepotong asa. Mengadu nasib di mancanegara. Bekerja jauh dari sanak keluarga. Untuk meraih impian hidup bahagia. Merelakan keringat tertumpah. Menjual tenaga demi segenggam upah. Yang terkadang tak pernah ia terima. Dera dan siska sebagai gantinya. Tanpa pernah tahu apa yang salah. Karena posisinya selalu kalah. Pahlawan itu kini terbujur kaku. Tubuhnya dingin dan membiru. Diam membisu di dalam kotak kayu. Tak boleh lagi duduk di kabin penumpang. Tempatnya lorong bagasi barang.
Setiap kali ada pekerja migran Indonesia yang disiksa, diperkosa, atau mati didera, hampir bisa dipastikan di kandang macan mana mereka bekerja, Malaysia, Singapura dan Jazirah Arabia. Namun, setiap tahun bertambah banyak saja pekerja migran yang dikirim ke kandang macan yang berjumlah tiga. Menjadi umpan mudah bagi macan yang siap menerkam dengan mulut menganga. Pemerintah lebih sering memanglingkan muka. Mereka TKI ilegal, katanya. Para pejabat menutup mata. Tak pernah bergerak kecuali dengan kata-kata. Seolah tak pernah ada fakta. Menganggap mereka sebatas angka-angka. Seluruhnya berjumlah sekian. Di negeri sini sekian. Di negara sana sekian. Yang legal sekian. Yang ilegal sekian. Yang kabur sekian. Yang dipenjarakan sekian. Yang diseterika sekian. Yang diperkosa sekian. Yang mati sekian. Hanya bilang kasihan.
Kandang macan pertama menampilkan kebengisan yang menyesakkan dada. Tanpa pernah diusut secara tuntas oleh polisi diraja. Sebagian masyarakat Malaysia memandang sebelah mata orang Indon yang mencari kerja dengan menjadi apa saja. Di negeri jiran itu, mereka dianggap manusia kelas dua. Dijual seperti butiran kelapa. Diperlakukan semena-mena. Ditangkap kapan saja. Disiksa semaunya. Menjadi kambing hitam bila terjadi sengketa antara majikan dan pekerja. Dikurung tanpa pernah diadili. Diperas bayar penalti. Bila perlu ditembak mati di tengah laut. Dijadikan makanan ikan pesut. Sesungguhnya, ini hanyalah sebuah manifestasi. Dari perasaan rendah diri. Mereka iri. Karena artis Indonesia cantik-cantik dan cakep-cakep. Sementara para pesohor mereka wajahnya seperti perawan kampung dan ban serep.
Sony pernah sekali pergi ke Malaysia. Kunjungan iseng tanpa peta. Hanya berwisata. Sekalian mengunjungi teman lama. Pergi sendirian saja. Tapi dia merasa tak betah di sana. Seseorang berseragam menghentikan langkahnya. Tatapan matanya kurang bersahabat. Seperti sedang merazia penjahat. Tangan kirinya bergelang kawat. Tangan kanannya menggaruk-garuk sesuatu di balik cawat. Wajahnya penuh jerawat. Berminyak dan tak terawat. Kumisnya tidak terlalu lebat. Tapi sepatunya mengkilat. Kayaknya baru dicat. Dari balik bajunya sepucuk pestol mencuat. Sungguh, pengalaman laknat. Ketemu oknum bejat. Mencecar pertanyaan-pertanyaan sesat. Dunia serasa mau kiamat. Rencana makan malam jadi telat.
Keesokan paginya Sony langsung cabut. Seumur hidup, tak mau lagi dia pergi ke kandang macan itu. Meski diberi tiket, uang saku dan disediakan kamar hotel supermewah. Mending ke kebon binatang. Ketemu Agnes, pacar barunya.
Tak mengherankan bila hubungan bilateral Indonesia-Malaysia selalu naik turun seperti ayunan di TK Melur. Sesekali naik, sering kali menghujam bagai sangkur. Rentan seperti kulit luar sebutir telur. Terkadang menggelinding liar membentur-bentur. Meluncur-luncur. Beberapa bagian retak dan hancur. Ketika majikan mencelakai orang yang kerja di dapur. Hanya karena salah menyajikan bubur. Kepada kakek yang sudah uzur. Layu seperti seikat sayur. Tergolek lemah di kasur. Sebentar lagi masuk kubur.
Cemeti langsung diulur. Lidahnya menjulur-julur. Suaranya mengguntur. Melukis garis-garis lurus membujur. Di punggung kurus yang melengkung seperti busur. Badan berbilur-bilur. Kucuran keringat menjadikan darah luntur. Semua persendian terasa kendur. Babak-belur. Tak mampu lagi kabur.
Tak hanya urusan pekerja migran Indonesia dizalimi, dalam banyak soal negeri jiran itu merasa superior. Meski dalam soal budaya selalu mengekor. Kepada saudara tuanya yang selalu tekor. Dan, berwajah jontor. Sering kali anak bawang itu berlagak seperi mandor. Bertamu sambil menggedor-gedor. Muka melengos masuk dengan kaki kotor. Kepala mendongak air seni menggelontor. Sayang, lupa tak pakai kolor.
Indonesia lebih suka mengalah. Bahkan ketika beberapa pulaunya ditilep dengan konspirasi gajah. Tentara gatal tangannya mau menembak. Senapan tak sabar ingin menyalak. Tapi pemerintah memilih menyingkirkan tombak. Meski harus berjalan di tengah ladang penuh onak. Dengan harga diri yang koyak. Nurani yang berontak. Meredam amarah yang bergejolak. Agar tak menjadi amuk yang menggelegak. Karena amunisi sudah memenuhi geladak. Tinggal disulut sumbunya pasti langsung meledak.
“Ganyang Malaysia.” Slogan pemompa nasionalisme yang begitu menggetarkan pada masa konfrontasi itu selalu muncul kembali setiap kali Indonesia bersinggung punggung dengan Malaysia. Pintar sekali Bung Karno mengocok kata-kata. Sederhana, tapi mobilizing, mengerakkan semua. Bahkan badak bercula satu dan orangutan dengan sukarela akan ikut angkat senjata.
Sony sependapat dengan sebagian orang, sesekali negeri congkak itu perlu diberi pelajaran. Dijewer kupingnya. Dipukul bokongnya. Orang diam bukan berarti takut. Hanya mencoba bersikap patut. Tapi jangan sembarangan kentut. Kalau tak mau dijadikan campuran sayur bakut.
“Tuan, tolong jangan berperilaku biadab. Kami orang-orang beradab. Tuan, berhentilah menganiaya. Kami bangsa berbudaya. Perbaiki perangai Tuan. Atau, kami yang akan meluruskan.”
Lain Malaysia lain lagi Singapura negeri makelar. Lobang hidungnya selalu mekar. Rambutnya kasar. Berkibar-kibar. Taringnya setajam cakar. Ekornya setengah melingkar. Memang, kadang macan kedua ini relatif kurang sangar. Tapi tak boleh disikapi dengan biar. Bisa-bisa tambah kurang ajar. Banyak saudara sebangsa merintih di sana karena dihajar. Disekap di dalam kamar. Sebagian malah masuk sangkar. Dan sebagian lagi pulang dibungkus tikar. Disisipkan uang beberapa lembar. Sebagai pengganti harapan yang telah buyar. Hati serasa terbakar. Melihat belati, tangan ingin menyambar. Tapi harus dicari jalan memutar. Karena Indonesia bukan bangsa barbar. Meski sering menderita luka dan memar. Lebih baik dibicarakan di dalam hanggar. Agar bara tidak semakin melebar. Hanya karena beberapa orang sudah tak sabar. Ingin menampar.
Kandang macan ketiga berada nun jauh di sana. Di tanah kerontang raja dahaga. Miskin air kaya minyaknya. Penduduknya gemar makan kurma. Menyantap daging domba. Ke mana-mana naik onta. Jazirah Arab namanya. Sebagian masyarakatnya masih menganut tradisi lama. Pekerja migran dianggap hamba sahaya. Dinilai sebagai harta. Ditimbang seperti tumpukan kain perca. Diperlakukan semaunya. Disentuh seenaknya. Di bagian dada. Di bagian paha. Karena telah dibeli dengan materai bergores pena. Perkosaan merajalela. Persis seperti perilaku kuda. Birahi dibiarkan menjadi raja. Atas nama tradisi yang bermuka dua. Diambil sisi enaknya saja. Sehingga korban dengan mudah menjadi tersangka. Dikurung di ruangan tanpa jendela. Tanpa seorang pun yang datang membela. Hakim telah menetapkan kata. Hukuman pancung menggelindingkan kepala.
Pahlawan devisa. Sebutan membanggakan itu begitu gampang meluncur dari mulut yang penuh busa. Tak seperti kenyataan pahit yang kerap mereka hadapi di luaran sana. Ketika siksa mendera. Ketika tamparan melukis wajah. Ketika sepiring makanan basi diberikan sebagai hadiah. Ketika tangan-tangan gatal majikan pria dengan penuh birahi menggerayangi tubuhnya. Ketika air mendidih disiramkan ke muka. Ketika setrika panas menggosok punggung. Ketika cambuk mengayun bergulung-gulung. Ketika raga meregang nyawa.
Mereka tak tahu harus mengadu kepada siapa. Tak tahu harus berlindung di mana. Tak tahu harus lari ke mana. Sebagian pulang dengan badan penuh luka. Sebagian malah ketawa-tawa karena gangguan jiwa. Sebagian menanggung malu berbadan dua. Sebagian lagi hanya pulang nama. Sampai kapan kita akan menutup mata? Menyaksikan anak bangsa mati disiksa. Kejadian seperti ini senantiasa berulang. Dan terus berbilang.
“Seperti lingkaran setan,” kata Heru dengan geram. “Padahal mereka telah berjasa besar mengurangi angka pengangguran di dalam negeri dan membawa masuk devisa yang jumlahnya hanya bisa dikalahkan oleh sektor migas. Itu pun belum dihitung dengan pemasukan devisa yang tidak tercatat dalam sistem perbankan dan jalur formal lainnya karena dibawa pulang dengan cara-cara tradisional. Bisa-bisa malah mengalahkan pendapatan devisa dari sektor migas,” dia menambahkan dengan berapi-api.
Heru sedang terlibat diskusi panas dengan Sony soal pekerja migran Indonesia. Sony mengiyakan pendapatnya. Tapi dia balik bertanya, “Memangnya, lingkaran setan itu apa, Her?”
Dengan tangkas Heru menjelaskan ucapannya, “Lingkaran setan adalah persoalan yang tak pernah bisa diselesaikan karena masalahnya terus berputar. Gambarannya begini, Pak. Tikus takut sama kucing. Kucing takut sama anjing. Anjing takut sama harimau. Harimau takut sama pemburu. Pemburu takut sama istrinya. Istri pemburu takut sama ibu mertua. Ibu mertua takut sama tikus. Berputar-putar terus. Tidak selesai-selesai. Masa, Pak Sony tidak tahu?”
Setelah Depnakertrans menyerahkan urusan pekerja migran kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) – tak lebih dari sekedar pelepasan organisasi – yang hingga kini belum juga kunjung pinter mengurusi, apalagi melindungi, para TKI, sudah saatnya dibentuk Kementerian/Departemen Pekerja Migran. Lembaga baru ini harus benar-benar bersih dari orang-orang lama yang gemar dengan status quo. Baik menterinya, pejabat eselonnya, karyawannya, hingga tukang sapunya. Semuanya harus orang baru. Tak boleh ada kaitan sedikit pun dengan mereka yang selama ini tak pernah becus mengurusi pekerja migran. Harus dipotong satu generasi. Seperti ketika Presiden SBY mengambil sikap tegas untuk tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru di IPDN selama setahun untuk memutus lingkaran setan kekerasan yang melingkupi sekolah calon camat itu.
Persoalan pekerja migran tidak pernah tuntas karena banyak pihak menghendaki demikian. Terlepas dari masih banyaknya TKI ilegal, posisi tawar PJTKI, baik yang lurus maupun yang culas, sangat lemah di hadapan agen penempatan pekerja migran di luar negeri. Dengan mudah mereka ditekan bila terjadi sesuatu yang tak normal atas pekerja migran Indonesia (yang legal). Dipaksa tidak membesar-besarkan persoalan yang dianggap ecek-ecek itu. Ancamannya, quota dipotong atau tidak bisa melakukan pengiriman lagi. Tentu saja, PJTKI keder dan memilih bungkam. APJATI akan segera melobi para pejabat agar tidak mengangkat permasalahan itu ke permukaan.
“Ini soal kecil. Satu di antara sejuta,” kata mereka. Angka-angka statistik membela mereka.
Ya, Tuhan! Sekalipun satu, itu insan. Bukan hewan. Bukan pula sekedar bilangan. Tapi karena sudah rutin mendapat setoran, para oknum tak berhati nurani memilih diam. Kalaupun bergerak, hanya mulutnya. Biar kelihatan kerja. Hayo …, berubah! Jangan bikin repot Presiden melulu.
Kementerian/Departemen Pekerja Migran yang baru harus merestrukturisasi hubungannya dengan PJTKI. Dari hubungan patron-klien, dikembalikan lagi menjadi sebentuk interaksi antara regulator dan pelaku usaha. Hentikan perselingkuhan bertumbal. Stop perilaku Dajal. Dari titik baru inilah bisa mulai dilakukan penataan dan pemetaan ulang semua PJTKI. Yang asal-asalan dibubarkan saja. Kalau perlu diracun pakai sambal superpedas. Biar perutnya mulas-mulas. Yang bagus dibina dan dibantu memperkuat posisi tawarnya terhadap agen penempatan pekerja migran di luar negeri, melalui jalur government-to-government dan semua akses yang bisa diberdayakan. Karena sebagian besar persoalan berada di luaran sana. Apabila di luar sudah beres, akan lebih mudah menata yang di dalam. Agar pekerja migran tidak lagi menjadi pekerja migren.
Kementerian/Departemen Pekerja Migran yang baru juga harus mampu meminimalisir dan secara bertahap menihilkan TKI ilegal, karena dari sinilah pokok persoalan sering kali bersumber. Mereka, para TKI ilegal itu, rentan sekali terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Ini sangat crucial. Harus segera ditangani. Lha wong TKI legal saja juga sering ketimpa sial, apalagi yang ilegal.
Sebenarnya bukan salah mereka menjadi TKI ilegal. Mereka tidak punya pilihan, karena biaya keberangkatan melalui jalur formal memang sangat muaahal. Di sinilah sebenarnya Kementerian/Departemen Pekerja Migran yang baru dapat mengambil peran. Sistem penempatan dan pemberangkatan TKI harus diubah total. Dalam sistem baru, biaya pemberangkatan dan penempatan dibebankan kepada tiga pihak – yaitu, calon TKI, PJTKI dan pemerintah – secara merata ataupun secara proporsional. Dana talangan tersebut harus dikembalikan oleh TKI dengan mencicil dari gaji bulanan mereka selama enam bulan sampai satu tahun hinggal lunas. Tidak seperti selama ini, di mana seluruh biaya keberangkatan harus ditanggung sendiri oleh calon TKI. PJTKI cuma bermodal dengkul.
Dengan cara ini, secara bertahap jumlah TKI ilegal bisa diminimalkan, dan akhirnya dinihilkan, karena mereka tidak perlu lagi menyiapkan dana yang terlalu besar untuk bekerja di luar negeri. PJTKI juga akan terseleksi secara alamiah. Mereka yang cuma bermodal dengkul dan tidak profesional akan tergerus dengan sendirinya. Sedangkan pemerintah sebagai salah satu pihak yang turut andil dalam membiayai keberangkatan TKI otomatis harus ikut memantau TKI yang ditempatkan agar duitnya bisa kembali dan menjadi dana bergulir bagi calon-calon TKI berikutnya. Karena harus terus memantau keberadaan para TKI di luar negeri, Kementerian/Departemen Pekerja Migran yang baru tersebut perlu menempatkan Atase Pekerja Migran di setiap KBRI di mana terdapat TKI yang sedang bekerja.
Namun persoalan ketenagakerjaan Indonesia tidak melulu berkaitan dengan para TKI yang bekerja di luar negeri. Di dalam negeri pun, persoalan ketenagakerjaan tidak kalah peliknya. Bahkan, boleh dibilang carut-marut. Kalau tak mau dibilang rumet, rumit dan bikin kepala mumet.
Departemen Tenaga Kerja memang makhluk yang luar biasa aneh. Setelah Departemen Transmigrasi dilikuidasi dan kemudian dicangkokkan ke ketiaknya, dia memanjangkan nama menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat Depnakertrans. Jaka Sembung, alias kagak nyambung. Urusan transmigrasi mestinya diplesterkan ke punggung Departemen Sosial, karena ia lebih banyak bersentuhan dengan soal-soal yang mengurai problematika sosial. Biar Depnaker bisa konsentrasi mengurus masalah tenaga kerja. Karena departemen yang satu ini agak telmi dan tabiatnya sedikit pemalas. Bertahun-tahun tak pernah mau belajar. Hanya asyik bermain gitar. PR selalu dikerjakan oleh ibunya. Walhasil, setiap kali menerbitkan aturan baru, selalu saja mengundang reaksi menyimpang dari dua pihak, pekerja dan pengusaha.
Para pengangguran berbusana necis yang justru berkantor di Depnakertrans sesungguhnya tidak pernah bekerja sepanjang para pekerja dengan wajah marah menarik garis demarkasi terhadap pengusaha. Demikian pula sebaliknya. Mereka saling bersiasat. Merentangkan pagar kawat. Mulut bertukar hujat. Padahal mereka bukanlah orang-orang jahat. Hanya saja, masing-masing takut dikepret dari belakang. Lengah sedikit bokong ditendang. Karena sang wasit asyik merapikan ikatan dasi. Mengusap-usap pantalon hitam yang begitu serasi. Seraya mengelus-elus jambul yang seksi. Urusan mendesak dibiarkan terbengkalai di lemari. Karena tak paham bagaimana menanak nasi. Beras setengah matang didiamkan di kuali. Akhirnya basi. Bau tak sedap merembes dari kisi-kisi. Menyuburkan jamur dan bakteri. Bikin keracunan orang-orang yang mengkonsumsi.
Sesungguhnya pekerja dan pengusaha adalah saudara kandung. Di tubuh mereka mengalir darah yang sama, merah. Membutuhkan udara yang sama, untuk bernapas dan memompa ban mobil. Makanannya juga sama, nasi berlauk semur jengkol, dengan ikan cuek dua ekor. Tujuannya sama, mencari nafkah. Hanya faktor kepemilikan yang membedakan mereka. Dan, otomatis, juga soal pendapatan. Tapi itu hukum ekonomi semata. Tidak perlu menempatkan diri dalam posisi yang berseberangan. Aku di sini kau di sana. Saling curiga. Merasa saling dimanfaatkan dan memanfaatkan. Pengusaha juga mati kutu tanpa pekerja. Sedangkan pekerja akan kesulitan menjual jasa apabila tidak ada pengusaha yang membuka lapangan kerja. Sama-sama saling membutuhkan. Tak perlu dikotori dengan prasangka yang bukan-bukan. Apalagi dikompori dengan omongan-omongan menyesatkan. Ayo …, bergandengan tangan. Bersalam-salaman. Berpeluk-pelukan.
Mereka pun bersalam-salaman dengan perasaan haru. Berpeluk-pelukan dengan tatapan mata sayu. Salsa menangis seharian. Tak mau makan. Dia sangat sedih. Orang yang selama ini dianggapnya sebagai kakak akan pergi. Sedangkan Rizky, terlihat diam saja. Sesekali dia mengucek mata. Sony tak tahu apa yang ada di dalam benak anak lelakinya. Titin pamit pulang. Emak-nya sudah menemukan jodoh untuknya. Tujuh tahun bekerja sebagai pembantu di rumah Sony, semenjak Salsa masih bayi, dia sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Tapi tidak dalam soal gaji. Sony selalu memberikan kenaikan gaji sepuluh persen setiap tahun. THR tak pernah terlewatkan sekalipun. Minimal satu kali gaji. Atau dua kali gaji, kalau lagi banyak rezeki. Sedang biaya mudik gratisan. Karena Titin bertetangga dengan Sony di kampung halaman.
Di perumahan di mana keluarga Sony tinggal, Titin yang berkulit legam dan berambut pendek itu tergolong pembantu bergaji besar. Dalam usianya yang masih belia, dia sudah mampu merenovasi rumah keluarganya di kampung halaman sana. Perhiasannya juga lumayan banyak. Disimpan di kotak disket di kamarnya. Pakaiannya bagus-bagus.
Pernah, beberapa sejawatnya iri kepadanya, dan kemudian mengajukan protes kepada majikan masing-masing. Malah, pakai mogok kerja segala. Menuntut gaji yang sama dengan gaji Titin. Prahara pun bermula. Akibatnya, sejumlah ibu-ibu lapor ke Pak RT, mendesaknya agar menegur keluarga Sony, karena dianggap mengganggu ketenteraman lingkungan dengan merusakan pasaran gaji pembantu.
Febriana, istri Sony, tak tahan. Telinganya merah sepulang dari arisan bulanan. Disindir oleh ibu-ibu. Meski ada juga beberapa orang yang membelanya. Tapi Sony tetap pada pendiriannya. Ini urusan domestik. Masalah kedaulatan republik. Tak boleh dikutak-katik. Tapi protes semakin bergema. Daripada harus berperang melawan tetangga, dicarilah jalan tengah. Titin pun di-briefing.
“Kamu ngomong saja sama teman-temanmu. Gajimu sudah diturunkan. Juga soal libur satu hari dalam seminggu itu. Bilang sudah dihapuskan. Pura-pura saja. Biar tidak ribut ini komplek.”
Titin setuju belaka. Dia sadar telah keceplosan omongan dan terlalu berterus-terang, sehingga menimbulkan gonjang-ganjing dalam hubungan pembantu-majikan. Syukurlah, setelah hampir sebulan masalah itu akhirnya reda juga.
Sony tak habis pikir, bagaimana mereka bisa sesewot itu. Dia hanya mencoba memanusiakan pembantu. Tapi tetap saja dianggap salah. Padahal pembantu rumah tangga bekerja lebih dari dua belas jam dalam sehari. Tujuh hari penuh dalam seminggu. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan penghargaan yang layak. Baik dalam hal fasilitas, perlakuan dan pendapatan.
Sebagai misal, kamar Titin dilengkapi radio-tape dan TV empat belas inci. Fasilitas ini diberikan karena Titin terlihat kurang nyaman dan agak sungkan bila nonton TV bareng di ruang keluarga. Apalagi Sony punya kebiasaan buruk pindah-pindah saluran. Sehingga sering berantem dengan istri dan kedua anaknya, yang akhirnya mengungsi ke kamar masing-masing untuk menonton acara kesukaan mereka di TV yang lebih kecil.
Demikian pula perlakukan keluarga Sony yang dianggap terlalu memanjakan pembantu oleh para tetangga, karena memberikan libur sehari dalam satu minggu kepada Titin. Bagi Sony, ini sama sekali tidak berlebihan. Toh, Titin jarang-jarang memanfaatkan hari liburnya. Lagian, kalau setiap hari hanya berkutat di rumah, bagaimana mereka bisa melihat dunia luar dan cari pacar? Apakah mereka tidak berhak mendapatkan pasangan?
Titin saja sudah dua kali pacaran. Pertama dengan Dahlan, tukang ojek di gerbang depan. Akhirnya putus, karena pemuda ceking itu ternyata mata keranjang. Kedua, dengan Tukijan, supir Sony. Tapi yang ini dipotong di tengah jalan oleh Sony, karena Tukijan sudah beristri, anaknya dua masih kecil-kecil. Keduanya dijewer oleh Febriana. Dicuci habis pakai Rinso. Hingga putih bersih. Dengan ancaman yang tidak main-main, bubar atau dikeluarkan.
Kini, Titin akan pergi. Di kampung telah menunggu calon pasangan hidupnya. Sugito, tukang becak yang tinggal di belakang rumahnya. Mudah-mudahan pemuda itu menjadi suami yang baik baginya. Sony tak kuasa berkata-kata. Istrinya sama saja. Matanya berkaca-kaca.
“Tin, baik-baik ya, di sana. Salam untuk emak-mu dan calon suamimu. Ini, saya beri pesangon tujuh kali gaji,” kata Sony dengan suara terbata-bata.
“Iya, Pak. Terima kasih,” jawabnya, sambil menadahkan tangan dan mengucurkan air mata.
Sementara Febriana yang terus-menerus kelilipan, mengulurkan sebuah amplop sambil berpesan, “Tin, aku ada uang lima juta. Mudah-mudahan cukup untuk biaya pernikahanmu. Sering-sering telepon ke sini, ya. Biar Rizky dan Salsa tidak kesepian. Jadi obat kangen buat mereka.”
Kedua perempuan itu kemudian saling berpelukan. Bertangis-tangisan. Sama-sama menumpahkan air mata. Lantai basah semua.
Pembantu. Pembantu. Pembantu. Sebagian orang suka menyebutnya babu. Belum lagi sebutan sinis lainnya, yang terkesan merendahkan, seperti jongos, kacung, bedinde, pesuruh, buruh dan lain sebagainya. Padahal mereka orang-orang yang sangat berjasa, dan luar biasa vital keberadaannya. Sony merasakan sendiri. Bila salah seorang karyawannya tidak masuk kerja, dia tak terlalu pusing asal ada alasan yang jelas. Tapi, bila Usep, office boy yang kocak itu, absen, kantor langsung lumpuh. Cari minum susah. Mau makan siang susah. Sampah menggunung. Piring dan gelas kotor semua. Pendeknya, minta ampun.
Begitu pula pada musim mudik Lebaran. Pembantu pada pulang. Banyak keluarga yang kelimpungan. Berhari-hari menyantap makanan kalengan. Sebagian terpaksa makan di restoran. Belum lagi soal cucian. Juga seterikaan. Punggung patah menyapu halaman. Encok kumat mengurus binatang piaraan. Karena tak tahan, akhirnya mengungsi ke penginapan.
Banyak orang bekerja sebagai pembantu karena tak punya lagi pilihan. Itulah pekerjaan yang paling gampang mereka dapatkan. Meski imbalan yang diterima sering kali tak sepadan. Dibanding kucuran keringat yang membasahi badan. Bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan. Kemudian membereskan cucian. Dilanjutkan dengan bermain tarik-ulur bersama gosokan. Siang malam disibukkan oleh pekerjaan. Mulai dari memasak hingga menjaga kebersihan. Istirahat tak lagi jadi perhitungan. Namun mulutnya tak pernah menyuarakan keluhan. Menerima apa adanya tugas yang dibebankan. Tak pernah sedikit pun berpikir soal masa depan. Yang penting tenaganya masih dibutuhkan. Sebagian malah menekuni profesinya hingga kepalanya penuh uban. Sebagian lagi tetap setia dengan panggilan jiwanya hingga hayat berpisah dengan badan.
Sony suka sedih mendengar berita-berita mengenai pembantu yang dianiaya. Gaji tak terbayar, badan penuh memar. Makan tak diberi, berhari-hari dikunci di kamar mandi. Geram hatinya. Menitik air matanya. Maka, dia berkirim surat kepada Presiden, dengan tembusan kepada Menakertrans. Karena sudah berkali-kali SMS-nya tak berjawab. Dia tulis surat itu dengan tinta jelaga yang diaduk dengan air mata. Tanda tangannya berbentuk sebuah crying face. Tak lupa dia sisipkan sepotong baju Titin yang tertinggal di rumahnya.
“Pak Presiden, tolong dong, ditunjuk seorang Dirjen PRT. Agar para pembantu rumah tangga di seluruh Indonesia mendapatkan penghargaan, perlindungan dan perlakuan sewajarnya. Dibuatkan standar gajinya. Ditentukan hak cutinya. Diberikan hari liburnya. Diperjuangkan nasibnya. Diangkat martabatnya.”
Jangan mentang-mentang mereka diam saja maka majikan bisa berlaku semena-mena. Kalau perlu kumpulkan beberapa PRT senior dari seluruh penjuru tanah air untuk diangkat menjadi staf ahli Pak Dirjen. Biar mereka memberikan masukan-masukan berharga bagi Direktorat Jenderal yang baru itu.
Surat itu tergeletak begitu saja di meja. Isinya singkat. Pemberitahuan pengunduran diri. Orangnya sudah tak nongol lagi. Padahal kemarin sore, pada saat gajian, Sony masih sempat berbicara dengannya. Menanyakan salah satu pekerjaan yang sudah harus selesai empat hari lagi.
Palgunadi, karyawan di Bagian Produksi, memilih kabur begitu saja tanpa merasa perlu bertemu dengannya. Sony agak kecewa. Sesungguhnya dia tak berharap berlebihan. Kalau masuknya dengan cara baik-baik, mestinya pergi dengan cara yang baik pula. Minimal ada pemberitahuan sebulan sebelumnya. Toh, Sony tak pernah melarang, apalagi menahan, orang yang mau mengundurkan diri. Biasa saja. Itu terjadi di mana-mana.
Sudahlah, tak perlu dimasukkan ke dalam hati. Beberapa karyawan mengatakan kepadanya, lulusan Universitas Diponegoro itu diterima bekerja di sebuah perusahaan raksasa di daerah Kuningan. Syukurlah kalau begitu.
Bukan sekali dua kali hasil didikan keras Sony dipanen orang lain. Palgunadi hanyalah salah satunya. Tapi Sony tak terlalu mempermasalahkannya. Dia ikhlas saja. Itu merupakan salah satu kontribusinya sebagai warga negara untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai bagi perusahaan lain. Asal tidak keterusan saja. Bisa kuwalat mereka. Sebab, sebagai pengusaha kecil, Sony cukup tahu diri untuk tidak merekrut tenaga kerja yang sudah jadi.
Makanya, dia telaten mencari bibit-bibit unggul yang kemudian dia godok dengan air garam. Tak lupa diceburkan tiga lembar daun salam. Juga selembar celana dalam. Direbus bermalam-malam. Hingga lebam-lebam. Dalam waktu tiga bulan, paling lama, seorang fresh graduate akan menjelma menjadi pekerja yang mumpuni di tangan Sony. Tapi dia tak pernah mencegah kutu loncat lari dari kantornya. Itu sudah garis tangan mereka. Dia hanya berdoa. Mudah-mudahan mereka menjadi anak manis, dan tidak nakal di luaran sana.
Tapi, kadang-kadang karyawan mau menangnya sendiri. Pernah Sony membuat peraturan baru karena beberapa karyawan suka titip absen padahal datang terlambat. Dia kumpulkan seluruh karyawannya dalam rapat paripurna. Sony meminta mereka berkata jujur, siapa yang suka nitip absen dan siapa yang sering dititipi absen. Tidak akan dikenai sanksi. Hanya perlu diperbaiki. Agar tidak menjadi tradisi.
Tak seorang pun mengaku. Resepsionis, yang mestinya paling tahu soal ini, karena mesin absen berada di samping mejanya, malah ketakutan. Sepertinya Amelia diancam, agar tidak membocorkan rahasia. Demikian pula Anita, yang setiap hari memeriksa absensi terkait dengan tugasnya menghitung uang makan. Wajahnya agak kecut karena dimusuhi beberapa karyawan. Ketika Sony panggil mereka berdua ke dalam ruangannya untuk menanyakan soal itu, mereka memilih bungkam. Inikah yang namanya solidaritas karyawan?
Biasa. Di mana-mana begitu. Namanya juga karyawan. Macam-macamlah kecurangannya. Sony mahfum adanya. Nyolong-nyolong sedikit dia biarkan. Asal tidak keterlaluan. Dia juga tahu klaim bensin terkadang aneh-aneh. Anita bahkan pernah menemukan sebundel bon bensin kosong tertinggal di mejanya. Tapi, yang bikin Sony gusar adalah kebocoran telepon. Dua bulan berturut-turut. Biayanya bengkak lebih dari delapan juta. Setelah di-print, ketahuan ada yang suka ngendon di kantor hingga malam hari untuk menelepon nomor esek-esek.
Penjaga malam langsung menunjuk hidung Rofi’i, orang Produksi yang belakangan suka lembur sendirian. Tinggal digelandang. Rofi’i mengaku. Minta ampun supaya tidak dipecat. Dia bersedia mengganti semua kerugian dengan dipotong gaji. Anehnya, besoknya dia ngilang. Tak pernah datang ke kantor lagi.
Tapi ada juga kecurangan yang benar-benar keterlaluan. Heru pernah bercerita kepada Sony mengenai Heri, kakaknya yang menjadi Penyelia Produksi di sebuah pabrik perakitan elektronik. Karena pusing mengurus pekerja-pekerja yang curang dan banyak ulah, dia stres dan akhirnya mengundurkan diri. Malu kepada manajemen.
Bagaimana tidak, mereka selalu mencari berbagai cara untuk memperlambat pekerjaan, bahkan dengan menjaili mesin. Tujuannya, lembur. Target produksi memang terpenuhi, tapi harus lembur setiap hari. Tak mungkin tambah shift, karena yang demikian berarti harus merekrut pekerja tambahan. Terlalu berisiko untuk order dadakan. Jadilah Heri ikut-ikutan lembur saban hari. Pola hidup jadi tak normal. Mending mundur teratur. Daripada babak belur. Kurang tidur.
Lembur boleh-boleh saja. Sesekali perlu dilakukan. Apalagi kalau tengat waktu sudah menampakkan taringnya. Tapi, kalau setiap hari lembur, berarti ada masalah. Boleh jadi karena cara kerjanya kurang efektif. Atau, mungkin saja, jumlah dan kapasitas SDM-nya tidak mencukupi.
Sesungguhnya, kerja lembur yang keterusan sama sekali tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menciptakan persoalan baru. Manusia pada dasarnya mempunyai keterbatasan. Ketika bekerja dari jam delapan pagi hingga pukul lima sore, kapasitasnya masih seratus persen. Apabila diteruskan hingga pukul sembilan malam, kapasitasnya tinggal lima puluh persen. Bila dilanjutkan lagi hingga tengah malam, sesungguhnya kapasitasnya tinggal dua puluh persen. Apalagi kalau digeber sampai pagi. Mereka bekerja dengan kapasitas cuma sepuluh persen. Apa yang bisa dihasilkan dengan kapasitas sekecil itu?
Lebih gawat lagi, setiap kali habis lembur, datangnya selalu telat. Tidur dulu, alasannya. Sehingga jam kerja dimulai siang hari, dan bahkan sore hari. Kalau terus-terusan begini, namanya menggeser jam kerja. Bagaimana mau berkoordinasi dalam teamwork? Mereka bekerja pada saat orang lain lagi enak-enaknya tidur di malam hari. Pagi hari, pada saat orang lain sibuk bekerja, mereka pada ngorok sambil ngiler di gudang bawah. Jarang mandi lagi. Celana dalam sudah side B. Andalannya cuma minyak wangi. Hal seperti itulah yang mendorong Sony agak ketat dalam soal absensi. Karena orang Pemasaran pernah komplain. Pagi-pagi klien sudah tanya ini-itu, tapi orang-orang Produksi belum pada nongol. Jadi tengsin. Bisa kabur itu peluang. Urung dapat bonus. Gondok mereka.
Tapi tak semua karyawan suka berulah. Sony paling salut kepada karyawannya di Bagian Pemasaran. Mereka semua pekerja keras. Saling bersaing satu sama lain, sehingga tak sedikit pun punya waktu luang untuk bertingkah aneh-aneh. Motivasi mereka hanya bonus. Siapa yang mendapatkan paling banyak bonus dialah raja. Tak peduli orang baru atau lama. Ukurannya hanya angka-angka.
Heru Wibowo, Manajer Pemasaran di kantor Sony, hanya jebolan SMA. Tapi dia orang yang luar biasa. Tidak kalah dengan anak buahnya yang hampir semua lulusan sarjana. Meski bicaranya suka belepotan, dia mampu menutupi kekurangannya dengan kepiawaiannya menyihir manusia. Terlebih lagi, dia ahli menyerap ilmu orang dalam sekejap. Meski baru kenal, dijamin, orang itu akan segera menjadi sahabatnya. Itulah Heru, orang Semarang yang sudah pernah melakoni semua jenis pekerjaan di ibukota. Seperti Tukul, manusia setengah monyet yang jenaka itu.
Sony pernah sekali merekrut seorang pemasar jebolan perusahaan besar. Hernawan namanya. Langsung dia tempatkan pemuda yang menyandang gelar pasca-sarjana dari Amerika itu sebagai wakil Heru. Harapan Sony, agar ilmunya dicuri habis-habisan sama Heru. Memang benar, Heru mengakui, ini orang ilmunya sangat tinggi. Tapi tidak sakti. Buktinya, selama enam bulan tak pernah bikin transaksi. Barang sebiji. Cuma pintar teori. Padahal gajinya bergerigi. Akhirnya dipersilahkan pergi. Setengahnya dia juga malu sendiri.
Sony menduga, selama ini karir itu orang moncer di tempat kerja sebelumnya karena perusahaan tersebut sudah mapan. Dia tak pernah menghampiri pelanggan. Sebaliknya, pelanggan yang datang kepadanya. Hanya menunggu. Kalau cuma beginian, tak perlu lulusan luar negeri.
Kasus seperti ini sering terjadi. Beberapa orang hebat dari perusahaan raksasa seperti mati kutu ketika memulai usaha sendiri atau pindah kerja. Kesaktiannya luntur begitu saja setelah tak lagi menjadi bagian dari institusi yang membesarkannya. Mereka kelihatan sakti hanya karena perusahaan tempatnya bekerja sudah well-established. Jadi, yang sakti sebenarnya perusahaannya. Bukan orangnya.
Banyak contohnya. Tak perlu sebut nama. Pasti yang bersangkutan manggut-manggut dan mengakui sendiri. Tapi banyak juga perkecualian. Misalnya, almarhum Cacuk Sudaryanto. Ini orang memang jagoan. Berlaga di mana saja tetap saja sakti mandraguna. Sesungguhnya, Sony pernah punya karyawan jenis ini. Sayang, setelah menikah, dia mengundurkan diri. Ikut suaminya yang melanjutkan sekolah ke luar negeri.
“Ke luar negeri? Kapan?” tanya Sony.
“Kemarin berangkatnya, Pak. Pulangnya seminggu lagi,” jawab Sandy, sekretarisnya.
Pagi itu Sony minta tolong sama si Belanda Depok agar disambungkan dengan Pak Ferdy, kliennya di Surabaya. Ternyata dia pergi ke Amerika Latin. Mendampingi Direktur Utama menghadiri simposium gula internasional. Ya sudah. Berarti harus menunggu minggu depan. Padahal ada pekerjaan yang membutuhkan approval Pak Ferdy. Tidak bisa digantikan orang lain. Pesannya sudah begitu. Mau dikata apa.
Pak Ferdy bukan klien biasa. Kebetulan, adiknya teman lama Sony. Pernah sekantor di daerah Sudirman di masa lalu. Bagi Sony, Pak Ferdy adalah sahabat sekaligus teman mengobrol yang mengasyikkan. Wawasannya luas. Analisanya tajam. Dan, suka berterus-terang.
Bulan lalu, mereka berdiskusi soal pekerja di perusahaan perkebunan pelat merah yang memproduksi gula, cemilan legit kegemaran semut itu. Sony bertanya kepada Pak Ferdy, kenapa perusahaan tempatnya bekerja piara karyawan hingga belasan ribu orang. Padahal mereka sibuk pada saat musim giling saja. Belum lagi karyawan kampanye, yang jumlahnya seperti rayap itu. Seandainya pola budidaya diintensifkan melalui mekanisasi dan dilakukan perbaikan teknologi pada pabrik-pabriknya yang sudah uzur, jumlah karyawan pasti bisa dipangkas hingga tinggal seperempatnya saja. Hari gini, teknologi gula tidaklah mahal. Sangat sepadan dengan efisiensi yang bisa dihasilkan.
Pertanyaan itu sebenarnya sudah lama menggantung di benaknya. Baru kali ini Sony berkesempatan menanyakan langsung kepada orang yang mestinya tahu betul masalah tersebut. Ternyata Sony sok tahu. Dan harus menanggung malu. Pak Ferdy yang wajahnya mirip bintang filem kawakan Herman Felani itu menjawab dan sekaligus mematahkan pertanyaannya secara telak dengan paparan logika yang sangat masuk akal.
Apabila dilakukan mekanisasi, bagaimana nasib ribuan karyawan dan keluarganya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan? Namanya juga BUMN. Ada misi bisnis sekaligus misi sosial yang dibebankan ke pundaknya. Jadi, tidak bisa dilongok dari hitung-hitungan bisnis semata. Demikian pula aktivitas di pabrik, yang sebagian besar mesinnya peninggalan dari zaman Belanda. Bahkan usianya jauh lebih tua dari para pekerjanya. Bila diganti dengan teknologi mutakhir, ribuan orang harus dirumahkan. Padahal, semenjak zaman dulu, yang namanya pabrik gula mampu memberikan efek berganda kepada masyarakat sekitar dalam jangkauan yang sangat luas. Tak hanya dalam spektrum ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Kalau harus diubah, sekian puluh ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Pasti mereka akan kesulitan untuk beralih profesi. Tatanan sosial-budaya juga akan terguncang. Jadi, dibiarkan saja begitu. Itulah pilihan yang paling masuk akal. Toh, perusahaan masih mampu mencetak laba operasi.
Tapi, Pak Ferdy yang sangat religius dan santun itu mengeluhkan soal serikat pekerja. Mereka luar biasa galak. Suka memaksakan kehendak. Main keroyokan. Unjuk kekuatan. Beberapa organisasi buruh dari luar negeri malah ikut-ikutan mengompori. Hampir semua BUMN dibelit persoalan serupa. Direksi kerepotan dibuatnya. Kalau tidak dilayani, percikan kecil akan berkobar ke mana-mana dan melumpuhkan aktivitas usaha. Bila sedikit saja diberi angin, mereka akan langsung nglunjak. Menuntut macam-macam sambil jual lagak. Seolah hendak menjadi manajemen bayangan. Ikut ngatur-ngatur jalannya perusahaan.
Sebenarnya ini anomali. Bukankah sejarah pergerakan kaum buruh di seluruh dunia dimotivasi oleh tuntutan akan jaminan kesejahteraan pasca-kerja? Mereka ini, para karyawan BUMN itu, adalah pekerja-pekerja yang sudah dijamin hari tuanya. Jadi, untuk apa lagi berserikat seperti itu? Situasi konyol ini tak ubahnya seperti satu raga yang diperebutkan oleh dua nyawa. Jadinya, kesurupan melulu. Bagaimana bila PNS, tentara dan polisi juga melakukan hal yang sama? Membentuk serikat pekerja? Sama sekali tak relevan. Dan cenderung mengada-ada. Bubarkan saja. Bergabung sajalah dalam koperasi dan paguyuban karyawan.
Pangkal masalah bermula dari Menteri BUMN yang sekarang, Pak Sofyan Djalil, Mister James itu, alias si Penjaga Mesjid. Bagaimanapun, penjaga masjid itulah, yang di masa lalu menjabat sebagai Deputi Bidang Komunikasi di bawah Menteri P-BUMN Tanri Abeng, yang membidani pembentukan serikat pekerja BUMN. Nuansanya serba politis. Karena mendekati Pemilu. Sekarang, terbukti menjadi senjata makan tuan. Tanya saja kepada semua direksi BUMN. Daripada tambah tidak keruan ke depan, mending buru-buru dikekang. Kalau perlu dilikuidasi sekalian. Bila dibiarkan terus-terusan begitu, lama-lama menjadi macan. Mau dicakar, kamu?
Silahkan dibereskan, Oom, mumpung masih menjabat. “Kau yang mulai kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji kau yang mengingkari.”
Ngomong-ngomong soal Mister James, Sony jadi teringat kawan lamanya. Dia langsung meneleponnya. “Halo, Pak Kopo. Keren sekarang. Sudah jadi Staf Ahli Menteri. Bagi-bagi kerjaan, dong.”
Sohib Sony yang kini menyandang gelar doktor itu kelihatannya sudah agak berubah. Sedikit pelit dalam berbagi informasi. Bicaranya seperti tertata dan diatur. Namanya juga pejabat. Tapi Sony yakin, meski belum sempat bertemu sejak beberapa lama, ada satu hal yang tak akan pernah berubah darinya, potongan rambut cepak. “Isis,” katanya.
Pak Kopo orangnya memang serius. Luar biasa cerdas bin pintar. Tapi suka berkelakar. Pernah dia mengeluh kepada Sony mengenai tidak enaknya tinggal di Bekasi. “Buku teleponnya tipis,” katanya, sambil membuka-buka Buku Petunjuk Telepon Jakarta yang setebal bantal bayi, di ruang rapat di kantor Sony, beberapa tahun lalu.
“Pak Kopo, saya dapat titipan amanat dari beberapa direksi BUMN kenalan saya, supaya Pak Menteri membubarkan saja serikat-serikat pekerja. Biar orang bisa bekerja dengan tenang. Agar pembayaran dividen naik terus. Kebetulan kan, dulu Mister James bidannya, sekarang bisa jadi algojonya.”
Pak Kopo tidak berkomentar sedikit pun mengenai permintaan itu. Hanya menanggapi dengan ucapan singkat tanpa makna, “Ya. Ya. Ya.”
Bagi Sony, tak penting apakah permintaannya diteruskan kepada Mister James atau tidak. Pokoknya, dia sudah menyampaikan amanat tersebut. Sebab, dia suka sedih melihat direksi BUMN yang memilih ngumpet dan tidak ngantor ketika serikat pekerja lagi angot. Takut ditodong ramai-ramai untuk membuat pernyataan tertulis.
“Tapi ini kan hanya tulisan. Tak akan berpengaruh terhadap produktivitas pekerja,” kata Pak Jumhur, sambil menyedot dalam-dalam rokok Gudang Garam merahnya.
Sony sedang mengobrol dengannya mengenai produktivitas karyawan di kantor Pak Jumhur, sebuah perusahaan pupuk raksasa bercat merah. Sungguh aneh, pria yang rambutnya sudah penuh uban kendati usianya belum terlalu tua itu malah mencotohkan dirinya sendiri. Dia pernah melakukan penelitian kecil-kecilan. Sebagai orang yang tergolong paling banyak pegang kerjaan di kantornya, dia malah menemukan bahwa dirinya bekerja secara efektif hanya dua jam dalam sehari. Sisa jam kerjanya dihabiskan untuk nyamper sana nyamper sini, telepon sana telepon sini, main games, ke kantin, bercanda dengan asap rokok, dan sesekali jalan ke mall. Panji Klantung, luntang-lantung.
Bukannya malas. Tapi sudah tak ada lagi pekerjaan yang perlu diselesaikan. Pekerjaan yang semestinya cukup ditangani satu orang, dikeroyok ramai-ramai oleh puluhan karyawan. Biar semuanya kebagian kerja, atau, pura-pura kerja. Bandingkan dengan pembantu rumah tangga yang harus bekerja keras hampir seharian penuh, sendirian lagi. Yang paling konyol, katanya, perusahaan tempatnya bekerja memelihara pekerja klerikal dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada pekerja teknis di pabrik. Seolah semua urusan pabrik berada di papan ketik komputer dan kertas-kertas yang berlembar-lembar itu.
“Jujur saja, urus pabrik beginian tak perlu sampai tiga ribu orang. Sudah hi-tech. Tinggal pencet-pencet tombol. Semuanya terpampang di monitor. Seandainya jumlah karyawan harus dipangkas habis hingga tinggal sepuluh persen saja, pasti masih bisa jalan,” begitu katanya.
Sony agak bingung, sesungguhnya Pak Jumhur berada di pihak mana?
Sebenarnya bukan hanya Pak Jumhur yang suka bengong kurang kerjaan. Banyak PNS malah tidak pernah bekerja sama sekali. Mas Hardi, tetangga sebelah rumah Sony di kampung halaman, adalah PNS yang lebih banyak meluangkan waktu bersama burung-burung dara kesayangannya.
“Nggak ngantor, Mas?” tanya Sony yang saat itu sedang pulang kampung untuk memperbaiki kijing keramik di makam ibunya yang patah karena tanahnya gembur.
“Nanti,” jawabnya. Besoknya juga begitu. Hanya sedikit agak panjang jawabannya. “Habis, tidak ada yang dikerjakan. Mendingan di rumah.”
Lha, kalau pekerjaannya sedikit, ngapain karyawannya mesti menyemut? Sehingga mereka bosan sendiri duduk-duduk di kantor, dan akhirnya lebih suka kelayapan di luaran atau tinggal di rumah saja. Namun, tidak semua PNS bebal seperti itu. Banyak juga yang pekerja keras, dan hebat-hebat. Pintar-pintar lagi. Sony banyak kenal orang-orang seperti itu. Bahkan, mereka bekerja jauh lebih keras daripada karyawan swasta. Tanya saja sama Pak Taufik Effendi.
Untuk mengubah tabiat buruk sebagian PNS, sejumlah Pemerintah Daerah getol merazia pegawainya yang kelayapan di luar pada saat jam kerja. Tapi jarang sekali yang terjaring. Padahal kantor-kantor pada melompong. Di manakah mereka? Apa ngumpet di got? Tak mungkin. Bau. Konon katanya, sebagian langsung menyamar jadi patung. Ada pula yang pura-pura jadi tukang dagang. Biar tidak ketangkep.
Kalaupun ada yang terjaring, biasanya ibu guru yang baru sempat pergi ke pasar sepulang mengajar. Para pahlawan tanpa tanda jasa yang memiliki tugas dan jam kerja yang jelas itu – meski banyak di antara mereka belum mengantongi status kepegawaian yang jelas – malah sering menjadi kambing hitam.
Sebenarnya, bukan itu pokok masalahnya. Jawaban Mas Hardi sudah jelas, “Tidak ada kerjaan.” Dengan demikian bisa dikatakan sebagian PNS adalah pengangguran tak kentara. Dibandingkan dengan para pekerja serabutan yang sering direndahkan dengan sebutan disguised unemployment, segolongan PNS malah lebih parah. Mereka real unemployment. Pengangguran tulen. Namanya juga PNS, eh, salah, penggangguran.
Setiap kali ada pekerja migran Indonesia yang disiksa, diperkosa, atau mati didera, hampir bisa dipastikan di kandang macan mana mereka bekerja, Malaysia, Singapura dan Jazirah Arabia. Namun, setiap tahun bertambah banyak saja pekerja migran yang dikirim ke kandang macan yang berjumlah tiga. Menjadi umpan mudah bagi macan yang siap menerkam dengan mulut menganga. Pemerintah lebih sering memanglingkan muka. Mereka TKI ilegal, katanya. Para pejabat menutup mata. Tak pernah bergerak kecuali dengan kata-kata. Seolah tak pernah ada fakta. Menganggap mereka sebatas angka-angka. Seluruhnya berjumlah sekian. Di negeri sini sekian. Di negara sana sekian. Yang legal sekian. Yang ilegal sekian. Yang kabur sekian. Yang dipenjarakan sekian. Yang diseterika sekian. Yang diperkosa sekian. Yang mati sekian. Hanya bilang kasihan.
Kandang macan pertama menampilkan kebengisan yang menyesakkan dada. Tanpa pernah diusut secara tuntas oleh polisi diraja. Sebagian masyarakat Malaysia memandang sebelah mata orang Indon yang mencari kerja dengan menjadi apa saja. Di negeri jiran itu, mereka dianggap manusia kelas dua. Dijual seperti butiran kelapa. Diperlakukan semena-mena. Ditangkap kapan saja. Disiksa semaunya. Menjadi kambing hitam bila terjadi sengketa antara majikan dan pekerja. Dikurung tanpa pernah diadili. Diperas bayar penalti. Bila perlu ditembak mati di tengah laut. Dijadikan makanan ikan pesut. Sesungguhnya, ini hanyalah sebuah manifestasi. Dari perasaan rendah diri. Mereka iri. Karena artis Indonesia cantik-cantik dan cakep-cakep. Sementara para pesohor mereka wajahnya seperti perawan kampung dan ban serep.
Sony pernah sekali pergi ke Malaysia. Kunjungan iseng tanpa peta. Hanya berwisata. Sekalian mengunjungi teman lama. Pergi sendirian saja. Tapi dia merasa tak betah di sana. Seseorang berseragam menghentikan langkahnya. Tatapan matanya kurang bersahabat. Seperti sedang merazia penjahat. Tangan kirinya bergelang kawat. Tangan kanannya menggaruk-garuk sesuatu di balik cawat. Wajahnya penuh jerawat. Berminyak dan tak terawat. Kumisnya tidak terlalu lebat. Tapi sepatunya mengkilat. Kayaknya baru dicat. Dari balik bajunya sepucuk pestol mencuat. Sungguh, pengalaman laknat. Ketemu oknum bejat. Mencecar pertanyaan-pertanyaan sesat. Dunia serasa mau kiamat. Rencana makan malam jadi telat.
Keesokan paginya Sony langsung cabut. Seumur hidup, tak mau lagi dia pergi ke kandang macan itu. Meski diberi tiket, uang saku dan disediakan kamar hotel supermewah. Mending ke kebon binatang. Ketemu Agnes, pacar barunya.
Tak mengherankan bila hubungan bilateral Indonesia-Malaysia selalu naik turun seperti ayunan di TK Melur. Sesekali naik, sering kali menghujam bagai sangkur. Rentan seperti kulit luar sebutir telur. Terkadang menggelinding liar membentur-bentur. Meluncur-luncur. Beberapa bagian retak dan hancur. Ketika majikan mencelakai orang yang kerja di dapur. Hanya karena salah menyajikan bubur. Kepada kakek yang sudah uzur. Layu seperti seikat sayur. Tergolek lemah di kasur. Sebentar lagi masuk kubur.
Cemeti langsung diulur. Lidahnya menjulur-julur. Suaranya mengguntur. Melukis garis-garis lurus membujur. Di punggung kurus yang melengkung seperti busur. Badan berbilur-bilur. Kucuran keringat menjadikan darah luntur. Semua persendian terasa kendur. Babak-belur. Tak mampu lagi kabur.
Tak hanya urusan pekerja migran Indonesia dizalimi, dalam banyak soal negeri jiran itu merasa superior. Meski dalam soal budaya selalu mengekor. Kepada saudara tuanya yang selalu tekor. Dan, berwajah jontor. Sering kali anak bawang itu berlagak seperi mandor. Bertamu sambil menggedor-gedor. Muka melengos masuk dengan kaki kotor. Kepala mendongak air seni menggelontor. Sayang, lupa tak pakai kolor.
Indonesia lebih suka mengalah. Bahkan ketika beberapa pulaunya ditilep dengan konspirasi gajah. Tentara gatal tangannya mau menembak. Senapan tak sabar ingin menyalak. Tapi pemerintah memilih menyingkirkan tombak. Meski harus berjalan di tengah ladang penuh onak. Dengan harga diri yang koyak. Nurani yang berontak. Meredam amarah yang bergejolak. Agar tak menjadi amuk yang menggelegak. Karena amunisi sudah memenuhi geladak. Tinggal disulut sumbunya pasti langsung meledak.
“Ganyang Malaysia.” Slogan pemompa nasionalisme yang begitu menggetarkan pada masa konfrontasi itu selalu muncul kembali setiap kali Indonesia bersinggung punggung dengan Malaysia. Pintar sekali Bung Karno mengocok kata-kata. Sederhana, tapi mobilizing, mengerakkan semua. Bahkan badak bercula satu dan orangutan dengan sukarela akan ikut angkat senjata.
Sony sependapat dengan sebagian orang, sesekali negeri congkak itu perlu diberi pelajaran. Dijewer kupingnya. Dipukul bokongnya. Orang diam bukan berarti takut. Hanya mencoba bersikap patut. Tapi jangan sembarangan kentut. Kalau tak mau dijadikan campuran sayur bakut.
“Tuan, tolong jangan berperilaku biadab. Kami orang-orang beradab. Tuan, berhentilah menganiaya. Kami bangsa berbudaya. Perbaiki perangai Tuan. Atau, kami yang akan meluruskan.”
Lain Malaysia lain lagi Singapura negeri makelar. Lobang hidungnya selalu mekar. Rambutnya kasar. Berkibar-kibar. Taringnya setajam cakar. Ekornya setengah melingkar. Memang, kadang macan kedua ini relatif kurang sangar. Tapi tak boleh disikapi dengan biar. Bisa-bisa tambah kurang ajar. Banyak saudara sebangsa merintih di sana karena dihajar. Disekap di dalam kamar. Sebagian malah masuk sangkar. Dan sebagian lagi pulang dibungkus tikar. Disisipkan uang beberapa lembar. Sebagai pengganti harapan yang telah buyar. Hati serasa terbakar. Melihat belati, tangan ingin menyambar. Tapi harus dicari jalan memutar. Karena Indonesia bukan bangsa barbar. Meski sering menderita luka dan memar. Lebih baik dibicarakan di dalam hanggar. Agar bara tidak semakin melebar. Hanya karena beberapa orang sudah tak sabar. Ingin menampar.
Kandang macan ketiga berada nun jauh di sana. Di tanah kerontang raja dahaga. Miskin air kaya minyaknya. Penduduknya gemar makan kurma. Menyantap daging domba. Ke mana-mana naik onta. Jazirah Arab namanya. Sebagian masyarakatnya masih menganut tradisi lama. Pekerja migran dianggap hamba sahaya. Dinilai sebagai harta. Ditimbang seperti tumpukan kain perca. Diperlakukan semaunya. Disentuh seenaknya. Di bagian dada. Di bagian paha. Karena telah dibeli dengan materai bergores pena. Perkosaan merajalela. Persis seperti perilaku kuda. Birahi dibiarkan menjadi raja. Atas nama tradisi yang bermuka dua. Diambil sisi enaknya saja. Sehingga korban dengan mudah menjadi tersangka. Dikurung di ruangan tanpa jendela. Tanpa seorang pun yang datang membela. Hakim telah menetapkan kata. Hukuman pancung menggelindingkan kepala.
Pahlawan devisa. Sebutan membanggakan itu begitu gampang meluncur dari mulut yang penuh busa. Tak seperti kenyataan pahit yang kerap mereka hadapi di luaran sana. Ketika siksa mendera. Ketika tamparan melukis wajah. Ketika sepiring makanan basi diberikan sebagai hadiah. Ketika tangan-tangan gatal majikan pria dengan penuh birahi menggerayangi tubuhnya. Ketika air mendidih disiramkan ke muka. Ketika setrika panas menggosok punggung. Ketika cambuk mengayun bergulung-gulung. Ketika raga meregang nyawa.
Mereka tak tahu harus mengadu kepada siapa. Tak tahu harus berlindung di mana. Tak tahu harus lari ke mana. Sebagian pulang dengan badan penuh luka. Sebagian malah ketawa-tawa karena gangguan jiwa. Sebagian menanggung malu berbadan dua. Sebagian lagi hanya pulang nama. Sampai kapan kita akan menutup mata? Menyaksikan anak bangsa mati disiksa. Kejadian seperti ini senantiasa berulang. Dan terus berbilang.
“Seperti lingkaran setan,” kata Heru dengan geram. “Padahal mereka telah berjasa besar mengurangi angka pengangguran di dalam negeri dan membawa masuk devisa yang jumlahnya hanya bisa dikalahkan oleh sektor migas. Itu pun belum dihitung dengan pemasukan devisa yang tidak tercatat dalam sistem perbankan dan jalur formal lainnya karena dibawa pulang dengan cara-cara tradisional. Bisa-bisa malah mengalahkan pendapatan devisa dari sektor migas,” dia menambahkan dengan berapi-api.
Heru sedang terlibat diskusi panas dengan Sony soal pekerja migran Indonesia. Sony mengiyakan pendapatnya. Tapi dia balik bertanya, “Memangnya, lingkaran setan itu apa, Her?”
Dengan tangkas Heru menjelaskan ucapannya, “Lingkaran setan adalah persoalan yang tak pernah bisa diselesaikan karena masalahnya terus berputar. Gambarannya begini, Pak. Tikus takut sama kucing. Kucing takut sama anjing. Anjing takut sama harimau. Harimau takut sama pemburu. Pemburu takut sama istrinya. Istri pemburu takut sama ibu mertua. Ibu mertua takut sama tikus. Berputar-putar terus. Tidak selesai-selesai. Masa, Pak Sony tidak tahu?”
Setelah Depnakertrans menyerahkan urusan pekerja migran kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) – tak lebih dari sekedar pelepasan organisasi – yang hingga kini belum juga kunjung pinter mengurusi, apalagi melindungi, para TKI, sudah saatnya dibentuk Kementerian/Departemen Pekerja Migran. Lembaga baru ini harus benar-benar bersih dari orang-orang lama yang gemar dengan status quo. Baik menterinya, pejabat eselonnya, karyawannya, hingga tukang sapunya. Semuanya harus orang baru. Tak boleh ada kaitan sedikit pun dengan mereka yang selama ini tak pernah becus mengurusi pekerja migran. Harus dipotong satu generasi. Seperti ketika Presiden SBY mengambil sikap tegas untuk tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru di IPDN selama setahun untuk memutus lingkaran setan kekerasan yang melingkupi sekolah calon camat itu.
Persoalan pekerja migran tidak pernah tuntas karena banyak pihak menghendaki demikian. Terlepas dari masih banyaknya TKI ilegal, posisi tawar PJTKI, baik yang lurus maupun yang culas, sangat lemah di hadapan agen penempatan pekerja migran di luar negeri. Dengan mudah mereka ditekan bila terjadi sesuatu yang tak normal atas pekerja migran Indonesia (yang legal). Dipaksa tidak membesar-besarkan persoalan yang dianggap ecek-ecek itu. Ancamannya, quota dipotong atau tidak bisa melakukan pengiriman lagi. Tentu saja, PJTKI keder dan memilih bungkam. APJATI akan segera melobi para pejabat agar tidak mengangkat permasalahan itu ke permukaan.
“Ini soal kecil. Satu di antara sejuta,” kata mereka. Angka-angka statistik membela mereka.
Ya, Tuhan! Sekalipun satu, itu insan. Bukan hewan. Bukan pula sekedar bilangan. Tapi karena sudah rutin mendapat setoran, para oknum tak berhati nurani memilih diam. Kalaupun bergerak, hanya mulutnya. Biar kelihatan kerja. Hayo …, berubah! Jangan bikin repot Presiden melulu.
Kementerian/Departemen Pekerja Migran yang baru harus merestrukturisasi hubungannya dengan PJTKI. Dari hubungan patron-klien, dikembalikan lagi menjadi sebentuk interaksi antara regulator dan pelaku usaha. Hentikan perselingkuhan bertumbal. Stop perilaku Dajal. Dari titik baru inilah bisa mulai dilakukan penataan dan pemetaan ulang semua PJTKI. Yang asal-asalan dibubarkan saja. Kalau perlu diracun pakai sambal superpedas. Biar perutnya mulas-mulas. Yang bagus dibina dan dibantu memperkuat posisi tawarnya terhadap agen penempatan pekerja migran di luar negeri, melalui jalur government-to-government dan semua akses yang bisa diberdayakan. Karena sebagian besar persoalan berada di luaran sana. Apabila di luar sudah beres, akan lebih mudah menata yang di dalam. Agar pekerja migran tidak lagi menjadi pekerja migren.
Kementerian/Departemen Pekerja Migran yang baru juga harus mampu meminimalisir dan secara bertahap menihilkan TKI ilegal, karena dari sinilah pokok persoalan sering kali bersumber. Mereka, para TKI ilegal itu, rentan sekali terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Ini sangat crucial. Harus segera ditangani. Lha wong TKI legal saja juga sering ketimpa sial, apalagi yang ilegal.
Sebenarnya bukan salah mereka menjadi TKI ilegal. Mereka tidak punya pilihan, karena biaya keberangkatan melalui jalur formal memang sangat muaahal. Di sinilah sebenarnya Kementerian/Departemen Pekerja Migran yang baru dapat mengambil peran. Sistem penempatan dan pemberangkatan TKI harus diubah total. Dalam sistem baru, biaya pemberangkatan dan penempatan dibebankan kepada tiga pihak – yaitu, calon TKI, PJTKI dan pemerintah – secara merata ataupun secara proporsional. Dana talangan tersebut harus dikembalikan oleh TKI dengan mencicil dari gaji bulanan mereka selama enam bulan sampai satu tahun hinggal lunas. Tidak seperti selama ini, di mana seluruh biaya keberangkatan harus ditanggung sendiri oleh calon TKI. PJTKI cuma bermodal dengkul.
Dengan cara ini, secara bertahap jumlah TKI ilegal bisa diminimalkan, dan akhirnya dinihilkan, karena mereka tidak perlu lagi menyiapkan dana yang terlalu besar untuk bekerja di luar negeri. PJTKI juga akan terseleksi secara alamiah. Mereka yang cuma bermodal dengkul dan tidak profesional akan tergerus dengan sendirinya. Sedangkan pemerintah sebagai salah satu pihak yang turut andil dalam membiayai keberangkatan TKI otomatis harus ikut memantau TKI yang ditempatkan agar duitnya bisa kembali dan menjadi dana bergulir bagi calon-calon TKI berikutnya. Karena harus terus memantau keberadaan para TKI di luar negeri, Kementerian/Departemen Pekerja Migran yang baru tersebut perlu menempatkan Atase Pekerja Migran di setiap KBRI di mana terdapat TKI yang sedang bekerja.
Namun persoalan ketenagakerjaan Indonesia tidak melulu berkaitan dengan para TKI yang bekerja di luar negeri. Di dalam negeri pun, persoalan ketenagakerjaan tidak kalah peliknya. Bahkan, boleh dibilang carut-marut. Kalau tak mau dibilang rumet, rumit dan bikin kepala mumet.
Departemen Tenaga Kerja memang makhluk yang luar biasa aneh. Setelah Departemen Transmigrasi dilikuidasi dan kemudian dicangkokkan ke ketiaknya, dia memanjangkan nama menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat Depnakertrans. Jaka Sembung, alias kagak nyambung. Urusan transmigrasi mestinya diplesterkan ke punggung Departemen Sosial, karena ia lebih banyak bersentuhan dengan soal-soal yang mengurai problematika sosial. Biar Depnaker bisa konsentrasi mengurus masalah tenaga kerja. Karena departemen yang satu ini agak telmi dan tabiatnya sedikit pemalas. Bertahun-tahun tak pernah mau belajar. Hanya asyik bermain gitar. PR selalu dikerjakan oleh ibunya. Walhasil, setiap kali menerbitkan aturan baru, selalu saja mengundang reaksi menyimpang dari dua pihak, pekerja dan pengusaha.
Para pengangguran berbusana necis yang justru berkantor di Depnakertrans sesungguhnya tidak pernah bekerja sepanjang para pekerja dengan wajah marah menarik garis demarkasi terhadap pengusaha. Demikian pula sebaliknya. Mereka saling bersiasat. Merentangkan pagar kawat. Mulut bertukar hujat. Padahal mereka bukanlah orang-orang jahat. Hanya saja, masing-masing takut dikepret dari belakang. Lengah sedikit bokong ditendang. Karena sang wasit asyik merapikan ikatan dasi. Mengusap-usap pantalon hitam yang begitu serasi. Seraya mengelus-elus jambul yang seksi. Urusan mendesak dibiarkan terbengkalai di lemari. Karena tak paham bagaimana menanak nasi. Beras setengah matang didiamkan di kuali. Akhirnya basi. Bau tak sedap merembes dari kisi-kisi. Menyuburkan jamur dan bakteri. Bikin keracunan orang-orang yang mengkonsumsi.
Sesungguhnya pekerja dan pengusaha adalah saudara kandung. Di tubuh mereka mengalir darah yang sama, merah. Membutuhkan udara yang sama, untuk bernapas dan memompa ban mobil. Makanannya juga sama, nasi berlauk semur jengkol, dengan ikan cuek dua ekor. Tujuannya sama, mencari nafkah. Hanya faktor kepemilikan yang membedakan mereka. Dan, otomatis, juga soal pendapatan. Tapi itu hukum ekonomi semata. Tidak perlu menempatkan diri dalam posisi yang berseberangan. Aku di sini kau di sana. Saling curiga. Merasa saling dimanfaatkan dan memanfaatkan. Pengusaha juga mati kutu tanpa pekerja. Sedangkan pekerja akan kesulitan menjual jasa apabila tidak ada pengusaha yang membuka lapangan kerja. Sama-sama saling membutuhkan. Tak perlu dikotori dengan prasangka yang bukan-bukan. Apalagi dikompori dengan omongan-omongan menyesatkan. Ayo …, bergandengan tangan. Bersalam-salaman. Berpeluk-pelukan.
Mereka pun bersalam-salaman dengan perasaan haru. Berpeluk-pelukan dengan tatapan mata sayu. Salsa menangis seharian. Tak mau makan. Dia sangat sedih. Orang yang selama ini dianggapnya sebagai kakak akan pergi. Sedangkan Rizky, terlihat diam saja. Sesekali dia mengucek mata. Sony tak tahu apa yang ada di dalam benak anak lelakinya. Titin pamit pulang. Emak-nya sudah menemukan jodoh untuknya. Tujuh tahun bekerja sebagai pembantu di rumah Sony, semenjak Salsa masih bayi, dia sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Tapi tidak dalam soal gaji. Sony selalu memberikan kenaikan gaji sepuluh persen setiap tahun. THR tak pernah terlewatkan sekalipun. Minimal satu kali gaji. Atau dua kali gaji, kalau lagi banyak rezeki. Sedang biaya mudik gratisan. Karena Titin bertetangga dengan Sony di kampung halaman.
Di perumahan di mana keluarga Sony tinggal, Titin yang berkulit legam dan berambut pendek itu tergolong pembantu bergaji besar. Dalam usianya yang masih belia, dia sudah mampu merenovasi rumah keluarganya di kampung halaman sana. Perhiasannya juga lumayan banyak. Disimpan di kotak disket di kamarnya. Pakaiannya bagus-bagus.
Pernah, beberapa sejawatnya iri kepadanya, dan kemudian mengajukan protes kepada majikan masing-masing. Malah, pakai mogok kerja segala. Menuntut gaji yang sama dengan gaji Titin. Prahara pun bermula. Akibatnya, sejumlah ibu-ibu lapor ke Pak RT, mendesaknya agar menegur keluarga Sony, karena dianggap mengganggu ketenteraman lingkungan dengan merusakan pasaran gaji pembantu.
Febriana, istri Sony, tak tahan. Telinganya merah sepulang dari arisan bulanan. Disindir oleh ibu-ibu. Meski ada juga beberapa orang yang membelanya. Tapi Sony tetap pada pendiriannya. Ini urusan domestik. Masalah kedaulatan republik. Tak boleh dikutak-katik. Tapi protes semakin bergema. Daripada harus berperang melawan tetangga, dicarilah jalan tengah. Titin pun di-briefing.
“Kamu ngomong saja sama teman-temanmu. Gajimu sudah diturunkan. Juga soal libur satu hari dalam seminggu itu. Bilang sudah dihapuskan. Pura-pura saja. Biar tidak ribut ini komplek.”
Titin setuju belaka. Dia sadar telah keceplosan omongan dan terlalu berterus-terang, sehingga menimbulkan gonjang-ganjing dalam hubungan pembantu-majikan. Syukurlah, setelah hampir sebulan masalah itu akhirnya reda juga.
Sony tak habis pikir, bagaimana mereka bisa sesewot itu. Dia hanya mencoba memanusiakan pembantu. Tapi tetap saja dianggap salah. Padahal pembantu rumah tangga bekerja lebih dari dua belas jam dalam sehari. Tujuh hari penuh dalam seminggu. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan penghargaan yang layak. Baik dalam hal fasilitas, perlakuan dan pendapatan.
Sebagai misal, kamar Titin dilengkapi radio-tape dan TV empat belas inci. Fasilitas ini diberikan karena Titin terlihat kurang nyaman dan agak sungkan bila nonton TV bareng di ruang keluarga. Apalagi Sony punya kebiasaan buruk pindah-pindah saluran. Sehingga sering berantem dengan istri dan kedua anaknya, yang akhirnya mengungsi ke kamar masing-masing untuk menonton acara kesukaan mereka di TV yang lebih kecil.
Demikian pula perlakukan keluarga Sony yang dianggap terlalu memanjakan pembantu oleh para tetangga, karena memberikan libur sehari dalam satu minggu kepada Titin. Bagi Sony, ini sama sekali tidak berlebihan. Toh, Titin jarang-jarang memanfaatkan hari liburnya. Lagian, kalau setiap hari hanya berkutat di rumah, bagaimana mereka bisa melihat dunia luar dan cari pacar? Apakah mereka tidak berhak mendapatkan pasangan?
Titin saja sudah dua kali pacaran. Pertama dengan Dahlan, tukang ojek di gerbang depan. Akhirnya putus, karena pemuda ceking itu ternyata mata keranjang. Kedua, dengan Tukijan, supir Sony. Tapi yang ini dipotong di tengah jalan oleh Sony, karena Tukijan sudah beristri, anaknya dua masih kecil-kecil. Keduanya dijewer oleh Febriana. Dicuci habis pakai Rinso. Hingga putih bersih. Dengan ancaman yang tidak main-main, bubar atau dikeluarkan.
Kini, Titin akan pergi. Di kampung telah menunggu calon pasangan hidupnya. Sugito, tukang becak yang tinggal di belakang rumahnya. Mudah-mudahan pemuda itu menjadi suami yang baik baginya. Sony tak kuasa berkata-kata. Istrinya sama saja. Matanya berkaca-kaca.
“Tin, baik-baik ya, di sana. Salam untuk emak-mu dan calon suamimu. Ini, saya beri pesangon tujuh kali gaji,” kata Sony dengan suara terbata-bata.
“Iya, Pak. Terima kasih,” jawabnya, sambil menadahkan tangan dan mengucurkan air mata.
Sementara Febriana yang terus-menerus kelilipan, mengulurkan sebuah amplop sambil berpesan, “Tin, aku ada uang lima juta. Mudah-mudahan cukup untuk biaya pernikahanmu. Sering-sering telepon ke sini, ya. Biar Rizky dan Salsa tidak kesepian. Jadi obat kangen buat mereka.”
Kedua perempuan itu kemudian saling berpelukan. Bertangis-tangisan. Sama-sama menumpahkan air mata. Lantai basah semua.
Pembantu. Pembantu. Pembantu. Sebagian orang suka menyebutnya babu. Belum lagi sebutan sinis lainnya, yang terkesan merendahkan, seperti jongos, kacung, bedinde, pesuruh, buruh dan lain sebagainya. Padahal mereka orang-orang yang sangat berjasa, dan luar biasa vital keberadaannya. Sony merasakan sendiri. Bila salah seorang karyawannya tidak masuk kerja, dia tak terlalu pusing asal ada alasan yang jelas. Tapi, bila Usep, office boy yang kocak itu, absen, kantor langsung lumpuh. Cari minum susah. Mau makan siang susah. Sampah menggunung. Piring dan gelas kotor semua. Pendeknya, minta ampun.
Begitu pula pada musim mudik Lebaran. Pembantu pada pulang. Banyak keluarga yang kelimpungan. Berhari-hari menyantap makanan kalengan. Sebagian terpaksa makan di restoran. Belum lagi soal cucian. Juga seterikaan. Punggung patah menyapu halaman. Encok kumat mengurus binatang piaraan. Karena tak tahan, akhirnya mengungsi ke penginapan.
Banyak orang bekerja sebagai pembantu karena tak punya lagi pilihan. Itulah pekerjaan yang paling gampang mereka dapatkan. Meski imbalan yang diterima sering kali tak sepadan. Dibanding kucuran keringat yang membasahi badan. Bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan. Kemudian membereskan cucian. Dilanjutkan dengan bermain tarik-ulur bersama gosokan. Siang malam disibukkan oleh pekerjaan. Mulai dari memasak hingga menjaga kebersihan. Istirahat tak lagi jadi perhitungan. Namun mulutnya tak pernah menyuarakan keluhan. Menerima apa adanya tugas yang dibebankan. Tak pernah sedikit pun berpikir soal masa depan. Yang penting tenaganya masih dibutuhkan. Sebagian malah menekuni profesinya hingga kepalanya penuh uban. Sebagian lagi tetap setia dengan panggilan jiwanya hingga hayat berpisah dengan badan.
Sony suka sedih mendengar berita-berita mengenai pembantu yang dianiaya. Gaji tak terbayar, badan penuh memar. Makan tak diberi, berhari-hari dikunci di kamar mandi. Geram hatinya. Menitik air matanya. Maka, dia berkirim surat kepada Presiden, dengan tembusan kepada Menakertrans. Karena sudah berkali-kali SMS-nya tak berjawab. Dia tulis surat itu dengan tinta jelaga yang diaduk dengan air mata. Tanda tangannya berbentuk sebuah crying face. Tak lupa dia sisipkan sepotong baju Titin yang tertinggal di rumahnya.
“Pak Presiden, tolong dong, ditunjuk seorang Dirjen PRT. Agar para pembantu rumah tangga di seluruh Indonesia mendapatkan penghargaan, perlindungan dan perlakuan sewajarnya. Dibuatkan standar gajinya. Ditentukan hak cutinya. Diberikan hari liburnya. Diperjuangkan nasibnya. Diangkat martabatnya.”
Jangan mentang-mentang mereka diam saja maka majikan bisa berlaku semena-mena. Kalau perlu kumpulkan beberapa PRT senior dari seluruh penjuru tanah air untuk diangkat menjadi staf ahli Pak Dirjen. Biar mereka memberikan masukan-masukan berharga bagi Direktorat Jenderal yang baru itu.
Surat itu tergeletak begitu saja di meja. Isinya singkat. Pemberitahuan pengunduran diri. Orangnya sudah tak nongol lagi. Padahal kemarin sore, pada saat gajian, Sony masih sempat berbicara dengannya. Menanyakan salah satu pekerjaan yang sudah harus selesai empat hari lagi.
Palgunadi, karyawan di Bagian Produksi, memilih kabur begitu saja tanpa merasa perlu bertemu dengannya. Sony agak kecewa. Sesungguhnya dia tak berharap berlebihan. Kalau masuknya dengan cara baik-baik, mestinya pergi dengan cara yang baik pula. Minimal ada pemberitahuan sebulan sebelumnya. Toh, Sony tak pernah melarang, apalagi menahan, orang yang mau mengundurkan diri. Biasa saja. Itu terjadi di mana-mana.
Sudahlah, tak perlu dimasukkan ke dalam hati. Beberapa karyawan mengatakan kepadanya, lulusan Universitas Diponegoro itu diterima bekerja di sebuah perusahaan raksasa di daerah Kuningan. Syukurlah kalau begitu.
Bukan sekali dua kali hasil didikan keras Sony dipanen orang lain. Palgunadi hanyalah salah satunya. Tapi Sony tak terlalu mempermasalahkannya. Dia ikhlas saja. Itu merupakan salah satu kontribusinya sebagai warga negara untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai bagi perusahaan lain. Asal tidak keterusan saja. Bisa kuwalat mereka. Sebab, sebagai pengusaha kecil, Sony cukup tahu diri untuk tidak merekrut tenaga kerja yang sudah jadi.
Makanya, dia telaten mencari bibit-bibit unggul yang kemudian dia godok dengan air garam. Tak lupa diceburkan tiga lembar daun salam. Juga selembar celana dalam. Direbus bermalam-malam. Hingga lebam-lebam. Dalam waktu tiga bulan, paling lama, seorang fresh graduate akan menjelma menjadi pekerja yang mumpuni di tangan Sony. Tapi dia tak pernah mencegah kutu loncat lari dari kantornya. Itu sudah garis tangan mereka. Dia hanya berdoa. Mudah-mudahan mereka menjadi anak manis, dan tidak nakal di luaran sana.
Tapi, kadang-kadang karyawan mau menangnya sendiri. Pernah Sony membuat peraturan baru karena beberapa karyawan suka titip absen padahal datang terlambat. Dia kumpulkan seluruh karyawannya dalam rapat paripurna. Sony meminta mereka berkata jujur, siapa yang suka nitip absen dan siapa yang sering dititipi absen. Tidak akan dikenai sanksi. Hanya perlu diperbaiki. Agar tidak menjadi tradisi.
Tak seorang pun mengaku. Resepsionis, yang mestinya paling tahu soal ini, karena mesin absen berada di samping mejanya, malah ketakutan. Sepertinya Amelia diancam, agar tidak membocorkan rahasia. Demikian pula Anita, yang setiap hari memeriksa absensi terkait dengan tugasnya menghitung uang makan. Wajahnya agak kecut karena dimusuhi beberapa karyawan. Ketika Sony panggil mereka berdua ke dalam ruangannya untuk menanyakan soal itu, mereka memilih bungkam. Inikah yang namanya solidaritas karyawan?
Biasa. Di mana-mana begitu. Namanya juga karyawan. Macam-macamlah kecurangannya. Sony mahfum adanya. Nyolong-nyolong sedikit dia biarkan. Asal tidak keterlaluan. Dia juga tahu klaim bensin terkadang aneh-aneh. Anita bahkan pernah menemukan sebundel bon bensin kosong tertinggal di mejanya. Tapi, yang bikin Sony gusar adalah kebocoran telepon. Dua bulan berturut-turut. Biayanya bengkak lebih dari delapan juta. Setelah di-print, ketahuan ada yang suka ngendon di kantor hingga malam hari untuk menelepon nomor esek-esek.
Penjaga malam langsung menunjuk hidung Rofi’i, orang Produksi yang belakangan suka lembur sendirian. Tinggal digelandang. Rofi’i mengaku. Minta ampun supaya tidak dipecat. Dia bersedia mengganti semua kerugian dengan dipotong gaji. Anehnya, besoknya dia ngilang. Tak pernah datang ke kantor lagi.
Tapi ada juga kecurangan yang benar-benar keterlaluan. Heru pernah bercerita kepada Sony mengenai Heri, kakaknya yang menjadi Penyelia Produksi di sebuah pabrik perakitan elektronik. Karena pusing mengurus pekerja-pekerja yang curang dan banyak ulah, dia stres dan akhirnya mengundurkan diri. Malu kepada manajemen.
Bagaimana tidak, mereka selalu mencari berbagai cara untuk memperlambat pekerjaan, bahkan dengan menjaili mesin. Tujuannya, lembur. Target produksi memang terpenuhi, tapi harus lembur setiap hari. Tak mungkin tambah shift, karena yang demikian berarti harus merekrut pekerja tambahan. Terlalu berisiko untuk order dadakan. Jadilah Heri ikut-ikutan lembur saban hari. Pola hidup jadi tak normal. Mending mundur teratur. Daripada babak belur. Kurang tidur.
Lembur boleh-boleh saja. Sesekali perlu dilakukan. Apalagi kalau tengat waktu sudah menampakkan taringnya. Tapi, kalau setiap hari lembur, berarti ada masalah. Boleh jadi karena cara kerjanya kurang efektif. Atau, mungkin saja, jumlah dan kapasitas SDM-nya tidak mencukupi.
Sesungguhnya, kerja lembur yang keterusan sama sekali tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menciptakan persoalan baru. Manusia pada dasarnya mempunyai keterbatasan. Ketika bekerja dari jam delapan pagi hingga pukul lima sore, kapasitasnya masih seratus persen. Apabila diteruskan hingga pukul sembilan malam, kapasitasnya tinggal lima puluh persen. Bila dilanjutkan lagi hingga tengah malam, sesungguhnya kapasitasnya tinggal dua puluh persen. Apalagi kalau digeber sampai pagi. Mereka bekerja dengan kapasitas cuma sepuluh persen. Apa yang bisa dihasilkan dengan kapasitas sekecil itu?
Lebih gawat lagi, setiap kali habis lembur, datangnya selalu telat. Tidur dulu, alasannya. Sehingga jam kerja dimulai siang hari, dan bahkan sore hari. Kalau terus-terusan begini, namanya menggeser jam kerja. Bagaimana mau berkoordinasi dalam teamwork? Mereka bekerja pada saat orang lain lagi enak-enaknya tidur di malam hari. Pagi hari, pada saat orang lain sibuk bekerja, mereka pada ngorok sambil ngiler di gudang bawah. Jarang mandi lagi. Celana dalam sudah side B. Andalannya cuma minyak wangi. Hal seperti itulah yang mendorong Sony agak ketat dalam soal absensi. Karena orang Pemasaran pernah komplain. Pagi-pagi klien sudah tanya ini-itu, tapi orang-orang Produksi belum pada nongol. Jadi tengsin. Bisa kabur itu peluang. Urung dapat bonus. Gondok mereka.
Tapi tak semua karyawan suka berulah. Sony paling salut kepada karyawannya di Bagian Pemasaran. Mereka semua pekerja keras. Saling bersaing satu sama lain, sehingga tak sedikit pun punya waktu luang untuk bertingkah aneh-aneh. Motivasi mereka hanya bonus. Siapa yang mendapatkan paling banyak bonus dialah raja. Tak peduli orang baru atau lama. Ukurannya hanya angka-angka.
Heru Wibowo, Manajer Pemasaran di kantor Sony, hanya jebolan SMA. Tapi dia orang yang luar biasa. Tidak kalah dengan anak buahnya yang hampir semua lulusan sarjana. Meski bicaranya suka belepotan, dia mampu menutupi kekurangannya dengan kepiawaiannya menyihir manusia. Terlebih lagi, dia ahli menyerap ilmu orang dalam sekejap. Meski baru kenal, dijamin, orang itu akan segera menjadi sahabatnya. Itulah Heru, orang Semarang yang sudah pernah melakoni semua jenis pekerjaan di ibukota. Seperti Tukul, manusia setengah monyet yang jenaka itu.
Sony pernah sekali merekrut seorang pemasar jebolan perusahaan besar. Hernawan namanya. Langsung dia tempatkan pemuda yang menyandang gelar pasca-sarjana dari Amerika itu sebagai wakil Heru. Harapan Sony, agar ilmunya dicuri habis-habisan sama Heru. Memang benar, Heru mengakui, ini orang ilmunya sangat tinggi. Tapi tidak sakti. Buktinya, selama enam bulan tak pernah bikin transaksi. Barang sebiji. Cuma pintar teori. Padahal gajinya bergerigi. Akhirnya dipersilahkan pergi. Setengahnya dia juga malu sendiri.
Sony menduga, selama ini karir itu orang moncer di tempat kerja sebelumnya karena perusahaan tersebut sudah mapan. Dia tak pernah menghampiri pelanggan. Sebaliknya, pelanggan yang datang kepadanya. Hanya menunggu. Kalau cuma beginian, tak perlu lulusan luar negeri.
Kasus seperti ini sering terjadi. Beberapa orang hebat dari perusahaan raksasa seperti mati kutu ketika memulai usaha sendiri atau pindah kerja. Kesaktiannya luntur begitu saja setelah tak lagi menjadi bagian dari institusi yang membesarkannya. Mereka kelihatan sakti hanya karena perusahaan tempatnya bekerja sudah well-established. Jadi, yang sakti sebenarnya perusahaannya. Bukan orangnya.
Banyak contohnya. Tak perlu sebut nama. Pasti yang bersangkutan manggut-manggut dan mengakui sendiri. Tapi banyak juga perkecualian. Misalnya, almarhum Cacuk Sudaryanto. Ini orang memang jagoan. Berlaga di mana saja tetap saja sakti mandraguna. Sesungguhnya, Sony pernah punya karyawan jenis ini. Sayang, setelah menikah, dia mengundurkan diri. Ikut suaminya yang melanjutkan sekolah ke luar negeri.
“Ke luar negeri? Kapan?” tanya Sony.
“Kemarin berangkatnya, Pak. Pulangnya seminggu lagi,” jawab Sandy, sekretarisnya.
Pagi itu Sony minta tolong sama si Belanda Depok agar disambungkan dengan Pak Ferdy, kliennya di Surabaya. Ternyata dia pergi ke Amerika Latin. Mendampingi Direktur Utama menghadiri simposium gula internasional. Ya sudah. Berarti harus menunggu minggu depan. Padahal ada pekerjaan yang membutuhkan approval Pak Ferdy. Tidak bisa digantikan orang lain. Pesannya sudah begitu. Mau dikata apa.
Pak Ferdy bukan klien biasa. Kebetulan, adiknya teman lama Sony. Pernah sekantor di daerah Sudirman di masa lalu. Bagi Sony, Pak Ferdy adalah sahabat sekaligus teman mengobrol yang mengasyikkan. Wawasannya luas. Analisanya tajam. Dan, suka berterus-terang.
Bulan lalu, mereka berdiskusi soal pekerja di perusahaan perkebunan pelat merah yang memproduksi gula, cemilan legit kegemaran semut itu. Sony bertanya kepada Pak Ferdy, kenapa perusahaan tempatnya bekerja piara karyawan hingga belasan ribu orang. Padahal mereka sibuk pada saat musim giling saja. Belum lagi karyawan kampanye, yang jumlahnya seperti rayap itu. Seandainya pola budidaya diintensifkan melalui mekanisasi dan dilakukan perbaikan teknologi pada pabrik-pabriknya yang sudah uzur, jumlah karyawan pasti bisa dipangkas hingga tinggal seperempatnya saja. Hari gini, teknologi gula tidaklah mahal. Sangat sepadan dengan efisiensi yang bisa dihasilkan.
Pertanyaan itu sebenarnya sudah lama menggantung di benaknya. Baru kali ini Sony berkesempatan menanyakan langsung kepada orang yang mestinya tahu betul masalah tersebut. Ternyata Sony sok tahu. Dan harus menanggung malu. Pak Ferdy yang wajahnya mirip bintang filem kawakan Herman Felani itu menjawab dan sekaligus mematahkan pertanyaannya secara telak dengan paparan logika yang sangat masuk akal.
Apabila dilakukan mekanisasi, bagaimana nasib ribuan karyawan dan keluarganya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan? Namanya juga BUMN. Ada misi bisnis sekaligus misi sosial yang dibebankan ke pundaknya. Jadi, tidak bisa dilongok dari hitung-hitungan bisnis semata. Demikian pula aktivitas di pabrik, yang sebagian besar mesinnya peninggalan dari zaman Belanda. Bahkan usianya jauh lebih tua dari para pekerjanya. Bila diganti dengan teknologi mutakhir, ribuan orang harus dirumahkan. Padahal, semenjak zaman dulu, yang namanya pabrik gula mampu memberikan efek berganda kepada masyarakat sekitar dalam jangkauan yang sangat luas. Tak hanya dalam spektrum ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Kalau harus diubah, sekian puluh ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Pasti mereka akan kesulitan untuk beralih profesi. Tatanan sosial-budaya juga akan terguncang. Jadi, dibiarkan saja begitu. Itulah pilihan yang paling masuk akal. Toh, perusahaan masih mampu mencetak laba operasi.
Tapi, Pak Ferdy yang sangat religius dan santun itu mengeluhkan soal serikat pekerja. Mereka luar biasa galak. Suka memaksakan kehendak. Main keroyokan. Unjuk kekuatan. Beberapa organisasi buruh dari luar negeri malah ikut-ikutan mengompori. Hampir semua BUMN dibelit persoalan serupa. Direksi kerepotan dibuatnya. Kalau tidak dilayani, percikan kecil akan berkobar ke mana-mana dan melumpuhkan aktivitas usaha. Bila sedikit saja diberi angin, mereka akan langsung nglunjak. Menuntut macam-macam sambil jual lagak. Seolah hendak menjadi manajemen bayangan. Ikut ngatur-ngatur jalannya perusahaan.
Sebenarnya ini anomali. Bukankah sejarah pergerakan kaum buruh di seluruh dunia dimotivasi oleh tuntutan akan jaminan kesejahteraan pasca-kerja? Mereka ini, para karyawan BUMN itu, adalah pekerja-pekerja yang sudah dijamin hari tuanya. Jadi, untuk apa lagi berserikat seperti itu? Situasi konyol ini tak ubahnya seperti satu raga yang diperebutkan oleh dua nyawa. Jadinya, kesurupan melulu. Bagaimana bila PNS, tentara dan polisi juga melakukan hal yang sama? Membentuk serikat pekerja? Sama sekali tak relevan. Dan cenderung mengada-ada. Bubarkan saja. Bergabung sajalah dalam koperasi dan paguyuban karyawan.
Pangkal masalah bermula dari Menteri BUMN yang sekarang, Pak Sofyan Djalil, Mister James itu, alias si Penjaga Mesjid. Bagaimanapun, penjaga masjid itulah, yang di masa lalu menjabat sebagai Deputi Bidang Komunikasi di bawah Menteri P-BUMN Tanri Abeng, yang membidani pembentukan serikat pekerja BUMN. Nuansanya serba politis. Karena mendekati Pemilu. Sekarang, terbukti menjadi senjata makan tuan. Tanya saja kepada semua direksi BUMN. Daripada tambah tidak keruan ke depan, mending buru-buru dikekang. Kalau perlu dilikuidasi sekalian. Bila dibiarkan terus-terusan begitu, lama-lama menjadi macan. Mau dicakar, kamu?
Silahkan dibereskan, Oom, mumpung masih menjabat. “Kau yang mulai kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji kau yang mengingkari.”
Ngomong-ngomong soal Mister James, Sony jadi teringat kawan lamanya. Dia langsung meneleponnya. “Halo, Pak Kopo. Keren sekarang. Sudah jadi Staf Ahli Menteri. Bagi-bagi kerjaan, dong.”
Sohib Sony yang kini menyandang gelar doktor itu kelihatannya sudah agak berubah. Sedikit pelit dalam berbagi informasi. Bicaranya seperti tertata dan diatur. Namanya juga pejabat. Tapi Sony yakin, meski belum sempat bertemu sejak beberapa lama, ada satu hal yang tak akan pernah berubah darinya, potongan rambut cepak. “Isis,” katanya.
Pak Kopo orangnya memang serius. Luar biasa cerdas bin pintar. Tapi suka berkelakar. Pernah dia mengeluh kepada Sony mengenai tidak enaknya tinggal di Bekasi. “Buku teleponnya tipis,” katanya, sambil membuka-buka Buku Petunjuk Telepon Jakarta yang setebal bantal bayi, di ruang rapat di kantor Sony, beberapa tahun lalu.
“Pak Kopo, saya dapat titipan amanat dari beberapa direksi BUMN kenalan saya, supaya Pak Menteri membubarkan saja serikat-serikat pekerja. Biar orang bisa bekerja dengan tenang. Agar pembayaran dividen naik terus. Kebetulan kan, dulu Mister James bidannya, sekarang bisa jadi algojonya.”
Pak Kopo tidak berkomentar sedikit pun mengenai permintaan itu. Hanya menanggapi dengan ucapan singkat tanpa makna, “Ya. Ya. Ya.”
Bagi Sony, tak penting apakah permintaannya diteruskan kepada Mister James atau tidak. Pokoknya, dia sudah menyampaikan amanat tersebut. Sebab, dia suka sedih melihat direksi BUMN yang memilih ngumpet dan tidak ngantor ketika serikat pekerja lagi angot. Takut ditodong ramai-ramai untuk membuat pernyataan tertulis.
“Tapi ini kan hanya tulisan. Tak akan berpengaruh terhadap produktivitas pekerja,” kata Pak Jumhur, sambil menyedot dalam-dalam rokok Gudang Garam merahnya.
Sony sedang mengobrol dengannya mengenai produktivitas karyawan di kantor Pak Jumhur, sebuah perusahaan pupuk raksasa bercat merah. Sungguh aneh, pria yang rambutnya sudah penuh uban kendati usianya belum terlalu tua itu malah mencotohkan dirinya sendiri. Dia pernah melakukan penelitian kecil-kecilan. Sebagai orang yang tergolong paling banyak pegang kerjaan di kantornya, dia malah menemukan bahwa dirinya bekerja secara efektif hanya dua jam dalam sehari. Sisa jam kerjanya dihabiskan untuk nyamper sana nyamper sini, telepon sana telepon sini, main games, ke kantin, bercanda dengan asap rokok, dan sesekali jalan ke mall. Panji Klantung, luntang-lantung.
Bukannya malas. Tapi sudah tak ada lagi pekerjaan yang perlu diselesaikan. Pekerjaan yang semestinya cukup ditangani satu orang, dikeroyok ramai-ramai oleh puluhan karyawan. Biar semuanya kebagian kerja, atau, pura-pura kerja. Bandingkan dengan pembantu rumah tangga yang harus bekerja keras hampir seharian penuh, sendirian lagi. Yang paling konyol, katanya, perusahaan tempatnya bekerja memelihara pekerja klerikal dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada pekerja teknis di pabrik. Seolah semua urusan pabrik berada di papan ketik komputer dan kertas-kertas yang berlembar-lembar itu.
“Jujur saja, urus pabrik beginian tak perlu sampai tiga ribu orang. Sudah hi-tech. Tinggal pencet-pencet tombol. Semuanya terpampang di monitor. Seandainya jumlah karyawan harus dipangkas habis hingga tinggal sepuluh persen saja, pasti masih bisa jalan,” begitu katanya.
Sony agak bingung, sesungguhnya Pak Jumhur berada di pihak mana?
Sebenarnya bukan hanya Pak Jumhur yang suka bengong kurang kerjaan. Banyak PNS malah tidak pernah bekerja sama sekali. Mas Hardi, tetangga sebelah rumah Sony di kampung halaman, adalah PNS yang lebih banyak meluangkan waktu bersama burung-burung dara kesayangannya.
“Nggak ngantor, Mas?” tanya Sony yang saat itu sedang pulang kampung untuk memperbaiki kijing keramik di makam ibunya yang patah karena tanahnya gembur.
“Nanti,” jawabnya. Besoknya juga begitu. Hanya sedikit agak panjang jawabannya. “Habis, tidak ada yang dikerjakan. Mendingan di rumah.”
Lha, kalau pekerjaannya sedikit, ngapain karyawannya mesti menyemut? Sehingga mereka bosan sendiri duduk-duduk di kantor, dan akhirnya lebih suka kelayapan di luaran atau tinggal di rumah saja. Namun, tidak semua PNS bebal seperti itu. Banyak juga yang pekerja keras, dan hebat-hebat. Pintar-pintar lagi. Sony banyak kenal orang-orang seperti itu. Bahkan, mereka bekerja jauh lebih keras daripada karyawan swasta. Tanya saja sama Pak Taufik Effendi.
Untuk mengubah tabiat buruk sebagian PNS, sejumlah Pemerintah Daerah getol merazia pegawainya yang kelayapan di luar pada saat jam kerja. Tapi jarang sekali yang terjaring. Padahal kantor-kantor pada melompong. Di manakah mereka? Apa ngumpet di got? Tak mungkin. Bau. Konon katanya, sebagian langsung menyamar jadi patung. Ada pula yang pura-pura jadi tukang dagang. Biar tidak ketangkep.
Kalaupun ada yang terjaring, biasanya ibu guru yang baru sempat pergi ke pasar sepulang mengajar. Para pahlawan tanpa tanda jasa yang memiliki tugas dan jam kerja yang jelas itu – meski banyak di antara mereka belum mengantongi status kepegawaian yang jelas – malah sering menjadi kambing hitam.
Sebenarnya, bukan itu pokok masalahnya. Jawaban Mas Hardi sudah jelas, “Tidak ada kerjaan.” Dengan demikian bisa dikatakan sebagian PNS adalah pengangguran tak kentara. Dibandingkan dengan para pekerja serabutan yang sering direndahkan dengan sebutan disguised unemployment, segolongan PNS malah lebih parah. Mereka real unemployment. Pengangguran tulen. Namanya juga PNS, eh, salah, penggangguran.
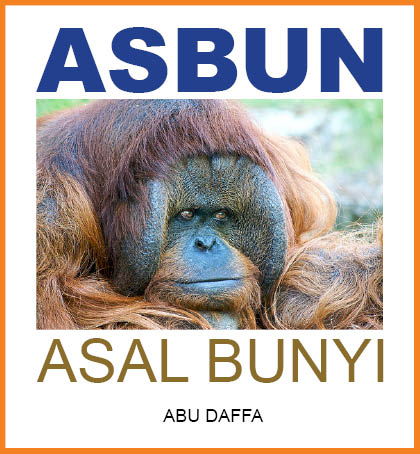
Tidak ada komentar:
Posting Komentar