Pencapaian tertinggi bagi orang-orang yang memilih berkarir di swasta berbeda-beda ukurannya. Sebagian orang merasa cukup puas dengan menjadi safety player, asal pekerjaan aman dan pendapatan menjulang. Tak peduli pegang jabatan atau hanya menjadi staf biasa. Bagi sebagian lainnya, menapak ke jenjang manajer sudah dianggap sebagai pencapaian yang lumayan membanggakan. Sementara para profesional mematok target yang lebih tinggi, mengincar posisi puncak, duduk di jajaran direksi. Apalagi bila dipercaya menjadi direktur utama, itulah pencapaian tertinggi. Tapi, banyak pula yang lebih suka bermetamorfosis menjadi ikan besar di kolam kecil. Berwiraswasta, menjadi pengusaha. Apabila keberuntungan memihaknya, suatu saat nanti bisa membesarkan kolamnya sendiri, menjadi telaga.
Sony mulai berwiraswasta pada usia dua puluh delapan tahun. Setelah dipikirkannya masak-masak, akhirnya dia memutuskan keluar dari pekerjaannya yang lumayan mapan. Dia berhimpun bersama dua orang rekannya mendirikan sebuah perusahaan. Hanya saja, kedua temannya itu, Rachmad Santosa dan Sunarna Wiguna, masih tetap menekuni pekerjaan masing-masing. Rachmad seorang wartawan. Sedang Sunarna adalah pengusaha perakitan komputer yang baru genap setahun memulai usaha sendiri setelah sebelumnya cukup lama ngenger di salah satu perusahaan milik pengusaha-politisi liat dan tahan banting asal Surabaya.
Maka, jadilah Sony pengelola tunggal perusahaan kelas gurem itu. Kedua sohibnya hanya seminggu sekali datang. Tak apa. Di luaran sana, mereka giat membantunya mencari order. Pekerjaan apa saja disabet. Pokoknya ada pemasukan. Dapat sedikit untung dibagi-bagi di antara mereka bertiga.
Sebuah rumah kos di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur, mempertemukan mereka di akhir tahun delapan puluhan. Sama-sama masih bujangan dan culun karena baru datang dari kampung. Rachmad, orang Solo itu, menyelesaikan kuliahnya di Institut Pertanian Bogor, jurusan Tanah. Makanya, kulitnya agak gelap. Malahan bisa dibilang gosong. Mungkin karena terlalu sering dijilati matahari. Sedangkan Sunarna, yang orang Cianjur, hanyalah tamatan SMA, namun sangat cerdas. Kemampuan analisanya luar biasa tajam dan selalu optimistis menatap masa depan. Keterbatasan ekonomi keluarga melarangnya duduk-duduk di bangku kuliah. Karena omongan yang sama-sama nyambung, jadilah mereka tiga serangkai yang ke mana-mana selalu bareng, pergi ke bioskop, berburu buku loak di Kwitang, menggoda waria di Taman Lawang, nonton video porno, termasuk main kyu-kyu.
Selama dua tahun pertama perusahaan baru itu tidak mengalami perkembangan berarti. Sekedar bisa jalan. Kantornya numpang di garasi rumah mertua Rachmad di daerah Kemang. Karyawan hanya dua orang. Nancy menangani administrasi. Sedangkan Suradi kebagian urusan umum. Tugasnya mengantar surat dan barang, bersih-bersih kantor, dan juga membelikan makan siang.
Memasuki awal tahun ketiga, Sony mulai terengah-engah. Gaji karyawan dua kali tertunda. Sementara kebutuhannya sendiri terus meningkat semenjak anak pertamanya lahir. Akhirnya Sony menyerah. Kantornya bubar. Sebulan kemudian dia diterima bekerja di sebuah perusahaan pameran. Di sinilah pertama kali dia bertemu Heru Wibowo, orang kepercayaannya saat ini. Juga Mualim, yang tidak terlalu pintar tapi hokinya besar. Dan Lexy, orang Manado yang berwajah cina itu.
Pak Mansyur, pemilik perusahaan tersebut, sangat menyukai Sony karena dianggap membawa banyak perubahan bagi kemajuan perusahaan. Dalam waktu kurang dari setahun dia dipromosikan jadi manajer. Namun promosi ini membawa berkah sekaligus petaka. Biasa, selalu ada sisi hitam dan putih, baik dan buruk. Djumali, orang lama kepercayaan Pak Mansyur, iri kepadanya. Dia merasa terancam, dan dipinggirkan. Beberapa kali Sony difitnah. Namun mental belaka.
Sebenarnya jenggah juga. Bekerja di bawah sorotan mata. Tapi Sony agak terhibur hatinya. Posisi baru tersebut memberinya kesempatan luas untuk memahami apa itu pengelolaan usaha. Yang sebelumnya dia jalani begitu saja. Apa adanya. Tanpa rencana. Inilah saatnya. Mencuri ilmu dari mulut yang menganga. Serap habis hingga tak bersisa. Biar tinggal tulang berbalut kulit bertambal kain kassa.
Hanya satu setengah tahun Sony bekerja di sana. Sungguh tak nyaman, sekaligus menyebalkan. Kaki kiri menginjak bara neraka, kaki kanan bertumpu di tubir surga. Akhirnya dengan berat hati dia keluar, dan memutuskan kembali berwiraswasta.
Ada beberapa pertimbangan yang membulatkan tekadnya. Pertama, Djumali yang gemar memakai sepatu koboi itu semakin keterlaluan. Sudah menjurus ke cara-cara edan. Kedua, Sony merasa tidak nyaman dengan istri bosnya yang sering datang ke kantor dan sok mengatur. Apalagi, perempuan ganjen itu cs berat dengan Djumali. Mereka seperti berkomplot untuk menjatuhkan Sony. Ketiga, merasa sudah makmur, Pak Mansyur mulai mengimpor lusinan kerabat dari kampung halaman untuk bekerja di kantornya. Sebagian orangnya baik-baik, tapi kebanyakan cuma merecoki orang yang lagi kerja. Keempat, Rachmad dan Sunarna mengajaknya bergabung kembali. Anak seorang konglomerat bersedia mendanai.
Keren benar. Sony berkantor di Menara Mulia. Karyawan langsung direkrut lima. Dia tarik Lexy menjadi pembantu utamanya. Ini baru namanya perusahaan, pikirnya. Namun, seperti biasanya, Rachmad dan Sunarna tidak bergabung penuh. Mereka memilih menjadi direktur freelance. Seperti yang sudah-sudah, kedua karibnya itu masih berat meninggalkan pekerjaan masing-masing. Sudahlah, tak perlu dirisaukan. Karena dua proyek besar sudah di genggaman tangan.
Baru sekali ini Sony benar-benar merasa percaya diri sebagai seorang pengusaha. Kejayaan sudah di pelupuk mata. Satu pekerjaan sudah diselesaikannya. Menghasilkan keuntungan yang luar biasa gendut. Segendut Pretty Asmara, perawan cantik dari Sukodono itu. Sementara pekerjaan kedua hampir kelar, dan beberapa pekerjaan baru segera menyusul.
Kiamat. Datang begitu cepat. Seperti kilat. Cakarnya menggurat-gurat. Langit langsung pekat. Sebulan setelah Sony berhasil menyelesaikan pekerjaan besarnya yang kedua, krisis ekonomi menyergap. Harapan tiba-tiba lenyap. Sirna ditelan senyap. Semua orang tergagap-gagap. Banyak yang megap-megap. Seolah mulutnya dibekap. Padahal mereka mangap. Masih untung, sebagian malah sudah tengkurap. Berenang di atas kayu sirap. Dengan paku-paku tajam yang menancap.
Palu godam datang dengan mengendap-endap. Kemudian mengepakkan sayap. Meliuk-liuk melintasi deretan atap. Berayun-ayun seperti tongkat sulap. Menghancurkan bisnis menyisakan asap. Bank-bank pada tiarap. Dari tubuh mereka berlelehan kecap. Tertatih-tatih beringsut merayap. Sementara bank sentral terus menghamburkan parap. Menyembelih anak-anaknya yang terperangkap. Sebagian berhasil lari menyelinap. Korban berjatuhan ke dalam lobang gelap. Berguguran seperti rayap. Mereka hanya bisa meratap. Sedikit berharap. Dan, kalap.
Dalam gilasan krisis, kantor baru Sony hanya mampu bertahan setahun. Keuntungan dari pekerjaan pertama dan kedua habis untuk menutup biaya bulanan. Beberapa pekerjaan batal. Hanya dua yang tetap jalan. Tanpa tetesan keuntungan. Krisis itu telah menggerus modal. Bubar.
Sony goyah. Malahan sempat memunggungi Tuhan. Karena kemalangan menimpanya justru pada saat kejayaan sedang bermula. Kecewa. Putus asa. Merasa seolah telah terlempar dan tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang sedang berputar. Beruntung, Febriana yang terkena PHK malah lebih tabah dan senantiasa mengingatkannya agar lebih tawakal. Benar, pikir Sony. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Dengan menjual mobilnya, sebuah sedan Toyota Corona keluaran tahun sembilan tiga, ditambah secawan perhiasan istrinya, Sony memulai usaha baru. Dia menyewa ruangan seukuran garasi di sebuah gedung jangkung yang matanya selalu awas memelototi kendaraan-kendaraan yang berlalu-lalang di jalan tol lingkar luar itu. Karyawannya hanya tiga. Heru, Anita dan Usep, office boy yang jenaka itu, yang masih kerabat jauh Sunarna.
Tapi kali ini Sony jalan sendirian saja. Single fighter. Tidak bergabung lagi bersama kawan-kawannya. Beruntung, Dewi Fortuna berpihak kepadanya. Belum genap dua bulan, Sony sudah mendapatkan pekerjaan yang lumayan besar dari sebuah perusahaan pupuk milik negara, dengan sedikit tepu-tepu, tentu saja. Dari sinilah dia mulai melebarkan kepakan sayapnya. Menembaki sasaran mudah. Sitting ducks. Institusi pemerintah dan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Dalam kenyataannya, banyak pengusaha yang lebih suka menguber proyek-proyek dari pemerintah atau institusi yang terkait dengan pemerintah, juga BUMN dan BUMD. Alasannya sederhana saja. Pertama, pasti dibayar, karena setiap proyek baru bisa dilaksanakan setelah anggaran turun. Artinya, uangnya sudah pasti ada. Kedua, harga bisa dimain-mainkan, bila perlu, diajak berjoget gaya jaipongan, semalam suntuk.
Di masa lalu, permainan harga cenderung gila-gilaan, hingga bisa digelembungkan sesukanya, seperti balon udara, sebagian lagi melar menjadi balon raksasa. Tetapi tetap ada batasnya, jangan sampai balon itu meletus dan memuntahkan isi perutnya yang berbau anyir.
“Monggo, Mas. Mau ambil untung berapa, asal setengahnya untuk kita,” kata mereka.
Hanya orang gila yang akan membuang muka menerima tawaran menggiurkan seperti itu. Dengan demikian, berarti para pengusaha adalah orang-orang yang waras. Kalau begitu, yang gila, siapa?
“Katakan tidak pada korupsi”, kata iklan sebuah partai politik. Ngawur itu. Iklan tersebut seolah menyiratkan bahwa kalangan dunia usaha suka usil menggoda para aparat birokrasi untuk melakukan korupsi. Terbalik, nyung. Aparat birokrasilah yang gemar mengajak para pengusaha untuk melakukan kong-kalikong. Mau bukti? Banyak. Ambil contoh, kasus BNI Melawai yang melibatkan Pauline Lumowa itu. Orang-orang BNI justru yang mengajari Bu Gendut dan mengatur segala sesuatunya.
Banyak orang geram menyaksikan praktek-praktek binal seperti itu. Dengan tatapan mata marah dan mulut berapi-api mereka menyebutnya korupsi. Wajar-wajar saja, karena mereka bersandar pada sudut pandang sistem. Bagi pengusaha seperti Sony, itu tak lebih dari sekedar biaya lobby, yang sudah diperhitungkan dan dianggarkan dalam pos biaya entertain atau pos-pos biaya lain yang disamarkan.
Memang tipis perbedaannya, antara korupsi dan biaya lobby, karena mereka berdua masih sedarah, terlahir dari bapak dan ibu kandung yang sama. Artinya, bukan anak haram, tapi anak blasteran. Buah cinta dari perselingkuhan nikmat antara para birokrat dan pengusaha. Karenanya, tak perlu dibikin pusing. Biarkan saja masing-masing melihat dengan cara pandangnya sendiri-sendiri. Korupsi, atau biaya lobby, boleh-boleh saja, asal jangan keterlaluan. Kenyataannya, begitu banyak, kalau tak mau dibilang jutaan, anak Indonesia yang dibesarkan dari uang hasil korupsi, termasuk sebagian pendemo itu, yang suka mejeng di TV.
Namun, sebagai warga negara, bagaimanapun, Sony juga ingin korupsi bisa terus ditekan di negeri ini. Kalau mau dibasmi, mustahil. Sampai kepalanya botak juga tak akan berhasil. Seperti orang yang kurang kerjaan saja, usil.
“Korupsi mempercepat derap langkah pembangunan, dan melahirkan para pahlawan.” Ini sama sekali bukan ucapan yang ngasal dan mengada-ada. Kalimat yang agak membingungkan itu meluncur dari mulut seorang mantan direktur sebuah bank bergincu merah yang telah beralih profesi menjadi pengusaha.
Siang itu, Sony sedang mengobrol sambil menyantap iga panggang di Tony’s Roma bersama sohib kentalnya tersebut, dan juga Ceng Li. Mereka bertiga sama-sama penggemar ikan hias air laut yang sering ketemu di pasar ikan hias di Jalan Sumenep hampir setiap Sabtu. Makanya, setiap kali makan bersama, mereka sebisa mungkin menghindari seafood. Jangan sampai PMP, pren makan pren.
“Maksudnya apa, Pak,” tanya Sony, sambil mengunyah gigitan kecil daging harum itu seraya memperhatikan Ceng Li yang tampaknya juga agak bingung dengan pernyataan aneh tersebut.
Kedua bola mata pria tinggi besar itu agak melotot. Pupilnya bergerak-gerak sedikit liar ke atas dan ke bawah. Berputar-putar lembut. Dari keningnya mulai menitik beberapa noktah cairan asin. Jakunnya naik turun pelan. Kedua tangannya diregangkan. Sepertinya dia kesulitan untuk menjawab pertanyaan Sony karena mulutnya penuh dengan potongan-potongan kecil daging iga yang lembut, manis dan pedas yang sedang dikunyahnya. Lelehan saus merah mengalir malas dari sudut-sudut bibirnya. Enak tenan. Mantap kale, kata Benu Buloe si jurumakan.
“Begini, Bung,” ujarnya sambil mengelap mulutnya. Tapi dia tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Napasnya masih belum teratur. Mungkin tenggorokannya bingung. Karena harus terus-terusan membuka tutup secara bergantian, saluran pernapasan untuk memberi jalan kepada pasukan yang sedang memanggul jutaan karung oksigen ke dalam paru-paru, dan saluran menuju lambung yang setiap saat kemasukan bagian-bagian kecil dari seekor sapi tak bernama. Salah langkah, bisa cegukan itu orang.
Setelah meneguk segelas air putih, barulah pria berbusana batik sutra itu terlihat agak rileks. Kemudian dengan tangkas dia menguraikan logikanya. Selama ini orang selalu menyorot korupsi dari sudut pandang sistem. Karena ada aturan yang dilanggar, maka ada pihak yang dirugikan dan ada pula pihak yang merugikan. Yang beginian sudah jamak di mana-mana. Sudah basi. Anak SD juga tahu. Persoalan korupsi mestinya didekati dengan tinjauan bisnis, dan juga sosiologis.
Para pelaku korupsi sebenarnya bukanlah orang-orang tamak bin serakah. Sebaliknya, merekalah pahlawan ekonomi, karena senantiasa berbagi hasil korupsi dengan keluarga, kerabat, sejawat, masyarakat dan dunia usaha, sehingga terbentuklah jutaan mata rantai ekonomi dalam untaian-untaian kecil namun panjang melalui uang hasil korupsi yang dibelanjakan tersebut. Konsumsi naik ekonomi bergerak. Sektor riil mau diajak beranjak. Asal jangan diinjak. Ayo …, korupsi. Edan.
Pahlawan ekonomi itu, para pelaku korupsi, tambahnya, janganlah diuber-uber. Mereka harus dihormati, dan diberi penghargaan. Kalau perlu disiapkan pin emas barang tiga atau lima gram. Bagaimanapun, tabiat buruk mereka selama ini terbukti mampu mempercepat laju pembangunan dan menggerakkan ekonomi, sehingga masyarakat dan para pelaku usaha pada tersenyum. Itulah chemistry yang paling pas untuk situasi faktual Indonesia.
Buktinya, setelah para pahlawan ekonomi itu diuber-uber dengan ganas, pembangunan jalan di tempat. Proyek-proyek cuma dikurung, tak dilepas. Pengusaha ngaplo. Masyarakat melongo. Duit Pemda yang jumlahnya ribuan kali lipat penduduk bumi itu dibiarkan berpesta mesum di bilik-bilik tertutup di kantor-kantor bank. Sehingga berceceranlah anak-anak haram yang dihasilkan dari perselingkuhan bejat itu. Mereka jadi malas beredar. Tiduran saja. Pinggulnya masih ngilu. Semalam bertempur habis-habisan.
Sekarang, kalau tukang uber-uber tersebut memang sakti, mampu kagak mereka memaksa trilyunan duit Pemda yang sedang pelesiran sambil menikmati wine dan menghisap cerutu Kuba itu agar segera check out dari kamar-kamar SBI dan perbankan? Agar Sony menari-nari riang. Karena main proyek di pemerintahan nikmat banget. Sedangkan, kalau main di swasta, agak seret. Harga ditekan habis. Pasti dibayar, meski ada juga yang tak terbayar. Karena pembiayaan pekerjaan biasanya dianggarkan dari proyeksi pemasukan. Kalau pemasukan agak terganggu, pembayaran bisa mundur tak keru-keruan. Menciptakan efek berantai yang merugikan banyak pihak serta menimbulkan ketidaknyamanan.
Sony sendiri tak pernah menolak pekerjaan dari swasta, bahkan terus mengubernya. Dia pegang pekerjaan besar dari salah satu perusahaan kawannya. Dia tekuni dengan serius meski marginnya kecil kalau dihitung per satuan. Namun, karena rutin dan volumenya lumayan tambun, akumulasi marginnya bisa menutup biaya bulanan.
Sony merasa sangat bersyukur karena usaha barunya berjalan relatif lancar. Sejumlah pekerjaan baru dia dapatkan. Fadli, adiknya itu, beberapa kali meminjaminya tambahan modal kerja. Tanpa bunga. Meski pekerjaan terus bertambah, dia belum punya keinginan merekrut karyawan baru untuk meringankan beban kerja. Masih melihat-lihat dulu. Tunggu sampai benar-benar aman. Panggil saja pekerja freelance. Banyak di luaran sana. Tidak perlu bayar gaji bulanan.
Dia lebih fokus pada pemupukan modal. Sebagian keuntungan dia sisihkan untuk beli mobil, sebagai ganti dari mobilnya yang telah dijual untuk modal awal, sehingga tak perlu lagi pinjam mobil istrinya bila berangkat kerja. Karena Febriana, istri kesayangannya itu, sudah bekerja lagi sebagai pemasar di sebuah perusahaan furnitur raksasa. Katanya, banyak klien gajah – sebagian besar instansi pemerintah dan BUMN – yang suka datang ke kantornya.
“Saya mau ke kantor Bapak besok pagi. Ada beberapa perbaikan yang harus saya periksa sendiri, karena menyangkut angka-angka.” Pak Jumhur menelepon Sony siang itu.
Gawat, pikirnya. Di luaran sana, selama ini dia selalu berkoar-koar kalau perusahaannya mapan dan memiliki daya dukung SDM yang kuat. Padahal, kantornya hanya seluas dua puluh empat meter persegi. Dengan empat set meja-kursi, dua komputer dan satu laptop. Karyawan hanya tiga. Plus freelance satu, yang datang sesuai panggilan.
Karenanya, Sony tak pernah sekalipun mengundang klien untuk datang ke kantornya. Malu-maluin. Ketahuan nanti kalau selama ini bo’ong. Makanya, dia yang aktif menyambangi klien-kliennya. Kalau mereka ingin berkunjung, dia selalu punya cara untuk mengelak. Sedang tidak berada di kantor adalah alasan yang paling mudah diterima. Sehingga dengan gampang mereka digiring masuk ke restoran atau numpang ngobrol di lobby hotel mewah. Biar kelihatan gaya. Tak perlu keluar uang banyak. Hanya segelas dua gelas minuman dingin, atau beberapa cangkir kopi. Tapi kali ini Sony tidak bisa mengelak. Sudah empat kali Pak Jumhur gagal ke kantornya. Harus putar akal. Cari cara yang tepat.
“Pak Sony, kok bengong saja? Ayo, ngobrol-ngobrol di kantor saya. Kayaknya saya jarang lihat Bapak di kantin.” Pak Hanggono dari kantor sebelah menyapanya.
Sony agak kaget. Baru tersadar, rupanya sudah cukup lama dia berdiri bengong di depan pintu kantornya. “Eh, Bapak. Bagaimana kabar? Iya, kayaknya sudah lama kita tidak ngobrol. Bolehlah ke kantor Bapak.”
Mereka pun berjalan beriringan menuju kantor Pak Angga, demikian nama panggilan tetangga kantornya itu. Di ruang kerja pria baya yang berbadan pendek-gemuk itu, mereka mengobrol seru soal BLBI dan bank-bank yang dilikuidasi.
“Persis seperti sapi goyor. Dikasih minum banyak-banyak, baru kemudian disembelih,” ujar Pak Angga, yang pensiunan pejabat itu, sambil ketawa.
“Betul, Pak. He ... he ... he,” Sony menimpali.
“Pak, mohon maaf ini. Kok, saya lihat seperti ada beban yang berat?” tanya Pak Angga tiba-tiba, dengan tatapan mata serius.
Sony terdiam sejenak. Tapi akal kotornya langsung bergerak. Seperti biasa, dia paling doyan menggiring orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kemudian dia bercerita mengenai Pak Jumhur. Belum sempat Sony menyelesaikan ceritanya, Pak Angga langsung memotong. “Gampang itu.”
Sony sudah tahu arahnya. Benar, kan. Pak Angga menawarkan kantornya untuk pura-pura dijadikan kantor Sony bila Pak Jumhur datang berkunjung besok pagi. Kebetulan, kedua kantor yang bersebelahan itu punya pintu penghubung yang selama ini dibikin mati. Tinggal pinjam kuncinya – kalau perlu sekalian dibikin duplikatnya – kepada pengelola gedung agar pintu itu bisa dibuka sementara. Sudah. Tak pusing lagi.
Jadi, begini rencananya. Dengan menggabungkan kantor Sony dan kantor Pak Angga, maka akan didapatkan sepuluh orang yang kelihatan sedang sibuk bekerja. Sambil bekerja seperti biasanya, mereka hanya perlu pura-pura sibuk menelepon dan menerima telepon. Pakai interkom saja. Juga, beres-beres ini itu. Sudah cukuplah untuk membangun kesan pertama yang meyakinkan. Tinggal panggil Idrus, pekerja freelance, agar melakukan atraksi. Urusan lainnya gampang. Semua bisa diatur. Kan, ada Heru, yang juga ahli kadal.
Sungguh kebetulan, besok si empunya kantor ada acara seminar di Hotel Borobudur. Seharian lagi. Maka Sony bisa menggunakan ruang kerja Pak Angga untuk bergaya di depan Pak Jumhur. Beberapa foto di ruangan itu langsung diturunkan. Herlina, sekretaris Pak Angga, di-briefing. “Lin, jangan lupa kasih tahu kawan-kawan yang lain. Bantu Pak Sony,” pesan orang Yogjakarta itu.
“Pagi. Bisa ketemu Pak Sony?”
Ini dia. Pak Jumhur sudah datang. Lina menyambut tamu yang dinanti-nanti. Setelah basa-basi sebentar, diajaknya Pak Jumhur menemui Sony di ruang kerja Pak Angga.
“Ee, Pak Jumhur. Sudah saya tunggu-tunggu dari tadi. Kena macet, ya?” Sony menyapa tamunya itu dengan penuh hormat.
Pak Jumhur langsung duduk dan kemudian membuka map yang sedari tadi dikempit di ketiaknya. Semua berjalan lancar. Pekerjaan lancar. Pembayaran uang muka lancar. Atraksi lancar. Sandiwara lancar. Tepu-tepu lancar.
“Wah, kantor Pak Sony nyaman sekali, ya. Karyawannya hebat-hebat. Pekerja keras semua.”
Sony tersenyum lebar menerima pujian yang tulus itu.
“Siapa tadi sekretarisnya, Pak?”
Sony langsung menyahut, “Lina.”
Pak Jumhur mengangguk sambil tersenyum. “Oh, ya. Mbak Lina. Cekatan sekali dia.”
Dua boks besar Dunkin’ Donats sudah cukuplah sebagai tanda terima kasih kepada para aktor dan aktris dadakan itu. Kadang-kadang juga Pizza Huts. Kalau dihitung-hitung, sudah enam kali Sony bersandiwara seperti itu, dengan tamu yang berbeda-beda. Sepanjang masih bisa membantu, Pak Angga yang rambutnya sudah beruban semua itu tampaknya sama sekali tidak keberatan. Kelihatannya dia sangat tulus. Begitu pula karyawannya. Terutama Lina. Sesekali Sony mentraktir Pak Angga makan di restoran kece sebagai ungkapan terima kasih. Juga bertandang ke rumahnya di Lebak Bulus. Sedangkan Pak Jumhur, yang kini menjadi sahabat dekat Sony dan keluarganya, cuma ketawa-tawa setiap kali diingatkan mengenai sandiwara di kantor sekuprit itu. Begitu obrolan mereka menyinggung-nyinggung soal kantor lama, dia pasti akan langsung berucap, “Lina.” Kemudian mereka tertawa bersama.
Herannya, setiap kali berhasil mengerjai orang, Sony selalu merasa menang dan puas. Dia mulai khawatir, jangan-jangan dirinya sebenarnya orang yang culas. Heru juga pernah curhat mengenai hal yang sama kepadanya. Malahan, bapak dua anak yang asli Semarang itu lebih parah lagi kalau soal ngerjain orang. Sampai-sampai dia tak pernah punya klien, yang ada hanyalah korban. Karena klien-klien yang rajin menggelembungkan bonusnya tak lebih dari korban-korban omongan gombalnya. Lebih mengherankan lagi, klien-klien itu tidak pernah merasa dikadali. Malah sebaliknya, merasa sangat dibantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
Tapi Sony tak ingin tabiat buruknya itu menurun ke anak-anaknya kelak. Makanya, setiap sehabis sholat, yang suka bolong-bolong itu, dia selalu berdoa agar sifat-sifat buruk tersebut diangkat dan dibersihkan darinya. Tapi, namanya juga Sony, setiap kali berubah menjadi orang baik sebentar, tak lama kemudian menjadi anak nakal lagi.
“Nakal anak ini. Mau menangnya sendiri.” Tapi Sony tak sependapat dengan istrinya. Dia tidak melihatnya seperti itu. Rizky, anak pertamanya, hanya manja. Bukan nakal. Buktinya, setelah adiknya lahir, dia berubah menjadi anak yang manis. Rasa tanggung jawabnya mulai tumbuh. Sudah tak pernah lagi menangis sambil berguling-guling hanya karena permintaannya tidak dituruti. Sudah berubah dia.
Memang, kelahiran Salsa, anak keduanya, membawa banyak perubahan bagi keluarga maupun bisnis Sony. Semenjak kelahiran anak keduanya itu, usaha Sony kian berderap melangkah. Jumlah karyawan bertambah dua lagi mengikuti pekerjaan yang terus berganda. Sudah saatnya pindah, pikirnya. Cari kantor yang lebih lega. Sebuah ruko berlantai tiga menjadi incarannya. Di daerah Mampang, tepatnya di Jalan Kemang Utara. Sewanya tergolong murah.
Dengan kantor barunya yang cukup lapang, Sony tak perlu lagi bersandiwara di hadapan kliennya. Malahan, dia suka mengundang mereka untuk memamerkan ruang kerjanya yang seluas lapangan badminton dan dilengkapi dengan meja rapat yang sangat besar. Di dalam ruang kerja yang dindingnya dicat biru muda itu terpasang empat foto raksasa seukuran daun pintu, dengan pigura tebal berwana keemasan.
Keempat-empatnya foto Sony semua. Masing-masing dengan busana yang berbeda-beda, tapi posenya sama. Tegap berwibawa. Foto pertama menampilkan Sony yang bergaya sebagai Panglima TNI merangkap KSAD, dengan lima bintang di pundaknya. Pada foto kedua, Sony berlagak sebagai KSAL. Sedangkan foto ketiga dan keempat, memperlihatkan Sony yang sedang tersenyum gagah dalam balutan seragam KSAU dan Kapolri.
Sebenarnya masih ada yang lebih unik lagi di ruangan itu. Melatarbelakangi meja kerja Sony yang besar dan bentuknya sangat sederhana, seperti meja pingpong dibelah dua, di dinding atas terpampang foto diri Sony yang sedang bergaya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sedangkan di sebelahnya dia pasang foto mendiang ibundanya yang sudah dikutak-katik sehingga dandanannya mirip Ratu Elizabeth.
Sony sama sekali tidak berolok-olok. Dia ingin mewujudkan cita-cita masa kecilnya, meski hanya dalam bentuk foto diri. Sebagian tamunya sangat respek atas gagasan besar itu. Namun, kebanyakan yang lainnya hanya melirik dengan senyum ditahan. Juga karyawan-karyawannya, yang suka mengganggapnya sebagai orang gila yang baik hati.
Selanjutnya, di samping kanan meja terpasang bendera merah putih. Sedangkan di ujung satunya lagi, berkibar dengan gagah panji-panji berwarna krem yang di tengahnya bergambar buaya sedang bercengkerama dengan seekor macan, melambangkan kerukunan.
Sony menciptakan sendiri logo itu. Karena selama ini dia merasa kurang sreg dengan ikon merpati sebagai lambang perdamaian dan persahabatan. Konon katanya, merpati tak punya empedu, sehingga tidak ada yang pahit di dalam dirinya. Seolah perdamaian dan persahabatan hanya bicara yang manis-manis. Tidak ada pertengkaran. Tanpa rasa cemburu. Nir-ancaman, dan berbagai negasi lainnya.
Padahal, kata Tolstoy, banyak orang yang bisa tidur nyenyak di rumahnya pada malam hari, karena ada orang lain yang pergi berperang untuknya. Damai, perang. Sahabat, musuh. Biasa saja itu, bahkan sangat natural. Seperti halnya ada malam ada siang. Gelap, terang. Laki, perempuan. Malahan, absennya empedu di tubuh merpati sangat merugikan. Mas Hardi, tetangga Sony di kampung halaman, yang memelihara banyak burung dara itu, suka marah-marah kalau ada tetangga yang menjemur nasi basi di genting. Begitu mematuk-matuk karak, nasi aking, atau nasi basi yang dikeringkan, burung dara langsung keracunan, dan mati.
Mati aku, kata Sony, dalam hati, seraya menepuk-nepuk ubun-ubunnya yang luas dan berambut tipis. Dia benar-benar lupa. Kemarin Rachmad meneleponnya. Sohib lamanya itu memberi tahu ada peluncuran VCD Pasir Berbisik di Hard Rock Café. Karena tahu kalau Sony tergila-gila pada Dian Sastro, Rachmad menyuruhnya datang ke sana. Tombo ati, katanya. Masih terngiang-ngiang dengan sangat jelas di telinga Sony akan janji kawannya itu, “Son, nanti saya coba atur supaya kamu bisa duduk semeja dan makan malam bareng dengan gadis pujaanmu.” Tapi dia juga berpesan, “Awas! Jangan dipelet!”
Tukijan langsung menyiapkan mobil. Begitu Sony sudah duduk nyaman di jok belakang, mobil langsung digeber. Menyelip-nyelip di sela-sela kemacetan. Lincah sekali. Seperti gerakan ikan yang sedang menghindari tangkapan tangan. Ciiiittt …. Ciiiittt …. Clep! Mobil masuk ke kolong truk. Hancur bagian depannya. Mangap. Sony tidak apa-apa. Tukijan hanya mendapatkan lecet-lecet kecil di tangannya. Digigit pecahan kaca. Bahkan, dia masih sempat cengengesan, sepertinya untuk meringankan rasa bersalahnya.
Namun, kecelakaan itu membuat Sony kehilangan mood untuk bertemu gadis pujaannya. Bukan soal mobilnya yang hancur. Tetapi seperti ada sesuatu yang membuat perasaannya seperti tak keruan. Dia sendiri juga tidak mengerti. “It’s not my day,” keluhnya. Meski Tukijan sudah menyetop taksi, Sony memutuskan tidak pergi. Batal. Dia malah menyuruh supir Taksi Express itu mengantarnya pulang ke rumah.
“Tunggulah aku, Dian. Suatu saat nanti kita akan bertemu. Saling jatuh cinta. Berpacaran. Meski hanya dalam mimpi.”
Bagi Sony, ini bencana. Mestinya hari itu dia mendapatkan kebahagiaan besar.
Benar-benar besar. Karena belum pernah Sony ketiban proyek sejumbo itu. Sering-sering saja begini, pikirnya. Saking girangnya, rambutnya mbrodol lima. Pun, seandainya disuruh lari mengelilingi Monas sebanyak tiga kali, pasti dia sanggupi. Cari saja orang yang agak mirip dengannya. Didandani sedikit, kemudian disuruh lari. Dia cukup menguntitnya dari belakang, sambil ngumpet di dalam mobil. Soal dokumentasi video, bisa direkayasa.
Sudahlah. Tak usah beranda-andai. Karena paket pekerjaan raksasa itu sudah di genggaman tangan. Semuanya harus segera diselesaikan. Cepat selesai cepat dibayar. Dari keuntungan proyek ini, Sony mengganti mobil inventaris yang dipakai Heru dengan mobil baru. Dan, menggeber habis penyelesaian pembangunan kantornya di Kebayoran yang sudah hampir setahun terhenti pada pekerjaan pondasi.
Setelah sempat dua setengah tahun ngantor di garasi yang sempit dan gerah di Kemang, kemudian melakukan big leap dengan berkantor sambil bergaya di gedung mentereng Menara Mulia selama satu setengah tahun, dilanjutkan dengan terjun bebas ke ruangan seluas dua puluh empat meter persegi di gedung jangkung di seberang jalan tol lingkar luar selama setahun akibat krisis ekonomi, kemudian menyeberang ke ruko tiga lantai di daerah Mampang setelah rezeki dan jumlah karyawan bertambah, pada tahun dua ribu empat Sony berhasil menyelesaikan pembangunan gedung kantornya sendiri di Kebayoran.
Kantor tiga lantai yang dibangun di atas sebidang tanah seluas tiga ratus empat puluh meter persegi itu merupakan hasil jerih payanya selama beberapa tahun berwiraswasta. Dua lantai di atas dia manfaatkan untuk kantor. Sedangkan lantai bawah dijadikan tempat parkir. Sony menamakan bangunan kantor barunya tersebut Gedung Sanga, dalam bahasa Jawa berarti angka sembilan. Nama itu muncul begitu saja di dalam benaknya. Maknanya, tidak ada sama sekali. Sekedar nama.
Tapi Ceng Li, temannya main golf itu, sangat percaya dengan keberuntungan yang melekat pada sebuah nama. Lima bulan lalu dia mengajak Sony pergi ke Gunung Kawi untuk berburu nama bagi perusahaan baru yang akan didirikannya. Dengan halus Sony menolak ajakan tersebut, karena dia tidak percaya dengan yang begitu-begitu. Baginya, soal keberuntungan dan hoki sudah ditetapkan di atas sana. Manusia tinggal berusaha. Mudah-mudahan saja hasilnya sesuai dengan yang telah dipatok oleh asa. Buktinya, Mualim, kawan lamanya, langsung sukses besar begitu memulai usaha. Padahal, pada awalnya banyak kawan yang meremehkannya. Menganggapnya tak punya daya, apalagi gaya, untuk menjadi pengusaha. Kenyataannya, tanpa harus menempuh jalan yang berliku, bisnisnya membesar begitu saja. Menjadikannya kaya raya.
Tidak harus pintar untuk menjadi pengusaha yang berhasil. Persis seperti yang pernah dikatakan pakar pendidikan Dr. Arief Rachman, bahwa bukan kepintaran yang menjadikan orang berhasil dalam pekerjaannya, tapi kualitas personalnya. Mualim adalah salah satu contohnya. Begitu banyak pengusaha sukses yang semasa sekolah tergolong siswa yang biasa-biasa saja. Bahkan ada juga yang putus sekolah. Tapi, begitu memasuki dunia kerja, dan kemudian membuka usaha, mereka menjelma menjadi orang-orang yang luar biasa hebat.
Namun, rasa-rasanya tak adil menyebut mereka tidak pintar. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang sangat pintar, karena jeli melihat peluang dan piawai membuat keputusan. Kemampuan itulah yang tidak dimiliki semua orang. Syukur-syukur kalau hebat di sekolah sekaligus memiliki kualitas personal yang bagus. Pasti tambah jadi.
Pengusaha pada dasarnya adalah orang yang baik. Di dunia ini, tidak ada pengusaha yang jahat. Kalaupun pernah ditemukan beberapa, jumlahnya sangat kecil. Jarang sekali. Dan, itu termasuk anomali. Sesungguhnya, mereka yang suka berperilaku amoral bukanlah pengusaha. Mereka hanyalah para petualang. Membuka usaha dengan tujuan culas di belakang. Seperti paguyuban tepu-tepu Qsar, koin emas, arisan lebaran dan lain sebagainya. Tujuannya jangka pendek saja. Mengumpulkan nasabah sebanyak-banyaknya. Sekali tepuk mati ribuan nyawa. Kemudian kabur dengan langkah tergesa-gesa. Ngumpet di rumah kerabatnya. Hingga polisi datang menjemputnya. Sebagian lagi, petualang kelas teri. Bikin perusahaan karena dapat proyek. Mengelabuhi pemodal dengan janji bonek. Setelah itu perusahaan di-engek-engek. Tak peduli karyawan pada kececeran ke mana-mana. Yang penting sudah tercapai tujuannya. Setelah itu berpetualang lagi, menjebak korban-korban berikutnya. Sekali lagi, mereka bukanlah pengusaha.
Lain petualang lain pula pengusaha. Pengusaha adalah orang-orang yang berhati mulia. Malahan, Sony yakin, para pengusaha sudah punya kavling masing-masing di surga. Bagaimana tidak? Mereka adalah pribadi-pribadi yang mampu menciptakan lapangan kerja, atau, dalam bahasa yang lebih sederhana, memberikan mata pencaharian dan nafkah bagi puluhan juta keluarga, dengan sekian banyak mulut yang menganga di belakangnya. Kalau boleh sedikit menepuk dada, para pengusaha berkontribusi besar bagi terciptanya kehidupan yang berkualitas di negeri ini. Tidak hanya melalui lapangan kerja yang mereka ciptakan, tetapi juga melalui jalannya kegiatan usaha sebagai salah satu engine yang memberikan power untuk menggerakkan ekonomi. Seraya membagi-bagikan daya beli. Sehingga terangkatlah kesejahteraan keluarga dan masyarakat, yang pada akhirnya juga berarti kesejahteraan bangsa.
Makanya, para pekerja tidak perlu mencurigai, apalagi memusuhi, pengusaha. Karena pada dasarnya pengusaha tak suka bermusuhan. Musuh hanya akan menutup jalan di depan. Malahan, pengusaha ingin merangkul kawan sebanyak-banyaknya. Termasuk menjadikan para pekerja sebagai mitra. Sesungguhnya, para pengusaha akan merasakan kebahagian dunia akherat ketika melihat para pekerjanya hidup sejahtera.
Tapi gegap-gempita euphoria demokrasi semenjak bergulirnya era reformasi telah menjadikan para pekerja Indonesia kehilangan tatakrama. Malahan, cenderung beringas. Sedikit-sedikit unjuk rasa, tanpa peduli dengan keadaan ekonomi yang terkadang kurang bersahabat. Di mata mereka, para pengusaha adalah orang-orang jahat. Tak pernah sedikitpun berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan wajah marah selalu menuntut pemerintah berdiri di belakang mereka. Padahal pemerintah harusnya berdiri di tengah, di antara pengusaha dan pekerja.
Kalau begini, namanya mau menang sendiri. Padahal, di samping puyeng menjalankan roda usaha, para pengusaha juga harus berpikir keras mengenai kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dan, mengantisipasi semua risiko yang setiap saat datang tanpa perlu diundang. Ujung-ujungnya, sebenarnya untuk para pekerja juga, dan, tentu saja, bagi kepentingan pengusaha sendiri. Sama-sama, agar masing-masing pihak, pekerja maupun pengusaha, tidak merugi. Agar perusahan tak sampai tutup dan para pekerjanya pada keleleran. Yang begini ini, para pekerja sering tak mau tahu. Menutup mata. Seolah hanya mereka yang punya hak untuk menuntut begini dan begitu.
Soal upah selalu menjadi pangkal sengketa. Masih untung ada UMP, UMR, standar biaya hidup minimal, atau apalah namanya. Kalau mau jujur, soal upah seharusnya tunduk pada hukum permintaan dan penawaran, mekanisme pasar. Cukup diselesaikan di antara pengusaha dan pekerja. Tak perlu memaksa-maksa pemerintah berpihak. Pemerintah harus berdiri sebagai wasit. Tak perlu cawe-cawe. Cukup mengawasi saja. Karena pengusaha dan pekerja adalah sama-sama warga negara yang harus dilindungi dan dibela kepentingannya. Harus diperlakukan sama. Tidak ada bedanya. Sama-sama makan nasi.
Semuanya harus diserahkan kepada hukum pasar. Mekanisme pasar akan bekerja dengan tangan-tangan gaibnya, kata orang pintar. Di Cina, misalnya, belum lama berselang pernah kejadian di mana suatu kawasan industri kehilangan semua pekerjanya karena mereka ramai-ramai pindah ke daerah dan perusahaan lain yang memberikan upah lebih besar. Biasa itu. Itu yang namanya mekanisme pasar, yang hampir saban hari didengung-dengungkan oleh banyak orang, termasuk pemerintah, dan juga para pekerja. Bahkan, orang-orang yang tinggal di pucuk gunung pun tunduk pada mekanisme pasar global, karena mereka harus membeli barang kebutuhan sehari-hari pada tingkat harga dunia, minyak goreng, misalnya.
Jadi, begini gampangnya. Kalau perusahaan mampunya hanya bayar segitu, mau di bilang apa? Kalau mau, ya silahkan kerja baik-baik, lah. Kalau tidak mau, ya cari saja kerja di tempat lain. Masih bagus bisa kerja. Banyak pengangguran di luaran sana yang bengong jadi penonton dengan mulut menganga. Pun, begitu pula yang berlaku bagi para pengusaha. Kalau mau mendapatkan pekerja yang baik dan terampil, atau supaya tidak ditinggalkan oleh pekerjanya, pasti mereka harus memenuhi tuntutan upah yang lebih tinggi dari para pekerja. Itulah hukum permintaan dan penawaran. Gitu aja kok repot.
Tidak perlu pakai demo-demo segala. Nyusahin orang lain. Mengganggu ketertiban. Memacetkan lalu-lintas. “Berisik,” kata Presiden. Setiap hari demo. Pakai sweeping segala. Itu tabiat keroyokan, alias tawuran. Memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak kita. Lagian, kalau keadaan dibiarkan begini terus, bisa runyam. Sony sedih melihat sekian banyak investasi asing yang memilih berkemas karena tak tahan dengan ulah para pekerja yang ugal-ugalan. Belum lagi para investor yang urung masuk.
Sony memang paling sebel melihat demo yang begitu marak di mana-mana. Setiap hari, pula. Selalu saja melibatkan, dan dimotori oleh, mahasiswa. Seolah demo sudah menjadi salah satu mata kuliah. Sudalah. Mahasiswa kan telah memberikan kontribusi yang luar biasa besar bagi bergulirnya era reformasi dengan menurunkan Presiden Soeharto melalui demo di gedung DPR. Cukup itu. Semua orang tahu. Dan, mengakui.
Sekarang ndak usah demo lagi, lah. Demo bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan kebebasan pendapat dan menyuarakan tuntutan. Apalagi dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat. Apa bener, itu? Mahasiswa kan calon intelektual bangsa? Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih intelek? Dengan tulisan-tulisan tajam yang menggugah di media massa, atau internet, misalnya. Ini zaman keterbukaan, Mas. Pasti mendapatkan perhatian. Paling tidak, akan direspon oleh mereka-mereka yang berkepentingan. Toh, koran ada di mana-mana. Mulai dari yang kelas kabupaten hingga nasional. Atau, pergi ke warnet. Apa susahnya?
Susahnya? Ya, nulisnya itu, Bung. Makanya, para mahasiswa harus dibiasakan mengorganisasikan pikiran-pikiran mereka dalam bentuk tulisan. Dengan demikian mereka dapat menyampaikan apa yang ada di kepala secara lebih sistematis, dan tidak bias. Kalau perlu, dosen diwajibkan membuat soal-soal ujian dengan jawaban yang berbentuk esai. Bukan pilihan ganda yang mirip tebak-tebakan itu. Juga kewajiban membuat paper untuk setiap mata kuliah. Dengan demikian, para calon intelektual itu akan lebih banyak mencurahkan waktu mereka untuk masuk ke dalam kebiasaan intelek tersebut. Mereka akan sibuk, sehingga tak sempat demo. He ... He ... He ....
Sebenarnya ada sesuatu yang salah di negeri ini sehingga setiap hari ada demo. Tapi, apa, atau siapa, yang salah? Jelas, media massa, terutama TV. Stasiun-stasiun televisi begitu gemar meliput demo, sehinga para pendemo merasa mendapat dukungan, dapat ngeceng, dan, unjuk muka sambil berteriak-teriak lantang dengan ucapan yang hebat-hebat. Bahkan, demo yang tidak jelas juntrungannya pun dijadikan berita. Sebaiknya media massa, terutama TV, tidak perlu meliput demo. Kalau perlu, memboikot demo. Kagak bakal naikin rating, kok. Jadi, kalau ada orang-orang yang lagi demo, tidak perlu lagi diliput. Biarin saja. Lama-lama mereka akan bosan sendiri. Capek. Kepanasan. Tidak ada penontonnya.
Ngomongnya jadi ke mana-mana, nih. Padahal tadi kan bicara soal hubungan antara pengusaha dan pekerja. Oh, ya. Beberapa tahun lalu Sony pernah diperkarakan oleh mantan karyawannya. Tapi, tiga kali surat panggilan dari pengadilan hubungan industrial dia abaikan begitu saja. Karena dia tidak mau melayani dendam dan fitnah. Mau lapor ke Depnakertrans kek, atau mengadu ke Presiden sekalipun, tidak akan dia gubris. Akhirnya mereka capek sendiri. Tidak ada kabarnya lagi.
Jadi, begini ceritanya. Yopie, mantan anak buah Heru itu, dikeluarkan karena tidak mampu membuat transaksi. Bahkan setelah diberi waktu perpanjangan selama tiga bulan, masih gagal juga. Ya sudah. Dikeluarkan saja. Model beginian sebenarnya sudah biasa di mana-mana. Marketing yang tak mampu membuat transaksi ya harus minggir. Biar tidak menuh-menuhin tempat. Kalau Depnakertrans ngotot membela pekerja model begini, itu kebangetan namanya. Karena dia sama sekali bukanlah orang yang dizalimi. Malahan, sebaliknya, dia menzalimi diri sendiri.
Ngapain repot-repot menanggapi orang model begini. Mending konsentrasi membesarkan usaha, dan melakukan pemupukan modal. Karena belakangan uang muka semakin susah didapatkan. Lagian, Sony bukanlah tipe pengusaha yang gemar mengambil kredit bank, meski beberapa orang marketing dari bank tempatnya membuka rekening berkali-kali datang ke kantornya menawarkan kredit usaha. Tapi Sony tetap kukuh dengan pendiriannya. Dia tak mau mengelola utang. Dia lebih memilih menempuh jalan tradisional, tidak boros dan tidak pula menunda-nunda membayar utang. Karenanya, pemupukan modal usaha sangat dia perhatikan. Sehingga tak perlu bingung cari pinjaman kiri kanan bila harus memodali pekerjaan-pekerjaan yang agak besar.
Fadli, adiknya, yang membesarkan pabrik pupuknya dengan kredit dari bank, bahkan pernah mengritiknya habis-habisan mengenai soal ini. “Kapan kamu jadi besar kalau tidak mau bersinergi dengan bank dan lembaga pendanaan,” katanya suatu kali.
Sony tak menanggapinya. Diam saja.
Demikian pula soal kartu kredit. Sony cuma punya satu, Visa Platinum. Selebihnya hanya dua keping kartu ATM. Mau dikata tidak modern, kuno, biar saja. Hal yang sama juga dia coba terapkan kepada para karyawannya. Dia berpesan kepada Anita jangan sampai sembarangan memberikan surat keterangan penghasilan atau rekomendasi lainnya kepada karyawan untuk kepentingan pembuatan kartu kredit. Dia tak ingin mereka terperangkap dalam jebakan kartu kredit, yang dengan mudah akan menjerumuskan orang ke dalam tabiat buruk lebih besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal tetap sohor. Hal yang seperti ini akan menjadikan hidup mereka tidak normal, karena dikejar-kejar utang. Gali lobang tutup lobang. Bikin kartu kredit baru untuk melunasi sebagian utang kartu kredit lama. Begitu seterusnya. Akhirnya, pekerjaan jadi ikut-ikutan kedodoran. Say no to credit cards? Ndak perlulah. Biar saja.
Namun, sudah waktunya pemerintah, YLKI, Bank Indonesia, atau siapapun dan juga lembaga apapun yang berkepentingan, mulai turun tangan. Memang tidak mungkin melarang orang memiliki kartu kredit, seperti halnya mustahil melarang orang merokok. Ini hak asasi. Toh, banyak juga orang yang mendapatkan manfaat positif dari kartu kredit karena cukup bijak, hati-hati dan bisa menahan diri dalam menggunakannya. Dan tidak mungkin pula bagi YLKI untuk memberikan advokasi kepada para penunggak kartu kredit yang terperangkap dalam utang berlapis-lapis. Bagaimanapun, mereka sudah menikmati berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan, hanya saja digunakan tanpa perhitungan dan benar-benar sembrono. Sebagian lagi karena pada dasarnya memang hobi ngemplang utang. Jadi, harus tanggung sendiri risiko ditongkrongi orang-orang berwajah garang.
Namun, perangkap kartu kredit yang menjebak sekian juta orang yang tidak siap itu sesungguhnya tak kalah merusak dibandingkan dengan berbagai kebiasaan buruk lain yang meracuni masyarakat, seperti merokok atau menenggak minuman beralkohol, misalnya. Bila pada kemasan rokok saja dicantumkan peringatan pemerintah – diadopsi dari aturan yang berlaku di seluruh dunia – yang berbunyi MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI, DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN, maka pada setiap keping kartu kredit mestinya juga bisa dituliskan peringatan sejenis, misalnya PENGGUNAAN KARTU KREDIT SECARA TIDAK BIJAKSANA DAPAT MENYEBABKAN PERILAKU LEBIH BESAR PASAK DARIPADA TIANG.
Di samping itu, persyaratan aplikasi dan persetujuan pemberian kartu kredit perlu lebih diperketat lagi dengan survai yang tidak asal-asalan. Upaya perlindungan seperti ini akan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak, nasabah dan bank penerbit kartu kredit. Masyarakat senantiasa diingatkan agar lebih bijaksana dan dapat menahan diri dalam penggunaan kartu kredit, agar tidak terjebak dalam pusaran utang. Sedangkan bank penerbit kartu kredit bisa menghimpun nasabah yang benar-benar memenuhi syarat sehingga jumlah tagihan bermasalah bisa ditekan. Tak perlu menyuburkan profesi tukang tagih.
Begitu gampangnya aplikasi kartu kredit diluluskan sehingga office boy pun bisa memiliki kartu kredit. Sony, yang memiliki kartu kredit Visa, tiba-tiba saja dikirimi kartu kredit Master oleh bank penerbitnya. Setelah dia telepon ke bank, jawabannya sederhana saja. “Kalau Bapak mau pakai, tinggal dilakukan aktivasi. Bila Bapak tidak berkenan, gunting saja kartu itu.” Seandainya kesempatan tersebut jatuh ke tangan orang yang pada dasarnya doyan berutang, pasti langsung diembat penawaran yang menggiurkan seperti itu.
Namun kartu kredit tidak selamanya buruk. Ada juga kolega Sony yang memulai usaha dengan bermodalkan sejumlah kartu kredit dan kredit tanpa agunan atau pinjaman personal. Memang agak berisiko. Gali lobang tutup lobang harus dilakukan. Syukurlah dia berhasil. Usahanya cepat berkembang. Seandainya saja gagal, pasti langsung kiamat. Kejadian deh, libur panjang.
“Libur lagi? Minggu kemarin ada hari libur. Masa, minggu ini masih saja ada tanggal merahnya?” Sony semakin tak paham saja. Sambil bersungut-sungut dia mematikan api rokoknya. Kalau libur hari Sabtu dan Minggu, wajar sajalah. Manusia membutuhkan waktu untuk beristirahat yang cukup setelah bekerja keras. Tapi, banyak banget hari kerja yang diwarnai merah pada kalender. Belum lagi soal cuti bersama. Termasuk penggeseran hari libur yang mengapit Harpitnas di tahun-tahun sebelumnya.
Apa pemerintah kurang kerjaan? Sepertinya senang betul kalau ketemu hari libur. Bagi Sony, libur sehari saja, berarti hilang sudah kesempatan untuk cari duit, sementara biaya bulanan tak mau sedikitpun dimintai libur. Pusing. Pusing. Pusing.
Beberapa jenis industri bahkan harus kelimpungan setiap kali hari kerjanya kepotong tanggal merah. Mereka tak mungkin mematikan mesin, karena butuh waktu berhari-hari untuk proses start up. Tapi pekerja pada menghilang. Jadilah mesin dibiarkan tetap menyala tanpa menghasilkan apa-apa. Utilities terpaksa jalan terus. Rugi. Mau dikata apa.
Sony setuju belaka kalau hari-hari besar keagamaan ditetapkan sebagai hari libur. Tapi mestinya hanya untuk penganut agama yang bersangkutan. Tak perlu berlaku untuk semua. Hari Raya Nyepi, misalnya, harusnya yang mendapatkan libur hanya orang-orang yang beragama Hindu Bali, dan sah-sah saja bila semua kegiatan di Pulau Bali dihentikan. Tapi, bagi penganut agama lain yang tidak tinggal di Pulau Dewata, tentu tak perlu ikut-ikutan diliburkan. Untuk apa? Sebagian besar mereka cuma tidur-tiduran di rumah. Hanya sebagian kecil orang yang punya kelebihan uang yang bisa menikmati long week end.
Pemerintah suka mengganggap semuanya sama rata. Gebyah uyah. Kalau yang satu libur, yang lain harus ikutan libur, meski tak punya kepentingan sama sekali dengan hari yang diliburkan itu. Mungkin mereka tak mau susah-susah membuat pengaturan hari libur yang lebih rinci. Toh, pada dasarnya mereka suka hari libur, karena memang kurang kerjaan. Sementara para pekerja swasta senang-senang saja dengan kebiasaan yang sama sekali tidak menguntungkan bagi kalangan pengusaha ini. Toh, mereka tidak merasa terikat dengan target produksi, target pemasukan dan beban-beban berat yang menghimpit lainnya. Itu urusan manajemen, kata mereka. Asal gaji tak sampai telat dan THR terbayar, mereka pada senyum. Sebaliknya, pengusaha puyeng dibuatnya. Mau protes tidak bisa. Karena sudah ditetapkan di kalender. Sudah formal. Final.
Seandainya pemerintah mau memperhatikan sedikit saja kepentingan para pengusaha dalam menetapkan hari-hari libur nasional dan keagamaan. Misalnya, pada Hari Raya Imlek, hanya masyarakat keturunan Tionghwa yang berhak mendapatkan hari libur. Sedangkan mereka yang tidak ikut merayakan hari yang serba merah itu tetap bekerja seperti biasanya. Kalaupun para pemilik toko di kawasan Glodok menutup toko mereka dan meliburkan karyawannya, itu sah-sah saja. Diliburkan boleh, tidak diliburkan juga tak apa. Terserah mereka. Dengan demikian, tidak perlu dibuat tanggal merah untuk hari libur seperti itu. Bisa saja diganti dengan warna biru atau hijau. Hal yang sama juga dapat diterapkan untuk hari-hari libur keagamaan lainnya.
Lebaran atau Idul Fitri merupakan perkecualian, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Sehingga ketika sebagian besar pekerja libur, tidak lucu juga bila kantor-kantor yang karyawannya tinggal satu atau dua orang tidak ikut meliburkan mereka sekalian. Kasihan. Pada bengong sendiri nanti. Tapi tidak perlu diatur-atur soal cuti bersama. Biar para pengusaha yang menentukan sendiri. Mereka toh juga punya toleransi dan cukup tahu diri. Lagian, cuti bersama kan cuma akal-akalan untuk mengatur sebagian PNS yang suka memulur-mulurkan hari libur. Maunya mengatur satu kelompok pekerja, tapi aturannya ditetapkan untuk semua. Ini aneh sekali. Untungnya Menpan sudah membatalkan cuti bersama sebagai hari libur bagi PNS, sehingga karyawan swasta tidak perlu ikut-ikutan menuntut libur.
Sudah waktunya dilakukan pengkajian ulang soal penetapan hari libur, baik libur nasional maupun libur keagamaan. Setiap agama mendapatkan hari libur secara adil dan berlaku khusus hanya untuk penganut agama yang bersangkutan. Jangan terlalu royal dengan hari libur. Itu bukan tabiat bangsa pekerja keras.
Sony mulai berwiraswasta pada usia dua puluh delapan tahun. Setelah dipikirkannya masak-masak, akhirnya dia memutuskan keluar dari pekerjaannya yang lumayan mapan. Dia berhimpun bersama dua orang rekannya mendirikan sebuah perusahaan. Hanya saja, kedua temannya itu, Rachmad Santosa dan Sunarna Wiguna, masih tetap menekuni pekerjaan masing-masing. Rachmad seorang wartawan. Sedang Sunarna adalah pengusaha perakitan komputer yang baru genap setahun memulai usaha sendiri setelah sebelumnya cukup lama ngenger di salah satu perusahaan milik pengusaha-politisi liat dan tahan banting asal Surabaya.
Maka, jadilah Sony pengelola tunggal perusahaan kelas gurem itu. Kedua sohibnya hanya seminggu sekali datang. Tak apa. Di luaran sana, mereka giat membantunya mencari order. Pekerjaan apa saja disabet. Pokoknya ada pemasukan. Dapat sedikit untung dibagi-bagi di antara mereka bertiga.
Sebuah rumah kos di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur, mempertemukan mereka di akhir tahun delapan puluhan. Sama-sama masih bujangan dan culun karena baru datang dari kampung. Rachmad, orang Solo itu, menyelesaikan kuliahnya di Institut Pertanian Bogor, jurusan Tanah. Makanya, kulitnya agak gelap. Malahan bisa dibilang gosong. Mungkin karena terlalu sering dijilati matahari. Sedangkan Sunarna, yang orang Cianjur, hanyalah tamatan SMA, namun sangat cerdas. Kemampuan analisanya luar biasa tajam dan selalu optimistis menatap masa depan. Keterbatasan ekonomi keluarga melarangnya duduk-duduk di bangku kuliah. Karena omongan yang sama-sama nyambung, jadilah mereka tiga serangkai yang ke mana-mana selalu bareng, pergi ke bioskop, berburu buku loak di Kwitang, menggoda waria di Taman Lawang, nonton video porno, termasuk main kyu-kyu.
Selama dua tahun pertama perusahaan baru itu tidak mengalami perkembangan berarti. Sekedar bisa jalan. Kantornya numpang di garasi rumah mertua Rachmad di daerah Kemang. Karyawan hanya dua orang. Nancy menangani administrasi. Sedangkan Suradi kebagian urusan umum. Tugasnya mengantar surat dan barang, bersih-bersih kantor, dan juga membelikan makan siang.
Memasuki awal tahun ketiga, Sony mulai terengah-engah. Gaji karyawan dua kali tertunda. Sementara kebutuhannya sendiri terus meningkat semenjak anak pertamanya lahir. Akhirnya Sony menyerah. Kantornya bubar. Sebulan kemudian dia diterima bekerja di sebuah perusahaan pameran. Di sinilah pertama kali dia bertemu Heru Wibowo, orang kepercayaannya saat ini. Juga Mualim, yang tidak terlalu pintar tapi hokinya besar. Dan Lexy, orang Manado yang berwajah cina itu.
Pak Mansyur, pemilik perusahaan tersebut, sangat menyukai Sony karena dianggap membawa banyak perubahan bagi kemajuan perusahaan. Dalam waktu kurang dari setahun dia dipromosikan jadi manajer. Namun promosi ini membawa berkah sekaligus petaka. Biasa, selalu ada sisi hitam dan putih, baik dan buruk. Djumali, orang lama kepercayaan Pak Mansyur, iri kepadanya. Dia merasa terancam, dan dipinggirkan. Beberapa kali Sony difitnah. Namun mental belaka.
Sebenarnya jenggah juga. Bekerja di bawah sorotan mata. Tapi Sony agak terhibur hatinya. Posisi baru tersebut memberinya kesempatan luas untuk memahami apa itu pengelolaan usaha. Yang sebelumnya dia jalani begitu saja. Apa adanya. Tanpa rencana. Inilah saatnya. Mencuri ilmu dari mulut yang menganga. Serap habis hingga tak bersisa. Biar tinggal tulang berbalut kulit bertambal kain kassa.
Hanya satu setengah tahun Sony bekerja di sana. Sungguh tak nyaman, sekaligus menyebalkan. Kaki kiri menginjak bara neraka, kaki kanan bertumpu di tubir surga. Akhirnya dengan berat hati dia keluar, dan memutuskan kembali berwiraswasta.
Ada beberapa pertimbangan yang membulatkan tekadnya. Pertama, Djumali yang gemar memakai sepatu koboi itu semakin keterlaluan. Sudah menjurus ke cara-cara edan. Kedua, Sony merasa tidak nyaman dengan istri bosnya yang sering datang ke kantor dan sok mengatur. Apalagi, perempuan ganjen itu cs berat dengan Djumali. Mereka seperti berkomplot untuk menjatuhkan Sony. Ketiga, merasa sudah makmur, Pak Mansyur mulai mengimpor lusinan kerabat dari kampung halaman untuk bekerja di kantornya. Sebagian orangnya baik-baik, tapi kebanyakan cuma merecoki orang yang lagi kerja. Keempat, Rachmad dan Sunarna mengajaknya bergabung kembali. Anak seorang konglomerat bersedia mendanai.
Keren benar. Sony berkantor di Menara Mulia. Karyawan langsung direkrut lima. Dia tarik Lexy menjadi pembantu utamanya. Ini baru namanya perusahaan, pikirnya. Namun, seperti biasanya, Rachmad dan Sunarna tidak bergabung penuh. Mereka memilih menjadi direktur freelance. Seperti yang sudah-sudah, kedua karibnya itu masih berat meninggalkan pekerjaan masing-masing. Sudahlah, tak perlu dirisaukan. Karena dua proyek besar sudah di genggaman tangan.
Baru sekali ini Sony benar-benar merasa percaya diri sebagai seorang pengusaha. Kejayaan sudah di pelupuk mata. Satu pekerjaan sudah diselesaikannya. Menghasilkan keuntungan yang luar biasa gendut. Segendut Pretty Asmara, perawan cantik dari Sukodono itu. Sementara pekerjaan kedua hampir kelar, dan beberapa pekerjaan baru segera menyusul.
Kiamat. Datang begitu cepat. Seperti kilat. Cakarnya menggurat-gurat. Langit langsung pekat. Sebulan setelah Sony berhasil menyelesaikan pekerjaan besarnya yang kedua, krisis ekonomi menyergap. Harapan tiba-tiba lenyap. Sirna ditelan senyap. Semua orang tergagap-gagap. Banyak yang megap-megap. Seolah mulutnya dibekap. Padahal mereka mangap. Masih untung, sebagian malah sudah tengkurap. Berenang di atas kayu sirap. Dengan paku-paku tajam yang menancap.
Palu godam datang dengan mengendap-endap. Kemudian mengepakkan sayap. Meliuk-liuk melintasi deretan atap. Berayun-ayun seperti tongkat sulap. Menghancurkan bisnis menyisakan asap. Bank-bank pada tiarap. Dari tubuh mereka berlelehan kecap. Tertatih-tatih beringsut merayap. Sementara bank sentral terus menghamburkan parap. Menyembelih anak-anaknya yang terperangkap. Sebagian berhasil lari menyelinap. Korban berjatuhan ke dalam lobang gelap. Berguguran seperti rayap. Mereka hanya bisa meratap. Sedikit berharap. Dan, kalap.
Dalam gilasan krisis, kantor baru Sony hanya mampu bertahan setahun. Keuntungan dari pekerjaan pertama dan kedua habis untuk menutup biaya bulanan. Beberapa pekerjaan batal. Hanya dua yang tetap jalan. Tanpa tetesan keuntungan. Krisis itu telah menggerus modal. Bubar.
Sony goyah. Malahan sempat memunggungi Tuhan. Karena kemalangan menimpanya justru pada saat kejayaan sedang bermula. Kecewa. Putus asa. Merasa seolah telah terlempar dan tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang sedang berputar. Beruntung, Febriana yang terkena PHK malah lebih tabah dan senantiasa mengingatkannya agar lebih tawakal. Benar, pikir Sony. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Dengan menjual mobilnya, sebuah sedan Toyota Corona keluaran tahun sembilan tiga, ditambah secawan perhiasan istrinya, Sony memulai usaha baru. Dia menyewa ruangan seukuran garasi di sebuah gedung jangkung yang matanya selalu awas memelototi kendaraan-kendaraan yang berlalu-lalang di jalan tol lingkar luar itu. Karyawannya hanya tiga. Heru, Anita dan Usep, office boy yang jenaka itu, yang masih kerabat jauh Sunarna.
Tapi kali ini Sony jalan sendirian saja. Single fighter. Tidak bergabung lagi bersama kawan-kawannya. Beruntung, Dewi Fortuna berpihak kepadanya. Belum genap dua bulan, Sony sudah mendapatkan pekerjaan yang lumayan besar dari sebuah perusahaan pupuk milik negara, dengan sedikit tepu-tepu, tentu saja. Dari sinilah dia mulai melebarkan kepakan sayapnya. Menembaki sasaran mudah. Sitting ducks. Institusi pemerintah dan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Dalam kenyataannya, banyak pengusaha yang lebih suka menguber proyek-proyek dari pemerintah atau institusi yang terkait dengan pemerintah, juga BUMN dan BUMD. Alasannya sederhana saja. Pertama, pasti dibayar, karena setiap proyek baru bisa dilaksanakan setelah anggaran turun. Artinya, uangnya sudah pasti ada. Kedua, harga bisa dimain-mainkan, bila perlu, diajak berjoget gaya jaipongan, semalam suntuk.
Di masa lalu, permainan harga cenderung gila-gilaan, hingga bisa digelembungkan sesukanya, seperti balon udara, sebagian lagi melar menjadi balon raksasa. Tetapi tetap ada batasnya, jangan sampai balon itu meletus dan memuntahkan isi perutnya yang berbau anyir.
“Monggo, Mas. Mau ambil untung berapa, asal setengahnya untuk kita,” kata mereka.
Hanya orang gila yang akan membuang muka menerima tawaran menggiurkan seperti itu. Dengan demikian, berarti para pengusaha adalah orang-orang yang waras. Kalau begitu, yang gila, siapa?
“Katakan tidak pada korupsi”, kata iklan sebuah partai politik. Ngawur itu. Iklan tersebut seolah menyiratkan bahwa kalangan dunia usaha suka usil menggoda para aparat birokrasi untuk melakukan korupsi. Terbalik, nyung. Aparat birokrasilah yang gemar mengajak para pengusaha untuk melakukan kong-kalikong. Mau bukti? Banyak. Ambil contoh, kasus BNI Melawai yang melibatkan Pauline Lumowa itu. Orang-orang BNI justru yang mengajari Bu Gendut dan mengatur segala sesuatunya.
Banyak orang geram menyaksikan praktek-praktek binal seperti itu. Dengan tatapan mata marah dan mulut berapi-api mereka menyebutnya korupsi. Wajar-wajar saja, karena mereka bersandar pada sudut pandang sistem. Bagi pengusaha seperti Sony, itu tak lebih dari sekedar biaya lobby, yang sudah diperhitungkan dan dianggarkan dalam pos biaya entertain atau pos-pos biaya lain yang disamarkan.
Memang tipis perbedaannya, antara korupsi dan biaya lobby, karena mereka berdua masih sedarah, terlahir dari bapak dan ibu kandung yang sama. Artinya, bukan anak haram, tapi anak blasteran. Buah cinta dari perselingkuhan nikmat antara para birokrat dan pengusaha. Karenanya, tak perlu dibikin pusing. Biarkan saja masing-masing melihat dengan cara pandangnya sendiri-sendiri. Korupsi, atau biaya lobby, boleh-boleh saja, asal jangan keterlaluan. Kenyataannya, begitu banyak, kalau tak mau dibilang jutaan, anak Indonesia yang dibesarkan dari uang hasil korupsi, termasuk sebagian pendemo itu, yang suka mejeng di TV.
Namun, sebagai warga negara, bagaimanapun, Sony juga ingin korupsi bisa terus ditekan di negeri ini. Kalau mau dibasmi, mustahil. Sampai kepalanya botak juga tak akan berhasil. Seperti orang yang kurang kerjaan saja, usil.
“Korupsi mempercepat derap langkah pembangunan, dan melahirkan para pahlawan.” Ini sama sekali bukan ucapan yang ngasal dan mengada-ada. Kalimat yang agak membingungkan itu meluncur dari mulut seorang mantan direktur sebuah bank bergincu merah yang telah beralih profesi menjadi pengusaha.
Siang itu, Sony sedang mengobrol sambil menyantap iga panggang di Tony’s Roma bersama sohib kentalnya tersebut, dan juga Ceng Li. Mereka bertiga sama-sama penggemar ikan hias air laut yang sering ketemu di pasar ikan hias di Jalan Sumenep hampir setiap Sabtu. Makanya, setiap kali makan bersama, mereka sebisa mungkin menghindari seafood. Jangan sampai PMP, pren makan pren.
“Maksudnya apa, Pak,” tanya Sony, sambil mengunyah gigitan kecil daging harum itu seraya memperhatikan Ceng Li yang tampaknya juga agak bingung dengan pernyataan aneh tersebut.
Kedua bola mata pria tinggi besar itu agak melotot. Pupilnya bergerak-gerak sedikit liar ke atas dan ke bawah. Berputar-putar lembut. Dari keningnya mulai menitik beberapa noktah cairan asin. Jakunnya naik turun pelan. Kedua tangannya diregangkan. Sepertinya dia kesulitan untuk menjawab pertanyaan Sony karena mulutnya penuh dengan potongan-potongan kecil daging iga yang lembut, manis dan pedas yang sedang dikunyahnya. Lelehan saus merah mengalir malas dari sudut-sudut bibirnya. Enak tenan. Mantap kale, kata Benu Buloe si jurumakan.
“Begini, Bung,” ujarnya sambil mengelap mulutnya. Tapi dia tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Napasnya masih belum teratur. Mungkin tenggorokannya bingung. Karena harus terus-terusan membuka tutup secara bergantian, saluran pernapasan untuk memberi jalan kepada pasukan yang sedang memanggul jutaan karung oksigen ke dalam paru-paru, dan saluran menuju lambung yang setiap saat kemasukan bagian-bagian kecil dari seekor sapi tak bernama. Salah langkah, bisa cegukan itu orang.
Setelah meneguk segelas air putih, barulah pria berbusana batik sutra itu terlihat agak rileks. Kemudian dengan tangkas dia menguraikan logikanya. Selama ini orang selalu menyorot korupsi dari sudut pandang sistem. Karena ada aturan yang dilanggar, maka ada pihak yang dirugikan dan ada pula pihak yang merugikan. Yang beginian sudah jamak di mana-mana. Sudah basi. Anak SD juga tahu. Persoalan korupsi mestinya didekati dengan tinjauan bisnis, dan juga sosiologis.
Para pelaku korupsi sebenarnya bukanlah orang-orang tamak bin serakah. Sebaliknya, merekalah pahlawan ekonomi, karena senantiasa berbagi hasil korupsi dengan keluarga, kerabat, sejawat, masyarakat dan dunia usaha, sehingga terbentuklah jutaan mata rantai ekonomi dalam untaian-untaian kecil namun panjang melalui uang hasil korupsi yang dibelanjakan tersebut. Konsumsi naik ekonomi bergerak. Sektor riil mau diajak beranjak. Asal jangan diinjak. Ayo …, korupsi. Edan.
Pahlawan ekonomi itu, para pelaku korupsi, tambahnya, janganlah diuber-uber. Mereka harus dihormati, dan diberi penghargaan. Kalau perlu disiapkan pin emas barang tiga atau lima gram. Bagaimanapun, tabiat buruk mereka selama ini terbukti mampu mempercepat laju pembangunan dan menggerakkan ekonomi, sehingga masyarakat dan para pelaku usaha pada tersenyum. Itulah chemistry yang paling pas untuk situasi faktual Indonesia.
Buktinya, setelah para pahlawan ekonomi itu diuber-uber dengan ganas, pembangunan jalan di tempat. Proyek-proyek cuma dikurung, tak dilepas. Pengusaha ngaplo. Masyarakat melongo. Duit Pemda yang jumlahnya ribuan kali lipat penduduk bumi itu dibiarkan berpesta mesum di bilik-bilik tertutup di kantor-kantor bank. Sehingga berceceranlah anak-anak haram yang dihasilkan dari perselingkuhan bejat itu. Mereka jadi malas beredar. Tiduran saja. Pinggulnya masih ngilu. Semalam bertempur habis-habisan.
Sekarang, kalau tukang uber-uber tersebut memang sakti, mampu kagak mereka memaksa trilyunan duit Pemda yang sedang pelesiran sambil menikmati wine dan menghisap cerutu Kuba itu agar segera check out dari kamar-kamar SBI dan perbankan? Agar Sony menari-nari riang. Karena main proyek di pemerintahan nikmat banget. Sedangkan, kalau main di swasta, agak seret. Harga ditekan habis. Pasti dibayar, meski ada juga yang tak terbayar. Karena pembiayaan pekerjaan biasanya dianggarkan dari proyeksi pemasukan. Kalau pemasukan agak terganggu, pembayaran bisa mundur tak keru-keruan. Menciptakan efek berantai yang merugikan banyak pihak serta menimbulkan ketidaknyamanan.
Sony sendiri tak pernah menolak pekerjaan dari swasta, bahkan terus mengubernya. Dia pegang pekerjaan besar dari salah satu perusahaan kawannya. Dia tekuni dengan serius meski marginnya kecil kalau dihitung per satuan. Namun, karena rutin dan volumenya lumayan tambun, akumulasi marginnya bisa menutup biaya bulanan.
Sony merasa sangat bersyukur karena usaha barunya berjalan relatif lancar. Sejumlah pekerjaan baru dia dapatkan. Fadli, adiknya itu, beberapa kali meminjaminya tambahan modal kerja. Tanpa bunga. Meski pekerjaan terus bertambah, dia belum punya keinginan merekrut karyawan baru untuk meringankan beban kerja. Masih melihat-lihat dulu. Tunggu sampai benar-benar aman. Panggil saja pekerja freelance. Banyak di luaran sana. Tidak perlu bayar gaji bulanan.
Dia lebih fokus pada pemupukan modal. Sebagian keuntungan dia sisihkan untuk beli mobil, sebagai ganti dari mobilnya yang telah dijual untuk modal awal, sehingga tak perlu lagi pinjam mobil istrinya bila berangkat kerja. Karena Febriana, istri kesayangannya itu, sudah bekerja lagi sebagai pemasar di sebuah perusahaan furnitur raksasa. Katanya, banyak klien gajah – sebagian besar instansi pemerintah dan BUMN – yang suka datang ke kantornya.
“Saya mau ke kantor Bapak besok pagi. Ada beberapa perbaikan yang harus saya periksa sendiri, karena menyangkut angka-angka.” Pak Jumhur menelepon Sony siang itu.
Gawat, pikirnya. Di luaran sana, selama ini dia selalu berkoar-koar kalau perusahaannya mapan dan memiliki daya dukung SDM yang kuat. Padahal, kantornya hanya seluas dua puluh empat meter persegi. Dengan empat set meja-kursi, dua komputer dan satu laptop. Karyawan hanya tiga. Plus freelance satu, yang datang sesuai panggilan.
Karenanya, Sony tak pernah sekalipun mengundang klien untuk datang ke kantornya. Malu-maluin. Ketahuan nanti kalau selama ini bo’ong. Makanya, dia yang aktif menyambangi klien-kliennya. Kalau mereka ingin berkunjung, dia selalu punya cara untuk mengelak. Sedang tidak berada di kantor adalah alasan yang paling mudah diterima. Sehingga dengan gampang mereka digiring masuk ke restoran atau numpang ngobrol di lobby hotel mewah. Biar kelihatan gaya. Tak perlu keluar uang banyak. Hanya segelas dua gelas minuman dingin, atau beberapa cangkir kopi. Tapi kali ini Sony tidak bisa mengelak. Sudah empat kali Pak Jumhur gagal ke kantornya. Harus putar akal. Cari cara yang tepat.
“Pak Sony, kok bengong saja? Ayo, ngobrol-ngobrol di kantor saya. Kayaknya saya jarang lihat Bapak di kantin.” Pak Hanggono dari kantor sebelah menyapanya.
Sony agak kaget. Baru tersadar, rupanya sudah cukup lama dia berdiri bengong di depan pintu kantornya. “Eh, Bapak. Bagaimana kabar? Iya, kayaknya sudah lama kita tidak ngobrol. Bolehlah ke kantor Bapak.”
Mereka pun berjalan beriringan menuju kantor Pak Angga, demikian nama panggilan tetangga kantornya itu. Di ruang kerja pria baya yang berbadan pendek-gemuk itu, mereka mengobrol seru soal BLBI dan bank-bank yang dilikuidasi.
“Persis seperti sapi goyor. Dikasih minum banyak-banyak, baru kemudian disembelih,” ujar Pak Angga, yang pensiunan pejabat itu, sambil ketawa.
“Betul, Pak. He ... he ... he,” Sony menimpali.
“Pak, mohon maaf ini. Kok, saya lihat seperti ada beban yang berat?” tanya Pak Angga tiba-tiba, dengan tatapan mata serius.
Sony terdiam sejenak. Tapi akal kotornya langsung bergerak. Seperti biasa, dia paling doyan menggiring orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kemudian dia bercerita mengenai Pak Jumhur. Belum sempat Sony menyelesaikan ceritanya, Pak Angga langsung memotong. “Gampang itu.”
Sony sudah tahu arahnya. Benar, kan. Pak Angga menawarkan kantornya untuk pura-pura dijadikan kantor Sony bila Pak Jumhur datang berkunjung besok pagi. Kebetulan, kedua kantor yang bersebelahan itu punya pintu penghubung yang selama ini dibikin mati. Tinggal pinjam kuncinya – kalau perlu sekalian dibikin duplikatnya – kepada pengelola gedung agar pintu itu bisa dibuka sementara. Sudah. Tak pusing lagi.
Jadi, begini rencananya. Dengan menggabungkan kantor Sony dan kantor Pak Angga, maka akan didapatkan sepuluh orang yang kelihatan sedang sibuk bekerja. Sambil bekerja seperti biasanya, mereka hanya perlu pura-pura sibuk menelepon dan menerima telepon. Pakai interkom saja. Juga, beres-beres ini itu. Sudah cukuplah untuk membangun kesan pertama yang meyakinkan. Tinggal panggil Idrus, pekerja freelance, agar melakukan atraksi. Urusan lainnya gampang. Semua bisa diatur. Kan, ada Heru, yang juga ahli kadal.
Sungguh kebetulan, besok si empunya kantor ada acara seminar di Hotel Borobudur. Seharian lagi. Maka Sony bisa menggunakan ruang kerja Pak Angga untuk bergaya di depan Pak Jumhur. Beberapa foto di ruangan itu langsung diturunkan. Herlina, sekretaris Pak Angga, di-briefing. “Lin, jangan lupa kasih tahu kawan-kawan yang lain. Bantu Pak Sony,” pesan orang Yogjakarta itu.
“Pagi. Bisa ketemu Pak Sony?”
Ini dia. Pak Jumhur sudah datang. Lina menyambut tamu yang dinanti-nanti. Setelah basa-basi sebentar, diajaknya Pak Jumhur menemui Sony di ruang kerja Pak Angga.
“Ee, Pak Jumhur. Sudah saya tunggu-tunggu dari tadi. Kena macet, ya?” Sony menyapa tamunya itu dengan penuh hormat.
Pak Jumhur langsung duduk dan kemudian membuka map yang sedari tadi dikempit di ketiaknya. Semua berjalan lancar. Pekerjaan lancar. Pembayaran uang muka lancar. Atraksi lancar. Sandiwara lancar. Tepu-tepu lancar.
“Wah, kantor Pak Sony nyaman sekali, ya. Karyawannya hebat-hebat. Pekerja keras semua.”
Sony tersenyum lebar menerima pujian yang tulus itu.
“Siapa tadi sekretarisnya, Pak?”
Sony langsung menyahut, “Lina.”
Pak Jumhur mengangguk sambil tersenyum. “Oh, ya. Mbak Lina. Cekatan sekali dia.”
Dua boks besar Dunkin’ Donats sudah cukuplah sebagai tanda terima kasih kepada para aktor dan aktris dadakan itu. Kadang-kadang juga Pizza Huts. Kalau dihitung-hitung, sudah enam kali Sony bersandiwara seperti itu, dengan tamu yang berbeda-beda. Sepanjang masih bisa membantu, Pak Angga yang rambutnya sudah beruban semua itu tampaknya sama sekali tidak keberatan. Kelihatannya dia sangat tulus. Begitu pula karyawannya. Terutama Lina. Sesekali Sony mentraktir Pak Angga makan di restoran kece sebagai ungkapan terima kasih. Juga bertandang ke rumahnya di Lebak Bulus. Sedangkan Pak Jumhur, yang kini menjadi sahabat dekat Sony dan keluarganya, cuma ketawa-tawa setiap kali diingatkan mengenai sandiwara di kantor sekuprit itu. Begitu obrolan mereka menyinggung-nyinggung soal kantor lama, dia pasti akan langsung berucap, “Lina.” Kemudian mereka tertawa bersama.
Herannya, setiap kali berhasil mengerjai orang, Sony selalu merasa menang dan puas. Dia mulai khawatir, jangan-jangan dirinya sebenarnya orang yang culas. Heru juga pernah curhat mengenai hal yang sama kepadanya. Malahan, bapak dua anak yang asli Semarang itu lebih parah lagi kalau soal ngerjain orang. Sampai-sampai dia tak pernah punya klien, yang ada hanyalah korban. Karena klien-klien yang rajin menggelembungkan bonusnya tak lebih dari korban-korban omongan gombalnya. Lebih mengherankan lagi, klien-klien itu tidak pernah merasa dikadali. Malah sebaliknya, merasa sangat dibantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
Tapi Sony tak ingin tabiat buruknya itu menurun ke anak-anaknya kelak. Makanya, setiap sehabis sholat, yang suka bolong-bolong itu, dia selalu berdoa agar sifat-sifat buruk tersebut diangkat dan dibersihkan darinya. Tapi, namanya juga Sony, setiap kali berubah menjadi orang baik sebentar, tak lama kemudian menjadi anak nakal lagi.
“Nakal anak ini. Mau menangnya sendiri.” Tapi Sony tak sependapat dengan istrinya. Dia tidak melihatnya seperti itu. Rizky, anak pertamanya, hanya manja. Bukan nakal. Buktinya, setelah adiknya lahir, dia berubah menjadi anak yang manis. Rasa tanggung jawabnya mulai tumbuh. Sudah tak pernah lagi menangis sambil berguling-guling hanya karena permintaannya tidak dituruti. Sudah berubah dia.
Memang, kelahiran Salsa, anak keduanya, membawa banyak perubahan bagi keluarga maupun bisnis Sony. Semenjak kelahiran anak keduanya itu, usaha Sony kian berderap melangkah. Jumlah karyawan bertambah dua lagi mengikuti pekerjaan yang terus berganda. Sudah saatnya pindah, pikirnya. Cari kantor yang lebih lega. Sebuah ruko berlantai tiga menjadi incarannya. Di daerah Mampang, tepatnya di Jalan Kemang Utara. Sewanya tergolong murah.
Dengan kantor barunya yang cukup lapang, Sony tak perlu lagi bersandiwara di hadapan kliennya. Malahan, dia suka mengundang mereka untuk memamerkan ruang kerjanya yang seluas lapangan badminton dan dilengkapi dengan meja rapat yang sangat besar. Di dalam ruang kerja yang dindingnya dicat biru muda itu terpasang empat foto raksasa seukuran daun pintu, dengan pigura tebal berwana keemasan.
Keempat-empatnya foto Sony semua. Masing-masing dengan busana yang berbeda-beda, tapi posenya sama. Tegap berwibawa. Foto pertama menampilkan Sony yang bergaya sebagai Panglima TNI merangkap KSAD, dengan lima bintang di pundaknya. Pada foto kedua, Sony berlagak sebagai KSAL. Sedangkan foto ketiga dan keempat, memperlihatkan Sony yang sedang tersenyum gagah dalam balutan seragam KSAU dan Kapolri.
Sebenarnya masih ada yang lebih unik lagi di ruangan itu. Melatarbelakangi meja kerja Sony yang besar dan bentuknya sangat sederhana, seperti meja pingpong dibelah dua, di dinding atas terpampang foto diri Sony yang sedang bergaya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sedangkan di sebelahnya dia pasang foto mendiang ibundanya yang sudah dikutak-katik sehingga dandanannya mirip Ratu Elizabeth.
Sony sama sekali tidak berolok-olok. Dia ingin mewujudkan cita-cita masa kecilnya, meski hanya dalam bentuk foto diri. Sebagian tamunya sangat respek atas gagasan besar itu. Namun, kebanyakan yang lainnya hanya melirik dengan senyum ditahan. Juga karyawan-karyawannya, yang suka mengganggapnya sebagai orang gila yang baik hati.
Selanjutnya, di samping kanan meja terpasang bendera merah putih. Sedangkan di ujung satunya lagi, berkibar dengan gagah panji-panji berwarna krem yang di tengahnya bergambar buaya sedang bercengkerama dengan seekor macan, melambangkan kerukunan.
Sony menciptakan sendiri logo itu. Karena selama ini dia merasa kurang sreg dengan ikon merpati sebagai lambang perdamaian dan persahabatan. Konon katanya, merpati tak punya empedu, sehingga tidak ada yang pahit di dalam dirinya. Seolah perdamaian dan persahabatan hanya bicara yang manis-manis. Tidak ada pertengkaran. Tanpa rasa cemburu. Nir-ancaman, dan berbagai negasi lainnya.
Padahal, kata Tolstoy, banyak orang yang bisa tidur nyenyak di rumahnya pada malam hari, karena ada orang lain yang pergi berperang untuknya. Damai, perang. Sahabat, musuh. Biasa saja itu, bahkan sangat natural. Seperti halnya ada malam ada siang. Gelap, terang. Laki, perempuan. Malahan, absennya empedu di tubuh merpati sangat merugikan. Mas Hardi, tetangga Sony di kampung halaman, yang memelihara banyak burung dara itu, suka marah-marah kalau ada tetangga yang menjemur nasi basi di genting. Begitu mematuk-matuk karak, nasi aking, atau nasi basi yang dikeringkan, burung dara langsung keracunan, dan mati.
Mati aku, kata Sony, dalam hati, seraya menepuk-nepuk ubun-ubunnya yang luas dan berambut tipis. Dia benar-benar lupa. Kemarin Rachmad meneleponnya. Sohib lamanya itu memberi tahu ada peluncuran VCD Pasir Berbisik di Hard Rock Café. Karena tahu kalau Sony tergila-gila pada Dian Sastro, Rachmad menyuruhnya datang ke sana. Tombo ati, katanya. Masih terngiang-ngiang dengan sangat jelas di telinga Sony akan janji kawannya itu, “Son, nanti saya coba atur supaya kamu bisa duduk semeja dan makan malam bareng dengan gadis pujaanmu.” Tapi dia juga berpesan, “Awas! Jangan dipelet!”
Tukijan langsung menyiapkan mobil. Begitu Sony sudah duduk nyaman di jok belakang, mobil langsung digeber. Menyelip-nyelip di sela-sela kemacetan. Lincah sekali. Seperti gerakan ikan yang sedang menghindari tangkapan tangan. Ciiiittt …. Ciiiittt …. Clep! Mobil masuk ke kolong truk. Hancur bagian depannya. Mangap. Sony tidak apa-apa. Tukijan hanya mendapatkan lecet-lecet kecil di tangannya. Digigit pecahan kaca. Bahkan, dia masih sempat cengengesan, sepertinya untuk meringankan rasa bersalahnya.
Namun, kecelakaan itu membuat Sony kehilangan mood untuk bertemu gadis pujaannya. Bukan soal mobilnya yang hancur. Tetapi seperti ada sesuatu yang membuat perasaannya seperti tak keruan. Dia sendiri juga tidak mengerti. “It’s not my day,” keluhnya. Meski Tukijan sudah menyetop taksi, Sony memutuskan tidak pergi. Batal. Dia malah menyuruh supir Taksi Express itu mengantarnya pulang ke rumah.
“Tunggulah aku, Dian. Suatu saat nanti kita akan bertemu. Saling jatuh cinta. Berpacaran. Meski hanya dalam mimpi.”
Bagi Sony, ini bencana. Mestinya hari itu dia mendapatkan kebahagiaan besar.
Benar-benar besar. Karena belum pernah Sony ketiban proyek sejumbo itu. Sering-sering saja begini, pikirnya. Saking girangnya, rambutnya mbrodol lima. Pun, seandainya disuruh lari mengelilingi Monas sebanyak tiga kali, pasti dia sanggupi. Cari saja orang yang agak mirip dengannya. Didandani sedikit, kemudian disuruh lari. Dia cukup menguntitnya dari belakang, sambil ngumpet di dalam mobil. Soal dokumentasi video, bisa direkayasa.
Sudahlah. Tak usah beranda-andai. Karena paket pekerjaan raksasa itu sudah di genggaman tangan. Semuanya harus segera diselesaikan. Cepat selesai cepat dibayar. Dari keuntungan proyek ini, Sony mengganti mobil inventaris yang dipakai Heru dengan mobil baru. Dan, menggeber habis penyelesaian pembangunan kantornya di Kebayoran yang sudah hampir setahun terhenti pada pekerjaan pondasi.
Setelah sempat dua setengah tahun ngantor di garasi yang sempit dan gerah di Kemang, kemudian melakukan big leap dengan berkantor sambil bergaya di gedung mentereng Menara Mulia selama satu setengah tahun, dilanjutkan dengan terjun bebas ke ruangan seluas dua puluh empat meter persegi di gedung jangkung di seberang jalan tol lingkar luar selama setahun akibat krisis ekonomi, kemudian menyeberang ke ruko tiga lantai di daerah Mampang setelah rezeki dan jumlah karyawan bertambah, pada tahun dua ribu empat Sony berhasil menyelesaikan pembangunan gedung kantornya sendiri di Kebayoran.
Kantor tiga lantai yang dibangun di atas sebidang tanah seluas tiga ratus empat puluh meter persegi itu merupakan hasil jerih payanya selama beberapa tahun berwiraswasta. Dua lantai di atas dia manfaatkan untuk kantor. Sedangkan lantai bawah dijadikan tempat parkir. Sony menamakan bangunan kantor barunya tersebut Gedung Sanga, dalam bahasa Jawa berarti angka sembilan. Nama itu muncul begitu saja di dalam benaknya. Maknanya, tidak ada sama sekali. Sekedar nama.
Tapi Ceng Li, temannya main golf itu, sangat percaya dengan keberuntungan yang melekat pada sebuah nama. Lima bulan lalu dia mengajak Sony pergi ke Gunung Kawi untuk berburu nama bagi perusahaan baru yang akan didirikannya. Dengan halus Sony menolak ajakan tersebut, karena dia tidak percaya dengan yang begitu-begitu. Baginya, soal keberuntungan dan hoki sudah ditetapkan di atas sana. Manusia tinggal berusaha. Mudah-mudahan saja hasilnya sesuai dengan yang telah dipatok oleh asa. Buktinya, Mualim, kawan lamanya, langsung sukses besar begitu memulai usaha. Padahal, pada awalnya banyak kawan yang meremehkannya. Menganggapnya tak punya daya, apalagi gaya, untuk menjadi pengusaha. Kenyataannya, tanpa harus menempuh jalan yang berliku, bisnisnya membesar begitu saja. Menjadikannya kaya raya.
Tidak harus pintar untuk menjadi pengusaha yang berhasil. Persis seperti yang pernah dikatakan pakar pendidikan Dr. Arief Rachman, bahwa bukan kepintaran yang menjadikan orang berhasil dalam pekerjaannya, tapi kualitas personalnya. Mualim adalah salah satu contohnya. Begitu banyak pengusaha sukses yang semasa sekolah tergolong siswa yang biasa-biasa saja. Bahkan ada juga yang putus sekolah. Tapi, begitu memasuki dunia kerja, dan kemudian membuka usaha, mereka menjelma menjadi orang-orang yang luar biasa hebat.
Namun, rasa-rasanya tak adil menyebut mereka tidak pintar. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang sangat pintar, karena jeli melihat peluang dan piawai membuat keputusan. Kemampuan itulah yang tidak dimiliki semua orang. Syukur-syukur kalau hebat di sekolah sekaligus memiliki kualitas personal yang bagus. Pasti tambah jadi.
Pengusaha pada dasarnya adalah orang yang baik. Di dunia ini, tidak ada pengusaha yang jahat. Kalaupun pernah ditemukan beberapa, jumlahnya sangat kecil. Jarang sekali. Dan, itu termasuk anomali. Sesungguhnya, mereka yang suka berperilaku amoral bukanlah pengusaha. Mereka hanyalah para petualang. Membuka usaha dengan tujuan culas di belakang. Seperti paguyuban tepu-tepu Qsar, koin emas, arisan lebaran dan lain sebagainya. Tujuannya jangka pendek saja. Mengumpulkan nasabah sebanyak-banyaknya. Sekali tepuk mati ribuan nyawa. Kemudian kabur dengan langkah tergesa-gesa. Ngumpet di rumah kerabatnya. Hingga polisi datang menjemputnya. Sebagian lagi, petualang kelas teri. Bikin perusahaan karena dapat proyek. Mengelabuhi pemodal dengan janji bonek. Setelah itu perusahaan di-engek-engek. Tak peduli karyawan pada kececeran ke mana-mana. Yang penting sudah tercapai tujuannya. Setelah itu berpetualang lagi, menjebak korban-korban berikutnya. Sekali lagi, mereka bukanlah pengusaha.
Lain petualang lain pula pengusaha. Pengusaha adalah orang-orang yang berhati mulia. Malahan, Sony yakin, para pengusaha sudah punya kavling masing-masing di surga. Bagaimana tidak? Mereka adalah pribadi-pribadi yang mampu menciptakan lapangan kerja, atau, dalam bahasa yang lebih sederhana, memberikan mata pencaharian dan nafkah bagi puluhan juta keluarga, dengan sekian banyak mulut yang menganga di belakangnya. Kalau boleh sedikit menepuk dada, para pengusaha berkontribusi besar bagi terciptanya kehidupan yang berkualitas di negeri ini. Tidak hanya melalui lapangan kerja yang mereka ciptakan, tetapi juga melalui jalannya kegiatan usaha sebagai salah satu engine yang memberikan power untuk menggerakkan ekonomi. Seraya membagi-bagikan daya beli. Sehingga terangkatlah kesejahteraan keluarga dan masyarakat, yang pada akhirnya juga berarti kesejahteraan bangsa.
Makanya, para pekerja tidak perlu mencurigai, apalagi memusuhi, pengusaha. Karena pada dasarnya pengusaha tak suka bermusuhan. Musuh hanya akan menutup jalan di depan. Malahan, pengusaha ingin merangkul kawan sebanyak-banyaknya. Termasuk menjadikan para pekerja sebagai mitra. Sesungguhnya, para pengusaha akan merasakan kebahagian dunia akherat ketika melihat para pekerjanya hidup sejahtera.
Tapi gegap-gempita euphoria demokrasi semenjak bergulirnya era reformasi telah menjadikan para pekerja Indonesia kehilangan tatakrama. Malahan, cenderung beringas. Sedikit-sedikit unjuk rasa, tanpa peduli dengan keadaan ekonomi yang terkadang kurang bersahabat. Di mata mereka, para pengusaha adalah orang-orang jahat. Tak pernah sedikitpun berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan wajah marah selalu menuntut pemerintah berdiri di belakang mereka. Padahal pemerintah harusnya berdiri di tengah, di antara pengusaha dan pekerja.
Kalau begini, namanya mau menang sendiri. Padahal, di samping puyeng menjalankan roda usaha, para pengusaha juga harus berpikir keras mengenai kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dan, mengantisipasi semua risiko yang setiap saat datang tanpa perlu diundang. Ujung-ujungnya, sebenarnya untuk para pekerja juga, dan, tentu saja, bagi kepentingan pengusaha sendiri. Sama-sama, agar masing-masing pihak, pekerja maupun pengusaha, tidak merugi. Agar perusahan tak sampai tutup dan para pekerjanya pada keleleran. Yang begini ini, para pekerja sering tak mau tahu. Menutup mata. Seolah hanya mereka yang punya hak untuk menuntut begini dan begitu.
Soal upah selalu menjadi pangkal sengketa. Masih untung ada UMP, UMR, standar biaya hidup minimal, atau apalah namanya. Kalau mau jujur, soal upah seharusnya tunduk pada hukum permintaan dan penawaran, mekanisme pasar. Cukup diselesaikan di antara pengusaha dan pekerja. Tak perlu memaksa-maksa pemerintah berpihak. Pemerintah harus berdiri sebagai wasit. Tak perlu cawe-cawe. Cukup mengawasi saja. Karena pengusaha dan pekerja adalah sama-sama warga negara yang harus dilindungi dan dibela kepentingannya. Harus diperlakukan sama. Tidak ada bedanya. Sama-sama makan nasi.
Semuanya harus diserahkan kepada hukum pasar. Mekanisme pasar akan bekerja dengan tangan-tangan gaibnya, kata orang pintar. Di Cina, misalnya, belum lama berselang pernah kejadian di mana suatu kawasan industri kehilangan semua pekerjanya karena mereka ramai-ramai pindah ke daerah dan perusahaan lain yang memberikan upah lebih besar. Biasa itu. Itu yang namanya mekanisme pasar, yang hampir saban hari didengung-dengungkan oleh banyak orang, termasuk pemerintah, dan juga para pekerja. Bahkan, orang-orang yang tinggal di pucuk gunung pun tunduk pada mekanisme pasar global, karena mereka harus membeli barang kebutuhan sehari-hari pada tingkat harga dunia, minyak goreng, misalnya.
Jadi, begini gampangnya. Kalau perusahaan mampunya hanya bayar segitu, mau di bilang apa? Kalau mau, ya silahkan kerja baik-baik, lah. Kalau tidak mau, ya cari saja kerja di tempat lain. Masih bagus bisa kerja. Banyak pengangguran di luaran sana yang bengong jadi penonton dengan mulut menganga. Pun, begitu pula yang berlaku bagi para pengusaha. Kalau mau mendapatkan pekerja yang baik dan terampil, atau supaya tidak ditinggalkan oleh pekerjanya, pasti mereka harus memenuhi tuntutan upah yang lebih tinggi dari para pekerja. Itulah hukum permintaan dan penawaran. Gitu aja kok repot.
Tidak perlu pakai demo-demo segala. Nyusahin orang lain. Mengganggu ketertiban. Memacetkan lalu-lintas. “Berisik,” kata Presiden. Setiap hari demo. Pakai sweeping segala. Itu tabiat keroyokan, alias tawuran. Memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak kita. Lagian, kalau keadaan dibiarkan begini terus, bisa runyam. Sony sedih melihat sekian banyak investasi asing yang memilih berkemas karena tak tahan dengan ulah para pekerja yang ugal-ugalan. Belum lagi para investor yang urung masuk.
Sony memang paling sebel melihat demo yang begitu marak di mana-mana. Setiap hari, pula. Selalu saja melibatkan, dan dimotori oleh, mahasiswa. Seolah demo sudah menjadi salah satu mata kuliah. Sudalah. Mahasiswa kan telah memberikan kontribusi yang luar biasa besar bagi bergulirnya era reformasi dengan menurunkan Presiden Soeharto melalui demo di gedung DPR. Cukup itu. Semua orang tahu. Dan, mengakui.
Sekarang ndak usah demo lagi, lah. Demo bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan kebebasan pendapat dan menyuarakan tuntutan. Apalagi dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat. Apa bener, itu? Mahasiswa kan calon intelektual bangsa? Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih intelek? Dengan tulisan-tulisan tajam yang menggugah di media massa, atau internet, misalnya. Ini zaman keterbukaan, Mas. Pasti mendapatkan perhatian. Paling tidak, akan direspon oleh mereka-mereka yang berkepentingan. Toh, koran ada di mana-mana. Mulai dari yang kelas kabupaten hingga nasional. Atau, pergi ke warnet. Apa susahnya?
Susahnya? Ya, nulisnya itu, Bung. Makanya, para mahasiswa harus dibiasakan mengorganisasikan pikiran-pikiran mereka dalam bentuk tulisan. Dengan demikian mereka dapat menyampaikan apa yang ada di kepala secara lebih sistematis, dan tidak bias. Kalau perlu, dosen diwajibkan membuat soal-soal ujian dengan jawaban yang berbentuk esai. Bukan pilihan ganda yang mirip tebak-tebakan itu. Juga kewajiban membuat paper untuk setiap mata kuliah. Dengan demikian, para calon intelektual itu akan lebih banyak mencurahkan waktu mereka untuk masuk ke dalam kebiasaan intelek tersebut. Mereka akan sibuk, sehingga tak sempat demo. He ... He ... He ....
Sebenarnya ada sesuatu yang salah di negeri ini sehingga setiap hari ada demo. Tapi, apa, atau siapa, yang salah? Jelas, media massa, terutama TV. Stasiun-stasiun televisi begitu gemar meliput demo, sehinga para pendemo merasa mendapat dukungan, dapat ngeceng, dan, unjuk muka sambil berteriak-teriak lantang dengan ucapan yang hebat-hebat. Bahkan, demo yang tidak jelas juntrungannya pun dijadikan berita. Sebaiknya media massa, terutama TV, tidak perlu meliput demo. Kalau perlu, memboikot demo. Kagak bakal naikin rating, kok. Jadi, kalau ada orang-orang yang lagi demo, tidak perlu lagi diliput. Biarin saja. Lama-lama mereka akan bosan sendiri. Capek. Kepanasan. Tidak ada penontonnya.
Ngomongnya jadi ke mana-mana, nih. Padahal tadi kan bicara soal hubungan antara pengusaha dan pekerja. Oh, ya. Beberapa tahun lalu Sony pernah diperkarakan oleh mantan karyawannya. Tapi, tiga kali surat panggilan dari pengadilan hubungan industrial dia abaikan begitu saja. Karena dia tidak mau melayani dendam dan fitnah. Mau lapor ke Depnakertrans kek, atau mengadu ke Presiden sekalipun, tidak akan dia gubris. Akhirnya mereka capek sendiri. Tidak ada kabarnya lagi.
Jadi, begini ceritanya. Yopie, mantan anak buah Heru itu, dikeluarkan karena tidak mampu membuat transaksi. Bahkan setelah diberi waktu perpanjangan selama tiga bulan, masih gagal juga. Ya sudah. Dikeluarkan saja. Model beginian sebenarnya sudah biasa di mana-mana. Marketing yang tak mampu membuat transaksi ya harus minggir. Biar tidak menuh-menuhin tempat. Kalau Depnakertrans ngotot membela pekerja model begini, itu kebangetan namanya. Karena dia sama sekali bukanlah orang yang dizalimi. Malahan, sebaliknya, dia menzalimi diri sendiri.
Ngapain repot-repot menanggapi orang model begini. Mending konsentrasi membesarkan usaha, dan melakukan pemupukan modal. Karena belakangan uang muka semakin susah didapatkan. Lagian, Sony bukanlah tipe pengusaha yang gemar mengambil kredit bank, meski beberapa orang marketing dari bank tempatnya membuka rekening berkali-kali datang ke kantornya menawarkan kredit usaha. Tapi Sony tetap kukuh dengan pendiriannya. Dia tak mau mengelola utang. Dia lebih memilih menempuh jalan tradisional, tidak boros dan tidak pula menunda-nunda membayar utang. Karenanya, pemupukan modal usaha sangat dia perhatikan. Sehingga tak perlu bingung cari pinjaman kiri kanan bila harus memodali pekerjaan-pekerjaan yang agak besar.
Fadli, adiknya, yang membesarkan pabrik pupuknya dengan kredit dari bank, bahkan pernah mengritiknya habis-habisan mengenai soal ini. “Kapan kamu jadi besar kalau tidak mau bersinergi dengan bank dan lembaga pendanaan,” katanya suatu kali.
Sony tak menanggapinya. Diam saja.
Demikian pula soal kartu kredit. Sony cuma punya satu, Visa Platinum. Selebihnya hanya dua keping kartu ATM. Mau dikata tidak modern, kuno, biar saja. Hal yang sama juga dia coba terapkan kepada para karyawannya. Dia berpesan kepada Anita jangan sampai sembarangan memberikan surat keterangan penghasilan atau rekomendasi lainnya kepada karyawan untuk kepentingan pembuatan kartu kredit. Dia tak ingin mereka terperangkap dalam jebakan kartu kredit, yang dengan mudah akan menjerumuskan orang ke dalam tabiat buruk lebih besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal tetap sohor. Hal yang seperti ini akan menjadikan hidup mereka tidak normal, karena dikejar-kejar utang. Gali lobang tutup lobang. Bikin kartu kredit baru untuk melunasi sebagian utang kartu kredit lama. Begitu seterusnya. Akhirnya, pekerjaan jadi ikut-ikutan kedodoran. Say no to credit cards? Ndak perlulah. Biar saja.
Namun, sudah waktunya pemerintah, YLKI, Bank Indonesia, atau siapapun dan juga lembaga apapun yang berkepentingan, mulai turun tangan. Memang tidak mungkin melarang orang memiliki kartu kredit, seperti halnya mustahil melarang orang merokok. Ini hak asasi. Toh, banyak juga orang yang mendapatkan manfaat positif dari kartu kredit karena cukup bijak, hati-hati dan bisa menahan diri dalam menggunakannya. Dan tidak mungkin pula bagi YLKI untuk memberikan advokasi kepada para penunggak kartu kredit yang terperangkap dalam utang berlapis-lapis. Bagaimanapun, mereka sudah menikmati berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan, hanya saja digunakan tanpa perhitungan dan benar-benar sembrono. Sebagian lagi karena pada dasarnya memang hobi ngemplang utang. Jadi, harus tanggung sendiri risiko ditongkrongi orang-orang berwajah garang.
Namun, perangkap kartu kredit yang menjebak sekian juta orang yang tidak siap itu sesungguhnya tak kalah merusak dibandingkan dengan berbagai kebiasaan buruk lain yang meracuni masyarakat, seperti merokok atau menenggak minuman beralkohol, misalnya. Bila pada kemasan rokok saja dicantumkan peringatan pemerintah – diadopsi dari aturan yang berlaku di seluruh dunia – yang berbunyi MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI, DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN, maka pada setiap keping kartu kredit mestinya juga bisa dituliskan peringatan sejenis, misalnya PENGGUNAAN KARTU KREDIT SECARA TIDAK BIJAKSANA DAPAT MENYEBABKAN PERILAKU LEBIH BESAR PASAK DARIPADA TIANG.
Di samping itu, persyaratan aplikasi dan persetujuan pemberian kartu kredit perlu lebih diperketat lagi dengan survai yang tidak asal-asalan. Upaya perlindungan seperti ini akan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak, nasabah dan bank penerbit kartu kredit. Masyarakat senantiasa diingatkan agar lebih bijaksana dan dapat menahan diri dalam penggunaan kartu kredit, agar tidak terjebak dalam pusaran utang. Sedangkan bank penerbit kartu kredit bisa menghimpun nasabah yang benar-benar memenuhi syarat sehingga jumlah tagihan bermasalah bisa ditekan. Tak perlu menyuburkan profesi tukang tagih.
Begitu gampangnya aplikasi kartu kredit diluluskan sehingga office boy pun bisa memiliki kartu kredit. Sony, yang memiliki kartu kredit Visa, tiba-tiba saja dikirimi kartu kredit Master oleh bank penerbitnya. Setelah dia telepon ke bank, jawabannya sederhana saja. “Kalau Bapak mau pakai, tinggal dilakukan aktivasi. Bila Bapak tidak berkenan, gunting saja kartu itu.” Seandainya kesempatan tersebut jatuh ke tangan orang yang pada dasarnya doyan berutang, pasti langsung diembat penawaran yang menggiurkan seperti itu.
Namun kartu kredit tidak selamanya buruk. Ada juga kolega Sony yang memulai usaha dengan bermodalkan sejumlah kartu kredit dan kredit tanpa agunan atau pinjaman personal. Memang agak berisiko. Gali lobang tutup lobang harus dilakukan. Syukurlah dia berhasil. Usahanya cepat berkembang. Seandainya saja gagal, pasti langsung kiamat. Kejadian deh, libur panjang.
“Libur lagi? Minggu kemarin ada hari libur. Masa, minggu ini masih saja ada tanggal merahnya?” Sony semakin tak paham saja. Sambil bersungut-sungut dia mematikan api rokoknya. Kalau libur hari Sabtu dan Minggu, wajar sajalah. Manusia membutuhkan waktu untuk beristirahat yang cukup setelah bekerja keras. Tapi, banyak banget hari kerja yang diwarnai merah pada kalender. Belum lagi soal cuti bersama. Termasuk penggeseran hari libur yang mengapit Harpitnas di tahun-tahun sebelumnya.
Apa pemerintah kurang kerjaan? Sepertinya senang betul kalau ketemu hari libur. Bagi Sony, libur sehari saja, berarti hilang sudah kesempatan untuk cari duit, sementara biaya bulanan tak mau sedikitpun dimintai libur. Pusing. Pusing. Pusing.
Beberapa jenis industri bahkan harus kelimpungan setiap kali hari kerjanya kepotong tanggal merah. Mereka tak mungkin mematikan mesin, karena butuh waktu berhari-hari untuk proses start up. Tapi pekerja pada menghilang. Jadilah mesin dibiarkan tetap menyala tanpa menghasilkan apa-apa. Utilities terpaksa jalan terus. Rugi. Mau dikata apa.
Sony setuju belaka kalau hari-hari besar keagamaan ditetapkan sebagai hari libur. Tapi mestinya hanya untuk penganut agama yang bersangkutan. Tak perlu berlaku untuk semua. Hari Raya Nyepi, misalnya, harusnya yang mendapatkan libur hanya orang-orang yang beragama Hindu Bali, dan sah-sah saja bila semua kegiatan di Pulau Bali dihentikan. Tapi, bagi penganut agama lain yang tidak tinggal di Pulau Dewata, tentu tak perlu ikut-ikutan diliburkan. Untuk apa? Sebagian besar mereka cuma tidur-tiduran di rumah. Hanya sebagian kecil orang yang punya kelebihan uang yang bisa menikmati long week end.
Pemerintah suka mengganggap semuanya sama rata. Gebyah uyah. Kalau yang satu libur, yang lain harus ikutan libur, meski tak punya kepentingan sama sekali dengan hari yang diliburkan itu. Mungkin mereka tak mau susah-susah membuat pengaturan hari libur yang lebih rinci. Toh, pada dasarnya mereka suka hari libur, karena memang kurang kerjaan. Sementara para pekerja swasta senang-senang saja dengan kebiasaan yang sama sekali tidak menguntungkan bagi kalangan pengusaha ini. Toh, mereka tidak merasa terikat dengan target produksi, target pemasukan dan beban-beban berat yang menghimpit lainnya. Itu urusan manajemen, kata mereka. Asal gaji tak sampai telat dan THR terbayar, mereka pada senyum. Sebaliknya, pengusaha puyeng dibuatnya. Mau protes tidak bisa. Karena sudah ditetapkan di kalender. Sudah formal. Final.
Seandainya pemerintah mau memperhatikan sedikit saja kepentingan para pengusaha dalam menetapkan hari-hari libur nasional dan keagamaan. Misalnya, pada Hari Raya Imlek, hanya masyarakat keturunan Tionghwa yang berhak mendapatkan hari libur. Sedangkan mereka yang tidak ikut merayakan hari yang serba merah itu tetap bekerja seperti biasanya. Kalaupun para pemilik toko di kawasan Glodok menutup toko mereka dan meliburkan karyawannya, itu sah-sah saja. Diliburkan boleh, tidak diliburkan juga tak apa. Terserah mereka. Dengan demikian, tidak perlu dibuat tanggal merah untuk hari libur seperti itu. Bisa saja diganti dengan warna biru atau hijau. Hal yang sama juga dapat diterapkan untuk hari-hari libur keagamaan lainnya.
Lebaran atau Idul Fitri merupakan perkecualian, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Sehingga ketika sebagian besar pekerja libur, tidak lucu juga bila kantor-kantor yang karyawannya tinggal satu atau dua orang tidak ikut meliburkan mereka sekalian. Kasihan. Pada bengong sendiri nanti. Tapi tidak perlu diatur-atur soal cuti bersama. Biar para pengusaha yang menentukan sendiri. Mereka toh juga punya toleransi dan cukup tahu diri. Lagian, cuti bersama kan cuma akal-akalan untuk mengatur sebagian PNS yang suka memulur-mulurkan hari libur. Maunya mengatur satu kelompok pekerja, tapi aturannya ditetapkan untuk semua. Ini aneh sekali. Untungnya Menpan sudah membatalkan cuti bersama sebagai hari libur bagi PNS, sehingga karyawan swasta tidak perlu ikut-ikutan menuntut libur.
Sudah waktunya dilakukan pengkajian ulang soal penetapan hari libur, baik libur nasional maupun libur keagamaan. Setiap agama mendapatkan hari libur secara adil dan berlaku khusus hanya untuk penganut agama yang bersangkutan. Jangan terlalu royal dengan hari libur. Itu bukan tabiat bangsa pekerja keras.
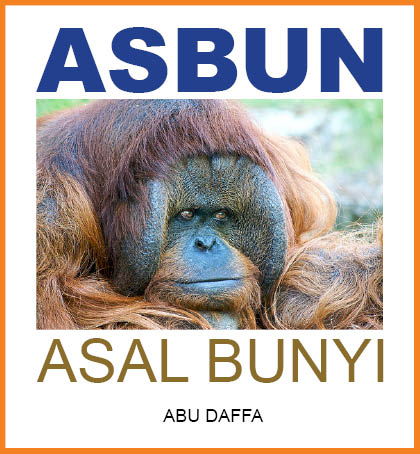
Tidak ada komentar:
Posting Komentar