Jadi orang jangan terlalu pintar. Karena semakin pintar, semakin gampang dikelabui. Lihat saja para korban Kospin, Qsar, Gold Coin, Ibist atau paguyuban tepu-tepu sejenisnya. Mereka semua orang-orang pintar dan terpelajar. Malahan ada yang bergelar doktor dan profesor segala. Sejumlah anggota parlemen juga termasuk di dalamnya. Tak terhitung lagi para pejabat negara, petinggi tentara, dan juga perwira polisi. Ibu rumah tangga, pensiunan, purnawirawan, guru, dukun dan bidan.
Mereka semua dengan sukarela, dan bahkan bergembira dengan wajah berseri merona, menyerahkan duitnya untuk diputar dengan kecepatan delapan belas ribu rpm. Dua kali lebih kecepatan putaran baling-baling helikopter. Dengan harapan mendapatkan imbal balik fulus berkoper-koper. Kenyataannya, sebagian besar uang itu lenyap ditelan pusaran. Jangan-jangan, sebenarnya mereka memang tidak pintar.
Organisasi-organisasi tipika-tipiki itu, tipu kanan tipu kiri, tak pernah sedikipun berminat untuk memperdayai orang bodoh. Di samping kurang menantang, orang bego biasanya tak punya uang. “Ndak level. Buang-buang waktu saja,” sesumbar mereka dengan nada menang, sambil memasukkan lembaran-lembaran uang ke dalam tas besar yang terus menggelembung.
Herannya, kejadian seperti ini terus berulang. Meninggalkan korban-korban yang malang. Dibiarkan terkapar makan tulang. Banyak orang meradang. Kaki serasa ingin menendang. Mulut bau para petualang. Yang bebas melenggang. Apakah mereka tak pernah mau belajar? Padahal mereka orang-orang terpelajar. Apakah mereka telah kehilangan nyala pijar? Yang tak mau lagi berpendar. Untuk mengingatkan manusia agar selalu sadar. Bahwa setiap orang harus bersabar. Dan itu pasti terbayar. Dasar! Manusia memang tamak.
Anton, karib Sony di kampung halaman sana, juga pernah jadi korban. Pohon berdaun emas meliuk-liuk seksi di hadapannya. Dengan belahan dada yang dibiarkan sedikit terbuka. Dan rok mini yang mengumbar paha. Menyapanya dengan kalimat-kalimat lembut bermantra, “Kamu tinggal siapkan pupuknya. Selebihnya serahkan sama saya. Ranting-ranting akan menjuntai. Daunnya melambai-lambai. Bisa dipanen berhelai-helai. Berkilau tanpa pernah padam. Suara gemerincing akan terdengar setiap malam.”
Bujuk rayu si empunya pohon emas itu, yang didendangkan oleh Karjo, juga teman Sony semasa SMA, sebenarnya sama sekali tak masuk akal. Bahkan sangat dangkal. Ketahuan jelas itu akal kadal. Janji-janji sundal. Tapi tetap terdengar senikmat cokelat. Keserakahan telah membungkam akal sehat.
Bapak, ibu, kakak, adik, pakde, bude, paklik, bulik, sepupu, sepaha, ipar, semua pada ditawari. Diajak bergabung. Semua kenalan dihubungi. Pak Lurah dan Pak Camat juga ikutan. Jadilah Anton yang berperawakan pendek dan kecil itu pengepul pupuk. “Boleh setor berapa saja. Nanti digabung jadi satu. Saya yang tanggung jawab. Sampeyan tinggal duduk-duduk manis. Koin emas akan menggelinding berlapis-lapis.”
Sedap benar kedengarannya. Semua orang pasti ngiler. Sekali dua kali tegukan air berkilau sempat menyegarkan dahaga mereka. Setelah itu tak ada lagi, setetes pun. Sudah kering. Ditunggu-tunggu juga tak kunjung datang kabarnya. Rasa was-was mulai menyergap. Jangan-jangan …. Jangan-jangan …, pikir Anton yang kian cemas dan gagap. Dia merasa harus segera bertindak sigap.
“Jo, bagaimana ini? Apakah pohonnya sudah layu?” Anton bertanya dengan curiga.
Namun Karjo terus berusaha menenangkannya dengan alasan sekenanya. “Matahari lagi tertutup awan tebal. Jadi klorofil tidak bekerja maksimal. Sabar. Jangan dulu gusar. Sebentar lagi awan akan pergi. Daun akan rimbun kembali.”
Namun awan gelap itu tak juga mau beranjak. Pohon itu layu bagai tonggak. Daunnya berguguran. Warnanya memudar. Yang tersisa hanyalah duri-duri tajam. Setajam silet, kata pembawa acara gosip di TV. Ribuan kepala langsung tertunduk lesu. Tatapan mata mereka sayu. Nafas Anton menderu-nderu. Tenggorokannya terasa kaku. Kepalanya seperti digetok palu. Dadanya serasa ditusuk-tusuk paku. Istrinya menangis tesedu-sedu. Keluarganya menanggung malu.
Karjo menghilang tanpa meninggalkan selembar pesan. Keluarganya masa bodoh dan terkesan lepas tangan. “Tidak tahu,” jawab mereka, tanpa berani menatap muka. Sony jadi teringat sebaris syair lagu mendayu-dayu yang dilantunkan Ratih Purwasih, “Jangankan menulis surat, menitip salam pun aku tak boleh ….”
Karjo. Karjo. Dua tahun kemudian Sony ketemu adiknya dalam acara halal bihalal sebuah partai politik di Jakarta. Maka dia tanyakan kabar kakaknya itu. “Bagaimana keadaan Karjo? Sudah lama tak terdengar kabarnya.”
Ichwan tampak kurang antusias menanggapi pertanyaan Sony. Sepertinya dia tak terlalu berminat untuk bercerita mengenai kakaknya. Maka Sony mengalihkan pembicaraan, berganti ke soal pekerjaan. Obrolan mereka semakin seru ketika nyerempet-nyerempet ke soal hantu.
“Karjo sekarang lebih banyak tinggal di rumah,” tiba-tiba Ichwan mengubah arah pembicaraan.
Maka mengalirlah cerita itu. Setelah terhempas oleh kasus koin emas, Karjo kehilangan gairah hidupnya. Setiap malam kerjanya cuma ngobrol ngalor-ngidul dengan pemuda-pemuda pengangguran di pos ronda. Subuh baru pulang. Kemudian tidur hingga tengah hari. Berubah dari makhluk diurnal menjadi nocturnal. Ngumpet di saat terang, keluyuran di kegelapan malam. Persis seperti kalong.
Saudara-saudaranya cemas. Tapi, anehnya, istri dan anak-anaknya tidak protes sama sekali. Mereka menganggap hal itu normal-normal saja. Bahkan mereka tetap menjalani hidup dengan gaya sok kaya. Kakak-kakak dan adiknya pun patungan modal bikin warung sembako, agar Karjo punya penghasilan. Ternyata tak juga jalan. Malahan, aset-aset warung habis dia jual. “Buat beli rokok,” katanya, tanpa merasa bersalah sedikitpun.
“Jengkel saya. Ini orang benar-benar susah dikasih tahu,” keluh Ichwan, seolah ingin mencurahkan semua kegalauan hatinya kepada Sony. Curhat.
Sony hanya mendengarkan keluh kesahnya, tanpa memberi komentar. Sungguh tak terbayangkan, Karjo yang pintar beradu argumentasi itu telah berubah total. Dari cerita yang disampaikan adiknya, Sony merasa tak mengenal Karjo lagi. Sudah lain. Bukan lagi Karjo yang suka bercanda dan bernyanyi, dan selalu gigih mewujudkan keinginannya.
“Son, kamu kan kawan baiknya. Tolong kasih tahu dia. Jangan keluyuran malam. Bangun pagi. Kerja apa saja. Pokoknya hidup normal. Masalah uang gampang. Keluarga bisa bantu,” imbuhnya dengan tatapan mata berharap.
“Saya akan coba,” Sony mengiyakan.
“Sementara ini,” kata Ichwan menutup pembicaraan, “memang tak ada jalan lain. Secara bergantian keluarga memberikan subsidi untuk biaya hidup Karjo dan keluarganya.”
Maka, siang itu Sony menelpon Karjo. Namun dia harus menelan kecewa. Tadinya dia berharap bisa mengobrol seperti teman lama. Sony jadi keki. Omongan Karjo selalu tinggi-tinggi. Nyerocos tanpa henti. Sangat jauh dari kenyataan hidupnya sehari-hari. Makanya, sengaja dia biarkan Karjo ngomong apa saja dalam percakapan satu arah itu. “Udahan ya Jo, pulsaku habis.”
Ketika besoknya mau menelepon Karjo lagi, Sony malah ragu-ragu. Tanpa sadar ibujarinya justru memencet nomor HP Anton. “Hey, Ton, aku sudah ketemu Karjo. Ada salam untukmu. Dia bilang sekantong koin emas sudah dikuburkan di halaman belakang rumahmu. Malam Jum’at coba kamu congkel pakai kayu. Pasti ketemu.”
Anton hanya cengengesan mendengar ledekan Sony. “Ya, Son. Saya coba malam Jum’at nanti. Tolong bantu doa. Salam buat Karjo.”
Tapi Sony penasaran, mengapa Karjo suka tidur sampai tengah hari. Jadi bangsawan. Bangsane tangi awan. Tanpa sengaja dia menemukan jawabannya pada waktu melakukan hal serupa di hari libur. Mimpinya bagus-bagus. Gila. Dia terbuai mimpi cinta pertamanya, dan Bethany juga datang menghampirinya. Kali lain, dia mimpi jadi milyuner, orang terkenal, bisa terbang, bisa ngilang, dan yang asyik-asyik lainnya. Day dream. Bikin ketagihan. Don’t try this at home.
Rupanya, ketika hari terang, di mana dunia sedang berada pada puncak aktivitasnya, demikian pula lingkungan sekitar, rangsangan-rangsangan dari luar berseliweran memicu aktivitas otak orang yang sedang tidur. Makanya, orang suka dibilang mimpi di siang bolong apabila ngomongnya muluk-muluk dan berkhayal yang bukan-bukan. Ya, benar. Mimpi di siang bolong.
“Siang, Bos. Lagi banyak kerjaan kayaknya.”
Sony agak pangling dengan penampilan tamu yang datang pada saat dia sedang bersiap makan siang di kantornya, di Mampang. Berdasi dan pakai jas segala. Rambutnya yang agak panjang diikat rapi membentuk ekor kuda buntung. Tubuhnya yang tak seberapa kekar menebar wangi jantan yang khas. Sepertinya dia kenal parfum itu. Ya, Hugo Boss. Sungguh lain dari biasanya.
“Hey, Drus, keren sekali kamu hari ini. Kerja di mana sekarang? Banyak uang, ya? Bagi-bagi, dong. Oh, ya, sudah makan? Kita makan bareng, yuk.”
Sony segera memanggil Usep, office boy kepercayaannya itu. “Sep, tolong belikan soto sulungnya satu lagi. Ada tamu penting. Kamu masih ingat kan, sama Pak Idrus? Sekalian, tambah krupuk udangnya.”
Usep hanya mengangguk. Dan langsung pergi.
Idrus adalah kawan lama. Pekerja freelance ketika Sony baru memulai usaha kembali setelah perusahaannya terjengkang dihempas krisis ekonomi. Idrus. Kreativitasnya memang luar biasa. Banyak klien yang suka dan puas dengan hasil kerjanya. Dulu, ketika Sony menawarkan kepadanya untuk bergabung saja, Idrus langsung menolak mentah-mentah.
“Mas, saya nggak mau merepotkan. Sampeyan kan sudah tahu. Bagaimana bila tiba-tiba saya ngilang enam bulan untuk bertapa? Mendinginkan bara di dada. Ngunduh ilmu sambil cari pusaka.”
Kecenderungan supranatural orang Purwokerto itu memang tampak jelas dari caranya berpakaian dan bahan obrolannya. Bahkan Sony pernah mendengar Idrus membeli seekor burung perkutut sakti seharga dua puluh juta. Tak disangka-sangka, besoknya burung itu mati begitu saja. Jagat klenik pula yang membawanya masuk ke dalam lingkaran pergaulan yang sangat luas. Idrus punya banyak kawan. Mulai dari kalangan selebriti hingga petinggi tentara.
“Saya jadi salesman sekarang,” katanya, tanpa menatap mata Sony. Lelaki berjenggot dan berkumis itu sedang sibuk berjoget lidah dengan semangkuk soto. Sendok di tangan kanan, krupuk di tangan kiri. Garpu dia biarkan merana di meja. Tanpa pernah disentuhnya. Idrus menyeruput kuah soto yang panas itu dengan lahapnya. Keringat mulai menitik di keningnya. Garis bibirnya agak bergetar memerah.
Dari caranya mengunyah, Sony tahu kawan lamanya itu sangat menikmati makanan kegemarannya. “Jualan apa, Drus?” tanya Sony, sambil menyelesaikan satu gigitan lagi krupuk udang yang renyah.
“Begini. Saya disuruh Jenderal Kancil menukarkan uangnya. Dari rupiah ke dolar Amerika. Dia mau terima dolar minimal satu juta. Harganya dua puluh persen lebih murah.”
Kemudian dia bercerita mengenai kenalannya. Sesama pemburu pusaka. Seorang tentara yang kaya raya. Uang berjibun disimpan di rumahnya. Hingga dua kamar banyaknya. Dalam tumpukan-tumpukan kardus yang tertata. Semuanya pecahan lima puluh ribu rupiah. Dia takut bank bertanya. Dari mana duit itu asalnya.
“Kenapa tidak pergi ke money changer saja?” tanya Sony asal bunyi. Sebab, bila Idrus mau menawarkan uang segede itu kepadanya, jelas dia tak punya.
“Ya tidak mungkin kita jual ke pedagang valuta. Terlalu besar jumlahnya. Mereka akan curiga. Kita bisa celaka. Makanya saya datang ke sini. Kalau ada kawan yang mau, tolong saya dikasih rekomendasi.”
Rupanya sudah hampir empat bulan dia pergi kesana-kemari. Tapi belum ada satu pun yang tergenggam jemari. Kemudian dia bercerita lagi bahwa duit seabrek itu dijaga oleh empat orang tentara. Tapi si empunya masih was-was hatinya. Sehingga harus ditambahkan sepeleton jin untuk mengawalnya. Sudrun nama komandannya.
Setelah ngobrol ngalor-ngidul, tiba-tiba Idrus melontarkan sebuah ajakan maut yang tak pernah sedikit pun terlintas dalam benak Sony. “Mas, bagaimana kalau sebagian uang itu kita colong saja. Hasilnya kita bagi dua. Saya pernah bicara sama Sudrun. Dia bilang mau bantu.”
Edan. Beginilah cara berpikir orang yang sudah putus asa. Atau, memang sudah sifat manusia untuk menjadi serakah. Dengan menghalalkan segala cara. Asalkan tercapai tujuannya. Tapi, aneh bin ajaib, Sony terpancing oleh ajakannya. “Bagaimana caranya, Drus?” tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu.
Idrus pun membeberkan rencananya. “Kita pakai kantor ini. Di sini. Ya, di sini. Di ruangan ini,” katanya, seraya memperhatikan dengan seksama setiap jengkal ruang kerja Sony. Dia tampak tersenyum setelah melihat ada jendela kaca yang dapat dibuka-tutup.
Tapi Sony masih belum mengerti maksudnya. Kalau mau nyolong, kan harus pergi ke rumah Jenderal Kancil. Pakai kostum hitam dan menyelinap di malam hari. Mengendap-endap membongkar kunci. “Maksudnya bagaimana, Drus?” tanya Sony dengan tak sabar.
“Begini, malam Jum’at nanti, tengah malam, kita di sini. Tinggal menunggu saja. Sudrun dan anak buahnya akan membawa uang itu ke sini. Yang penting jendela dibuka. Maka uang akan melayang-layang dan masuk. Bertumpuk-tumpuk. Besok saya temui Sudrun, untuk membicarakan rencana ini.”
Tak berapa lama kemudian Idrus pamit pulang. Sony menyuruh Tukijan mengantarnya. Ini tamu yang sangat penting. VVIP. Harus diservis habis-habisan.
Sony benar-benar termakan oleh rencana jahat itu. Khayalannya langsung melayang-layang. Paling tidak bisa beli Jaguar barang sebiji. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana mungkin hasilnya dibagi dua? Kan ada pihak ketiga? Sudrun dan konco-konco-nya. Emangnya dia mau kerja gratisan. Mana mungkin? Bagaimana kalau dia minta imbalan nyawa?
Sony jadi ketakutan sendiri memikirkannya. Gamang hatinya. Tapi ini urusan duit besar. Sayang kalau dilepas begitu saja. Lama sekali dia terpekur memikirkan jalan keluar yang paling mungkin dan aman, sampai akhirnya dia temukan solusi yang tokcer. Bila Sudrun benar-benar minta imbalan nyawa, itu tak masalah. Asal jangan nyawanya. Ambil saja salah satu nyawa dari kantor sebelah. Karena mereka suka menyerobot tempat parkirnya. Beres sudah.
Kamis sore, langit temaram. Pukul setengah enam. Semua karyawan sudah pada menghilang. Tukijan sudah duluan dia suruh pulang. “Ada pekerjaan penting yang harus saya selesaikan malam ini,” kata Sony kepada Usep, yang tampak agak bingung.
Office boy itu dia tahan hingga pukul delapan. Sony menghabiskan waktu dengan main games di laptop. Menunggu Idrus datang berselop. Tapi, hingga pukul sepuluh, pintu belum juga ada yang mengetuk. Sementara Sony mulai diserang rasa kantuk. Sambil menguap dia menengok jam di dinding. Jarum-jarumnya runcing menuding. Bulu kuduknya terasa agak merinding.
“Drus …. Idrus …. Di mana kamu? Ini sudah jam dua belas malam. Aku takut Sudrun keburu bertandang.”
Tak ada yang menjawab. Senyap. Dan tidak pula ada yang datang. Panggilan telepon tak berjawab. SMS tak bertanggap. Sony pun merebahkan diri di sofa. Langsung pulas.
Keesokan paginya Sony buru-buru menghubungi Idrus. Tapi HP-nya mati terus. Dia berusaha tanpa putus. Hingga panggilan keseratus. Tak juga tembus. Gagal sudah rencana dapat fulus. Kini saatnya pergi ke kakus. Membuang isi usus. Ampas nasi bungkus. Sambil nongkrong, pikirannya berputar-putar dalam beberapa jurus.
Jangan-jangan Idrus telah dikhianati oleh Sudrun. Bisa jadi jin plin-plan itu melapor kepada majikannya mengenai rencana konspirasi kelas kakap. Sehingga Idrus langsung ditangkap. Pergelangan tangannya digari. Sementara di keningnya sepucuk pestol menari-nari. Pelatuknya tinggal menunggu ditekan dengan jari.
Sudah. Sudah. Sony membuang jauh-jauh pikiran buruk itu. Tak mau lagi dia berhubungan dengan Idrus. Bikin perut murus. Otak kobong. Tolooong … tolooong … tolooong ….
“Mas, tolong Candra. Saya tak tahu harus bagaimana. Barang-barang di rumah sudah ludes semua. Dijual paksa. Sebagian lagi disita. Keluarga sudah pasrah. Nyerah.”
Perempuan tua itu terisak di kantor Sony. Suaranya terbata-bata. Tersendat-sendat mengalirkan kata. Berkali-kali dia menyeka matanya yang berkaca-kaca. Dengan sapu tangan yang terbuat dari kain perca. Di lehernya menggantung kacamata baca.
Candra, putra kebanggaannya itu, keranjingan berburu harta karun. Ke mana-mana yang dicari selalu dukun. Kalau diajak bicara lagaknya seperti orang pilun. Menyeringai sambil mengelus jakun. Meski kadang-kadang memasang muka tekun. Lehernya bergoyang-goyang seperti ayam kalkun.
Candra sahabat Sony semasa kuliah. Pernah bersama-sama dalam senang dan susah. Rasanya sudah lama dia tak bersua dengannya. Semenjak Candra melanjutkan studinya ke Australia. Memang, setahun sebelumnya Candra pernah datang ke kantornya. Sekali saja. Hanya sempat bertukar beberapa kata. Tampaknya dia sedang tergesa-gesa. Saat pamit pulang dia mengutarakan niatnya. Mau pinjam fulus seratus juta. Dengan jaminan selembar sertifikat tanah. Ditambah sebaris sumpah. Katanya sedang urus bisnis permata. Batu merah delima.
Sony tak bisa memenuhi permintaannya. “Sorry, Ndra. Aku nggak bisa kasih, karena uang saya harus terus diputar. Tapi, kalau kamu ada kesulitan, aku bisa bantu,” katanya sambil memberikan amplop berisi uang dua juta.
Candra. Candra. Candra. Dulu Sony mengenalnya sebagai mahasiswa yang pintar. Gemar memetik gitar. Memelihara seekor ular. Meski omongannya kadang berputar-putar. Tapi tak pernah kehilangan kelakar. Senyumnya lebar. Raut mukanya selalu bersinar. Dahinya bundar. Dengan aura terang yang senantiasa memancar. Tutur katanya halus dan mengalir lancar. Setahun sekali dia ganti pacar. Cewek-cewek yang naksir pada ngantri berjajar. Dengan hati yang bergetar. Sony iri kepadanya.
Tapi kini Candra telah banyak berubah. Garis wajahnya kaku seperti muka kuda. Bajunya dekil berwarna ungu muda. Jaketnya tengil berlubang di dada. Dalam usianya sudah tak lagi muda, dia hidup melajang tak berkeluarga. Sehari-hari numpang di rumah orangtuanya. Sony pernah mendengar Candra sudah menduda.
Candra menerlantarkan bisnisnya dengan sumpah serapah. Akibat rencana yang mentah. Rugi segede gajah. Merasa masa depannya patah-patah. Dia beralih mengejar harta dari antah berantah. Dengan pancingan sepotong emas dan asap dupa. Berharap akan berjatuhan latakan-latakan kuning menyala. Dari langit yang tak berwarna. Di tengah orang-orang yang duduk bersila. Wajah-wajah serius mengadu asa. Siapa tahu keberuntungan segera tiba. Dan impian jadi nyata. Dengan merapalkan mantra. Tanpa pernah tahu apa maknanya.
Mulut mbah dukun komat-kamit. Mengunyah kunyit. Tangannya mengayun-ayunkan sendal jepit. Mencoba memanggil demit. Ditunggu hingga bermenit-menit. Belum juga muncul pertanda barang sekelumit.
“Ada yang belum ikhlas hatinya,” kilah Mbah Cokro yang alis matanya putih menjuntai itu.
Lempengan emas seberat seratus gram, yang dibeli secara patungan oleh Candra bersama ketiga orang temannya, lenyap begitu saja. Sedikit pun tak bersisa. Ini bukan tipuan mata. Tapi sesuatu yang nyata. Padahal tadi jelas-jelas ditanam di hadapan mereka. Oleh dua orang asisten dukun celaka. Yang bekerja tanpa berkata-kata.
Candra tak percaya dengan penglihatannya. Tangannya langsung meraba-raba. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Setelah mengorek-ngorek tanah agak dalam lagi, dia temukan sepotong kayu kecil berwana cokelat muda. Ukurannya persis sama. Bentuknya serupa. Dengan latakan emas yang telah sirna. Hanya berbeda warna. Dan, tentu saja, lain jenisnya.
“Minggu depan kita ulangi. Maharnya lebih tinggi. Dua ratus gram,” kata mbah dukun yang berwajah garang itu.
Anehnya, mereka menurut saja. Berkali-kali nyaris belaka. Dan maharnya semakin besar pula.
Seorang mantan pejabat pernah jadi korban. Rayuan gombal menggiringnya masuk ke dalam sebuah jebakan. Meski tak terlalu akrab, Sony cukup lama mengenalnya. Malang benar nasibnya. Pria terhormat bergelar doktor itu harus kehilangan fulus. Sebanyak lima kardus. Dalam jutaan, nilainya mencapai tujuh ratus. Hangus.
Petaka bermula dari hasrat yang membabi buta. Mengejar harta durjana dengan cara-cara yang nista. Modalnya memang sangat besar. Tapi dia haqul yakin duitnya bakal mekar. Sudah disiapkan dua truk kekar. Diparkir di sela-sela belukar. Kendaraan raksasa beroda sepuluh itu akan pulang dengan berkardus-kardus uang. Setiap truk diberi tanda silang. Supirnya dikawal oleh dua orang pawang. Masing-masing bersenjatakan pestol dan kelewang. Juga cabe rawit dan bawang. Ditusuk-tusuk melintang. Untuk menangkal tuyul jail dalam perjalanan pulang.
Di tengah hutan mereka berhimpun. Tanpa nyanyian-nyanyian gembira ataupun api unggun. Tak seperti Pramuka yang ramai-ramai berkemah sekali dalam setahun. Sebaliknya, hanya wajah-wajah yang tekun. Dengan duduk bersila mereka melakukan ritual dipimpin mbah dukun. Mengelilingi kardus-kardus berisi uang yang telah disusun. Tertutup rapi di bawah tumpukan daun. Rapalan-rapalan mantra segera mengalun. Tubuh sang dukun terayun-ayun.
Secara perlahan muncul kabut pekat. Sementara bau dupa kian menyengat. Lingkaran manusia itu mulai merapat. Membentuk segi empat. Mantra-mantra dilafalkan dengan penuh semangat. Dalam hentakan nada cepat. Untuk mengundang arwah jahat. Yang datang tanpa pakai cawat. Maka setan-setan besepakat. Membawa mereka ke jalan sesat.
Psssttt …. Terdengar bunyi mendesis dari dalam tumpukan daun. Tangan mbah dukun langsung berhenti mengayun. Kepala diangkat, mata menatap langit. Keningnya sedikit berkernyit. Ini dia. Mantra itu sudah bekerja. Angan-angan sudah di depan mata. Kardus-kardus itu pasti akan segera menggunung seperti tumpukan batu bata.
Namun, segaris api yang berkilat tiba-tiba menyambar. Anak-anaknya yang menyengat berlarian berkobar-berkobar. Tanpa banyak koar-koar. Langsung berbuat makar. Kardus-kardus berisi uang itu habis terbakar. Keenam kaki-tangan mbah dukun saling melirik dengan lobang hidung yang mekar. Karena sesungguhnya kardus-kardus itu telah mereka tukar. Di dalamnya ditaruh potongan koran berlembar-lembar. Ditetesi sedikit minyak ketumbar. Penanda yang baunya samar. Agar tak salah kamar. Pasti mereka dapat persenan besar.
Dukun Sumo yang perutnya buncit itu berjalan menghampiri Pak Doktor. Tatapan matanya begitu kotor. Dengan nada tinggi dia menghardik pria baya yang sedang kebingungan tersebut, “Sampeyan tidak ikhlas. Akibatnya, mahar amblas.” Sambil membuang muka, tangannya mengibas-ngibas. Bergerak-gerak seperti kipas. Mengusir hawa panas. Diteguknya air putih segelas.
Ini orang benar-benar raja tega. Tabiat celaka. Sony menduga mbah dukun pernah bergabung dalam sebuah teater. Terlihat benar dia piawai memainkan karakter. Sekalipun harus berperan sebagai dokter.
Kasihan Pak Doktor yang badannya pendek gemuk seperti Semar. Dia terduduk lesu dengan hati memar. Perasaannya hambar. Matanya nanar. Otaknya serasa terbakar. Sudah kehilangan uang, dicaci maki pula.
Sony jadi bertanya-tanya, benarkah jin bisa kasih manusia harta berlimpah? Banyak orang yang percaya begitu. Seperti Pak Doktor itu. Sony sendiri tak tahu. “Seandainya saja ketemu jin, akan aku tanyakan masalah itu. Tapi hingga hari ini, belum pernah ketemu. Tak tahu jin itu rupanya kayak apa, baunya seperti apa, kesaktiannya setinggi apa,” kata Sony kepada Heru, yang terlihat bosan karena diajak ngobrol terus sedari siang. Sampai lupa makan.
“Kalau Bapak ingin lihat jin, ada orang yang bisa bantu.” Sony teringat perkataan Pak RT dua bulan lalu. Ketika mereka sedang kerja bakti di hari Minggu. “Biayanya tiga juta. Tidak pakai syarat puasa,” dia menambahkan sambil menyebutkan nama seorang kyai yang tinggal di Jakarta Timur.
Kalau harus pakai biaya, Sony pasti ogah. Sebaliknya, dia akan minta uang sama jin. Akan ditolaknya bila hanya dikasih nomor togel. Terlalu banyak ketidakpastian. Harus diramesi dulu. Dan itu pun belum tentu tepat. Karena jin menyebutkan angka-angka dalam bahasanya sendiri. Sementara orang harus menafsirkannya ke dalam bahasa manusia.
“Met, memangnya ada orang yang pernah dikasih duit sama jin?” tanya Sony kepada Slamet, kakaknya yang dukun itu, ketika dia sedang berkunjung ke rumahnya, mengantarkan mangga hasil panen di kampung halaman sana.
“Ada. Di Bogor. Diberi dua karung.”
Sony jadi bertanya-tanya. Duit kok ukurannya karung, bukan juta atau milyar. Dan lagi, tidak dirinci apakah karungnya besar atau kecil. Bekas atau baru. Kalau isinya pecahan logam seratus rupiah semua, atau duit seribuan, sama juga bo’ong. Berapa nilainya?
“Bagaimana caranya agar jin mau kasih saya duit?” Sony mulai melemparkan pancingan iseng.
Anehnya, kali ini Slamet tidak langsung menyambar umpan yang renyah itu. Sebaliknya, dia menatap mata Sony dalam-dalam. Dari matanya mengalir seutas cahaya tipis berwarna biru yang menembus syaraf-syaraf penglihatan Sony, mengalir ke otaknya dengan berkelok-kelok dan kemudian turun menyusuri ruas-ruas tulang belakang, berhenti dan mentok di tulang ekor. Bokongnya terasa sedikit panas. Sony jadi tidak mengerti, kok begini jadinya. Agak rikuh juga dia.
“Kalau kamu, ndak mungkin dikasih. Lha wong kamu serakah,” jawabnya dengan seenaknya sambil menyeruput kopi panas yang baru saja dihidangkan Febriana.
Sialan, dibilang serakah. Terus terang saja, Sony benar-benar tersinggung dikatain serakah. Dia sama sekali bukan orang yang serakah. Cuma mata duitan.
Bukannya mbelain, Fadli yang duduk di sampingnya malah ikut-ikutan memojokkannya. “Bisa saja kamu dikasih duit banyak, tapi uang jin. Mau dipakai beli apa? Belanja di mana? Paling-paling harus pergi dulu ke pasar jin.”
Benar juga apa yang dia bilang. Money changer pasti menolak duit jin. Demikian pula bank. Di samping tidak tahu harus ditukar pada nilai kurs berapa, pasti mereka juga kebingungan harus dijual ke mana lagi uang jin itu.
Tapi, tunggu sebentar. Bagaimana, ya, kira-kira bentuk uang jin? Apakah sama dengan duit manusia? Bisa jadi wujudnya bermacam-macam. Segitiga, jajaran genjang, lingkaran, pita atau bulatan-bulatan kecil seperti permen karet yang berwarna-warni. Kalau memang demikian, berarti manusia selama ini kurang kreatif, karena hanya mengenal alat tukar dalam bentuk koin dan kertas yang dipotong-potong persegi panjang.
“Potong yang benar! Ukurannya harus sama persis. Kalau perlu saya bayar lebih.” Candra memaki pegawai toko kertas itu. Dia merasa tidak dihargai dan dilecehkan. Pemuda yang rambutnya panjang dikelabang tersebut senyam-senyum melulu. Rekan kerja di sebelahnya, yang membantunya menata dalam tumpukan-tumpukan rapi potongan-potongan kecil kertas itu, juga demikian. Mereka saling lempar kedipan. Dengan seulas senyuman kecil yang tertahan.
Candra membeli kertas HVS 80 gram ukuran plano besar sebanyak tiga rim. Dipotong-potong seukuran duit seratus ribu. Selembar uang merah dijadikan mal untuk ditiru. Diukur secara teliti. Tak boleh meleset barang semili, apalagi sesenti. Dia periksa ulang setiap sisi. Semuanya harus presisi. Kemudian dia bawa pergi ketiga bungkusan besar itu dengan taksi.
Bahan baku sudah siap, pikirnya. Sekarang harus cari kongsi untuk patungan beli minyak Jafaron. Ini bukan minyak sembarangan. Didatangkan langsung dari Arab. Konon, parfum ini sangat disukai bangsa jin dari kalangan atas, baik generasi tua maupun remaja. Parfum pilihan. Sekelas Channel di dunia manusia. Satu tetes harganya empat juta. Dibutuhkan satu ampul kecil agar jin sakti mau datang untuk menyulap potongan-potongan kertas itu menjadi lembaran-lembaran rupiah.
Candra mencoba menghubungi teman-temannya sesama pemburu harta. Sebagian tinggal di luar kota. Namun banyak juga yang berumah di Jakarta. Sungguh sial. Tak seorang pun memberi sinyal. Mereka semua pada tiarap. Kehabisan cakap. Karena baru dikerjain habis-habisan oleh seorang dukun keparat dari Cilacap.
Candra kebingungan. Duit yang ada di tangannya hanya lima belas juta. Bahkan sudah berkurang lima puluh ribu. Dipakai beli rokok dan makan siang. Ditimang-timangnya segepok uang lusuh yang berikat karet gelang berwarna kuning mentah. Hasil penjualan motor kesayangan adiknya dan semua perhiasan ibunya.
Sepuluh juta sudah dialokasikan untuk jasa mbah dukun. Angka itu sama sekali tak bisa ditawar. Sedangkan yang satu juta untuk biaya transport dan kelengkapan ritual. Berarti hanya bisa beli satu tetes. Padahal satu ampul harusnya berisi dua puluh empat tetes. Masih jauh. Tapi Candra tak kehilangan akal. Beli satu tetes saja. Nanti dicampur alkohol. Jin yang kurang teliti pasti tidak tahu. Beginilah, cara berpikir orang yang biasa beli parfum tembakan.
Candra segera berangkat ke rumah gurunya, Mbah Bardam, di Sukabumi. Sang dukun ternyata tak tahu kalau minyak Jafaron itu oplosan. Berarti aman, pikirnya. Tinggal syarat-syarat tambahan. Kembang tujuh rupa. Air dari tujuh sumur yang berbeda. Tujuh butir merica. Seekor ayam jantan putih mulus. Dan terakhir, sepotong celana dalam gadis perawan, harus sudah dipakai tapi belum dicuci. Lebih afdol lagi kalau ada sedikit bekas pipis.
Sudah siap semua sekarang. Kertas bahan baku bersama kelengkapan lainnya kemudian dibungkus dengan tiga lapis kain kafan. Kecuali ayam jago, yang dipotong dan digoreng dengan bumbu kuning. Bagian dada dan brutu disantap Mbah Bardam. Paha dan sayap sudah diembat duluan sama istrinya di dapur. Leher hingga kerongkongan khusus dipersembahkan untuk Timung, kucing belang kesayangan sang dukun. Candra cuma kebagian ceker.
Tak apalah, pikirnya. Sesekali ngalah sama kucing. Lihat saja nanti. Kalau duitnya sudah jadi, akan dia belikan kucing malas itu seratus ekor ayam potong. Biar overweight, dan kolesterolnya naik. Stroke, kemudian mati. We lha, balas dendam kok sama kucing.
“Dung dung pret, ada kodok disangka kampret.”
Setelah tuntas dijampi-jampi selama tiga hari tiga malam di sebuah kamar yang gelap dan pengap, bungkusan itu harus diperam dulu selama tiga minggu. Tak boleh dikutak-katik. Apalagi diintip. Biar cepat matang. Pasukan jin akan melukis kertas-kertas itu menjadi uang.
“Tanggal lima belas kamu datang lagi ke sini. Bawa pengawal. Biar pulangnya aman,” ujar Mbah Bardam sambil mengulurkan bungkusan kecil yang terbuat dari kain kasar berwarna hitam kepada Candra. “Ini jengger ayam jago. Simpan baik-baik. Warnanya harus tetap merah. Jangan lupa, setiap tengah malam kamu bacakan mantranya. Seribu kali banyaknya. Sudah hapal belum?” sekali lagi dukun sakti itu mengingatkannya.
“Ya, Mbah, sudah tahu. Dung dung pret, ada kodok disangka kampret. Gitu, kan?”
Mbah Bardam menangguk sambil tersenyum.
Maka, pada hari yang telah ditentukan, Candra sudah siap menjadi orang kaya. Dia pinjam baju dan sepatu adiknya. Agak kekecilan memang. Tapi terlihat lebih seksi. Mobil angkot sengaja disewa dari tetangga sebelah. Dua orang preman menemani. Yang satu berbadan ceking dan wajahnya penuh dengan jerawat besar-besar, sedangkan yang satunya lagi gendut luar biasa. Persis seperti angka sepuluh bila mereka berjalan bersama.
Sobar, si gendut itu, badannya penuh lukisan. Di dadanya tergambar tato besar sendok dan garpu menyilang di atas sebuah mangkuk. Sebagai penanda bahwa dia seorang jagoan. Jago makan. Memang, Sobar sohib kental Benu Buloe si jurumakan. Mereka berkenalan di rumah sakit MMC ketika sama-sama hendak melakukan operasi tambah lambung. Sobar baru pertama kali, sedangkan si Benu kedua kali. Jadi, lambung Benu Buloe sekarang ada tiga. “Biar tambah kuat makan,” katanya.
“Maaf ya, tidak ada makanan. Istri saya lagi pulang ke rumah bapaknya,” kata Mbah Bardam seraya mengajak tamunya masuk ke dalam rumah.
Candra sama sekali tak terpikir soal makan. “Bagaimana, Mbah, sudah bisa dibuka?” Pertanyaan itu terlontar begitu saja bahkan sebelum dia dipersilahkan duduk oleh si empunya rumah. Kelihatan sekali, Candra sudah tak sabaran.
“Kalau begitu, mari kita buka sama-sama.”
Mereka pun berjalan beriring menuju kamar di mana bungkusan itu disimpan. Lampu segera menyala dan tali pengikat dibuka. Weesssss …. Candra melonjak kegirangan melihat duit merah bertumpuk-tumpuk. Kesampaian sudah impiannya. Pikirannya langsung melayang-layang. Mau beli ini beli itu. Pokoknya bela-beli.
“Ini bonusnya, Mbah,” katanya sambil memberikan tiga gepok uang kepada mbah dukun. “Tapi Mbah Bardam jangan kawin lagi, ya,” tambahnya sambil bercanda. Bahkan, si Timung, kucing belang kesayangan mbah dukun, yang saat itu anguk-anguk di depan pintu, dia kasih dua lembar.
“Baaaaarrr …. Duuuuulll …, sini …. Bantu saya angkat ini.”
Bungkusan yang cukup berat itu pun mereka gotong bertiga dan dimasukkan ke dalam mobil.
“Sudah beres? Aman?”
Sekali lagi Candra memastikan semuanya aman dan terkendali. Dengan teropong besar bermotif loreng bikinan Cina dia mengawasi lingkungan sekitar. Sambil berputar-putar, dia perhatikan dengan seksama setiap rimbun pepohonan. Siapa tahu, ada orang jahat yang sedang mengintai dari balik dedaunan. Dia tak ingin kecolongan kali ini. Karena duit itu sudah benar-benar menjelma.
“Ini jatah kalian.”
Masing-masing preman mendapat segepok uang. Gembira benar mereka. Belum pernah pegang fulus sebanyak itu. Saking gembiranya, Sobar melemparkan duit itu ke atas sehingga beterbangan dan jatuh berceceran di tanah. Hujan uang. Kayak di filem-filem.
“Lha, Bos, uang apaan ini? Masa gambarnya hanya sebelah?”
Dengan berjongkok, Sobar terus membolak-balik uang yang berserakan di tanah. Sementara Adul langsung memeriksa uang yang ada di tangannya. Sialan. Sama saja. Maka dicampakkannya uang merah bermuka satu itu ke tanah. Makin luas saja hamparan karpet dengan kombinasi warna merah putih di tanah yang berdebu itu. Sebagian malah terbang terbawa angin.
Candra tertegun. Berdegup keras jantungnya. Ubun-ubunnya terasa mendidih. Nafasnya tersengal. Matanya gatal. Benar. Duit itu bergambar satu muka. Balikannya kosong melompong. Putih bersih. Tidak ada gambar apapun. Candra langsung melompat ke dalam mobil dan buru-buru membuka bungkusan kain kafan. Dia bongkar tumpukan duit itu. Cilaka. Semuanya cuma bergambar satu muka. Lututnya terasa lemas. Dadanya panas. Susah bernafas. Impiannya kandas.
Mendengar keributan itu, mbah dukun tergopoh-gopoh mendatangi mereka. Dia ikut-ikutan memeriksa tumpukan uang tersebut. Dibolak-balik. Dikibas-kibaskan. Dibacakan mantra. Tetap saja tak berubah. Semuanya satu muka.
“Kalau dipakai beli sepatu dapat sebelah.” Adul yang sedari tadi membisu tiba-tiba nyeletuk.
Mbah dukun langsung berlari ke dalam rumah. Tiga gepok uang yang diterimanya tadi ternyata juga sama. Segera dia balik lagi ke mobil. Dia periksa sekali lagi tumpukan uang setengah jadi itu. Dibantu Sobar dan Adul, dia turunkan bungkusan tersebut. Diletakkan di tanah. Dia teliti sisa-sisa sesaji. Merica masih utuh. Air tujuh sumur tinggal sedikit, mungkin menguap. Celana dalam gadis perawan juga tidak robek, dan masih bau pesing. Kembang tujuh rupa kering semua. Terakhir, hidungnya mengendus-endus tumpukan sesajen.
“Ndra, kamu pakai minyak Jafaron palsu, ya? Beli di mana? Masa tidak ada sisa baunya sama sekali.”
Candra diam saja. Bergerak pun dia tak kuasa.
“Kita lem saja. Biar jadi dua muka.” Rupanya Sobar punya usulan jitu. Dia mencoba menempelkan dua lembar uang setengah jadi itu menjadi satu. Dilem dengan ludahnya. Dicampur sedikit ingus. Biar tidak terlalu encer. Di samping kirinya, Adul memperhatikan dengan seksama usaha keras kawannya itu. Dia rebut uang hasil rekayasa tersebut dari tangan Sobar. Dia bolak-balik.
“Betul Bar. Dua muka. Depan belakang sama. Dipakai beli sepatu dapat dua. Kiri semua,” kata Adul, sambil melemparkan uang yang bau jigong itu ke tanah. Dia sangat kecewa. Karena tidak jadi beli sepatu yang sudah lama diidam-idamkannya.
Sementara dari dalam rumah, si belang Timung berjalan gontai menghampiri mereka, dengan dua lembar uang merah di mulutnya. Diletakkannya uang itu di atas sepatu Candra. Dia ingin mengembalikannya.
Empat bulan berlalu semenjak kejadian uang satu muka, Candra datang ke kantor Sony ditemani ibunya.
“Ya sudah, Ndra. Kamu kerja di sini saja,” kata Sony.
Sesungguhnya, Sony dan ibu Candra sudah mengatur pertemuan itu dua minggu sebelumnya. Pada mulanya memang agak kaku. Tapi soto sulung berhasil mencairkan suasana. Mereka mengobrol sambil tertawa-tawa lepas. Sampai mulas. Bernostalgia, mengingat masa-masa jaya ketika kuliah.
Senang melihat Candra bisa tertawa lagi. Sepertinya sebagian beban berat itu telah terangkat dari pikirannya. Sony ingin membantu Candra. Keluar dari dunia khayal para pemburu. Sehingga tak perlu lagi keluar masuk hutan tanpa bekal peluru. Hanya untuk ditipu.
Candra seorang pekerja luar biasa. Pintar dan cepat mengerti. Sony mempercayakan beberapa klien kepadanya. Untuk diurus dan dilayani. Dia bekerja sama lumayan padu dengan Heru, yang mendapat tugas khusus dari Sony untuk membimbingnya.
Hampir setahun, banyak kemajuan yang diraih, bagi Candra maupun bagi Sony. Hingga pada suatu sore Candra menghadap Sony, dengan mata berkaca-kaca. “Saya mengundurkan diri.”
Sony masih tak mempercayai pendengarannya. “Apa?”
“Mengundurkan diri,” sahut Candra, sekali lagi.
Sony akhirnya mengiyakan, walaupun sedikit khawatir. Takut kalau-kalau Candra kambuh lagi. Bergelut dengan dunia gaib kembali. Kekhawatiran Sony ternyata tak terbukti. Lega hatinya, mendengar kabar Candra sudah bikin usaha sendiri. Bergabung dengan Jupri, mantan karyawannya. Beberapa klien Sony dia ambil. Biar saja. Sony tak terlalu pusing. Bisa dicari lagi.
Tapi dia benar-benar gundah ketika delapan bulan kemudian mendapat berita kurang sedap. Candra dicari-cari orang. Beberapa pemasoknya ngamuk-ngamuk, karena belum pernah dibayar. Di mana kamu, Ndra? HP-nya mati. Tak pernah bisa dihubungi. Akhirnya Jupri ditangkap polisi. Candra menghilang ditelan bumi.
Dung dung pret, ada kodok disangka kampret.
Mereka semua dengan sukarela, dan bahkan bergembira dengan wajah berseri merona, menyerahkan duitnya untuk diputar dengan kecepatan delapan belas ribu rpm. Dua kali lebih kecepatan putaran baling-baling helikopter. Dengan harapan mendapatkan imbal balik fulus berkoper-koper. Kenyataannya, sebagian besar uang itu lenyap ditelan pusaran. Jangan-jangan, sebenarnya mereka memang tidak pintar.
Organisasi-organisasi tipika-tipiki itu, tipu kanan tipu kiri, tak pernah sedikipun berminat untuk memperdayai orang bodoh. Di samping kurang menantang, orang bego biasanya tak punya uang. “Ndak level. Buang-buang waktu saja,” sesumbar mereka dengan nada menang, sambil memasukkan lembaran-lembaran uang ke dalam tas besar yang terus menggelembung.
Herannya, kejadian seperti ini terus berulang. Meninggalkan korban-korban yang malang. Dibiarkan terkapar makan tulang. Banyak orang meradang. Kaki serasa ingin menendang. Mulut bau para petualang. Yang bebas melenggang. Apakah mereka tak pernah mau belajar? Padahal mereka orang-orang terpelajar. Apakah mereka telah kehilangan nyala pijar? Yang tak mau lagi berpendar. Untuk mengingatkan manusia agar selalu sadar. Bahwa setiap orang harus bersabar. Dan itu pasti terbayar. Dasar! Manusia memang tamak.
Anton, karib Sony di kampung halaman sana, juga pernah jadi korban. Pohon berdaun emas meliuk-liuk seksi di hadapannya. Dengan belahan dada yang dibiarkan sedikit terbuka. Dan rok mini yang mengumbar paha. Menyapanya dengan kalimat-kalimat lembut bermantra, “Kamu tinggal siapkan pupuknya. Selebihnya serahkan sama saya. Ranting-ranting akan menjuntai. Daunnya melambai-lambai. Bisa dipanen berhelai-helai. Berkilau tanpa pernah padam. Suara gemerincing akan terdengar setiap malam.”
Bujuk rayu si empunya pohon emas itu, yang didendangkan oleh Karjo, juga teman Sony semasa SMA, sebenarnya sama sekali tak masuk akal. Bahkan sangat dangkal. Ketahuan jelas itu akal kadal. Janji-janji sundal. Tapi tetap terdengar senikmat cokelat. Keserakahan telah membungkam akal sehat.
Bapak, ibu, kakak, adik, pakde, bude, paklik, bulik, sepupu, sepaha, ipar, semua pada ditawari. Diajak bergabung. Semua kenalan dihubungi. Pak Lurah dan Pak Camat juga ikutan. Jadilah Anton yang berperawakan pendek dan kecil itu pengepul pupuk. “Boleh setor berapa saja. Nanti digabung jadi satu. Saya yang tanggung jawab. Sampeyan tinggal duduk-duduk manis. Koin emas akan menggelinding berlapis-lapis.”
Sedap benar kedengarannya. Semua orang pasti ngiler. Sekali dua kali tegukan air berkilau sempat menyegarkan dahaga mereka. Setelah itu tak ada lagi, setetes pun. Sudah kering. Ditunggu-tunggu juga tak kunjung datang kabarnya. Rasa was-was mulai menyergap. Jangan-jangan …. Jangan-jangan …, pikir Anton yang kian cemas dan gagap. Dia merasa harus segera bertindak sigap.
“Jo, bagaimana ini? Apakah pohonnya sudah layu?” Anton bertanya dengan curiga.
Namun Karjo terus berusaha menenangkannya dengan alasan sekenanya. “Matahari lagi tertutup awan tebal. Jadi klorofil tidak bekerja maksimal. Sabar. Jangan dulu gusar. Sebentar lagi awan akan pergi. Daun akan rimbun kembali.”
Namun awan gelap itu tak juga mau beranjak. Pohon itu layu bagai tonggak. Daunnya berguguran. Warnanya memudar. Yang tersisa hanyalah duri-duri tajam. Setajam silet, kata pembawa acara gosip di TV. Ribuan kepala langsung tertunduk lesu. Tatapan mata mereka sayu. Nafas Anton menderu-nderu. Tenggorokannya terasa kaku. Kepalanya seperti digetok palu. Dadanya serasa ditusuk-tusuk paku. Istrinya menangis tesedu-sedu. Keluarganya menanggung malu.
Karjo menghilang tanpa meninggalkan selembar pesan. Keluarganya masa bodoh dan terkesan lepas tangan. “Tidak tahu,” jawab mereka, tanpa berani menatap muka. Sony jadi teringat sebaris syair lagu mendayu-dayu yang dilantunkan Ratih Purwasih, “Jangankan menulis surat, menitip salam pun aku tak boleh ….”
Karjo. Karjo. Dua tahun kemudian Sony ketemu adiknya dalam acara halal bihalal sebuah partai politik di Jakarta. Maka dia tanyakan kabar kakaknya itu. “Bagaimana keadaan Karjo? Sudah lama tak terdengar kabarnya.”
Ichwan tampak kurang antusias menanggapi pertanyaan Sony. Sepertinya dia tak terlalu berminat untuk bercerita mengenai kakaknya. Maka Sony mengalihkan pembicaraan, berganti ke soal pekerjaan. Obrolan mereka semakin seru ketika nyerempet-nyerempet ke soal hantu.
“Karjo sekarang lebih banyak tinggal di rumah,” tiba-tiba Ichwan mengubah arah pembicaraan.
Maka mengalirlah cerita itu. Setelah terhempas oleh kasus koin emas, Karjo kehilangan gairah hidupnya. Setiap malam kerjanya cuma ngobrol ngalor-ngidul dengan pemuda-pemuda pengangguran di pos ronda. Subuh baru pulang. Kemudian tidur hingga tengah hari. Berubah dari makhluk diurnal menjadi nocturnal. Ngumpet di saat terang, keluyuran di kegelapan malam. Persis seperti kalong.
Saudara-saudaranya cemas. Tapi, anehnya, istri dan anak-anaknya tidak protes sama sekali. Mereka menganggap hal itu normal-normal saja. Bahkan mereka tetap menjalani hidup dengan gaya sok kaya. Kakak-kakak dan adiknya pun patungan modal bikin warung sembako, agar Karjo punya penghasilan. Ternyata tak juga jalan. Malahan, aset-aset warung habis dia jual. “Buat beli rokok,” katanya, tanpa merasa bersalah sedikitpun.
“Jengkel saya. Ini orang benar-benar susah dikasih tahu,” keluh Ichwan, seolah ingin mencurahkan semua kegalauan hatinya kepada Sony. Curhat.
Sony hanya mendengarkan keluh kesahnya, tanpa memberi komentar. Sungguh tak terbayangkan, Karjo yang pintar beradu argumentasi itu telah berubah total. Dari cerita yang disampaikan adiknya, Sony merasa tak mengenal Karjo lagi. Sudah lain. Bukan lagi Karjo yang suka bercanda dan bernyanyi, dan selalu gigih mewujudkan keinginannya.
“Son, kamu kan kawan baiknya. Tolong kasih tahu dia. Jangan keluyuran malam. Bangun pagi. Kerja apa saja. Pokoknya hidup normal. Masalah uang gampang. Keluarga bisa bantu,” imbuhnya dengan tatapan mata berharap.
“Saya akan coba,” Sony mengiyakan.
“Sementara ini,” kata Ichwan menutup pembicaraan, “memang tak ada jalan lain. Secara bergantian keluarga memberikan subsidi untuk biaya hidup Karjo dan keluarganya.”
Maka, siang itu Sony menelpon Karjo. Namun dia harus menelan kecewa. Tadinya dia berharap bisa mengobrol seperti teman lama. Sony jadi keki. Omongan Karjo selalu tinggi-tinggi. Nyerocos tanpa henti. Sangat jauh dari kenyataan hidupnya sehari-hari. Makanya, sengaja dia biarkan Karjo ngomong apa saja dalam percakapan satu arah itu. “Udahan ya Jo, pulsaku habis.”
Ketika besoknya mau menelepon Karjo lagi, Sony malah ragu-ragu. Tanpa sadar ibujarinya justru memencet nomor HP Anton. “Hey, Ton, aku sudah ketemu Karjo. Ada salam untukmu. Dia bilang sekantong koin emas sudah dikuburkan di halaman belakang rumahmu. Malam Jum’at coba kamu congkel pakai kayu. Pasti ketemu.”
Anton hanya cengengesan mendengar ledekan Sony. “Ya, Son. Saya coba malam Jum’at nanti. Tolong bantu doa. Salam buat Karjo.”
Tapi Sony penasaran, mengapa Karjo suka tidur sampai tengah hari. Jadi bangsawan. Bangsane tangi awan. Tanpa sengaja dia menemukan jawabannya pada waktu melakukan hal serupa di hari libur. Mimpinya bagus-bagus. Gila. Dia terbuai mimpi cinta pertamanya, dan Bethany juga datang menghampirinya. Kali lain, dia mimpi jadi milyuner, orang terkenal, bisa terbang, bisa ngilang, dan yang asyik-asyik lainnya. Day dream. Bikin ketagihan. Don’t try this at home.
Rupanya, ketika hari terang, di mana dunia sedang berada pada puncak aktivitasnya, demikian pula lingkungan sekitar, rangsangan-rangsangan dari luar berseliweran memicu aktivitas otak orang yang sedang tidur. Makanya, orang suka dibilang mimpi di siang bolong apabila ngomongnya muluk-muluk dan berkhayal yang bukan-bukan. Ya, benar. Mimpi di siang bolong.
“Siang, Bos. Lagi banyak kerjaan kayaknya.”
Sony agak pangling dengan penampilan tamu yang datang pada saat dia sedang bersiap makan siang di kantornya, di Mampang. Berdasi dan pakai jas segala. Rambutnya yang agak panjang diikat rapi membentuk ekor kuda buntung. Tubuhnya yang tak seberapa kekar menebar wangi jantan yang khas. Sepertinya dia kenal parfum itu. Ya, Hugo Boss. Sungguh lain dari biasanya.
“Hey, Drus, keren sekali kamu hari ini. Kerja di mana sekarang? Banyak uang, ya? Bagi-bagi, dong. Oh, ya, sudah makan? Kita makan bareng, yuk.”
Sony segera memanggil Usep, office boy kepercayaannya itu. “Sep, tolong belikan soto sulungnya satu lagi. Ada tamu penting. Kamu masih ingat kan, sama Pak Idrus? Sekalian, tambah krupuk udangnya.”
Usep hanya mengangguk. Dan langsung pergi.
Idrus adalah kawan lama. Pekerja freelance ketika Sony baru memulai usaha kembali setelah perusahaannya terjengkang dihempas krisis ekonomi. Idrus. Kreativitasnya memang luar biasa. Banyak klien yang suka dan puas dengan hasil kerjanya. Dulu, ketika Sony menawarkan kepadanya untuk bergabung saja, Idrus langsung menolak mentah-mentah.
“Mas, saya nggak mau merepotkan. Sampeyan kan sudah tahu. Bagaimana bila tiba-tiba saya ngilang enam bulan untuk bertapa? Mendinginkan bara di dada. Ngunduh ilmu sambil cari pusaka.”
Kecenderungan supranatural orang Purwokerto itu memang tampak jelas dari caranya berpakaian dan bahan obrolannya. Bahkan Sony pernah mendengar Idrus membeli seekor burung perkutut sakti seharga dua puluh juta. Tak disangka-sangka, besoknya burung itu mati begitu saja. Jagat klenik pula yang membawanya masuk ke dalam lingkaran pergaulan yang sangat luas. Idrus punya banyak kawan. Mulai dari kalangan selebriti hingga petinggi tentara.
“Saya jadi salesman sekarang,” katanya, tanpa menatap mata Sony. Lelaki berjenggot dan berkumis itu sedang sibuk berjoget lidah dengan semangkuk soto. Sendok di tangan kanan, krupuk di tangan kiri. Garpu dia biarkan merana di meja. Tanpa pernah disentuhnya. Idrus menyeruput kuah soto yang panas itu dengan lahapnya. Keringat mulai menitik di keningnya. Garis bibirnya agak bergetar memerah.
Dari caranya mengunyah, Sony tahu kawan lamanya itu sangat menikmati makanan kegemarannya. “Jualan apa, Drus?” tanya Sony, sambil menyelesaikan satu gigitan lagi krupuk udang yang renyah.
“Begini. Saya disuruh Jenderal Kancil menukarkan uangnya. Dari rupiah ke dolar Amerika. Dia mau terima dolar minimal satu juta. Harganya dua puluh persen lebih murah.”
Kemudian dia bercerita mengenai kenalannya. Sesama pemburu pusaka. Seorang tentara yang kaya raya. Uang berjibun disimpan di rumahnya. Hingga dua kamar banyaknya. Dalam tumpukan-tumpukan kardus yang tertata. Semuanya pecahan lima puluh ribu rupiah. Dia takut bank bertanya. Dari mana duit itu asalnya.
“Kenapa tidak pergi ke money changer saja?” tanya Sony asal bunyi. Sebab, bila Idrus mau menawarkan uang segede itu kepadanya, jelas dia tak punya.
“Ya tidak mungkin kita jual ke pedagang valuta. Terlalu besar jumlahnya. Mereka akan curiga. Kita bisa celaka. Makanya saya datang ke sini. Kalau ada kawan yang mau, tolong saya dikasih rekomendasi.”
Rupanya sudah hampir empat bulan dia pergi kesana-kemari. Tapi belum ada satu pun yang tergenggam jemari. Kemudian dia bercerita lagi bahwa duit seabrek itu dijaga oleh empat orang tentara. Tapi si empunya masih was-was hatinya. Sehingga harus ditambahkan sepeleton jin untuk mengawalnya. Sudrun nama komandannya.
Setelah ngobrol ngalor-ngidul, tiba-tiba Idrus melontarkan sebuah ajakan maut yang tak pernah sedikit pun terlintas dalam benak Sony. “Mas, bagaimana kalau sebagian uang itu kita colong saja. Hasilnya kita bagi dua. Saya pernah bicara sama Sudrun. Dia bilang mau bantu.”
Edan. Beginilah cara berpikir orang yang sudah putus asa. Atau, memang sudah sifat manusia untuk menjadi serakah. Dengan menghalalkan segala cara. Asalkan tercapai tujuannya. Tapi, aneh bin ajaib, Sony terpancing oleh ajakannya. “Bagaimana caranya, Drus?” tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu.
Idrus pun membeberkan rencananya. “Kita pakai kantor ini. Di sini. Ya, di sini. Di ruangan ini,” katanya, seraya memperhatikan dengan seksama setiap jengkal ruang kerja Sony. Dia tampak tersenyum setelah melihat ada jendela kaca yang dapat dibuka-tutup.
Tapi Sony masih belum mengerti maksudnya. Kalau mau nyolong, kan harus pergi ke rumah Jenderal Kancil. Pakai kostum hitam dan menyelinap di malam hari. Mengendap-endap membongkar kunci. “Maksudnya bagaimana, Drus?” tanya Sony dengan tak sabar.
“Begini, malam Jum’at nanti, tengah malam, kita di sini. Tinggal menunggu saja. Sudrun dan anak buahnya akan membawa uang itu ke sini. Yang penting jendela dibuka. Maka uang akan melayang-layang dan masuk. Bertumpuk-tumpuk. Besok saya temui Sudrun, untuk membicarakan rencana ini.”
Tak berapa lama kemudian Idrus pamit pulang. Sony menyuruh Tukijan mengantarnya. Ini tamu yang sangat penting. VVIP. Harus diservis habis-habisan.
Sony benar-benar termakan oleh rencana jahat itu. Khayalannya langsung melayang-layang. Paling tidak bisa beli Jaguar barang sebiji. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana mungkin hasilnya dibagi dua? Kan ada pihak ketiga? Sudrun dan konco-konco-nya. Emangnya dia mau kerja gratisan. Mana mungkin? Bagaimana kalau dia minta imbalan nyawa?
Sony jadi ketakutan sendiri memikirkannya. Gamang hatinya. Tapi ini urusan duit besar. Sayang kalau dilepas begitu saja. Lama sekali dia terpekur memikirkan jalan keluar yang paling mungkin dan aman, sampai akhirnya dia temukan solusi yang tokcer. Bila Sudrun benar-benar minta imbalan nyawa, itu tak masalah. Asal jangan nyawanya. Ambil saja salah satu nyawa dari kantor sebelah. Karena mereka suka menyerobot tempat parkirnya. Beres sudah.
Kamis sore, langit temaram. Pukul setengah enam. Semua karyawan sudah pada menghilang. Tukijan sudah duluan dia suruh pulang. “Ada pekerjaan penting yang harus saya selesaikan malam ini,” kata Sony kepada Usep, yang tampak agak bingung.
Office boy itu dia tahan hingga pukul delapan. Sony menghabiskan waktu dengan main games di laptop. Menunggu Idrus datang berselop. Tapi, hingga pukul sepuluh, pintu belum juga ada yang mengetuk. Sementara Sony mulai diserang rasa kantuk. Sambil menguap dia menengok jam di dinding. Jarum-jarumnya runcing menuding. Bulu kuduknya terasa agak merinding.
“Drus …. Idrus …. Di mana kamu? Ini sudah jam dua belas malam. Aku takut Sudrun keburu bertandang.”
Tak ada yang menjawab. Senyap. Dan tidak pula ada yang datang. Panggilan telepon tak berjawab. SMS tak bertanggap. Sony pun merebahkan diri di sofa. Langsung pulas.
Keesokan paginya Sony buru-buru menghubungi Idrus. Tapi HP-nya mati terus. Dia berusaha tanpa putus. Hingga panggilan keseratus. Tak juga tembus. Gagal sudah rencana dapat fulus. Kini saatnya pergi ke kakus. Membuang isi usus. Ampas nasi bungkus. Sambil nongkrong, pikirannya berputar-putar dalam beberapa jurus.
Jangan-jangan Idrus telah dikhianati oleh Sudrun. Bisa jadi jin plin-plan itu melapor kepada majikannya mengenai rencana konspirasi kelas kakap. Sehingga Idrus langsung ditangkap. Pergelangan tangannya digari. Sementara di keningnya sepucuk pestol menari-nari. Pelatuknya tinggal menunggu ditekan dengan jari.
Sudah. Sudah. Sony membuang jauh-jauh pikiran buruk itu. Tak mau lagi dia berhubungan dengan Idrus. Bikin perut murus. Otak kobong. Tolooong … tolooong … tolooong ….
“Mas, tolong Candra. Saya tak tahu harus bagaimana. Barang-barang di rumah sudah ludes semua. Dijual paksa. Sebagian lagi disita. Keluarga sudah pasrah. Nyerah.”
Perempuan tua itu terisak di kantor Sony. Suaranya terbata-bata. Tersendat-sendat mengalirkan kata. Berkali-kali dia menyeka matanya yang berkaca-kaca. Dengan sapu tangan yang terbuat dari kain perca. Di lehernya menggantung kacamata baca.
Candra, putra kebanggaannya itu, keranjingan berburu harta karun. Ke mana-mana yang dicari selalu dukun. Kalau diajak bicara lagaknya seperti orang pilun. Menyeringai sambil mengelus jakun. Meski kadang-kadang memasang muka tekun. Lehernya bergoyang-goyang seperti ayam kalkun.
Candra sahabat Sony semasa kuliah. Pernah bersama-sama dalam senang dan susah. Rasanya sudah lama dia tak bersua dengannya. Semenjak Candra melanjutkan studinya ke Australia. Memang, setahun sebelumnya Candra pernah datang ke kantornya. Sekali saja. Hanya sempat bertukar beberapa kata. Tampaknya dia sedang tergesa-gesa. Saat pamit pulang dia mengutarakan niatnya. Mau pinjam fulus seratus juta. Dengan jaminan selembar sertifikat tanah. Ditambah sebaris sumpah. Katanya sedang urus bisnis permata. Batu merah delima.
Sony tak bisa memenuhi permintaannya. “Sorry, Ndra. Aku nggak bisa kasih, karena uang saya harus terus diputar. Tapi, kalau kamu ada kesulitan, aku bisa bantu,” katanya sambil memberikan amplop berisi uang dua juta.
Candra. Candra. Candra. Dulu Sony mengenalnya sebagai mahasiswa yang pintar. Gemar memetik gitar. Memelihara seekor ular. Meski omongannya kadang berputar-putar. Tapi tak pernah kehilangan kelakar. Senyumnya lebar. Raut mukanya selalu bersinar. Dahinya bundar. Dengan aura terang yang senantiasa memancar. Tutur katanya halus dan mengalir lancar. Setahun sekali dia ganti pacar. Cewek-cewek yang naksir pada ngantri berjajar. Dengan hati yang bergetar. Sony iri kepadanya.
Tapi kini Candra telah banyak berubah. Garis wajahnya kaku seperti muka kuda. Bajunya dekil berwarna ungu muda. Jaketnya tengil berlubang di dada. Dalam usianya sudah tak lagi muda, dia hidup melajang tak berkeluarga. Sehari-hari numpang di rumah orangtuanya. Sony pernah mendengar Candra sudah menduda.
Candra menerlantarkan bisnisnya dengan sumpah serapah. Akibat rencana yang mentah. Rugi segede gajah. Merasa masa depannya patah-patah. Dia beralih mengejar harta dari antah berantah. Dengan pancingan sepotong emas dan asap dupa. Berharap akan berjatuhan latakan-latakan kuning menyala. Dari langit yang tak berwarna. Di tengah orang-orang yang duduk bersila. Wajah-wajah serius mengadu asa. Siapa tahu keberuntungan segera tiba. Dan impian jadi nyata. Dengan merapalkan mantra. Tanpa pernah tahu apa maknanya.
Mulut mbah dukun komat-kamit. Mengunyah kunyit. Tangannya mengayun-ayunkan sendal jepit. Mencoba memanggil demit. Ditunggu hingga bermenit-menit. Belum juga muncul pertanda barang sekelumit.
“Ada yang belum ikhlas hatinya,” kilah Mbah Cokro yang alis matanya putih menjuntai itu.
Lempengan emas seberat seratus gram, yang dibeli secara patungan oleh Candra bersama ketiga orang temannya, lenyap begitu saja. Sedikit pun tak bersisa. Ini bukan tipuan mata. Tapi sesuatu yang nyata. Padahal tadi jelas-jelas ditanam di hadapan mereka. Oleh dua orang asisten dukun celaka. Yang bekerja tanpa berkata-kata.
Candra tak percaya dengan penglihatannya. Tangannya langsung meraba-raba. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Setelah mengorek-ngorek tanah agak dalam lagi, dia temukan sepotong kayu kecil berwana cokelat muda. Ukurannya persis sama. Bentuknya serupa. Dengan latakan emas yang telah sirna. Hanya berbeda warna. Dan, tentu saja, lain jenisnya.
“Minggu depan kita ulangi. Maharnya lebih tinggi. Dua ratus gram,” kata mbah dukun yang berwajah garang itu.
Anehnya, mereka menurut saja. Berkali-kali nyaris belaka. Dan maharnya semakin besar pula.
Seorang mantan pejabat pernah jadi korban. Rayuan gombal menggiringnya masuk ke dalam sebuah jebakan. Meski tak terlalu akrab, Sony cukup lama mengenalnya. Malang benar nasibnya. Pria terhormat bergelar doktor itu harus kehilangan fulus. Sebanyak lima kardus. Dalam jutaan, nilainya mencapai tujuh ratus. Hangus.
Petaka bermula dari hasrat yang membabi buta. Mengejar harta durjana dengan cara-cara yang nista. Modalnya memang sangat besar. Tapi dia haqul yakin duitnya bakal mekar. Sudah disiapkan dua truk kekar. Diparkir di sela-sela belukar. Kendaraan raksasa beroda sepuluh itu akan pulang dengan berkardus-kardus uang. Setiap truk diberi tanda silang. Supirnya dikawal oleh dua orang pawang. Masing-masing bersenjatakan pestol dan kelewang. Juga cabe rawit dan bawang. Ditusuk-tusuk melintang. Untuk menangkal tuyul jail dalam perjalanan pulang.
Di tengah hutan mereka berhimpun. Tanpa nyanyian-nyanyian gembira ataupun api unggun. Tak seperti Pramuka yang ramai-ramai berkemah sekali dalam setahun. Sebaliknya, hanya wajah-wajah yang tekun. Dengan duduk bersila mereka melakukan ritual dipimpin mbah dukun. Mengelilingi kardus-kardus berisi uang yang telah disusun. Tertutup rapi di bawah tumpukan daun. Rapalan-rapalan mantra segera mengalun. Tubuh sang dukun terayun-ayun.
Secara perlahan muncul kabut pekat. Sementara bau dupa kian menyengat. Lingkaran manusia itu mulai merapat. Membentuk segi empat. Mantra-mantra dilafalkan dengan penuh semangat. Dalam hentakan nada cepat. Untuk mengundang arwah jahat. Yang datang tanpa pakai cawat. Maka setan-setan besepakat. Membawa mereka ke jalan sesat.
Psssttt …. Terdengar bunyi mendesis dari dalam tumpukan daun. Tangan mbah dukun langsung berhenti mengayun. Kepala diangkat, mata menatap langit. Keningnya sedikit berkernyit. Ini dia. Mantra itu sudah bekerja. Angan-angan sudah di depan mata. Kardus-kardus itu pasti akan segera menggunung seperti tumpukan batu bata.
Namun, segaris api yang berkilat tiba-tiba menyambar. Anak-anaknya yang menyengat berlarian berkobar-berkobar. Tanpa banyak koar-koar. Langsung berbuat makar. Kardus-kardus berisi uang itu habis terbakar. Keenam kaki-tangan mbah dukun saling melirik dengan lobang hidung yang mekar. Karena sesungguhnya kardus-kardus itu telah mereka tukar. Di dalamnya ditaruh potongan koran berlembar-lembar. Ditetesi sedikit minyak ketumbar. Penanda yang baunya samar. Agar tak salah kamar. Pasti mereka dapat persenan besar.
Dukun Sumo yang perutnya buncit itu berjalan menghampiri Pak Doktor. Tatapan matanya begitu kotor. Dengan nada tinggi dia menghardik pria baya yang sedang kebingungan tersebut, “Sampeyan tidak ikhlas. Akibatnya, mahar amblas.” Sambil membuang muka, tangannya mengibas-ngibas. Bergerak-gerak seperti kipas. Mengusir hawa panas. Diteguknya air putih segelas.
Ini orang benar-benar raja tega. Tabiat celaka. Sony menduga mbah dukun pernah bergabung dalam sebuah teater. Terlihat benar dia piawai memainkan karakter. Sekalipun harus berperan sebagai dokter.
Kasihan Pak Doktor yang badannya pendek gemuk seperti Semar. Dia terduduk lesu dengan hati memar. Perasaannya hambar. Matanya nanar. Otaknya serasa terbakar. Sudah kehilangan uang, dicaci maki pula.
Sony jadi bertanya-tanya, benarkah jin bisa kasih manusia harta berlimpah? Banyak orang yang percaya begitu. Seperti Pak Doktor itu. Sony sendiri tak tahu. “Seandainya saja ketemu jin, akan aku tanyakan masalah itu. Tapi hingga hari ini, belum pernah ketemu. Tak tahu jin itu rupanya kayak apa, baunya seperti apa, kesaktiannya setinggi apa,” kata Sony kepada Heru, yang terlihat bosan karena diajak ngobrol terus sedari siang. Sampai lupa makan.
“Kalau Bapak ingin lihat jin, ada orang yang bisa bantu.” Sony teringat perkataan Pak RT dua bulan lalu. Ketika mereka sedang kerja bakti di hari Minggu. “Biayanya tiga juta. Tidak pakai syarat puasa,” dia menambahkan sambil menyebutkan nama seorang kyai yang tinggal di Jakarta Timur.
Kalau harus pakai biaya, Sony pasti ogah. Sebaliknya, dia akan minta uang sama jin. Akan ditolaknya bila hanya dikasih nomor togel. Terlalu banyak ketidakpastian. Harus diramesi dulu. Dan itu pun belum tentu tepat. Karena jin menyebutkan angka-angka dalam bahasanya sendiri. Sementara orang harus menafsirkannya ke dalam bahasa manusia.
“Met, memangnya ada orang yang pernah dikasih duit sama jin?” tanya Sony kepada Slamet, kakaknya yang dukun itu, ketika dia sedang berkunjung ke rumahnya, mengantarkan mangga hasil panen di kampung halaman sana.
“Ada. Di Bogor. Diberi dua karung.”
Sony jadi bertanya-tanya. Duit kok ukurannya karung, bukan juta atau milyar. Dan lagi, tidak dirinci apakah karungnya besar atau kecil. Bekas atau baru. Kalau isinya pecahan logam seratus rupiah semua, atau duit seribuan, sama juga bo’ong. Berapa nilainya?
“Bagaimana caranya agar jin mau kasih saya duit?” Sony mulai melemparkan pancingan iseng.
Anehnya, kali ini Slamet tidak langsung menyambar umpan yang renyah itu. Sebaliknya, dia menatap mata Sony dalam-dalam. Dari matanya mengalir seutas cahaya tipis berwarna biru yang menembus syaraf-syaraf penglihatan Sony, mengalir ke otaknya dengan berkelok-kelok dan kemudian turun menyusuri ruas-ruas tulang belakang, berhenti dan mentok di tulang ekor. Bokongnya terasa sedikit panas. Sony jadi tidak mengerti, kok begini jadinya. Agak rikuh juga dia.
“Kalau kamu, ndak mungkin dikasih. Lha wong kamu serakah,” jawabnya dengan seenaknya sambil menyeruput kopi panas yang baru saja dihidangkan Febriana.
Sialan, dibilang serakah. Terus terang saja, Sony benar-benar tersinggung dikatain serakah. Dia sama sekali bukan orang yang serakah. Cuma mata duitan.
Bukannya mbelain, Fadli yang duduk di sampingnya malah ikut-ikutan memojokkannya. “Bisa saja kamu dikasih duit banyak, tapi uang jin. Mau dipakai beli apa? Belanja di mana? Paling-paling harus pergi dulu ke pasar jin.”
Benar juga apa yang dia bilang. Money changer pasti menolak duit jin. Demikian pula bank. Di samping tidak tahu harus ditukar pada nilai kurs berapa, pasti mereka juga kebingungan harus dijual ke mana lagi uang jin itu.
Tapi, tunggu sebentar. Bagaimana, ya, kira-kira bentuk uang jin? Apakah sama dengan duit manusia? Bisa jadi wujudnya bermacam-macam. Segitiga, jajaran genjang, lingkaran, pita atau bulatan-bulatan kecil seperti permen karet yang berwarna-warni. Kalau memang demikian, berarti manusia selama ini kurang kreatif, karena hanya mengenal alat tukar dalam bentuk koin dan kertas yang dipotong-potong persegi panjang.
“Potong yang benar! Ukurannya harus sama persis. Kalau perlu saya bayar lebih.” Candra memaki pegawai toko kertas itu. Dia merasa tidak dihargai dan dilecehkan. Pemuda yang rambutnya panjang dikelabang tersebut senyam-senyum melulu. Rekan kerja di sebelahnya, yang membantunya menata dalam tumpukan-tumpukan rapi potongan-potongan kecil kertas itu, juga demikian. Mereka saling lempar kedipan. Dengan seulas senyuman kecil yang tertahan.
Candra membeli kertas HVS 80 gram ukuran plano besar sebanyak tiga rim. Dipotong-potong seukuran duit seratus ribu. Selembar uang merah dijadikan mal untuk ditiru. Diukur secara teliti. Tak boleh meleset barang semili, apalagi sesenti. Dia periksa ulang setiap sisi. Semuanya harus presisi. Kemudian dia bawa pergi ketiga bungkusan besar itu dengan taksi.
Bahan baku sudah siap, pikirnya. Sekarang harus cari kongsi untuk patungan beli minyak Jafaron. Ini bukan minyak sembarangan. Didatangkan langsung dari Arab. Konon, parfum ini sangat disukai bangsa jin dari kalangan atas, baik generasi tua maupun remaja. Parfum pilihan. Sekelas Channel di dunia manusia. Satu tetes harganya empat juta. Dibutuhkan satu ampul kecil agar jin sakti mau datang untuk menyulap potongan-potongan kertas itu menjadi lembaran-lembaran rupiah.
Candra mencoba menghubungi teman-temannya sesama pemburu harta. Sebagian tinggal di luar kota. Namun banyak juga yang berumah di Jakarta. Sungguh sial. Tak seorang pun memberi sinyal. Mereka semua pada tiarap. Kehabisan cakap. Karena baru dikerjain habis-habisan oleh seorang dukun keparat dari Cilacap.
Candra kebingungan. Duit yang ada di tangannya hanya lima belas juta. Bahkan sudah berkurang lima puluh ribu. Dipakai beli rokok dan makan siang. Ditimang-timangnya segepok uang lusuh yang berikat karet gelang berwarna kuning mentah. Hasil penjualan motor kesayangan adiknya dan semua perhiasan ibunya.
Sepuluh juta sudah dialokasikan untuk jasa mbah dukun. Angka itu sama sekali tak bisa ditawar. Sedangkan yang satu juta untuk biaya transport dan kelengkapan ritual. Berarti hanya bisa beli satu tetes. Padahal satu ampul harusnya berisi dua puluh empat tetes. Masih jauh. Tapi Candra tak kehilangan akal. Beli satu tetes saja. Nanti dicampur alkohol. Jin yang kurang teliti pasti tidak tahu. Beginilah, cara berpikir orang yang biasa beli parfum tembakan.
Candra segera berangkat ke rumah gurunya, Mbah Bardam, di Sukabumi. Sang dukun ternyata tak tahu kalau minyak Jafaron itu oplosan. Berarti aman, pikirnya. Tinggal syarat-syarat tambahan. Kembang tujuh rupa. Air dari tujuh sumur yang berbeda. Tujuh butir merica. Seekor ayam jantan putih mulus. Dan terakhir, sepotong celana dalam gadis perawan, harus sudah dipakai tapi belum dicuci. Lebih afdol lagi kalau ada sedikit bekas pipis.
Sudah siap semua sekarang. Kertas bahan baku bersama kelengkapan lainnya kemudian dibungkus dengan tiga lapis kain kafan. Kecuali ayam jago, yang dipotong dan digoreng dengan bumbu kuning. Bagian dada dan brutu disantap Mbah Bardam. Paha dan sayap sudah diembat duluan sama istrinya di dapur. Leher hingga kerongkongan khusus dipersembahkan untuk Timung, kucing belang kesayangan sang dukun. Candra cuma kebagian ceker.
Tak apalah, pikirnya. Sesekali ngalah sama kucing. Lihat saja nanti. Kalau duitnya sudah jadi, akan dia belikan kucing malas itu seratus ekor ayam potong. Biar overweight, dan kolesterolnya naik. Stroke, kemudian mati. We lha, balas dendam kok sama kucing.
“Dung dung pret, ada kodok disangka kampret.”
Setelah tuntas dijampi-jampi selama tiga hari tiga malam di sebuah kamar yang gelap dan pengap, bungkusan itu harus diperam dulu selama tiga minggu. Tak boleh dikutak-katik. Apalagi diintip. Biar cepat matang. Pasukan jin akan melukis kertas-kertas itu menjadi uang.
“Tanggal lima belas kamu datang lagi ke sini. Bawa pengawal. Biar pulangnya aman,” ujar Mbah Bardam sambil mengulurkan bungkusan kecil yang terbuat dari kain kasar berwarna hitam kepada Candra. “Ini jengger ayam jago. Simpan baik-baik. Warnanya harus tetap merah. Jangan lupa, setiap tengah malam kamu bacakan mantranya. Seribu kali banyaknya. Sudah hapal belum?” sekali lagi dukun sakti itu mengingatkannya.
“Ya, Mbah, sudah tahu. Dung dung pret, ada kodok disangka kampret. Gitu, kan?”
Mbah Bardam menangguk sambil tersenyum.
Maka, pada hari yang telah ditentukan, Candra sudah siap menjadi orang kaya. Dia pinjam baju dan sepatu adiknya. Agak kekecilan memang. Tapi terlihat lebih seksi. Mobil angkot sengaja disewa dari tetangga sebelah. Dua orang preman menemani. Yang satu berbadan ceking dan wajahnya penuh dengan jerawat besar-besar, sedangkan yang satunya lagi gendut luar biasa. Persis seperti angka sepuluh bila mereka berjalan bersama.
Sobar, si gendut itu, badannya penuh lukisan. Di dadanya tergambar tato besar sendok dan garpu menyilang di atas sebuah mangkuk. Sebagai penanda bahwa dia seorang jagoan. Jago makan. Memang, Sobar sohib kental Benu Buloe si jurumakan. Mereka berkenalan di rumah sakit MMC ketika sama-sama hendak melakukan operasi tambah lambung. Sobar baru pertama kali, sedangkan si Benu kedua kali. Jadi, lambung Benu Buloe sekarang ada tiga. “Biar tambah kuat makan,” katanya.
“Maaf ya, tidak ada makanan. Istri saya lagi pulang ke rumah bapaknya,” kata Mbah Bardam seraya mengajak tamunya masuk ke dalam rumah.
Candra sama sekali tak terpikir soal makan. “Bagaimana, Mbah, sudah bisa dibuka?” Pertanyaan itu terlontar begitu saja bahkan sebelum dia dipersilahkan duduk oleh si empunya rumah. Kelihatan sekali, Candra sudah tak sabaran.
“Kalau begitu, mari kita buka sama-sama.”
Mereka pun berjalan beriring menuju kamar di mana bungkusan itu disimpan. Lampu segera menyala dan tali pengikat dibuka. Weesssss …. Candra melonjak kegirangan melihat duit merah bertumpuk-tumpuk. Kesampaian sudah impiannya. Pikirannya langsung melayang-layang. Mau beli ini beli itu. Pokoknya bela-beli.
“Ini bonusnya, Mbah,” katanya sambil memberikan tiga gepok uang kepada mbah dukun. “Tapi Mbah Bardam jangan kawin lagi, ya,” tambahnya sambil bercanda. Bahkan, si Timung, kucing belang kesayangan mbah dukun, yang saat itu anguk-anguk di depan pintu, dia kasih dua lembar.
“Baaaaarrr …. Duuuuulll …, sini …. Bantu saya angkat ini.”
Bungkusan yang cukup berat itu pun mereka gotong bertiga dan dimasukkan ke dalam mobil.
“Sudah beres? Aman?”
Sekali lagi Candra memastikan semuanya aman dan terkendali. Dengan teropong besar bermotif loreng bikinan Cina dia mengawasi lingkungan sekitar. Sambil berputar-putar, dia perhatikan dengan seksama setiap rimbun pepohonan. Siapa tahu, ada orang jahat yang sedang mengintai dari balik dedaunan. Dia tak ingin kecolongan kali ini. Karena duit itu sudah benar-benar menjelma.
“Ini jatah kalian.”
Masing-masing preman mendapat segepok uang. Gembira benar mereka. Belum pernah pegang fulus sebanyak itu. Saking gembiranya, Sobar melemparkan duit itu ke atas sehingga beterbangan dan jatuh berceceran di tanah. Hujan uang. Kayak di filem-filem.
“Lha, Bos, uang apaan ini? Masa gambarnya hanya sebelah?”
Dengan berjongkok, Sobar terus membolak-balik uang yang berserakan di tanah. Sementara Adul langsung memeriksa uang yang ada di tangannya. Sialan. Sama saja. Maka dicampakkannya uang merah bermuka satu itu ke tanah. Makin luas saja hamparan karpet dengan kombinasi warna merah putih di tanah yang berdebu itu. Sebagian malah terbang terbawa angin.
Candra tertegun. Berdegup keras jantungnya. Ubun-ubunnya terasa mendidih. Nafasnya tersengal. Matanya gatal. Benar. Duit itu bergambar satu muka. Balikannya kosong melompong. Putih bersih. Tidak ada gambar apapun. Candra langsung melompat ke dalam mobil dan buru-buru membuka bungkusan kain kafan. Dia bongkar tumpukan duit itu. Cilaka. Semuanya cuma bergambar satu muka. Lututnya terasa lemas. Dadanya panas. Susah bernafas. Impiannya kandas.
Mendengar keributan itu, mbah dukun tergopoh-gopoh mendatangi mereka. Dia ikut-ikutan memeriksa tumpukan uang tersebut. Dibolak-balik. Dikibas-kibaskan. Dibacakan mantra. Tetap saja tak berubah. Semuanya satu muka.
“Kalau dipakai beli sepatu dapat sebelah.” Adul yang sedari tadi membisu tiba-tiba nyeletuk.
Mbah dukun langsung berlari ke dalam rumah. Tiga gepok uang yang diterimanya tadi ternyata juga sama. Segera dia balik lagi ke mobil. Dia periksa sekali lagi tumpukan uang setengah jadi itu. Dibantu Sobar dan Adul, dia turunkan bungkusan tersebut. Diletakkan di tanah. Dia teliti sisa-sisa sesaji. Merica masih utuh. Air tujuh sumur tinggal sedikit, mungkin menguap. Celana dalam gadis perawan juga tidak robek, dan masih bau pesing. Kembang tujuh rupa kering semua. Terakhir, hidungnya mengendus-endus tumpukan sesajen.
“Ndra, kamu pakai minyak Jafaron palsu, ya? Beli di mana? Masa tidak ada sisa baunya sama sekali.”
Candra diam saja. Bergerak pun dia tak kuasa.
“Kita lem saja. Biar jadi dua muka.” Rupanya Sobar punya usulan jitu. Dia mencoba menempelkan dua lembar uang setengah jadi itu menjadi satu. Dilem dengan ludahnya. Dicampur sedikit ingus. Biar tidak terlalu encer. Di samping kirinya, Adul memperhatikan dengan seksama usaha keras kawannya itu. Dia rebut uang hasil rekayasa tersebut dari tangan Sobar. Dia bolak-balik.
“Betul Bar. Dua muka. Depan belakang sama. Dipakai beli sepatu dapat dua. Kiri semua,” kata Adul, sambil melemparkan uang yang bau jigong itu ke tanah. Dia sangat kecewa. Karena tidak jadi beli sepatu yang sudah lama diidam-idamkannya.
Sementara dari dalam rumah, si belang Timung berjalan gontai menghampiri mereka, dengan dua lembar uang merah di mulutnya. Diletakkannya uang itu di atas sepatu Candra. Dia ingin mengembalikannya.
Empat bulan berlalu semenjak kejadian uang satu muka, Candra datang ke kantor Sony ditemani ibunya.
“Ya sudah, Ndra. Kamu kerja di sini saja,” kata Sony.
Sesungguhnya, Sony dan ibu Candra sudah mengatur pertemuan itu dua minggu sebelumnya. Pada mulanya memang agak kaku. Tapi soto sulung berhasil mencairkan suasana. Mereka mengobrol sambil tertawa-tawa lepas. Sampai mulas. Bernostalgia, mengingat masa-masa jaya ketika kuliah.
Senang melihat Candra bisa tertawa lagi. Sepertinya sebagian beban berat itu telah terangkat dari pikirannya. Sony ingin membantu Candra. Keluar dari dunia khayal para pemburu. Sehingga tak perlu lagi keluar masuk hutan tanpa bekal peluru. Hanya untuk ditipu.
Candra seorang pekerja luar biasa. Pintar dan cepat mengerti. Sony mempercayakan beberapa klien kepadanya. Untuk diurus dan dilayani. Dia bekerja sama lumayan padu dengan Heru, yang mendapat tugas khusus dari Sony untuk membimbingnya.
Hampir setahun, banyak kemajuan yang diraih, bagi Candra maupun bagi Sony. Hingga pada suatu sore Candra menghadap Sony, dengan mata berkaca-kaca. “Saya mengundurkan diri.”
Sony masih tak mempercayai pendengarannya. “Apa?”
“Mengundurkan diri,” sahut Candra, sekali lagi.
Sony akhirnya mengiyakan, walaupun sedikit khawatir. Takut kalau-kalau Candra kambuh lagi. Bergelut dengan dunia gaib kembali. Kekhawatiran Sony ternyata tak terbukti. Lega hatinya, mendengar kabar Candra sudah bikin usaha sendiri. Bergabung dengan Jupri, mantan karyawannya. Beberapa klien Sony dia ambil. Biar saja. Sony tak terlalu pusing. Bisa dicari lagi.
Tapi dia benar-benar gundah ketika delapan bulan kemudian mendapat berita kurang sedap. Candra dicari-cari orang. Beberapa pemasoknya ngamuk-ngamuk, karena belum pernah dibayar. Di mana kamu, Ndra? HP-nya mati. Tak pernah bisa dihubungi. Akhirnya Jupri ditangkap polisi. Candra menghilang ditelan bumi.
Dung dung pret, ada kodok disangka kampret.
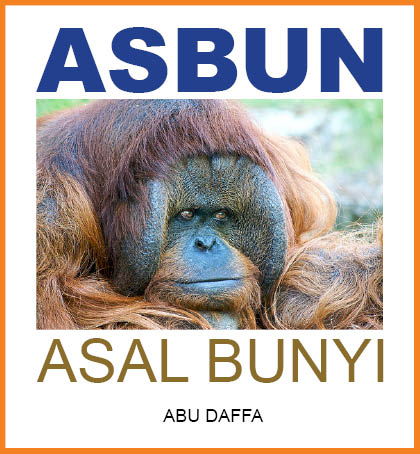
Tidak ada komentar:
Posting Komentar